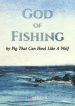Yuri no Aida ni Hasamareta Watashi ga, Ikioi de Futamata shiteshimatta Hanashi LN - Volume 4 Chapter 8
Epilog: Seandainya Kau Ada di Sana untukku
“Tidak, tidak, ini tidak akan berhasil. Ini sama sekali tidak akan berhasil,” katanya sebelum merobek selembar kertas dari buku catatannya, meremasnya menjadi bola, dan melemparkannya ke tanah. Aku sudah kehilangan hitungan berapa banyak lembaran kertas yang mengalami nasib serupa sebelumnya.
Aku berhenti di tengah kalimat yang sedang kuketik di laptopku, mengambil segumpal kertas dari lantai, dan membukanya. “Aku rasa ini sudah cukup,” kataku sambil membaca sekilas apa yang telah ditulisnya… tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dengan sedih.
Aku ragu sejenak, menahan keinginan untuk menghela napas, lalu membaca ulang makalah itu. Tidak buruk . Bahkan, aku akan memberinya nilai lebih dari lulus. Namun, aku bisa mengerti mengapa dia tidak mudah puas. Lagipula, tidak ada metode pasti dan siap pakai untuk apa yang ingin dia capai.
Jika saya harus meringkas misinya dalam istilah metaforis… saya kira saya akan mengatakan bahwa itu seperti melubangi lambung kapal yang terbuat dari lumpur, lalu meyakinkan para penumpang kapal itu untuk meninggalkannya dan beralih ke kapal miliknya sendiri.
Sejumlah masalah menghalangi tercapainya tujuan tersebut. Pertama, kapal lumpur itu, bagi para penumpangnya, memang merupakan kapal yang luar biasa. Layarnya besar, hiasan haluannya berlapis emas, dan bahkan dilengkapi dengan sistem autopilot canggih. Para penumpang berbaring di deknya, tidur siang dan dengan senang hati berjemur di bawah sinar matahari. Mereka bermimpi, sama sekali tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa kapal mereka sedang hancur di bawah mereka. Sang komandan harus membangunkan para penumpang dari tidur mereka sebelum melakukan hal lain, dan itulah mengapa ia harus membuat lubang di lambung kapal: untuk memperingatkan mereka tentang bahaya sebelum terlambat bagi mereka untuk memiliki kesempatan melarikan diri.
Masalah kedua: Sekalipun ia membawa kapal baru dan mendesak para penumpang untuk menaikinya, faktanya tetap bahwa kapten kapal baru itu—yaitu, dirinya sendiri—bukanlah pilot yang paling dapat diandalkan. Terlebih lagi, kapal yang mampu ia siapkan jauh dari kapal paling mengesankan yang pernah berlayar di lautan. Memang kapal itu tidak sedang tenggelam, tetapi tidak memiliki layar, kompas, dan bahkan peta laut. Awak kapal harus mendayung dengan sekuat tenaga dengan harapan dapat menyeberangi samudra luas dan mencapai tujuan mereka. Tidak seorang pun akan mau menaiki kapal seperti itu, kecuali dalam keadaan yang sangat putus asa.
Lalu ada masalah dengan sang kapten sendiri. Niatnya adalah membangunkan para penumpang, membujuk mereka untuk naik ke kapalnya… dan kemudian segera meninggalkan kemudi, membiarkan orang lain mengambil alih kepemimpinannya dan menjadi hanya seorang pekerja biasa. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memimpin, bahkan tidak memiliki sebagian kecil karisma yang diperlukan untuk menarik orang kepadanya. Namun demikian, kapalnya—dan kaptennya—pada dasarnya dapat diandalkan. Mungkin mereka tidak dapat menjamin para penumpang bahwa mereka akan berlayar langsung ke tujuan mereka tanpa gagal, tetapi paling tidak, mereka akan memulai perjalanan yang akan membuat semua orang tidak menyesal.
Tapi tentu saja…kurasa aku bisa mengatakan semua ini karena aku memiliki perspektif orang luar sepenuhnya terhadap masalah ini.
Saya menyimpang dari topik. Intinya adalah, tidak peduli berapa kali dia memikirkan rencananya—tidak peduli berapa banyak lembar kertas buku catatan yang dia buang—saya yakin hampir pasti dia akan gagal pada akhirnya. Namun, terlepas dari prediksi itu, saya memilih untuk menemaninya dalam usahanya. Itu sebagian karena dia meminta bantuan saya, tetapi juga karena saya ingin membantunya mencapai tujuannya… atau begitulah klaim saya, tetapi mungkin itu terlalu memihak. Cara yang lebih praktis untuk mengatakannya adalah bahwa saya telah membayangkan bagaimana rasanya gagal bersama dengannya, dan telah memutuskan bahwa saya kurang lebih baik-baik saja dengan itu.
“Kurasa sekarang mungkin waktu yang tepat bagimu untuk beristirahat,” saranku.
“Ugh… Maaf sudah membuatmu menanggung ini, Koganezaki,” jawabnya sambil mengangguk meminta maaf.
“Aku akan menuangkan teh,” kataku. Aku tidak bermaksud membuatnya meminta maaf. Niatku sama sekali bukan untuk menuduhnya melakukan apa pun.
Aku berdiri, melangkah ke dapurku, dan membuka sebotol teh plastik. Sambil mengisi sepasang gelas, aku teringat tumpukan kertas yang secara bertahap ia tambahkan dengan efisiensi yang hampir seperti jalur perakitan. Dari sudut pandang tertentu, orang bisa melihat tumpukan itu sebagai bukti fisik betapa sungguh-sungguhnya ia menuliskan setiap secuil ide yang muncul di benaknya. Namun, ada satu ciri yang dimiliki oleh setiap naskah yang telah ia tulis sejauh ini.
“Maafkan saya. Saya minta maaf.”
Setiap pidatonya, tanpa terkecuali, selalu menyertakan semacam permintaan maaf. Itu adalah perwujudan dari kurangnya kepercayaan dirinya—suatu kondisi yang, dalam beberapa hal, hampir terasa seperti kutukan. Apakah dia dipaksa untuk terus-menerus berada dalam keadaan kurang percaya diri karena tindakan orang lain, ataukah dia sendiri yang telah melakukan pelecehan terhadap dirinya sendiri? Saya tidak tahu pasti, tetapi bagaimanapun juga, luka emosionalnya jauh melampaui kemampuan saya untuk mengobatinya.
“Ini dia,” kataku sambil meletakkan gelas di depannya.
Bahkan gestur yang paling tidak berbahaya sekalipun membuat bahunya terkulai karena menyesal. “Maaf…” katanya.
“Saya rasa maksud Anda adalah ‘terima kasih’,” jawab saya. “Sangat penting untuk memilih kata yang tepat.”
“Maaf— maksudku, terima kasih.”
Aku mengoreksinya secara refleks… yang, aku tahu, tidak menguntungkan kami berdua. Aku hanya bersikap cerewet. Aku sadar secara objektif bahwa aku secara umum dianggap sebagai orang yang agak menakutkan, dan itu terlihat dari sikapnya terhadapku. Aku tidak pernah menyiratkan bahwa dia harus berhati-hati saat berbicara denganku, tetapi dia tetap melakukannya, mungkin karena dia takut akan pembalasan jika dia terlalu santai denganku. Namun, secara membingungkan dan tidak konsisten, dia juga sangat memaksa ketika menegaskan bahwa kami berdua berteman.
“Sungguh menjengkelkan,” pikirku, sambil iseng mengulurkan tangan untuk menyentuh rambutnya dengan lembut.
“Hah? Koganezaki?”
Mengabaikan kebingungannya, aku memisahkan helaian rambut yang telah kusentuh, lalu mencubit telinganya yang baru saja terbuka.
“Hyeeek?!” teriaknya, sambil melepaskan diri dari genggamanku. “A-Apa yang kau lakukan?!”
“Kau tampak murung,” jawabku. Aku sadar sepenuhnya bahwa jawaban itu sama sekali bukan penjelasan, tetapi aku mengucapkannya dengan nada percaya diri yang membuat bahkan omong kosong pun sulit dibantah.
Dan ternyata, dia tidak mengorek lebih dalam. Lelucon kecilku langsung dilupakan begitu saja. “Maaf…” dia meminta maaf sekali lagi. Jelas sekali dia kehilangan kepercayaan diri dengan cepat.
Sekali lagi, saya sama sekali tidak bermaksud mengkritiknya… atau, yah, dalam kasus ini, mungkin memang saya bermaksud mengkritiknya. Menyebut seseorang “murung” tentu saja bukanlah pujian, setidaknya. Tapi kurasa motif saya bukanlah faktor terpenting di sini, bukan?
“Menurutmu sudah saatnya berhenti?” tanyaku. Aku agak terkejut dengan betapa banyak kasih sayang yang kudengar dalam nada suaraku sendiri—meskipun pada saat yang sama, aku tahu bahwa aku sedang menawarinya godaan yang sama sekali tidak dia butuhkan. Dan, lebih dari itu, aku terkejut dengan betapa tulusnya aku mengatakannya. Bagaimanapun, ketulusan itu adalah tanda bahwa aku sendiri menganggap masalah ini cukup serius.
Dia menarik napas tajam dan menatapku. Aku bisa melihat tekad di matanya goyah sesaat… tapi kemudian dia memalingkan muka lagi, berkata, “Aku akan terus mencoba sedikit lebih lama,” dengan nada lemah dan pelan, lalu tersenyum. “Jadi, umm… Maaf karena membuatmu menunggu dengan— Aduh?!”
“Kalau begitu, kurangi bicara, perbanyak menulis,” kataku, memotong ucapannya sebelum dia menyelesaikan pemikiran yang sangat tidak ingin kudengar sampai selesai. Ngomong-ngomong, aku melakukannya dengan meletakkan tangan di kepalanya dan menekannya. Aku menekannya cukup keras, sehingga senyumnya sebagai respons agak membingungkan.
“Hehehe… Pasti seperti inilah rasanya punya kakak perempuan,” katanya.
“Kamu satu-satunya kakak perempuan di sini,” jawabku.
“Tentu, tapi kau terasa seperti kakak perempuan, Koganezaki! Kau sangat cocok dengan gambaran ideal itu.”
“Yang ideal…”
Sebuah cita-cita—dengan kata lain, bukan kenyataan. Sifat yang ia lihat dalam diriku adalah sifat yang pernah dicari orang lain dariku, dan sifat yang pada gilirannya pernah kucoba tunjukkan seolah-olah aku memilikinya. Namun pada akhirnya, cita-cita hanyalah cita-cita. Kepalsuan hanyalah kepalsuan. Aku merasakan kebenaran itu lebih tajam dari sebelumnya, berada di hadapan sosok yang sebenarnya.
“Terima kasih untuk ini! Kurasa aku bisa mendorongnya sekali lagi!” katanya sambil tersenyum polos dan berseri-seri.
Aku memberinya satu pukulan lembut lagi di kepala, lalu membalikkan badan membelakanginya.
Jika dia bisa memberikan dorongan lagi, itu karena dia memang menginginkannya—bukan karena apa pun yang saya lakukan.
Aku ingin mengatakan fakta yang sangat jelas itu dengan lantang. Aku tidak ingin memukul kepalanya—aku ingin menepuknya, perlahan dan lembut. Aku ingin memujinya dan memeluknya. Namun, itu adalah keinginan egois yang kutekan. Mewujudkan keinginan itu akan menjadi kesalahan, dan aku tahu itu. Aku tahu itu dengan sangat menyakitkan.
Bagian diriku yang seperti kakak perempuan itu benar-benar palsu dan tidak masuk akal… tetapi di sisi lain, aku tetap tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa bagi sisi palsu diriku itu, dia mungkin memang adik perempuan yang ideal.
◇◇◇
Ketika saya masih duduk di bangku SMP, saya bersekolah di sebuah institusi bernama Akademi Putri Seiran: sebuah dunia kecil yang terisolasi dan menjadi tempat saya menjalani sebagian besar hidup saya. Sekolah itu memiliki sejarah keanggunan dan tradisi, hanya dihadiri oleh orang kaya dan istimewa… atau setidaknya itulah reputasi yang dimilikinya di mata publik, yang baru saya ketahui setelah saya meninggalkannya. Saat itu, saya tidak pernah terpikir bagaimana orang lain akan memandangnya dari luar, karena bagi saya, sekolah itu adalah segalanya.
“Selamat pagi, kakak!” sapa siswa lain kepadaku, memberi hormat sopan saat aku berjalan menyusuri lorong-lorong sekolah.
“Dan selamat pagi juga untukmu,” jawabku sambil tersenyum tipis. Meskipun memalukan untuk mengakuinya, saat itu, aku bisa melakukan hal-hal seperti itu tanpa merasa sedikit pun malu. Aku masih kelas tiga SMP—baru berusia empat belas tahun—tetapi aku merasa seolah-olah aku sudah dewasa dan matang seperti layaknya seorang anak.
Aku selalu tinggi, relatif terhadap teman-teman sekelasku. Yang menambah daya tarikku adalah fakta bahwa nama belakangku, Koganezaki, tidak umum—bahkan di sekolah seperti itu—dan karenanya menonjol. Setiap kali aku naik kelas, aku diperlakukan semakin dewasa oleh orang-orang di sekitarku. Lebih buruk lagi, sebuah tradisi lama—atau, sebagian orang mungkin berpendapat, sebuah kesalahan mendasar—di Akademi Seiran adalah cara siswa yang lebih muda memanggil senior mereka sebagai kakak perempuan. Itulah mengapa adik kelasku, dan juga sejumlah teman sebayaku, memanggilku “kakak perempuan,” yang menunjukkan rasa hormat yang tinggi yang mereka berikan kepadaku.
Percaya atau tidak, saya justru bangga dengan perlakuan itu. Hal itu membuat saya merasa bertanggung jawab, sehingga rasanya wajar saja ketika saya terpilih menjadi perwakilan kelas. Saya sering mampir untuk melihat kegiatan adik kelas saya, dan secara proaktif membantu guru-guru saya sebisa mungkin. Itu adalah cara yang sangat sederhana untuk membangun reputasi saya sendiri, dan sebelum saya menyadarinya, jauh lebih banyak siswa di sekolah saya yang mulai mengagumi saya daripada yang saya sadari.
Di antara banyak siswa itu, ada tiga orang yang sangat akrab denganku. Salah satunya bernama Ritsuka Shinomoto: seorang gadis di kelasku yang sudah berteman sejak kami masih sangat kecil. Dia ceria dan ramah, dan selalu merasa malu ketika siswa lain memanggilnya “kakak perempuan.” Dia juga salah satu dari sedikit orang yang tidak memperlakukanku seolah-olah aku istimewa. Dia selalu menyapaku dengan senyum yang sama seperti biasanya, bertindak seolah-olah kami setara. Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa dihormati oleh siswa lain adalah sumber stres dan kecemasan yang mendalam bagiku, atau sesuatu yang seserius itu, tetapi itu agak melelahkan dari waktu ke waktu, dan dia adalah satu-satunya orang yang bisa kucurahkan kelelahan yang terpendam ketika aku merasa perlu.
Salah satu dari ketiganya adalah Emiri Shirahama. Ia setahun lebih muda dariku, dan mengidolakanku dengan sangat istimewa dan luar biasa. Ia juga sangat sopan dan anggun—wanita muda yang berkelas dan anggun yang diasumsikan orang bersekolah di sekolah seperti sekolah kami. Namun, kepadaku, ia menunjukkan semacam keterikatan yang menggemaskan dan kekanak-kanakan. Misalnya, ketika gadis-gadis lain berbicara denganku, ia selalu cemberut. Aku menganggap kecemburuan kecil itu menawan, dan senang menjadi objek kasih sayangnya. Kasih sayang, sebenarnya, adalah salah satu dari sedikit penghargaan yang kuterima atas usahaku. Itu membuat kerja keras untuk memainkan peranku—cukup keras hingga menjadi sumber stres—terasa berharga. Rasanya seperti bukti bahwa aku dibutuhkan. Itu menjadi alasan keberadaanku.
Dan begitulah… akhirnya saya salah mengira bahwa saya tidak mungkin salah.
“Hei, Mai? Aku harus memberitahumu sesuatu. Aku…aku mencintaimu. Bukan sebagai teman. Maksudku, aku benar-benar mencintaimu.”
“Aku sangat menyayangimu, kakak! Maukah kau mempertimbangkan untuk menjalin hubungan denganku?”
Lalu Ritsuka dan Emiri mengajakku kencan. Keduanya. Dan yang lebih ajaib lagi, mereka melakukannya di hari yang sama.
“ Apa…? ”
Awalnya, satu-satunya reaksi yang bisa saya berikan hanyalah menegang karena kebingungan. Ritsuka—yang pertama kali mengungkapkan perasaannya kepada saya—telah menjadi teman saya selama bertahun-tahun, dan selama itu saya tidak pernah sekalipun mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia memiliki niat romantis terhadap saya. Itu seperti petir di siang bolong. Meskipun Emiri memiliki perasaan kepada saya bukanlah hal yang mengejutkan, fakta bahwa dia memilih untuk mengungkapkannya segera setelah Ritsuka melakukannya adalah kebetulan yang sangat menggelikan, itu membuat saya tercengang.
Yang bisa saya katakan, dalam kasus mereka berdua, adalah bahwa saya tidak pernah merasakan ketertarikan romantis seperti yang mereka rasakan terhadap saya—dan sebenarnya, saya belum pernah merasakan ketertarikan seperti itu kepada siapa pun sama sekali.
Aku selalu merasa bahwa kejujuran adalah kebijakan terbaik. Itu berlaku dua kali lipat dalam hal percintaan, dunia yang sama sekali tidak kukenal. Memulai hubungan yang didasarkan pada kebohongan terasa seperti bunuh diri bagiku. Ritsuka dan Emiri bukanlah pengecualian—aku merasakan hal yang sama bahkan dalam kasus teman-teman terdekatku. Atau mungkin sebaliknya. Mungkin justru karena mereka adalah teman-teman terdekatku, aku merasa berkewajiban untuk membalas dengan ketulusan sepenuhnya.
“Maaf,” kataku sambil membungkuk penuh penyesalan. “Untuk saat ini, saya tidak berniat berkencan dengan siapa pun.” Saya tidak tahu dari mana saya mempelajari cara menolak seseorang seperti itu, tetapi saya menggunakannya dua kali, persis seperti yang saya ucapkan.
“Oh… Mengerti. Ya, cukup adil! Ha ha—maaf soal ini. Dari mana sih asalnya itu?” kata Ritsuka sambil tertawa sebelum melanjutkan perjalanannya.
Sebaliknya, Emiri tidak begitu mengerti. “Apa? Tapi… Tapi kenapa? Apa yang ada padaku yang tidak cukup baik untukmu?!” dia hampir memohon.
“Tidak ada yang salah denganmu. Ini bukan salahmu sama sekali. Aku hanya…” ucapku, suaranya menghilang.
Apa yang tepat untuk kukatakan padanya? Bagaimana aku bisa memastikan dia tidak terluka? Aku dengan panik mencari jawaban di antara semua pengetahuan yang telah kudapatkan selama empat belas tahun hidupku—tetapi sayangnya, aku juga tanpa ragu lebih bingung daripada yang pernah kurasakan selama empat belas tahun itu. Pikiranku terasa kacau. Aku bahkan merasa pusing.
Pada akhirnya, saya yakin bahwa saya memang mengatakan sesuatu kepadanya. Saya merangkai serangkaian kata-kata canggung dan kaku yang saya harap tidak akan menyakitinya atau memberinya harapan palsu bahwa saya akan membalas perasaannya. Saya tidak ingat persis apa yang saya katakan. Kata-kata yang keluar dari mulut saya begitu lemah dan tidak dapat diandalkan sehingga rasanya lenyap begitu saja saat saya mengucapkannya.
Sebelum aku menyadarinya, Emiri sudah pergi. Namun, ketika aku menyentuh dadaku, aku masih bisa merasakan sedikit kelembapan di tempat dia membenamkan wajahnya. Jejak air matanya.
Jika mengingat kembali, saya tidak bisa tidak berpikir bahwa saya juga punya alasan yang sama untuk menangis seperti dia.
Hampir tidak butuh waktu lama sampai rumor mulai beredar. Lebih spesifiknya, rumor bahwa Emiri dan aku adalah sepasang kekasih.
“Jadi? Jelaskan dirimu,” kata Ritsuka, menatapku dengan tatapan penuh penghinaan.
“II…” Aku tergagap. Aku menginginkan penjelasan sama seperti dia. Rumor itu tidak berdasar. Aku yakin bahwa aku telah menolak Emiri, dengan sangat jelas.
“Kamu bilang kamu tidak akan berkencan dengan siapa pun, kan?!”
Apakah aku telah berbohong padanya? Apakah aku tidak memiliki kesopanan untuk menanggapi perasaannya yang tulus dengan balasan yang tulus pula? Dia mulai menangis—air mata kemarahan, dan sekaligus, rasa malu.
“Kakak perempuan,” sebuah suara yang sangat tenang terdengar, menggema di telingaku. Itu Emiri, dan dia tersenyum. Senyum yang belum pernah kulihat di wajahnya sebelumnya.
“ Kau …” geram Ritsuka. Sasaran amarahnya tiba-tiba bergeser.
“Oh, astaga, ternyata Shinomoto! Selamat siang,” kata Emiri dengan seringai yang hampir bernada kasihan.
Itu bukanlah ungkapan yang seharusnya ditujukan kepada senior. Sebaliknya, itu jelas merupakan upaya provokasi—yang membuat Ritsuka termakan umpannya sepenuhnya. Dia sangat marah.
Sejujurnya…aku tidak ingat detail percakapan yang terjadi setelah itu. Yang kuingat adalah bagaimana mereka berdua saling menghina secara verbal dengan cara yang, dalam keadaan biasa, tidak pernah kubayangkan akan mereka lakukan. Sementara itu, aku terjebak di antara mereka, menggigil dalam diam sementara sakit kepala yang hebat menguji batas ketahananku.
Semuanya terjadi begitu cepat. Sebelum aku menyadarinya, desas-desus palsu bahwa aku berpacaran dengan Emiri telah ditambah dengan lapisan lain yang bahkan lebih jahat: bahwa aku telah mempermainkan perasaan Emiri dan Ritsuka, melukai mereka dalam prosesnya. Desas-desus khusus ini, tampaknya, bukan disebarkan oleh mereka berdua. Sebaliknya, itu adalah ulah gadis-gadis lain di sekolah kami yang sangat menghormati mereka berdua. Mereka berdua menonjol, dan disukai serta dipercaya oleh teman-teman sebaya mereka. Wajar jika tidak sedikit siswa lain yang merasakan hal yang sama terhadap mereka seperti yang mereka rasakan terhadapku.
Tentu saja, saya segera menjadi musuh bebuyutan para siswa itu. Mereka ingin menjatuhkan saya dari kedudukan saya, melemparkan saya ke tanah, dan mengubur saya hidup-hidup di lumpur. Rasanya seperti saya tenggelam dalam permusuhan mereka yang tak terkendali.
Jika ada satu sisi positif dari situasi ini, itu adalah kenyataan bahwa semua ini terjadi tepat sebelum saya lulus dari divisi sekolah menengah akademi. Setelah saya lulus, jarak tertentu akan terbentuk antara saya dan Emiri. Namun, Ritsuka akan tetap menjadi teman sekelas saya.
Setelah semua kekacauan itu, Ritsuka rupanya akhirnya berpacaran dengan salah satu adik kelasnya. Bahkan saat itu pun, aku sesekali memperhatikannya, selalu menatapku dengan tatapan jijik atau kasihan. Aku tidak pernah bisa memastikan yang mana.
Sementara itu, saya benar-benar terisolasi. Saya tidak pernah menemukan bukti konkret bahwa kabar tentang reputasi saya yang tercoreng telah sampai ke guru-guru kami, tetapi dengan satu atau lain cara, mereka semua akhirnya menghindari saya sebisa mungkin, sama seperti teman-teman saya yang lain.
Yah, tidak juga—itu tidak sepenuhnya benar. Mungkin hanya ada satu pengecualian.
“Kakak!” katanya, kata-kata bahasa Swedia-nya yang fasih terdengar hampir membelai telingaku. “Aku sudah mencarimu ke mana-mana!”
“Emma…”
Dia adalah teman sekelas ketiga yang sangat dekat denganku—meskipun kurasa pada saat itu, dia adalah satu-satunya teman sekelas yang dekat denganku sama sekali. Dia juga seorang gadis dengan kecantikan yang menakjubkan, seolah-olah dia jatuh ke bumi langsung dari surga. Dia memiliki darah campuran Jepang dan Swedia, dan meskipun namanya terdengar agak Jepang, dia telah tinggal di Swedia sejak masih sangat muda. Kebetulan, orang tuaku berteman dengan orang tuanya, dan kami telah bertemu beberapa kali di masa lalu, tetapi tidak pernah terlalu dekat…sampai, dia pindah ke divisi sekolah menengah Akademi Seiran.
“Kamu seharusnya tidak berbicara seperti itu padaku, Emma,” jawabku dalam bahasa Swedia.
“Untuk apa?”
“Karena… Yah, kamu sudah mendengar rumornya, kan?”
“Aku hanya ingin berada di dekatmu, itu saja!”
Saat itu, dia juga sama sekali tidak fasih berbahasa Jepang. Aku tidak tahu apakah dia bercanda atau memang benar-benar tidak menyadari rumor yang beredar, tetapi bagaimanapun juga, dia memberiku senyum cerah dan memelukku.
Emma adalah orang yang sangat aneh. Rasanya waktu mengalir berbeda baginya dibandingkan orang lain. Mungkin itulah sebabnya, betapapun bebasnya dia—betapapun anehnya perilakunya—orang-orang di sekitarnya pada umumnya menerima semuanya sebagai kekhasannya. Itu adalah jenis kebebasan yang tidak diizinkan untukku, dan aku akui, aku iri… tetapi di sisi lain, aku tahu itu mungkin juga menimbulkan kesulitan tersendiri.
“Katakan padaku, Emma…” aku mulai lagi dalam bahasa Swedia.
“Ya, Kakak?”
“Apa yang akan kamu katakan…jika kukatakan padamu bahwa aku tidak berencana untuk melanjutkan ke divisi sekolah menengah atas akademi ini?”
“Kalau begitu, aku juga tidak mau!” jawab Emma sambil tersenyum. Dia bahkan tidak ragu-ragu. Rupanya, itu adalah jawaban termudah di dunia baginya.
Aku harus berasumsi bahwa keadaan keluarga kami memang berbeda. Aku sudah banyak berpikir tentang bagaimana aku akan membiayai kepindahanku ke sekolah yang sama sekali berbeda. Setelah semua yang telah kulalui, semangatku benar-benar terkuras. Sesuatu di dalam diriku hampir hancur berkeping-keping. Aku sangat ingin melarikan diri dari dunia kecil yang terisolasi tempatku tinggal. Itulah mengapa aku bernegosiasi dengan orang tuaku, mengajak kakekku untuk berpihak padaku, dan mengamankan kesepakatan: Selama aku bisa masuk ke sekolah menengah dengan nilai rata-rata ujian yang lebih tinggi daripada Akademi Seiran, aku akan diizinkan untuk pindah. Bagaimana situasi Emma dibandingkan? Aku tidak tahu, dan merasa bukan hakku untuk ikut campur.
“Kakak… perempuan?”
Aku tersentak bangun. Aku bahkan tidak menyadari bahwa aku telah menundukkan kepala sampai Emma berbicara kepadaku—dan melakukannya dalam bahasa Jepang yang sangat terbata-bata, bahasa yang baru saja mulai dipelajarinya.
“Kakak…saudari…bersama…selalu…sungguh!”
“Emma…”
Air mata menggenang di mataku. Saat itu, tidak ada yang bisa membuatku lebih bahagia daripada mendengar bahwa seseorang ingin bersamaku—bahwa seseorang masih menghargaiku.
“Maaf,” kataku. “Aku harus meninggalkanmu sendirian untuk sementara waktu.”
Dia memanggilku kakak perempuannya, dan setidaknya, aku ingin menjadi seseorang yang pantas menerima sebutan sayang itu. Dengan begitu, bahkan jika aku melarikan diri—bahkan jika aku kehilangan segalanya—aku bisa tahu bahwa suatu hari nanti, dia pasti akan menemukanku lagi.
Jadi, aku pindah ke SMA Eichou: sekolah dengan reputasi yang cukup terhormat untuk memuaskan orang tuaku. Itu berarti meninggalkan rumah keluargaku, tetapi kakekku memfasilitasi kepindahanku, mengizinkanku tinggal di salah satu kamar di gedung apartemen bertingkat tinggi miliknya. Begitu aku lulus dari sekolah menengah pertama, aku pindah untuk mulai hidup sendiri… dan begitu aku mulai sekolah menengah atas, aku bertemu dengan mereka .
“Hei, apa kau melihat kedua orang itu?”
“Mereka sangat cantik… Dan bukankah mereka terlihat sangat serasi bersama?”
Mereka berdua memang sangat istimewa. Tentu saja, mereka memiliki aura yang luar biasa sebagai individu, tetapi ketika bersama, perasaan harmoni dan keintiman yang mereka pancarkan tak tertandingi. Hal itu membuat kelebihan masing-masing individu semakin bersinar.
Sebagian besar siswa di kelas kami yang baru masuk memandang mereka dengan kekaguman yang polos. Namun, aku melihatnya berbeda. Tak ada yang tahu kapan tatapan polos itu akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, pikirku. Suatu hari nanti kekaguman itu bisa berubah menjadi iri hati, bahkan permusuhan… dan meskipun aku sama sekali tidak mengenal mereka, aku tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan hal itu terjadi.
Itulah mengapa aku membuat pilihan. Aku memutuskan untuk melindungi mereka. Mungkin itu kesombongan dariku, tetapi aku tetap akan melakukannya. Itu akan menjadi caraku untuk bertanggung jawab atas gadis-gadis yang telah kusakiti—caraku untuk menghukum diriku sendiri karena tidak mampu berbuat apa pun selain melarikan diri dari mereka.
Aku merasa tak perlu berada di pusat perhatian. Beroperasi dari balik bayangan sudah cukup bagiku. Aku akan melakukan apa pun yang kubisa untuk mendukung mereka, tanpa pernah mengharapkan upaya itu diakui sedikit pun. Itu hanyalah peran yang kupilih untuk diriku sendiri.
◇◇◇
Aku bisa merasakan tatapan mereka. Sepasang tatapan curiga dan waspada menusukku dari belakang—tatapan milik Yuna Momose dan Rinka Aiba. Aku hampir tidak pernah berbicara dengan mereka berdua sebelumnya, tetapi jelas, mereka berdua menyadari keberadaanku… dan tentu saja, kesadaran itu bukanlah hal yang positif.
Aku tidak berjanji padanya bahwa aku akan mengambil tindakan seperti ini. Bahkan, aku bertindak sepenuhnya secara independen. Aku juga tidak melakukannya untuk Momose atau Aiba kali ini. Jika aku harus mengatakan atas nama siapa aku bertindak … kurasa aku tidak punya pilihan selain mengakui bahwa aku melakukan ini untuk diriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana hasilnya nanti, tetapi aku tahu bahwa aku ingin melihat hasilnya dengan mata kepala sendiri. Dengan kata lain, aku didorong oleh keinginan egoisku sendiri ketika aku memilih untuk mendekati mereka.
“Jadi? Kalian mau membawa kami ke mana?” tanya Momose, tanpa berusaha menyembunyikan ketidakpuasannya. “Sebenarnya kami sedang sibuk sekarang, kalau kalian belum menyadarinya.”
“Ini hanya akan memakan waktu sebentar,” jawabku. “Kupikir akan lebih baik jika kalian berdua mengetahuinya.”
“Mengetahui apa ?”
“Kamu harus mencari tahu sendiri.”
Aku sama sekali bukan teman mereka. Aku berniat melindungi mereka, tetapi sama sekali tidak berniat untuk akur dengan mereka. Terlebih lagi, bagi mereka, aku adalah wakil presiden klub penggemar Sacrosanct. Dengan kata lain, aku adalah sosok yang membuat hidup mereka—hidup mereka dan juga dirinya —lebih menyesakkan daripada yang seharusnya. Singkatnya, bagi mereka, aku adalah kekuatan antagonis. Dalam keadaan normal, aku yakin mereka tidak akan pernah setuju untuk mengikutiku ke mana pun, dan dalam keadaan normal, aku tidak akan terus melakukannya. Namun kali ini…
“Permisi, Koganezaki?”
Aku ragu sejenak. “Ya, Oda?”
“Apakah kau mengantar kami ke ruangan kelas 2-A?”
Sejak dia pindah beberapa minggu sebelumnya, Makina Oda telah menjadi sumber stres terbesar dalam hidupku… tetapi dia juga orang pertama yang setuju untuk ikut denganku. Proses berpikirnya benar-benar tidak dapat kupahami—bahkan lebih tidak dapat kupahami daripada duo Sacrosanct—tetapi serangkaian keadaan yang kebetulan aneh telah membuat kami bertemu sebelumnya, selama liburan musim panas. Emma dan aku bertemu Oda saat mengunjungi akuarium bersama. Lebih tepatnya, kami bertemu Oda dan pacarnya , yang sedang berkencan.
Di satu sisi, kami secara teknis telah menonton pertunjukan lumba-lumba bersama, yang membuat kami terdengar cukup dekat, tetapi di sisi lain, kami hampir tidak berbicara sama sekali selama pengalaman itu. Oda hanya memperhatikan dirinya sendiri , yang juga kebetulan mendominasi perhatianku, meskipun karena alasan yang sama sekali berbeda, jauh kurang positif. Namun, Oda tampaknya setidaknya mengingat namaku, dan telah membentuk asosiasi mental antara aku dan dirinya . Itulah mungkin mengapa dia bisa menduga bahwa kelas 2-A— kelasnya —adalah tujuanku.
“Tunggu, kelas kita?” tanya Momose.
“Saya rasa mereka seharusnya mengadakan pertemuan untuk mempromosikan penampilan kami hari ini,” kata Aiba.
“Benar,” kataku. “Pertemuan yang kehadiranmu tidak diminta.”
“Baiklah…dan mengapa itu urusanmu? Kau bahkan bukan teman sekelas kami,” kata Momose.
“Aku penasaran?”
“ Lihat , kau bocah kecil—”
“Yuna,” kata Aiba, memotong pembicaraan sebelum Momose bisa menyerangku. Momose bertingkah seperti anjing penjaga yang gila, dan meskipun Aiba menahannya, Aiba jelas masih sangat mencurigaiku juga.
“Mereka benar-benar menciptakan keseimbangan yang mengesankan satu sama lain, ” pikirku. “Meskipun begitu, saat ini, mereka berdua tampak sangat tegang. Apakah mereka hanya cemas karena harus tampil di atas panggung dengan idola populer seperti Oda? Atau apakah ini juga ada hubungannya dengan Oda ?”
“Saya yakin rencananya adalah agar kita diberitahu tentang keputusan yang dibuat dalam rapat tersebut setelah kejadian?” kata Oda.
“Benar,” jawabku, “tapi tidak ada salahnya kalau kau menonton dari pinggir lapangan dengan tenang, kan? Dan seandainya mereka menuduhmu menguping, yang perlu kau katakan hanyalah aku menyeretmu ke sana melawan kehendakmu. Itu seharusnya cukup menjadi alasan yang masuk akal untuk meredakan ketegangan.”
Oda terdiam—begitu pula Momose dan Aiba. Ketiganya pasti penasaran dengan isi pertemuan itu, tetapi mereka juga mengerti bahwa kehadiran mereka di ruangan itu hanya akan menjadi penghalang. Mereka sengaja menahan diri untuk tidak berpartisipasi agar pertemuan dapat berjalan lancar, mungkin karena mempertimbangkan teman-teman sekelas mereka, atau mungkin karena itu lebih nyaman bagi mereka juga.
Tidak… aku harus menghentikan itu. Mengapa aku selalu merasa perlu meragukan niat orang lain?
Di saat-saat seperti ini, saya bisa merasakan bahwa gaya hidup saya selama setahun terakhir mulai memberikan pengaruh yang berbeda pada kepribadian saya. Rasanya saya hanya bisa mempercayai seseorang ketika saya mengetahui aspek-aspek kepribadian mereka yang paling dalam dan tersembunyi—dan setelah mengetahui sifat-sifat seseorang yang kurang baik, saya langsung menyimpulkan bahwa itulah keseluruhan sifat asli orang tersebut. Saya tahu bahwa itu adalah cara bersosialisasi yang regresif yang hanya akan membuat saya memiliki musuh, tetapi saya tidak bisa menahan diri.
Kami tiba di luar kelas 2-A tepat pada waktunya untuk mendengar perdebatan sengit yang terdengar dari dalam kelas.
“Aku bilang, kita harus habis-habisan memamerkannya dengan foto! Foto-foto besar, mencolok, dan langsung menarik perhatian! Kita juga bisa memasang banyak foto di balik layar di mana-mana!”
“Tapi bukankah video akan jauh lebih baik dari itu?! Kita harus membuat video! Video itu akan menyebar dengan cepat jika kita mengunggahnya ke situs web!”
“Apa…?!” kata Momose sambil tersentak mundur.
“Mereka tidak mungkin bermaksud…?” gumam Aiba sambil mengerutkan kening.
Sementara itu, Oda sama sekali tidak mengatakan apa pun. Namun, dia tampak seperti sedang berpikir keras.
Ini pasti akan sulit diterima, jika saya termasuk orang-orang yang terlibat, pikir saya. Mereka pasti merasa kelas mereka memperlakukan mereka seperti mainan.
Tentu saja… mengingat bahwa saya adalah pemain kunci dalam memaksa Momose dan Aiba masuk ke dalam kerangka Sacrosanct, mengendalikan lingkungan di sekitar mereka secara ketat, saya jelas tidak memiliki hak untuk berbicara tentang hal-hal seperti itu. Namun demikian, saya tahu betul bahwa itu bukanlah topik yang menyenangkan bagi mereka untuk didengar dibicarakan secara terbuka.
Sebagai orang luar, saya bisa melihat bahwa kelas itu sama sekali tidak menyadari betapa jahatnya mereka. Mereka adalah koki, dan trio pemain itu adalah bahan-bahan mereka. Hidangan akhir adalah satu-satunya hal yang mereka khawatirkan. Penderitaan apa yang mungkin dialami bahan-bahan itu dan tagihan apa yang harus dibayar setelah makan bukanlah hal yang mereka pertimbangkan. Betapa mengerikannya bagi mereka bertiga ketika menyadari bahwa mereka telah diletakkan di atas talenan? Akankah mereka dicincang? Digiling? Digoreng? Atau mungkin, setelah para koki puas mempermainkan mereka, mereka akan dianggap sebagai eksperimen yang gagal dan dibuang ke tempat sampah.
Justru karena itulah seseorang perlu menyadarkan kelas dari kelengahan mereka.
“Saya—saya menentang kedua usulan itu!”
Momose, Aiba, dan Oda semuanya terkejut. Sementara aku, di sisi lain, merasakan senyum tersungging di wajahku.
◇◇◇
“Tidak mungkin ! Aku benar-benar yakin tentang ini. Maksudku, aku tidak pernah menjadi pusat perhatian, jadi jika semua orang tiba-tiba mulai memperhatikanku dan memintaku untuk mewakili mereka atau apa pun… Aduh, hanya memikirkannya saja membuatku ingin muntah!”
Dia pernah mengatakan itu padaku belum lama ini. Dia mengatakannya dengan panik dan sungguh-sungguh, dengan cara yang tidak menyisakan keraguan bahwa dia berbicara dari lubuk hatinya. Itu persis seperti yang kuharapkan dari seseorang yang sangat pemalu dan mahir dalam mencambuk diri sendiri seperti dia, dan pada saat itu, aku sama sekali tidak meragukannya. Setiap orang memiliki bakat dan kelemahan masing-masing, dan dia bukanlah tipe orang yang bisa berdiri di depan banyak orang dan mengemban panji suatu tujuan.
Namun, sekarang aku mulai mempertimbangkan kembali. Saat aku mendengarkan pidatonya melalui pintu kelas, rasanya seperti aku sedang menatap wajah diriku di masa lalu. Ya, dia pemalu. Ya, sangat mungkin dia saat ini sedang dalam proses melukai dirinya sendiri secara emosional. Namun, terlepas dari segalanya, nadanya sangat kuat. Rasanya kata-katanya menusuk langsung ke hatiku, mungkin karena ketulusan mutlak yang terkandung di dalamnya. Aku bisa merasakan panas yang membara mulai menyebar ke seluruh tubuhku, tanpa kusadari.
Aku tadinya berpikir bahwa dia tidak memiliki sedikit pun karisma dalam bentuk apa pun yang mungkin dimilikinya… tetapi jika memang begitu, mengapa gadis-gadis dengan karisma berlimpah terus berdatangan ke sisinya, satu per satu? Bagaimana dia bisa menyampaikan pidato seperti ini—pidato yang membuat semua orang yang mendengarkannya meneteskan air mata? Mungkin bukan karena dia kurang karisma. Mungkin cara karismanya terwujud memang berbeda dari bentuk apa pun yang kukenal.
“Jadi… kumohon. Aku ingin kalian semua membantu!”
Dengan kata-kata itu, pidatonya berakhir. Keheningan menyelimuti ruangan. Tak terdengar suara apa pun dari dalam kelas… dan aku membayangkan bahwa saat ini, dia pasti sangat khawatir karena tak seorang pun bereaksi.
Bukan berarti dia punya alasan untuk khawatir, pikirku. Aku tahu itu dengan sangat baik. Aku yakin.
“Saya rasa Hazama benar. Dia benar tentang semua ini.”
Melihat?
Seorang anak laki-laki angkat bicara, dan seketika itu juga, persetujuan terhadap idenya menyebar ke seluruh kelas seperti api yang menjalar. Dia mungkin bingung, tetapi sama sekali tidak ada yang perlu diherankan. Kata-katanya persuasif, sederhana dan lugas. Dia tidak mencoba memaksakan kehendaknya dengan argumen logis—dia menyampaikan pidato langsung dan penuh emosi yang tepat sasaran. Bahkan aku pun merasakannya, jadi tidak mungkin teman-teman sekelasnya tidak merasakannya.
“Koganezaki…”
“Ya, Aiba?”
“Seberapa banyak yang kamu ketahui? Apa yang kamu ketahui tentang kami…?”
“Itu…pertanyaan yang sangat bagus,” kataku sambil mengangkat bahu, sepenuhnya menyadari bahwa aku bersikap terlalu tertutup. Jika aku memberikan jawaban jujur, jawabannya pasti “Semuanya, dari awal sampai akhir.” Namun, bagaimana semuanya berjalan, sepenuhnya berkat tindakan gadis lain, dan rasanya tidak pantas bagiku untuk mengambil pujian atas hasil tersebut. “Yang lebih penting, bukankah kau harus pergi ke suatu tempat?”
“Hah?” gerutu Aiba.
“Kurasa saat ini tidak ada yang berminat untuk mencegahmu ikut serta dalam pertemuan ini,” jawabku.
“Kurasa begitu. Ya, kau benar. Yuna?”
“Aku tahu, oke?!” Momose menjawab dengan kesal. Sejujurnya, itu adalah sikap yang cukup menggemaskan darinya, tetapi tampaknya dia berpikir bahwa perilaku seperti itu tidak pantas untuknya. Dia menampar pipinya beberapa kali, menenangkan diri, dan melangkah masuk ke kelas bersama Aiba.
Aku ditinggalkan di lorong… bersama Makina Oda.
“Yotsy… sama sekali tidak mengerti,” bisik Oda, seolah ditujukan kepada siapa pun. “Aku bukan orang yang sempurna dan cantik seperti yang dia pikirkan. Aku hanya…”
“Mungkin begitu,” sela saya, sepenuhnya menyadari bahwa pendapat saya tidak diminta.
Oda melirik ke arahku. Kebingungan dan keraguannya terlihat jelas di ekspresinya.
“Terkadang sulit untuk memahami perasaan sendiri—dan di sisi lain, terkadang sangat mudah bagi orang luar untuk melihat kebohongan di balik perasaan tersebut dalam sekejap.”
Hal itu tentu juga berlaku untuknya .
“Kurasa sudah saatnya kau meletakkan penamu.”
“Hah? Tapi aku…”
“Berhentilah menulis. Bicaralah. Katakan padaku bagaimana perasaanmu, dan aku akan menuliskan kata-katamu. Yang kau capai dengan menatap selembar kertas dan mengurung diri di duniamu sendiri hanyalah menyiksa dirimu sendiri… jadi aku akan melakukan bagian itu untukmu.”
“Aku… Baik! Aku akan melakukannya!”
Malam sebelumnya, kami telah menulis naskah sederhana untuk pidatonya bersama-sama, dan juga menyiapkan dokumen untuk metode promosi yang akan dia usulkan. Tampaknya pada akhirnya dia memilih untuk tidak membaca naskahnya kata demi kata, tetapi saya yakin bahwa waktu yang kami habiskan untuk membahas perasaannya tentang masalah ini tetap berharga baginya.
Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dimiliki Makina Oda. Aku bisa tahu hanya dengan melihatnya. Dia adalah individu yang bangga akan kemandiriannya… atau mungkin, yang percaya bahwa dia harus melakukannya. Selama bertahun-tahun dia hidup di dunia yang didominasi oleh persaingan antarpribadi yang sengit, yang pasti telah mengajarkannya bahwa pada akhirnya, satu-satunya orang yang benar-benar dapat diandalkan adalah dirinya sendiri.
Tetapi jika memang demikian, mengapa dia begitu terobsesi dengannya ?
Aku hampir bisa meyakinkan diriku sendiri bahwa Oda yang ada di hadapanku sekarang adalah orang yang sama sekali berbeda dari yang kutemui di akuarium. Paling tidak, saat itu aku tidak merasakan keterasingan darinya seperti yang kurasakan sekarang—perasaan bahwa baginya, dia benar-benar sendirian di dunia ini.
“Tidak ada seorang pun yang sempurna,” kataku. “Itu mustahil. Itulah mengapa kita membutuhkan orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang dapat mendukung kita.”
Saya sama sekali bukan seorang optimis buta. Pada akhirnya, setiap orang akan lebih menghargai diri sendiri daripada orang lain. Orang-orang saling mengkhianati karena alasan egois setiap hari. Ada banyak sekali individu yang terluka dan putus asa karena hubungan mereka. Saya sangat memahami dorongan untuk menutup diri dari dunia dan hidup dalam cangkang kecil yang terisolasi.
“Jika saya harus menebak… saya akan mengatakan bahwa justru itulah yang menarik mereka, dan Anda, kepadanya . Kejujuran dan ketulusannya telah memikat hati Anda.”
Dia sepertinya tidak pernah memikirkan keuntungannya sendiri sama sekali… setidaknya, begitulah kemungkinannya. Dia jelas memberi kesan bahwa dia selalu lebih peduli pada orang lain daripada dirinya sendiri. Dia juga sepertinya tidak pernah menginginkan imbalan atas hal-hal yang dilakukannya… dan bahkan, hampir seolah-olah dia tidak memahami konsep imbalan atas tindakannya sama sekali. Dia bisa bersikap menjilat dengan cara yang paling aneh dan menyerah pada dorongan yang paling irasional, tetapi ketika tiba saatnya baginya untuk membantu seseorang, dia mencurahkan seluruh hati dan jiwanya ke dalam tugas itu, jauh lebih besar daripada yang pernah dia lakukan untuk dirinya sendiri. Saya merasa bahwa saat dia mulai menganggap seseorang penting baginya, dia langsung kehilangan kemampuan untuk meninggalkan mereka. Itu, tentu saja, adalah salah satu kebajikannya. Setidaknya, saya melihatnya seperti itu.
Sekali lagi, Oda menundukkan kepalanya dalam diam. Aku yakin dia sedang berpikir—mungkin tentang siapa dirinya bagi Oda , atau tentang apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Aku tidak bisa membaca pikirannya sedalam itu… tetapi aku merasa terdorong untuk ikut campur sedikit lagi, untuk terakhir kalinya.
“Nah?” kataku. “Masuklah ke dalam. Tidak mungkin kau melewatkan fakta bahwa dia bekerja sekeras itu sebagian demi dirimu .”
Oda ragu sejenak…lalu mengangguk lemah. “Baik,” katanya.
Dia belum menyelesaikan perasaannya—dia belum punya waktu—itulah sebabnya saya menduga bahwa gadis yang murung yang saya lihat di hadapan saya mungkin sebenarnya adalah jati dirinya yang sebenarnya.
“Rasanya seperti aku sedang melihat diriku sendiri di masa lalu,” pikirku. Aku tak bisa menahan perasaan simpati.
Aku berjalan sendirian menyusuri lorong-lorong sekolah kami. Untuk sementara waktu, tugasku telah selesai. Rencananya telah berhasil, dan kelas 2-A telah meninggalkan perahu lumpur mereka untuk berlayar dengan kapal yang terbuat dari barang-barang bekas dan disatukan oleh harapan dan impian. Ke mana kapal itu akhirnya akan membawa mereka? Kurasa, itu adalah pertanyaan yang tidak akan pernah kujawab.
Pada akhirnya, bisa dikatakan bahwa tak satu pun dari masalah yang membebani saya benar-benar terselesaikan. Saya tidak hanya gagal menemukan jawaban mengenai masa depan klub penggemar Sacrosanct, tetapi saya juga menghentikan upaya untuk melakukannya, menyerahkannya sepenuhnya kepada takdir. Namun anehnya… saya merasa lega. Saya merasa ingin bersenandung, atau bahkan melompat-lompat… meskipun tentu saja, saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu kasar dan di luar karakter saya.
Tapi…kurasa aku bisa melakukan sebanyak ini.
Whump!
Aku menghentakkan kakiku ke tanah sedikit lebih keras dari biasanya—cukup keras hingga menimbulkan suara. Setidaknya, itu terasa seperti ekspresi yang boleh kulakukan.
“Yotsuba Hazama…” gumamku. Rasanya aku sudah sangat terbiasa menyebut nama itu akhir-akhir ini. Itu bukan nama yang aneh, tapi entah kenapa, mengucapkannya dengan lantang membuatku merasa…segar, kurasa, dengan cara yang unik.
Kau tahu, Hazama… sejak hari itu—hari ketika Emma membawamu ke rumahku, berharap kau bisa membantu setelah aku kehilangan arah—dari waktu ke waktu, sangat jarang, sebuah pikiran terlintas di benakku.
Bagaimana jika kau ada di sana untukku?
Bagaimana jika kau berada di sisiku, dengan segala kecanggungan dan kesungguhanmu yang putus asa, dengan sikap riang yang selalu membuatku merasa seperti orang bodoh karena selalu memikirkan segala sesuatu dengan begitu serius? Mungkin тогда Ritsuka, Emiri, dan aku akan selamat tanpa luka. Mungkin kau akan mewujudkan keajaiban yang tak seorang pun bisa impikan, menyelamatkan kami semua sekaligus.
Atau mungkin justru akulah yang akhirnya terobsesi… denganmu .
“Jujur saja…” gumamku pada diri sendiri, tersenyum getir memikirkan khayalan-khayalanku yang tak berarti. Bahkan aku sendiri bisa merasakan betapa hampa dan riangnya kata itu terdengar, tetapi karena tidak ada orang lain di sekitar, kata itu menghilang ditelan cahaya langit senja tanpa terdengar.