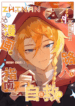Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu LN - Volume 8.5 Chapter 7
Bab 7
Kami telah melakukan pemeriksaan terakhir. Perlengkapan, tubuh, pikiran—semuanya siap untuk pertarungan. Pertarungan yang sesungguhnya.
Pertemuan kami dengan Eris terjadi di gerbang barat. Ketika dia melihat kami, dia berbincang sebentar dengan teknisi teleportasi, lalu berjalan santai seperti biasa.
“Kali ini, aku nggak akan jagain kalian,” katanya sambil menepuk pelan pinggang kami sambil lewat. “Ngelap pantat kalian sendiri, cewek-cewek.”
Begitu saja, dia pergi.
Keren sekali.
“Jadi di sinilah tempatnya?” tanya Abelia.
Aku mengangguk. “Ya, ini tempatnya.”
Lokasi yang kami tuju bukanlah lahan terbuka di tepi danau yang sama seperti terakhir kali. Melainkan dataran tandus—angin kencang menyapu tanah cokelat kusam, tanpa sedikit pun kehijauan atau tanda-tanda kehidupan.
Izumo adalah orang pertama yang menemukan Naga Kecil. “Jin,” katanya, suaranya tenang namun fokus. “Satu klik ke timur laut. Hanya beberapa monster kecil di jalan.”
Kali ini, kamilah yang mendapat drop.
Aku mengangguk dalam diam, sambil mengatur sudut pandang kami agar tidak mendekat melalui jalur terpendek, melainkan jalur dengan perlindungan terbaik, dengan memperhitungkan arah angin.
“Belum ada tanda-tanda dia menyadari keberadaan kita. Semuanya, mulai membentuk formasi,” kata Shifu. Dia juga sudah menemukan targetnya, dan mulai memimpin tim bersama Izumo.
Izumo tidak hanya menggerakkan kami maju—ia memanipulasi udara, menggunakan arus halus untuk menutupi pendekatan kami. Setiap langkah diperhitungkan dan dikendalikan.
Mereka semua menjadi lebih kuat. Begitu juga aku.
Penyergapan bersih memang ideal, tetapi di area terbuka seperti ini—dengan hampir tidak ada medan untuk bersembunyi—hal itu tidak mungkin terjadi. Namun, kami akan melakukan apa pun yang kami bisa karena kali ini, kami tidak sombong.
“Aku akan melawan aumannya,” kata Abelia. “Yuno, kali ini fokusmu pada tombak, kan?”
“Yap,” Yuno mengangguk. “Akhirnya aku menemukan gayaku. Bow dicadangkan untuk saat ini.”
Abelia jelas sudah bersiap untuk ini. Dia sudah menyusun berbagai strategi melawan efek status—sesuatu yang penting jika kita ingin menghadapi raungan yang melumpuhkan itu.
Kami, para garda terdepan, memang bisa memperkuat diri, tapi auman itu bukan sesuatu yang bisa kami abaikan begitu saja dengan buff dan seruan perang. Bahkan dengan semua sihir pertahanan dan mantra perlawanan kami, sebagian bergantung pada keberuntungan. Dan keberuntungan bukanlah sebuah strategi.
Di sinilah peran penyihir yang baik. Jika Abelia berkata dia akan menghentikannya, kita akan percaya padanya untuk melakukannya.
“Oke,” kataku. “Untuk tembakan jarak jauh, kami mengandalkanmu, Shifu, dan Izumo.”
Para petarung jarak menengah dan jauh mengangguk, dan menjalankan perannya secara alami.
“Mithra dan aku yang memimpin. Daena yang mendukung dan mengapit. Tak ada kejutan di sana,” tambahku, mataku menyapu garis depan kami. “Kita yang menahannya. Kuasai medan. Kalau kita bisa menguasainya dan menghabisinya di sana, bahkan lebih baik.”
Itulah tugas kami sebagai garda terdepan: Pukul. Tahan. Tarik ke bawah.
Sisanya—waktu, posisi, strategi—hanya penting jika kami bisa tetap tenang menghadapi tekanannya. Daena dan Mithra langsung menangkap maksudku, menjawab dengan anggukan singkat dan percaya diri.
“Baiklah. Semuanya masuk—tapi tetap waspada,” kata Daena, suaranya mantap.
“Sama-sama. Jangan panik. Kita tetap fokus sampai selesai,” tambah Mithra.
Jarak antara kami dan Naga Kecil semakin mengecil, dan seiring itu, adrenalin kami melonjak. Fokus terkunci dan gerakan terasa kaku. Setiap tarikan napas terasa disengaja.
Kemudian-
“Dia melihat kita!” Izumo memperingatkan.
Tentu saja. Mustahil kami bisa menyelesaikan bagian terakhir itu tanpa ketahuan. Kami sudah menduganya. Kami sudah tidak peduli lagi.
“Ayo pergi!” teriakku.
Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutku ketika tim itu menyerbu maju. Pada saat yang sama, mantra Abelia terpicu—penghalang cahaya berkilauan terbentuk di sekitar kami masing-masing, mantra antiraungannya aktif sepenuhnya. Sedetik kemudian, Shifu menembakkan salvo pembukanya. Garis api yang membakar melesat melintasi dataran, melesat menuju monster itu.
Izumo mengeluarkan mantra untuk meningkatkan semua kecepatan gerakan kami, memotong waktu pertarungan hingga menjadi hitungan detik.
“Kali ini perang, dasar kadal besar!” raung Daena, suaranya membara penuh harap saat ia menumpuk mantra penguat pada dirinya sendiri.
Ia berpura-pura melancarkan serangan pembuka, lalu melesat melewati sisi tubuh Naga Kecil dengan cepat. Gerakan tiba-tiba itu menarik perhatiannya—kepalanya yang bersisik abu-abu menoleh tajam ke arahnya.
“Mithra, Yuno—serang sekarang!” teriakku.
“Mengerti!!!”
“Serahkan padaku!”
Mereka bergerak serempak, pedang-pedang mereka berkilat, dan melancarkan serangan ke arah monster itu secara bersamaan. Waktunya tepat. Kami mendekat bersamaan, menyerang tubuh monster setinggi empat meter itu dengan kekuatan yang bersih dan terkoordinasi.
Izumo dan Shifu sudah merapal mantra ofensif di belakang kami, menciptakan api dan petir di antara tangan mereka. Abelia, yang selalu serba bisa, melapisi sihir pertahanan sambil mempersiapkan mantra penyembuhan secara paralel—teknik mantra ganda tingkat lanjut.
Melantunkan mantra dan mengantre mantra secara bersamaan—dua keterampilan sihir tersulit yang harus dikuasai saat masih sekolah. Kalau kamu bisa menguasainya, orang-orang bilang masa depanmu hampir terjamin.
Bagus sekali, Abelia.
Daena, yang telah menarik perhatian Naga Kecil dengan ejekan pertama itu, tidak berhenti di situ. Sementara kami yang lain tetap di depan, ia langsung melancarkan serangan susulan dari belakang.

Terkadang, Daena menggunakan tubuh Naga Kecil itu sendiri sebagai batu loncatan, melancarkan serangan berantai demi serangan—tidak cukup untuk menimbulkan kerusakan besar sendiri, tetapi mendaratkan begitu banyak serangan hingga kekuatannya menumpuk. Bahkan dengan serangan ringan, tingkat peningkatannya yang luar biasa mulai merobek tubuh makhluk itu. Sisik abu-abunya yang tebal mulai terbelah akibat pukulan bertubi-tubi.
Tentu saja, Naga Kecil tidak hanya berdiri di sana dan menerimanya.
Cakar, tungkai, ekor, dan taring menyerang dengan kombinasi yang ganas. Serangan yang tak mampu kami hadapi secara langsung. Yuno dan aku terus menghindar dengan ketat, memotong tepat di luar jangkauan serangan. Mithra bersiap di depan, menangkis serangan terburuk dengan kekuatan penuh, melawan balik laju monster itu.
Dari belakang, mantra-mantra Shifu mulai diluncurkan—pilar-pilar api, pusaran angin yang dipenuhi panas dan tekanan. Api itu mengalir deras dengan kekuatan yang mengesankan.
Belum lama sejak terakhir kali aku melihatnya bertarung, tetapi sihirnya tampak semakin kuat.
Naga Kecil itu tampaknya memiliki ketahanan api yang lumayan, tetapi itu tidak penting. Kedekatan Shifu dengannya—ketepatannya, kendalinya—memastikan serangannya tetap berhasil.
Ia dan Izumo telah berhenti menyebarkan elemen mereka ke seluruh papan. Mereka kini fokus—api dan angin, terjalin menjadi rentetan serangan berlapis. Berhasil.
Kita berhasil melakukannya.
Kami melawan Naga Kecil. Dan mempertahankan posisi kami.
“Raungan? Bukan—itu serangan napas!” Peringatan Abelia terdengar dari belakang. “Mundur semua!!!”
Dia mengawasi seluruh lapangan. Berkat itu, kami semua bisa tetap fokus pada peran masing-masing tanpa takut dikejutkan.
Kami mundur cepat, melepaskan tembakan penekan untuk mengulur waktu saat kami mengubah posisi.
Sedetik kemudian, Naga Kecil itu mundur dan melepaskan semburan api raksasa, seolah-olah melemparkan batu besar yang menyala langsung ke bumi. Ia menghantam tanah tepat di depan, meletus dalam gelombang panas yang meleleh dan bergulung ke arah kami bagai gelombang api pasang.
Kotoran!
Penghalangnya mungkin takkan kuat. Kita akan terbakar.
Tekanan di udara berubah saat Shifu mati-matian menyuntikkan lebih banyak mana ke dalam penghalang. Ia melangkah ke sampingnya, memaksanya kembali ke arah kobaran api.
“Tidak, Shifu! Jangan berhenti menyerang—kami butuh senjatamu!!!” teriak Mithra dengan suara tajam.
“Mithra?!”
Dia melangkah maju, tepat di depan api, matanya berkobar penuh keyakinan. Dia akan melakukan sesuatu.
“Terus tekan! Jangan menyerah—kita akan hancurkan mereka di sini!” teriak Mithra, mengangkat pedang besarnya ke atas.
Dia menjatuhkannya dalam lengkungan penuh—langsung menembus penghalang dan menuju ke arah tembakan yang datang.
“Momen ini milikku—Di Valier!!!”
Keahliannya memicu gelombang kekuatan. Sebuah teknik yang belum pernah kudengar sebelumnya.
Begitu diaktifkan, semburan api itu membelok tak wajar, menyedot ke arah pedang Mithra. Api itu lenyap ke dalam logam seolah telah dilahap.
Tidak, ia telah menyerapnya. Dan bilah pedang itu—kini bersinar, membara merah membara, ditenagai oleh napas yang seharusnya memusnahkan kami.
Apakah kamu bercanda?!
Dia baru saja memakan napas naga dan mengubahnya menjadi senjata?
“Apa-apaan, Mithra-senpai?! Kapan kamu membuka benda sehebat itu?!” teriak Yuno, matanya terbelalak.
“Gila! Kalau begitu aku selanjutnya!” Daena menyeringai, sudah menggumamkan sesuatu dalam hati.
“Aku mulai lagi gipsku!” teriak Shifu, sudah kembali bekerja.
“Aku sudah menutupi penghalangnya—jadilah liar!” Abelia menambahkan, suaranya tenang namun cepat.
“Aku akan mengunci pergerakannya!” teriak Izumo.
Saat mereka memastikan napas telah hilang, semua orang kembali beraksi.
Mantra Daena selesai beberapa saat kemudian, dan aura hijau lembut menyelimutinya—awalnya samar, lalu semakin dalam menjadi cahaya hijau yang terang. Kehadirannya semakin intens. Tekanan terpancar darinya bergelombang. Dia telah menambahkan peningkatan tambahan di atas kondisinya yang sudah overclock?! Kekuatan tekad dan ketangguhan fisik yang dibutuhkan untuk menghadapinya sungguh tak nyata.
“Ini jurus spesialku yang sesungguhnya! Aku menyebutnya—Tahap Dua!”
Oke, nama itu memang jelek. Tapi efeknya gila.
“Bodoh banget—tapi keren banget! Ughhh, aku masih belum bisa ngelakuin hal kayak gitu!” rengek Yuno sambil mengejarnya, nggak kuat nahan kecepatan larinya.
Sejujurnya, mustahil kita bisa menandingi kecepatan seperti itu. Tanpa membakar segalanya.
Daena, sebaiknya kau tahu apa yang kau lakukan, pikirku. Gerakannya itu seperti “ledakan jangka pendek”. Kalau dia tidak segera menyelesaikannya, dia akan kelelahan parah.
Aku maju, mengejar Yuno tepat saat Mithra dan Daena menerobos masuk. Sosok mereka kabur, sudah melancarkan serangan. Aku melirik Yuno.
Dia juga sudah berubah.
Bukan hanya teknik tombaknya. Ada sesuatu yang berbeda dari cara dia bergerak—cara dia menggunakan seluruh tubuhnya. Lebih luwes dan terintegrasi. Dia tidak lagi terpaku pada senjatanya. Lengan, kaki, koordinasi seluruh tubuh—dia menggunakan segalanya. Satu orang lagi yang akan dia hadapi di pertarungan berikutnya.
Ledakan-ledakan!
Dua ledakan keras membelah udara di dekat Naga Kecil. Angin berderak dan meledak bagai guntur.
Izumo.
Mantra supresinya bukan sekadar suara bising. Mantra itu kini memiliki daya gigih—daya henti yang sesungguhnya. Dia bukan lagi orang yang dulu mengandalkan bilah angin dan trik tekanan dasar. Persenjataannya telah meningkat, dan itu terlihat jelas.
Jika itu dapat mengenai Naga Kecil, itu dapat mengenai siapa pun di antara kita dengan mudah.
“Dan Ousa Liberuno… Aerial!!! Aku berhasil!” teriak Izumo. “Semuanya—ini kesempatan kalian!”
Ia telah menciptakan lingkaran mantra penuh di bawah kaki Naga Kecil—lingkaran mantra yang rumit, dijalin dengan sihir angin yang dibalut kilauan hijau. Saat mantra itu aktif, angin menderu ke atas dari bumi, melilit Naga Kecil dalam spiral yang melilit dan menghancurkan.
Anggota tubuhnya meronta-ronta tak berdaya, hanya bergerak lamban dan putus asa. Tak ada serangan balik yang berarti. Tak ada gerakan mengelak. Ia terbuka lebar.
Itu dia.
“Raaaaaaah!!! ” Mithra meraung, mengayunkan pedang besarnya yang berkobar api membentuk lengkungan menyapu tepat ke kaki monster itu. Pedang merah membara itu mengiris dalam—membelah otot, membakar kulit dan urat. Udara dipenuhi bau menyengat daging hangus.
“Gyeeiiiie!!! ” teriak Naga Kecil—tak lagi menantang, tak lagi tenang. Jeritan itu penuh kesakitan. Tapi ia masih membeku, terperangkap mantra Izumo. Lalu—secepat awalnya—jeritan itu terputus.
“Cukup dengan jeritanmu yang menyebalkan itu.” Suara Abelia dingin dan tegas. “Jangan ada lagi auman atau serangan napas.” Panahnya telah tepat sasaran, menembus tepat ke mulut Naga Kecil yang terbuka. Ia tergantung di sana—setengah megap-megap, setengah membeku—pita suaranya terjepit dari dalam.
Tidak ada anak panah biasa—yang terkena sihir atau tidak—yang dapat menembus kulit naga.
Itu pasti teknik barunya.
Dengan serangan terakhir itu, aku tahu pertarungan telah usai. Saat aku menebas Naga Kecil itu berulang kali, sebagian diriku sudah tersenyum.
Suara Shifu menggema—tenang, namun tajam menembus medan perang. “Semuanya… Aku akan melempar yang besar. Mundur, oke?”
Di belakangku, aku bisa merasakan udara terdistorsi oleh aliran mana yang deras. Aku tak perlu berbalik. Cukup mengangguk, lalu bergerak. Mithra dan aku langsung menjauh. Daena berlari kecil melewati kami sambil menyeringai, bersiul riang seolah-olah sedang jalan-jalan. Yuno berlari kecil di belakangnya, menggumamkan sesuatu tentang “jangan mati karena tembakan teman.”
Mata semua orang otomatis tertuju ke atas—termasuk mataku. Di atas kami melayang sebuah batu besar, seukuran Naga Kecil itu sendiri. Melihatnya melayang saja sudah mengesankan.
Dia menyalurkan kekuatan elemen tanah yang luar biasa besar. Tapi aku juga bisa merasakan mana api yang kuat mengalir melaluinya.
Tunggu—apa dia merapal keduanya sekaligus?! Mantranya sudah dirapalkan, aktivasinya sedang berlangsung. Aku bahkan tidak tahu dia memanggilnya apa.
“Sihir roh dan fusi elemen,” seru Shifu. “Api terkuatku saat ini. Rasakan ini!!!”
Api?Di mana— Lalu aku melihatnya. Bongkahan batu besar itu menjulang lebih tinggi lagi, sampai kami harus menjulurkan leher agar tetap terlihat. Dan kemudian, dari intinya ke luar, batu itu mulai bersinar merah.
Anda pasti bercanda.
Sihir apinya memanaskan batu besar itu dari dalam, sementara roh bumi menahannya. Bahkan dari tanah, kami bisa merasakan panasnya memancar ke bawah. Batu itu tidak terbakar. Ia mencair.
“Yo—Izumo! Penghalang, sekarang!!!”
“Y-Yap! Di atas!”
“Aku tidak peduli apa pun maksudnya, Kak—jangan libatkan aku dalam hal itu!” teriak Yuno sambil berlari lebih cepat.
Bongkahan batu cair itu jatuh, menderu ke arah Naga Kecil yang terjepit seperti bintang yang dijatuhkan dari orbit. Sebuah benturan yang dalam dan dahsyat, gelombang kejut menghantam kami bahkan menembus penghalang yang baru saja diangkat. Panas menggulung kulit kami dalam gelombang. Bahkan dengan perisai yang terpasang, panasnya membakar udara di sekitar kami.
Saat aku membuka mata, Naga Kecil itu sudah mati. Aku bahkan tak perlu bertanya; kau bisa merasakannya. Secara teknis, sebagian tubuhnya masih terlihat seperti naga, tentu—tapi hanya sedikit. Kau harus menyipitkan mata.
Kami berdiri di sana dalam keheningan yang tertegun selama beberapa detik.
“Shifu. Jangan pernah mengarahkan itu ke orang lain,” kata Abelia datar.
“Kau berjanji kita akan bicara sebelum menggunakan benda seperti itu,” imbuh Yuno sambil mendesah lelah.
Itu cukup untuk memecah keheningan. Seketika, semua orang menghela napas—dan bersamaan dengan itu, ketegangan meninggalkan tubuh kami. Dan sebagai gantinya, gelombang kepuasan. Beban di dada kami terangkat.
Aku tak dapat mengingat kapan terakhir kali aku merasakan pertumbuhanku sendiri sejelas dan sejelas saat ini.
Kami menang.
Lebih dari itu, kita mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Semua rasa frustrasi, semua rasa malu karena dipermalukan oleh hal ini… telah hilang. Kita bisa melangkah maju lagi. Hadapi festival sekolah dengan kepala tegak. Berdiri tegak sebagai murid-murid Raidou-sensei.
“Masih terasa seperti Shifu mencuri seluruh akhir cerita,” gumam Daena sambil menyeringai miring, mengangkat bahunya.
“Aku belum sampai di sana,” jawab Shifu lembut. “Aku terus merapal mantra, dan aku masih mengacaukan mantranya lebih dari sekali. Nyaris tidak berhasil. Sejujurnya, menggunakannya di tengah pertarungan seperti itu terlalu gegabah.”
Kalau itu yang disebutnya belum siap, aku bahkan tak mau memikirkan performa akhirnya. Intinya, aku juga merasakan hal yang sama. Aku tidak memimpin tim ini—aku hanya berusaha mengimbanginya.
“Hei, Jin. Sepertinya kepalanya masih utuh. Ayo kita ambil tanduk dan beberapa taringnya. Mungkin beberapa sisik, kalau bisa diselamatkan.”
“Ide bagus!”
Mengikuti jejak Daena, saya berlari kecil untuk mengklaim trofi kami.
“Eh, bukan matanya—itu sudah ditembak. Sepertinya mendidih dari dalam. Tanduknya sebagian besar masih utuh. Tapi taringnya? Ya, kelihatannya kurang bagus. Soal sisiknya… Mungkin ada beberapa yang bisa diselamatkan,” gumamku, berjongkok di samping mayat yang masih mengepulkan asap.
“Jangan langsung bawa ini ke toko di Rotsgard,” saran Mithra datar. “Kalau sampai ketahuan, bisa kacau nih. Lebih baik kembali ke akademi dulu, lalu diam-diam menjualnya di kota lain. Biaya transfernya sepadan—dan aku nggak mungkin jalan kaki sekarang.”
Sulit untuk membantahnya. Tak satu pun dari kami punya energi untuk pergi ke kota guild terdekat, terutama setelah pertarungan ini. Pilihan terbaik kami adalah menggunakan item pengembalian, teleportasi kembali ke kampus, lalu langsung pindah ke kota acak untuk menjual barang-barang tersebut. Kami bahkan bisa mengirim salah satu dari kami sendirian—lebih sedikit perhatian, lebih hemat biaya.
“Juga, Mithra-senpai, gerakanmu itu? Ketika kamu baru saja”Showm , menahan serangan napas itu? Gila banget!”
“Oh, itu. Di Valier. Ternyata aku mempelajarinya kemarin sebagai Keahlian Unik,” jawab Mithra sambil menggaruk pipinya seolah itu bukan masalah besar.
“Tunggu, apa?! Skill Unik?! Luar biasa!” Mata Yuno terbelalak takjub.
Yah, tidak heran. Keahlian Unik itu langka sekali—sesuatu yang hanya bisa didapatkan oleh petualang papan atas atau veteran ksatria setelah bertahun-tahun berusaha. Dan Mithra baru saja mendapatkannya saat masih menjadi murid.
Sialan dia.
Aku tahu dia berorientasi bertahan, tapi tetap saja. Itu tidak adil.
“Itu membuatku menyerap kerusakan yang tidak mematikan dan mengubahnya menjadi dorongan untuk menyerang atau bertahan,” jelasnya dengan tenang.
“Itu tidak hanya berguna, itu pada dasarnya adalah penangkal steroid,” kata Abelia, matanya menyipit.
“Tapi ada kendalanya…” Suara Mithra melemah.
Jeda itu mencurigakan.
“Tangkapan?” tanyaku.
“Itu tidak meniadakan kerusakan. Itu hanya… menundanya,” akunya.
“Permisi?”
“Kamu bahkan tidak terluka,” kata Yuno.
“Ya, tapi tunggu sekitar tiga puluh menit. Nanti kena. Mungkin nanti aku bakal kena luka bakar parah. Haha…”
“Anda Bodoh! Abelia meledak. “Kau begitu saja menjatuhkannya begitu saja pada kami sekarang?! Itu tidak menyerap—itu hanya menunda rasa sakit!”
“Heh. Mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanannya,” jawab Mithra sambil tersenyum seolah-olah semua ini biasa saja.
Jadi, bahkan Keterampilan Unik yang sangat langka pun ada harganya. Memang tidak ada kemampuan yang sempurna. Figur.
“Jin, Daena—cepat kumpulkan! Mithra bakal hancur sebentar lagi, dan kita harus pindah!” bentak Abelia, sudah menguasai situasi.
Saat aku berlari kecil menghampiri, Daena menatapku dengan tatapan setengah jengkel, setengah lega, lalu bergumam cukup keras hingga kudengar, “Sejenak kupikir Mithra benar-benar meninggalkanku, tapi ternyata aku tidak terlalu jauh di belakang. Dan jika skill barunya yang canggih tidak memblokir damage instan, maka dia tidak jauh berbeda dari kita semua. Maksudku, jika mantra terakhir Shifu mengenainya secara langsung, dia pasti akan tamat.”
“Kamu luar biasa, Daena. Sungguh…” Aku tertawa sinis dan mengangkat bahu. “Rasanya agak kecewa karena aku tidak berkontribusi banyak.”
Kata-kata itu keluar lebih mudah dari yang kuduga. Mungkin karena itu Daena. Mungkin karena aku percaya dia akan mengerti.
Harus bekerja lebih keras. Berusaha lebih keras lagi.
Kalau aku terus mengejar Raidou-sensei dengan sekuat tenagaku, tidak mungkin aku sudah mencapai batasku.
“Kau serius berpikir begitu?” tanyanya tak percaya. “Kau mengayunkan dua pedang panjang seolah tak ada apa-apanya, dan kau bilang kau tidak berbuat banyak? Aksi seperti itu, tanpa keahlian khusus atau trik canggih—itulah yang kami sebut monster, Jin.”
Monster, ya.
Dalam situasi yang berbeda, aku mungkin akan marah mendengarnya. Tapi saat itu juga—rasanya seperti pujian tertinggi yang bisa diberikan siapa pun kepadaku.
“Maksudku, dibandingkan dengan yang lain… aku hanya menambahkan satu pedang lagi dan bertarung sedikit lebih mencolok. Masih terasa cukup jinak.”
“Kau menggunakan sihir pendukung, pengembangan diri, dan penggunaan dua senjata seperti ritme giliranmu yang biasa, dan kau sebut itu jinak? Serius, semua orang punya dorongan luar biasa untuk berkembang—sebenarnya ini cukup menginspirasi. Ugh. Aku jadi bersemangat lagi.”
Saya hanya mengambil pedang kedua karena terasa alami—serangan ganda, keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Tidak ada logika yang mendalam di baliknya. Hanya insting.
Jika itu masih membuatku terlihat cukup kuat untuk disebut monster… maka mungkin aku telah melangkah lebih jauh dari yang kukira.
“Heh. Sampai jumpa di semester kedua, Daena.”
“Kembali padamu. Dan ya, kita harus mendorong Kadal Biru itu untuk serius juga.”
Tidak diragukan lagi.
Saat ini, kami berdiri di jalan yang lurus dan terbuka.
Semakin kita berjalan, semakin jauh kita pergi.
Semakin banyak kami berlari, semakin cepat kami bergerak maju.
Jauh, jauh di depan—ada dua bayangan. Raidou-sensei dan Shiki. Selalu di luar jangkauan, tak pernah membiarkan kami mengejar, tapi tetap membimbing kami maju.
Lebih kuat. Aku ingin menjadi lebih kuat.
Aku ingin terus menapaki jalan ini selama yang kubisa. Keinginan itu—hal yang selama ini kukejar tanpa sepenuhnya kupahami—akhirnya menjadi sangat jelas di benakku. Aku penasaran, sejauh mana kita bisa menunjukkan perkembangan kita kepada Sensei selama festival akademi nanti.
Setelah tanduk, taring, dan sisik Naga Kecil dikemas, kami kembali ke akademi. Kami membawa pulang lebih dari sekadar penghasilan tak terduga—kami membawa pulang sesuatu yang tak ternilai harganya.
Penyesalan bersama, penebusan dosa yang diperoleh dengan susah payah, dan ikatan yang hanya terjalin dari hampir mati bersama.
Itu adalah akhir musim panas pertama kami sejak bertemu Raidou-sensei.
※※※
Sebidang tanah sempit terbentang di antara wilayah manusia dan kaum iblis—sebuah celah rapuh di antara dua kekuatan besar. Di sepanjang jalan tanah yang sepi di tanah tak bertuan ini, seorang perempuan dan seorang anak berjalan berdampingan.
“Pahlawan, iblis, perang… Dunia memang tak pernah melambat, kan?” gumam wanita itu, nadanya ringan namun mengandung sesuatu yang tajam di dalamnya.
Anak laki-laki itu menoleh ke arahnya, suaranya rendah dan datar. “Ada apa ini? Jangan bilang kau tiba-tiba diliputi rasa iba atas nyawa yang hilang dalam perang. Itu tidak seperti dirimu.”
Dia mengangkat bahu sedikit, rambut birunya menangkap sinar matahari yang berayun di belakangnya. “Sama sekali tidak. Aku hanya berpikir betapa semua kekacauan ini ternyata cukup menguntungkan kita.”
“Heh. Benar juga. Selain pertengkaran dengan Raidou tadi, semuanya berjalan sesuai rencana.”
“Raidou…
Perempuan itu, dengan rambut biru mencolok dan pedang besar yang diikatkan di punggungnya, memiliki sikap seorang petualang kawakan. Sebaliknya, anak laki-laki itu tampak sama sekali tak bersenjata dan tanpa baju zirah. Namun, dari cara mereka bergerak, irama percakapan mereka—jelas mereka bukan keluarga. Bukan wali dan anak. Mereka adalah kawan. Setara dalam tujuan, meskipun tidak dalam penampilan.
“Dengan kekuatanmu sekarang, bahkan Raidou tidak akan menjadi tantangan besar, kan, Sofia?”
“Sebaiknya tidak,” jawabnya dingin. “Demi dia—dan demi kamu, Mitsurugi.”
Sofia, sang Pembunuh Naga. Dan Mitsurugi, sang Naga Besar yang konon pernah dibunuhnya.
“Tetap saja,” katanya sambil sedikit mengernyit, “kenapa kita malah menuju ke zona mati seperti itu?”
Matanya menyipit karena curiga saat dia melirik Mitsurugi, yang berjalan dengan tangan di belakang punggungnya, tenang seperti biasanya.
“Sulit untuk memastikannya,” jawabnya. “Tapi belum lama ini, aku menangkap jejak samar keberadaan Luto di area ini. Jejak itu langsung hilang… tapi kupikir perlu diselidiki.”
“Luto? Baiklah. Itu alasan yang cukup. Aku hanya berharap kita tidak membuang-buang waktu untuk urusan yang sia-sia. Kalau ada waktu luang, kita harus mengumpulkan informasi tentang Shin—atau bersiap menghadapi Sazanami.”
“Untuk melacak Shin, kita harus pergi ke alam liar dari Tsige. Medannya tidak mudah. Sazanami berikutnya. Aku punya petunjuk tentang cara kita bisa masuk ke Gurun Putih.”
Nada bicara Mitsurugi tenang dan apa adanya.
Shin. Sazanami.
Keduanya adalah Naga Besar seperti dirinya. Namun Sofia telah terang-terangan berbicara tentang membunuh mereka—dan Mitsurugi tidak membantahnya. Malahan, ia melanjutkan diskusi dengan tenang.
Seekor Naga Besar berencana membunuh kaumnya sendiri.
“‘Sekutu’ yang kau sebutkan di dalam Kekaisaran itu… Itu berkat mereka, ya? Lumayan,” kata Sofia, dengan nada setuju dalam suaranya.
“Lagipula, rumah lamaku berada di dalam wilayah kekaisaran. Aku masih punya beberapa koneksi. Seorang hyuman yang pernah kuampuni, misalnya.”
“Kamu? Mengampuni seseorang?”
“Kadang-kadang kalau mereka tidak layak diburu. Tergantung suasana hatiku.”
Dia tersenyum tipis, seolah-olah itu bukan apa-apa. “Pokoknya. Setelah kita selesai di sini, mari kita lakukan persiapan terakhir. Lalu kita akan memburu nenek sihir Gront, si Gelombang Pasir.”
Sofia menyeringai, matanya berbinar. “Kedengarannya sempurna. Aku sudah menantikannya.”
Mitsurugi melirik ke depan, lalu memiringkan dagunya ke arah cakrawala.
“Seharusnya ada desa di dekat sini. Bagaimana, Sofia? Mau mampir?”
“Sebuah desa, ya…
“Lumayan besar untuk wilayah ini. Agak tidak biasa, sih. Bahkan ada cabang Guild Petualang. Namanya Bilroan.”
Mendengar nama itu, Sofia berhenti sejenak. Hanya sesaat, tapi jelas. Lalu, seolah tak terjadi apa-apa, ia kembali berjalan.
“Kita tidak perlu berhenti,” serunya. “Aku punya firasat di mana tempat yang kita cari. Ayo kita pergi.”
“Hah? Uh, benar juga…” Alis Mitsurugi berkerut. “Tapi tunggu dulu—kenapa kau begitu mengenal daerah ini? Kau pernah ke sini sebelumnya?”
Sofia memang tak biasa melewatkan kesempatan minum, apalagi ada cabang guild di dekat sini. Sikapnya yang tiba-tiba ingin menghindari desa dan caranya bercerita tentang tujuan mereka—rasanya aneh.
“Aku pernah berburu chimera di hutan di depan sana,” katanya santai. “Yang aneh, dengan lengan manusia tumbuh di seluruh punggungnya.”
Mitsurugi mengerjap, matanya menajam karena menyadari sesuatu. “Tangan di punggungnya… Itu pasti Chimera Spellhand. Binatang penjaga tingkat atas, biasanya ditempatkan untuk melindungi bengkel penyihir.”
“Kedengarannya benar. Hampir saja aku mati. Jadi… itu kan bengkel Luto.”
“Tunggu—bengkel? Kau pergi ke sana? Yang lebih penting, apa maksudmu dengan ‘hampir membunuhmu’? Memang, Spellhand itu monster yang tangguh, tapi seharusnya kau tidak kesulitan menghadapinya.”
“Aku sendirian,” katanya, suaranya berubah lembut dan jauh. “Dan seorang anak. Dua belas tahun… atau mungkin tiga belas tahun saat itu? Aku sudah tidak ingat lagi.”
“Jujur saja, sungguh ajaib kau selamat,” gumamnya sambil mengembuskan napas. “Kau memang selalu punya sifat nekat, ya?”
Senyum kecil miring menyentuh bibirnya.
“Ya. Kurasa begitu. Aku jadi liar waktu itu. Dengan caraku mengobrak-abrik tempat itu, mungkin tak ada yang tersisa.”
“Kita hanya harus berharap yang terbaik.”
“Aku akan memimpin. Ikuti aku.”
Dengan itu, mereka pun melupakan pokok bahasan itu.
Tepat seperti yang Sofia nyatakan, mereka tak melirik desa itu sedikit pun. Melewati lahan pertanian, mereka berdua menuju hutan yang menempel di kaki gunung.
“Jadi, perburuan chimera kecilmu itu sebenarnya membuka jalan bagi semua lahan pertanian ini, ya?” Mitsurugi berkomentar, sambil melirik ke arah ladang-ladang yang sudah ditanami.
“Dulu di sini hutan semua. Masuk akal,” jawabnya sambil mengangkat bahu.
“Tapi sepertinya mereka tidak bisa membersihkan semuanya. Mulai sekarang, hutan lagi. Aku sudah bisa merasakan monster di dekat sini.”
Sofia melangkah maju, matanya tertuju pada barisan pepohonan yang menjulang tinggi.
“Bengkel yang saya temukan ada di sini.”
Dia memasuki hutan tanpa keraguan sedikit pun, meskipun kanopi hutan menimbulkan kesuraman yang berat, cukup tebal untuk menghalangi cahaya siang hari.
Bukan karena jalannya familiar. Melainkan karena apa pun yang keluar dari hutan itu, ia yakin ia bisa menghancurkannya. Keyakinan itulah satu-satunya penuntunnya.
“Hanya ini?”
“Kurang lebih,” jawab Sofia sambil menatap ke seberang lahan terbuka kecil itu. “Kalau ingatanku benar, bengkelnya dulu ada di sini.”
Tak ada yang tersisa selain beberapa tunggul di tempat pepohonan dulu berdiri. Lahan terbuka itu terasa terlupakan, terhapus. Namun—
“Hmph. Ingatanmu itu lumayan juga. Masih ada penghalang di sini—masih aktif, bahkan sekarang. Terselubung,” kata Mitsurugi.
“Sudah kuduga. Bisakah kamu masuk sendiri?” tanya Sofia.
“Tentu saja.”
“Kalau begitu aku akan menunggu di sini. Kalau kamu menemukan sesuatu yang menarik, beri tahu aku.”
“Baiklah. Aku tidak akan lama.”
Setelah menggumamkan mantra singkat, Mitsurugi berjalan perlahan di sekitar lapangan terbuka. Ia berhenti tiba-tiba, lalu menyelinap tanpa suara menembus udara kosong—menghilang melalui pintu tak kasat mata, bagaikan tinta yang tenggelam ke dalam air.
Bengkel… Tempat di mana semuanya bermula bagiku, bisik Sofia begitu ia sendirian. Ia duduk di salah satu tunggul pohon, menghela napas pelan.
Aku penasaran… Anak itu—apa yang dia lakukan sekarang? Mungkin sedang menjaga desa atau semacamnya…
Hutan di sekelilingnya masih lebat dan gelap, jenis hutan yang menelan sinar matahari. Namun di sini, di tempat terbuka itu, berkas-berkas cahaya tipis menembus pepohonan, menyelimuti ruang itu dengan ketenangan yang redup dan tak nyaman. Tidak terlalu terang—tetapi cukup jernih untuk mengamati sekeliling. Dan cukup sunyi untuk diingat.
Sofia memberi dirinya waktu langka untuk merenung.
Ia tak pernah mengenal orang tuanya. Dibesarkan di desa kecil yang telah menampungnya, masa kecilnya diwarnai oleh darah dan pertempuran. Sejak ia bisa berjalan, ia dipaksa melawan monster-monster yang mengintai di hutan. Ia selalu kuat. Terlalu kuat. Dan kekuatan itulah yang telah mengubah nasibnya sejak awal.
Ia masih balita ketika kejadian pertama terjadi—ketika ia tak sengaja meremukkan pergelangan tangan perempuan yang merawatnya. Setelah itu, penduduk desa menjaga jarak. Namun, mereka tak bisa mengabaikan kekuatannya. Mereka melihatnya sebagai aset, bukan seorang anak. Maka, mereka menjadikannya perisai desa.
Demi-human, binatang buas, atau monster apa pun yang berani menyerang—mereka semua tumbang di hadapannya. Luka yang dideritanya seringkali parah. Namun, sedalam apa pun lukanya, yang ia dapatkan hanyalah perban dan perintah tegas untuk bertarung lagi begitu ia bisa berdiri. Ia pulih dengan cepat. Sangat cepat. Tak ada manusia biasa yang sembuh seperti itu.
Tak seorang pun penduduk desa lain pernah bertarung bersamanya. Tak seorang pun mencoba. Ia bertarung sendirian. Tapi itu sepertinya tak pernah mengganggunya. Ketika ia tak mampu menyelesaikan sesuatu, yang lain akan mengerumuninya berbondong-bondong. Ia menyadari perbedaan kekuatan mereka, tentu saja. Tapi ia tak pernah terlalu memikirkannya.
Akhirnya, ia percaya bahwa kekuatannya sama sekali bukan manusia. Sesuatu yang asing. Terkutuk. Dan jika ia tak bisa diterima, setidaknya ia akan melindungi. Di situlah tempatnya.
Kemudian, suatu hari, seorang anak laki-laki mulai berkelahi di sisinya.
“Siapa namanya tadi?” gumamnya, matanya menyipit saat ia mencoba menarik ingatan itu keluar dari kabut. “Hmm…
Dia putra bungsu salah satu keluarga terkaya di desa. Sebuah klan pemilik tanah. Dia berbeda dari yang lain. Seperti ibunya, dia punya ketertarikan yang aneh pada pertarungan. Bakat, bisa dibilang. Saat dia berusia sepuluh tahun, tak ada seorang pun tersisa di desa yang bisa menghentikan mereka berdua—terutama di zona perburuan monster di pinggiran kota.
Ia tak pernah takut padanya. Justru sebaliknya—ia mengaguminya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sofia—yang saat itu masih bernama Miranda—merasakan secercah kehangatan. Kebahagiaan yang tenang dan tak pernah ia rasakan sebelumnya.
Tetapi…
“Aku tidak ingat. Sama sekali,” gumamnya, menghela napas frustrasi. “Ah, sudahlah. Sekarang sudah tidak penting. Aku bukan Miranda Bulga lagi.”
Saat itu, ia diutus untuk mengintai sebidang hutan untuk kemungkinan perluasan. Para tetua yakin hutan itu bisa dibuka untuk lahan pertanian, tetapi insting Sofia mengatakan ada sesuatu yang berbahaya mengintai di sana. Anak laki-laki itu, seperti biasa, mencoba mengikutinya. Ia menepisnya, sengaja membuatnya tersesat di antara pepohonan.
Dia ingin pergi sendiri.
Sayangnya, ia ternyata lebih cerdik daripada yang dipikirkannya. Alih-alih mengikuti, ia malah berputar di depan—menunggu wanita itu langsung masuk ke dalam penyergapannya. Bahkan ketika wanita itu menyuruhnya kembali, ia tak mau mendengarkan. Maka, mereka berdua pun menjelajahi hutan bersama hari itu.
Hingga saat itu, penyelidikannya hanya menimbulkan kegelisahan yang samar dan samar. Namun malam itu… ia membuat kesalahan dengan lengah—hanya sesaat.
Dia membiarkan dirinya rileks—sedikit saja—terbungkus dalam kehangatan asing yang hanya dirasakannya saat anak laki-laki itu berada di sampingnya.
Saat itulah semuanya terjadi. Mereka bertemu.
Chimera yang pernah dibicarakannya kepada Mitsurugi—makhluk mengerikan dengan tangan manusia yang menggeliat di punggungnya.
Anak laki-laki itu langsung jatuh, terhantam pukulan pembuka makhluk itu. Tak sadarkan diri dan tak berdaya. Dan menghadapi sesuatu yang jauh melampaui level apa pun yang pernah ia lawan sebelumnya, Sofia tetap teguh pada pendiriannya. Ia bertarung dengan sekuat tenaga, melindungi anak laki-laki itu dengan tubuhnya, setiap serangan dipicu oleh keputusasaan.
Lalu… dia mendengar suara itu.
Suara itu datang dari jauh di dalam hutan. Sebuah suara yang hanya bisa didengarnya—berbisik, memerintah. Dan tanpa tahu mengapa, ia menurut. Ia melepaskan kekuatan yang tersembunyi di dalam dagingnya, membuka sesuatu yang kuno dan ganas. Dan ketika pikirannya mulai memahami siapa dirinya sebenarnya, pedangnya mencabik chimera itu dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa.
Pada saat itu, Sofia merasakannya.
Makhluk di hadapannya—monster yang hampir membunuhnya—tidak kuat. Ia lemah.
Chimera yang sama yang beberapa detik sebelumnya mengunggulinya kini terasa tak lebih dari sekadar gangguan. Ia tak tahu apakah perubahan itu berasal dari suara itu, kekuatan itu, atau kebenaran yang baru mulai ia pahami—tetapi hasilnya jelas.
Kekuatan membanjirinya. Kekuatan itu meledak dari suatu tempat yang dalam, kasar, dan tak terbatas. Dan tak lama kemudian, chimera itu tak lebih dari tumpukan daging yang berkedut dan terpotong-potong.
Pertarungan berakhir dalam keheningan. Dan dalam keheningan itu, Miranda Bulga mengerti.
Seandainya ia hanyalah seorang yatim piatu yang tertinggal di desa perbatasan yang terlupakan, betapa lebih mudah—betapa lebih bahagia—hidupnya nanti? Namun, kenyataan hidupnya tak menawarkan kenyamanan seperti itu. Rasanya aneh, tak wajar, dan salah.
Dia tidak bisa menahan tawa.
Ia teringat fantasi-fantasi yang dulu ia khayalkan, semasa muda. Mimpi-mimpi yang mungkin—mungkin saja—kekuatan di dalam dirinya menandainya sebagai orang terpilih, seorang pahlawan dengan takdir gemilang.
Lucu sekali.
“Aku tidak dipilih untuk apa pun,” gumamnya pada pepohonan. “Aku bukan pahlawan yang dianugerahi para dewa. Aku istimewa, tentu. Tapi bukan dalam hal yang berarti.”
Setelah pertempuran, dia mengikuti kenangan yang terukir di otaknya—kenangan yang tidak terasa seperti miliknya, namun menuntunnya tanpa ragu menelusuri hutan.
Di sana, tepat seperti yang dijanjikan suara itu, ia menemukan reruntuhan sebuah bengkel. Dan di dalamnya… ia menemukan namanya.
Atau lebih tepatnya, apa yang dikiranya adalah namanya.
Sofia—itu bukan miliknya. Itu nama direktur fasilitas itu. Identitas asli yang mereka tinggalkan untuknya hanyalah serangkaian karakter. Sebuah kode.
Suatu produk.
Miranda Bulga, gadis yang pernah berjuang melindungi desa yang tak pernah menyambutnya, berdiri di hadapan sisa-sisa asal-usulnya dengan senyum getir yang membeku di wajahnya. Tawa dan duka bercampur aduk saat ia menatap huruf-huruf yang terukir di dinding yang dingin.
Dia bukan Miranda lagi. Tidak setelah itu.
Jadi, dia mengambil nama yang pada awalnya bukan miliknya dan mengukirnya di dalam dirinya.
Sofia.
Setidaknya, dia tidak bisa lagi menjadi gadis itu.
“Luto, Sang Warna-Warni,” bisik Sofia, suaranya nyaris tak terdengar di bawah gemerisik dedaunan. “Yang terikat pada bengkel ini… yang menjadi sumber kekuatanku. Sang Naga Agung, yang namanya sendiri terukir dalam sejarah.”
Pandangannya terpaku pada pepohonan, tidak benar-benar melihatnya.
Sejak pertama kali bertemu denganmu, tujuanku menjadi jelas: aku akan melahapmu. Dan sekarang… bahkan tujuan itu hanyalah satu langkah lagi di sepanjang jalan. Tunggu saja—Gront, Shin, aku akan melahap kalian berdua, lalu akhirnya aku akan mencapainya…
Saat itu, ia telah mengobrak-abrik bengkel bak badai. Dokumen atau catatan apa pun yang tersimpan, kemungkinan besar telah ia hancurkan dalam amukannya. Kemungkinan menemukan sesuatu yang utuh kini sangat tipis. Mitsurugi pernah bilang patut dicoba, meskipun kemungkinannya kecil. Jika ia kembali dengan kesal, Sofia sudah memutuskan untuk meminta maaf secara halus dan melupakan masa lalunya.
Lagipula, mereka berdua bukan teman. Tidak juga.
Mereka telah menghabiskan cukup waktu bersama untuk disebut pasangan, dan tujuan mereka selaras sempurna—tapi tak lebih. Tak ada rasa percaya, tak ada rasa sayang. Hanya tujuan bersama.
Itulah satu-satunya ikatan di antara mereka. Itulah sebabnya, bahkan sekarang, Sofia tetap sendiri. Ia tak pernah membiarkan siapa pun memasuki hatinya. Sekali pun tidak.
“Hah… kalau dipikir-pikir,” gumamnya dalam hati, alisnya berkerut, “bagaimana aku dan anak itu bisa berpisah? Dia tidak mati saat melawan chimera, aku yakin itu… jadi…?”
Kenangan itu—yang dulu begitu nyata—telah memudar begitu jauh hingga ia tak mampu lagi memahami garis besarnya. Satu-satunya orang yang pernah menunjukkan kehangatan manusiawi yang sesungguhnya telah lenyap dari benaknya bagai kabut.
Sofia sang Pembunuh Naga telah lama berhenti berusaha memahami orang lain atau berusaha dipahami. Ia mengasah kekuatannya yang luar biasa dalam kesendirian, mengejar hasrat yang lahir dari kedalaman sesuatu yang gelap. Setiap rintangan yang ia hadapi ditebas tanpa ampun, dan hanya sedikit musuhnya yang diingat.
Semua kecuali satu.
Satu-satunya orang yang benar-benar telah mengalahkannya—Raidou, pria misterius yang mereka sebut Si Jahat.
Ia menghela napas, menepis pikiran itu. “Sudahlah, tak ada gunanya merenung. Untuk saat ini, memburu Naga Besar dan membereskan Raidou adalah prioritas.”
Dia berdiri, meregangkan badan sedikit, saat indranya mulai tergelitik.
“Saat ini… Mitsurugi seharusnya keluar dengan sisa-sisa apa pun yang bisa dia temukan—oh?”
Tepat pada waktunya, Mitsurugi muncul dari pintu masuk yang tersembunyi, membersihkan debu dari jubahnya sambil mendesah berlebihan.
“Sofia! Kau benar-benar mengacaukan tempat itu, ya?! Aku harus mengarungi puing-puing berjam-jam hanya untuk menemukan sesuatu yang bisa digunakan!”
Dia menyeringai tanpa penyesalan. “Maaf, maaf. Aku masih kecil, ingat?”
“Hmph… yah, aku berhasil menemukan beberapa petunjuk. Bisa saja lebih buruk.”
“Seperti yang diharapkan darimu, Mitsurugi. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bersiap untuk perburuan Gront?”
“Belum. Ada panggilan. Yang tidak bisa kita abaikan.”
“Begitu. Lagipula, kita memang berutang pada mereka,” katanya sambil mendesah. “Sebaiknya kita lunasi utang itu.”
“Tepat sekali. Kewajiban terakhir, tidak lebih. Lagipula, kalau kita berurusan dengan hyuman lagi, kita mungkin akan bertemu Raidou.”
Dia terkekeh pelan. “Pasti menyenangkan. Dan hei, kalaupun tidak, kita mungkin bisa bermain dengan salah satu pahlawan. Kedengarannya seperti bahan pemanasan yang bagus.”
“Bicaramu seperti ancaman. Ayo kita pergi.”
“Benar.”
Sofia menatap hutan itu sekali lagi—hutan ini, tempat yang menjadi saksi bisu awal mula hidupnya, tempat yang seharusnya menyimpan nostalgia, penyesalan, atau setidaknya secercah emosi.
Tidak ada.
Karena tidak merasakan apa pun, dia membalikkan badannya, mengikuti Mitsurugi saat keduanya menghilang di balik pepohonan, hanya menyisakan percakapan mereka yang penuh teka-teki menggantung di udara bagai kabut.
Jauh di timur, saat kota akademi mendekati musim gugur dan musim festival semakin dekat, orang yang pernah berselisih dengan Raidou—Sang Pembunuh Naga sendiri—terus tumbuh lebih kuat.
Materi Belakang
Penulis: Azumi Kei
Lahir di Prefektur Aichi. Pada tahun 2012, Kei mulai menerbitkan Tsuki ga Michibiku Isekai Dochu (Tsukimichi: Moonlit Fantasy) secara daring. Seri ini dengan cepat menjadi populer dan memenangkan Penghargaan Pilihan Pembaca di Alphapolis Fantasy Novel Awards ke-5. Pada bulan Mei 2013, setelah revisi, Kei memulai debut penerbitan mereka dengan Tsuki ga Michibiku Isekai Dochu.
Ilustrasi oleh Mitsuaki Matsumoto
http://transparnaut.web.fc2.com/
Buku ini merupakan versi revisi dan terbitan dari karya yang awalnya diposting di situs web “Shōsetsuka ni Narō” (http://syosetu.com/)
Catatan kaki
[←1]
OEDO (お江戸): Sebuah referensi bergaya untuk Edo, nama historis Tokyo pada era samurai. Penulisannya dalam huruf kapital memberikan kesan unik, seperti permainan, atau futuristik, sementara furigana-nya mengingatkan kita pada Jepang klasik.
Terima kasih semuanya
Terima kasih telah menyelesaikan Tsukimichi Moonlit Fantasy Volume 8.5! Semoga Anda menikmati petualangan Makoto yang berkelanjutan di dunia magis ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami!
Untuk membantu kami menghadirkan lebih banyak cerita fantastis, silakan bagikan pendapat Anda di Amazon. Ulasan Anda tidak hanya memberi tahu kami apa yang Anda sukai (atau tidak!), tetapi juga membantu kami memutuskan novel ringan mana yang akan kami hadirkan berikutnya.