Ore wa Subete wo “Parry” Suru LN - Volume 8 Chapter 1




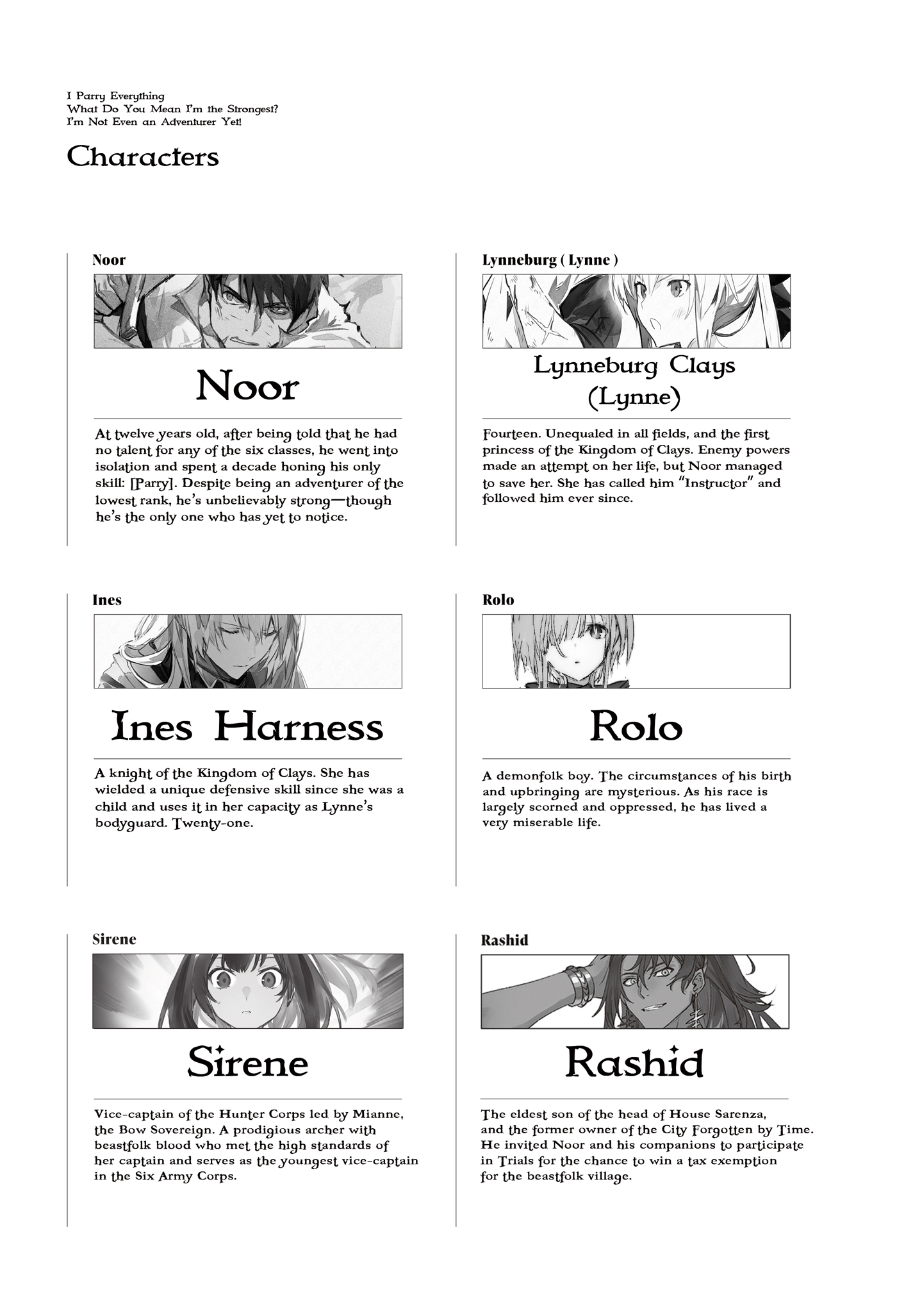
Bab 152: Shawza dan Sirene
“Namamu Sirene, benar? Kamu datang sendirian?”
Rashid, mantan pemilik City Forgotten by Time, tersenyum ramah saat melihat tamunya memasuki ruangan. Ia sudah menduga kedatangannya. Sebaliknya, Sirene harus memberanikan diri untuk mengetuk pintu yang berat itu. Ia tampak terkejut dengan sambutan hangat itu.
“Y-Ya,” jawabnya. “Ini urusan pribadi, bagaimanapun juga. Meskipun aku sudah mendapat persetujuan dari nona.”
“Urusan pribadi, ya? Tapi di mana sopan santunku? Silakan duduk. Apakah kamu minum teh? Kalau ya, daun teh apa yang kamu suka?”
“Apa saja boleh, asal tidak terlalu panas.”
“Kalau begitu, Melissa, tolong siapkan teh terbaik yang kita punya. Ah, dan pastikan cangkirnya berkualitas baik untuk tamu kita.”
“Pak.”
“U-Um… Kau tak perlu bersusah payah seperti itu demi…aku…”
Sirene duduk di sofa yang ditunjuk tuan rumahnya, merasa takut dengan suasana yang menyambutnya. Awalnya, dia tampak terkejut dengan betapa nyamannya sofa itu, tetapi dia segera mengecil dan menatap sekeliling ruangan dengan canggung seolah mencari apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Melissa menyeduh teh dengan cepat, mengamati ketidaknyamanan Sirene dengan pandangan sekilas, dan meletakkan cangkir di depan tamu mereka. “Ini untukmu. Aku sudah mendinginkannya hingga suhu yang nyaman untuk diminum.”
“Terima kasih… Oh, ini benar-benar enak.”
“Saya senang Anda menyukainya,” kata Rashid. “Sekarang, Anda menyebutkan ada urusan di sini?”
Sirene tersentak, mengalihkan perhatiannya dari teh dan aromanya yang menyenangkan. “B-Benar. Um, jadi, yah…” Meskipun si pemburu muda itu berusaha keras untuk menjelaskan alasannya berada di sana, tatapannya merupakan indikasi yang bagus—tatapannya diarahkan langsung ke Shawza.
Rashid tersenyum. Jarang ada tamu yang ia hibur yang begitu mudah dibaca. “Apakah urusanmu dengan Shawza, mungkin?”
“H-Hah? Oh, um… Ya, sebenarnya.”
“Ah, bodoh sekali aku menaruh harapan. Melissa, bagaimana kalau kita keluar? Mereka pasti ingin privasi.”
“Sesuai keinginan Anda, Tuan.”
“Kalau begitu, kami pamit dulu. Silakan santai saja.”
“O-oke. Hmm, terima kasih?”
Dengan lambaian riang, Rashid meninggalkan ruangan bersama Melissa. Sirene dan Shawza saling berhadapan tanpa sepatah kata pun, yang satu sedikit gugup, yang lain tampak agak kesal.
Orang pertama yang memecah keheningan canggung itu adalah pria berjas hitam, yang berbicara dengan suara yang menyerupai geraman pelan. “Apa yang kauinginkan dariku? Katakan saja.”
Sirene meletakkan cangkir tehnya yang kosong tanpa suara, sama ragunya seperti sebelumnya. “Eh, aku… Pertama-tama, aku minta maaf karena ini terlalu tiba-tiba.”
“Jangan salah paham—kamu tidak menyinggung perasaanku. Aku hanya menyuruhmu untuk tidak berbasa-basi dan langsung ke intinya.”
“Sebelumnya, selama Ujian…aku melihat tanda di belakang lehermu. Aku ingin bertanya tentang itu.”
Wajah Shawza berubah menjadi cemberut masam. “Ah. Kau melihatnya?”
“Maaf. Seharusnya aku tidak membicarakannya?”
“Tidak, tidak apa-apa. Aku tidak akan menyangkal bahwa itu ada di sana. Tapi, bagaimana dengan itu?”
“Dulu itu tato, bukan? Tato yang kamu hapus.”
Ekspresi Shawza tetap dingin saat dia berbalik. “Ya.”
“Saya ingin tahu lebih banyak tentang suku yang memiliki tato itu sebagai tandanya,” desak Sirene. “Keluarga saya adalah bagian darinya, tetapi saya tidak tahu harus mulai mencari dari mana.”
Kecurigaan di mata Shawza berubah menjadi kesadaran, lalu ketidakpedulian saat Sirene menyampaikan pendapatnya. Dia menggelengkan kepala. “Jadi, kau salah satu dari kami, ya? Kalau begitu, kurasa aku bisa menceritakan sebagian kejadiannya.”
“B-Benarkah?!”
“Tetap saja, apa gunanya mengetahui? Kisah yang kau cari adalah kisah tentang orang-orang yang hancur. Memahami asal usulmu tidak akan memberimu apa pun.”
“Meskipun kau mungkin benar, aku telah menjalani seluruh hidupku dalam kegelapan. Aku akan mengambil apa pun yang bisa kudapatkan, tidak peduli seberapa kecilnya. Aku tidak bisa mengatakan alasanku lebih dari itu, tetapi aku tetap ingin tahu.”
“Jadi kamu hanya ingin memuaskan rasa ingin tahumu?”
“Saya rasa begitu, ya.”
Meskipun Sirene menggaruk pipinya dengan canggung, sorot matanya tulus. Shawza membuka mulutnya perlahan, seolah-olah berbicara saja sudah merupakan usaha yang berat. “Dan kau tidak punya petunjuk lain?” tanyanya.
“Tidak, sama sekali tidak. Sudah lebih dari satu dekade sejak aku berpisah dengan ayah dan kakakku, dan aku belum mendengar kabar dari mereka sejak saat itu. Aku bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup.”
“Jadi, minat Anda terutama pada keluarga Anda.”
“Ya. Nama saudara laki-lakiku adalah Rigel. Aku tidak pernah diberi tahu nama ayahku. Satu-satunya kenangan yang kumiliki untuk mengingat mereka—kalau kau bisa menyebutnya begitu—adalah tanda pada liontin ini. Kupikir kau mungkin tahu sesuatu, karena tanda itu cocok dengan apa yang dulu ada di belakang lehermu.”
Shawza menundukkan kepalanya, tetapi mendongak saat Sirene menyebut nama saudaranya. Rasa terkejut memenuhi matanya yang masih sehat saat ia menatap liontin itu.
“Itu… begitu. Kupikir aku mengenalinya.”
“Apakah kamu kebetulan mengenal keluargaku?”
“Ya, aku melakukannya.”
“L-Lalu—!”
Meskipun ekspresi Sirene berbinar karena antisipasi, ekspresi Shawza mendung. Kata-kata berikutnya yang diucapkannya penuh dengan kebencian.
“Liontin itu memberitahuku siapa dirimu—itu benar. Aku percaya kau sedang mencari ayah dan saudaramu. Tapi katakan padaku: Apa gunanya mengetahui nasib orang-orang bodoh itu?”
“’Bodoh”…?”
“Ya. Jika kau ingin tahu kebenarannya, aku akan memberikannya, tetapi kau akan menyesal bertanya padaku. Satu-satunya cerita yang bisa kuceritakan adalah tentang dua orang malang yang menjadi kutukan bagi orang-orang di sekitar mereka. Kau tidak akan senang mendengarnya. Aku tidak akan senang menceritakannya.”
Gadis yang duduk di hadapan Shawza memiliki mata yang tajam. Yang mereka cari hanyalah kebenaran. “Aku akan memutuskan apakah aku akan menyesali keputusanku setelah mendengar apa yang kau katakan.”
“Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Aku tidak akan menutup-nutupinya hanya karena mereka keluargamu.”
“Tidak apa-apa. Malah, aku lebih suka kalau kamu tidak melakukannya.”
Shawza memperhatikan Sirene sejenak, menunggu untuk melihat apakah tekadnya akan goyah, lalu menghela napas kecil. “Pertama-tama, seberapa banyak yang kau ketahui tentang orang-orang kita yang hancur?”
“Hampir tidak ada. Saya hanya tahu nama mereka sejak datang ke Sarenza. Ibu saya selalu menolak memberi tahu saya apa pun.”
“Aku tidak bisa bilang aku terkejut. Itu tindakan yang bijak darinya.” Pria berjas hitam itu semakin tenggelam ke kursinya dan menghela napas. “Lebih dari satu dekade yang lalu, orang-orang kami—Suku Mio—mengumpulkan permukiman beastfolk paling berpengaruh di negara ini di bawah satu panji dan memberontak terhadap badan penguasanya: Wangsa Sarenza.”

“Melawan Keluarga Sarenza…?”
“Ya. Kami menyalakan api pemberontakan di dalam diri para beastfolk yang tidak puas dengan status quo…hanya untuk dihancurkan dalam hitungan hari. Jika aku meninggalkannya di sana, kau sudah akan mengetahui sebagian besar ceritanya.”
“Apa yang terjadi…dengan ayah dan saudara laki-lakiku?”
“Ayahmu adalah kepala suku kami, pemimpin dari delapan belas suku yang telah mengangkat senjata demi tujuan itu. Hanya namanya saja, ingatlah—dia seorang pengecut, murni dan sederhana.”
“Seorang pengecut…?”
“Dan putranya, Rigel, meskipun diagung-agungkan sebagai pahlawan, dia tidak lebih dari seorang pemarah dan bodoh.”
Sirene tetap diam saat mencerna ucapan pedas Shawza. Dia tidak mengatakan apa pun sebagai protes dan hanya mendengarkan saat Shawza melanjutkan.
“Menyebut apa yang terjadi sebagai ‘pertempuran’ akan terlalu berlebihan. Itu adalah pembantaian sepihak. Di hadapan sumber daya House Sarenza yang tak terbatas, kami tidak berdaya. Para pemanah kami tercabik-cabik oleh golem mereka, jika tidak hancur berkeping-keping atau hancur total. Semua pertumpahan darah itu, dan untuk apa? Tidak ada apa-apa. Orang-orang kami tewas berbondong-bondong, tetapi tahukah Anda siapa yang selamat? Ayah Anda dan saudara laki-laki Anda, Rigel. Mereka ditangkap—hampir seluruhnya tidak terluka—dan dibawa untuk dieksekusi.”
“Dieksekusi…?”
“Ya. Sehari setelah mereka ditangkap, ayahmu dieksekusi di depan umum di ibu kota. Mereka mengikatnya di tiang gantungan dan memotong tangan dan kakinya. Kemudian, saat dia menangis dan kejang-kejang, mereka memenggal kepalanya dan menjadikannya makanan bagi monster.”
Tak sepatah kata pun keluar dari bibir Sirene. Setelah lebih dari satu dekade dalam kegelapan, ia mengira ia siap menghadapi yang terburuk. Ia tahu bahwa ayah dan saudara laki-lakinya mungkin sudah meninggal, tetapi nasib ayahnya lebih mengerikan daripada yang pernah dibayangkannya. Keadaan itu semakin terasa berat ketika pengawal bermata satu itu menjelaskannya, setiap kata-katanya dipenuhi dengan rasa jijik. Kekuatan emosinya yang meluap mengosongkan pikiran Sirene, dan butuh waktu lama baginya untuk menemukan kekuatan untuk memintanya melanjutkan.
“Dan… saudaraku? Apa yang terjadi padanya?”
“Rigel dinyatakan sama seperti ayahmu: seorang pemimpin pemberontakan. Maka, nasibnya pun sama buruknya. Dagingnya dipotong-potong dan tulang-tulangnya dipatahkan hingga ia menjadi orang yang malang, menangis dan memohon agar hidupnya diampuni. Kemudian mereka melepaskannya dan memberinya sedikit kebebasan sebelum menangkapnya lagi dan akhirnya memenggal kepalanya.”
Sekali lagi, Sirene tidak berkata apa-apa. Ia merasa hampir tidak bisa bernapas.
“Di situlah kisahnya berakhir. Mereka membakar mayatnya, jadi kau bahkan tidak punya tulang untuk diratapi.”
“Jadi begitu…”
Sirene menunduk menatap lantai, kepalanya tenggelam dalam cerita Shawza. Saat ia akhirnya menerima nasib keluarganya, secercah harapan muncul dari kegelapan—kesempatan untuk mendapatkan akhir yang sangat dibutuhkan.
“Tapi ayah dan saudara laki-lakiku… Mereka berjuang dan mati demi apa yang mereka yakini, kan? Demi—”
“Tidak. Apakah kamu mendengarkannya?”
Upayanya yang putus asa untuk mencari kenyamanan baru saja terwujud ketika upaya itu dihancurkan hingga tak bersisa oleh pria yang duduk di seberangnya.
“Keyakinan mereka tidak ada hubungannya dengan itu,” gerutu Shawza. “Aku ragu mereka punya keyakinan sejak awal, mengingat betapa sedikitnya pemikiran yang mereka curahkan dalam tindakan mereka. Mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak mengumpulkan informasi atau mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Sebaliknya, mereka membiarkan diri mereka terbawa oleh orang-orang di sekitar mereka. Kakakmu bukanlah pahlawan yang diharapkan semua orang; dia adalah seorang idiot yang berpura-pura menjadi pahlawan. Itu salahnya bahwa begitu banyak orang kita meninggal dengan kematian yang tidak berarti—bahwa kita, kaum beastmen, berada dalam posisi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Bahkan pada akhirnya, dia membuktikan kurangnya kehormatannya dengan mencoba melarikan diri secara pengecut untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kepercayaan? Apa yang diketahui orang seperti itu tentang kepercayaan ?”
Di akhir tulisannya, kata-kata Shawza menjadi semakin tajam dan tajam. Sirene menyadari apa adanya: kebencian yang murni dan mendalam.
“Mereka seharusnya mati di medan perang bersama rakyat mereka,” kata Shawza. “Akan jauh, jauh lebih baik jika mereka mati. Jika aku berhadapan langsung dengan mereka sekarang? Aku akan mencabik-cabik mereka dengan tanganku sendiri. Sepuluh kali, seratus kali, seribu kali tidak akan cukup.”
Ia melotot ke lantai, lengannya yang tersisa menegang dengan setiap kata penuh kebencian. Sirene merasakan udara di sekitar mereka bergetar setiap kali ia mengepalkan tinjunya. Kebenciannya telah berubah menjadi kemarahan yang murni dan mematikan. Bahkan mengetahui bahwa itu tidak ditujukan padanya, Sirene merasa dirinya menegang dan membeku.
Setelah terdiam beberapa saat, Shawza mendesah pelan. “Maaf. Seharusnya aku tidak memberitahumu.”
“Tidak, aku bersyukur kau melakukannya. Terima kasih.”
“Meskipun begitu… Dengar—lupakan semua khayalan indah yang mungkin pernah kau alami. Kakakmu sudah tiada. Bahkan jika dia masih hidup, itu artinya dia tidak menghubungimu selama lebih dari satu dekade. Apakah menurutmu dia punya sedikit rasa iba terhadap keluarganya? Aku tahu pria macam apa dia. Dia tidak akan pernah kembali padamu dan ibumu—dia bahkan tidak akan mengingat janji yang dia buat denganmu.”
Ada jeda sebentar sebelum Sirene berbicara. “Kau…tidak bisa mengatakan itu dengan pasti.”
“Kenapa tidak? Aku mengenalnya jauh lebih baik daripada dirimu. Dia pengecut, dari dalam dan luar. Dia lari dari kesulitan sekecil apa pun, melarikan diri dari kenyataan untuk menikmati delusi yang nyaman sampai dia meninggalkan segalanya. Pada akhirnya, tugas dan tanggung jawab terabaikan karena dia tidak memikirkan apa pun kecuali dirinya sendiri. Itulah dirinya yang sebenarnya. Jangan repot-repot mencoba belajar lebih banyak; keluarga atau bukan, dia tidak sepadan dengan waktumu.”
Begitu kuatnya amarah Shawza hingga dinding mulai berderit. Bahkan peralatan teh di rak pun berderak dan berdenting. Sirene mencengkeram liontin itu di lehernya.
Shawza mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya terdengar rendah dan parau. “Peringatan lainnya—kamu harus membuang perhiasan itu. Meskipun dulu perhiasan itu melambangkan persatuan rakyat kita, sekarang kita melihatnya dengan jijik dan hina. Bahwa kamu memiliki darah yang sama dengan Suku Mio sudah cukup untuk membuatmu mendapatkan banyak musuh, dan tindakan membawa benda itu bersamamu akan membuatmu dicap sebagai pertanda bencana. Jika sedikit saja sentimentalitas yang keras kepala membuatmu tidak dapat melakukannya sendiri, maka biar aku yang menghancurkannya untukmu, di sini dan sekarang. Demi kebaikanmu dan ibumu.”
Dia mengulurkan tangan untuk mengambil liontin itu, tetapi Sirene menariknya kembali.
“Tolong jangan.”
Pria bermata satu itu berhenti sejenak, lalu menarik lengannya. “Maafkan saya. Itu milik Anda. Bagaimana Anda menanggapi peringatan saya, itu terserah Anda dan Anda sendiri.”
“Aku tidak akan membuangnya. Tidak akan pernah.”
“Jadilah begitu.”
Berpaling dari Sirene, yang masih meremas liontinnya, Shawza kembali duduk di sofa. “Ada lagi yang ingin kau tanyakan? Bukan berarti aku punya jawaban lain untuk diberikan.”
“Tidak, kau sudah cukup bercerita padaku. Terima kasih.”
Masih memegang erat liontinnya seolah menyembunyikannya, Sirene berdiri dan membungkukkan badan sedikit kepada Shawza, matanya tertunduk. Begitu selesai melakukannya, dia menghilang, menyelinap melewati pintu ruangan yang berat itu.
Begitu sosok rampingnya tak terlihat lagi, penghuni ruangan yang tersisa mendesah. “Saudaramu Rigel adalah pengecut yang paling hina dan paling keji. Kau tidak akan menemukannya, tidak peduli seberapa keras kau mencarinya. Jadi, mengapa repot-repot menggali masa lalu…?”
Suaranya yang rendah menggema di seluruh ruangan, tetapi menghilang sebelum mencapai telinga siapa pun. Apakah kekesalannya ditujukan pada Sirene atau dirinya sendiri, tidak ada yang tahu.





