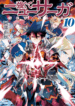Musume Janakute Mama ga Sukinano!? LN - Volume 6 Chapter 9
Pendahuluan
♦
Sekarang sudah bulan Desember, jadi tiga bulan telah berlalu sejak penugasan sementara ibuku, di mana ia dikirim untuk tinggal sendiri di Tokyo—yah, ia akhirnya berbagi kondominium dengan Taku, jadi ia tidak benar-benar sendirian. Entah bagaimana, rasanya lama dan singkat di saat yang bersamaan.
Ibu akhirnya pulang hari ini. Aku merasa gelisah sejak aku bangun. Sejujurnya… kurasa aku sedikit senang karenanya. Aku tidak pernah sendirian sejak nenekku datang ke rumah kami untuk tinggal bersamaku, tetapi tetap saja, ada banyak saat ketika aku merasa kesepian saat ibuku tidak ada di rumah selama tiga bulan. Tentu saja, aku tidak pernah memberitahunya bahwa aku merasakan hal itu…
“Aku pulang!” seru sebuah suara. “Aku pulang, Miu!”
Dia tiba di sore hari. Aku ingin segera berlari ke pintu masuk, tetapi akan memalukan jika berpura-pura menunggunya, jadi…
“Selamat datang kembali,” jawabku datar dari ruang tamu.
“Fiuh, di sini dingin sekali… Tokyo masih hangat,” kata ibuku, mengomentari perbedaan suhu antara wilayah Kanto dan Tohoku saat ia berjalan menuju ruang tamu. “Senang sekali bisa pulang,” katanya sambil mendesah. “Entah mengapa terasa… nostalgia. Aku merasa sangat emosional.”
“Kamu sangat dramatis. Baru tiga bulan.”
“Sudah tiga bulan ! Kamu merindukanku, bukan?”
“Tidak juga. Aku tidak keberatan kalau kamu tinggal di Tokyo lebih lama.”
“Astaga, kamu jahat sekali!” kata ibuku sambil menggembungkan pipinya sambil melepaskan mantelnya. Sepertinya dia meninggalkan kopernya di pintu masuk. Dia memegang kantong kertas, yang sepertinya berisi semacam hadiah, dan kantong plastik.
“Kau pulang lebih lambat dari yang kuduga,” kataku.
“Ya, saya mampir ke toko obat untuk membeli sesuatu,” katanya sambil mengangkat kantong plastik.
“Begitu ya… Oh, benar juga.” Aku teringat sesuatu yang diminta untuk kuurus, dan aku menuju dapur. Aku mengambil sebotol sake yang hampir dua liter dan menunjukkannya kepada ibuku sementara ia mengeluarkan beberapa barang dari kantong plastik dan menaruhnya di atas meja. “Ini dia. Ini alkohol.”
“Apa…? Di mana kamu mendapatkan ini?”
“Itu dari nenek dan kakek. Mereka mendapatkannya di suatu festival di kota asal mereka atau semacamnya. Rupanya harganya sangat mahal dan berkualitas tinggi, tetapi kakek tidak menyukainya.”
“Oh, benar juga. Ayah hanya minum bir dan shochu.” Ibu mengambil botol dan membaca labelnya. “Oh, kurasa aku pernah mendengar jenis ini sebelumnya. Ini cukup terkenal.”
“Begitu ya. Baguslah.” Aku sama sekali tidak tertarik pada alkohol, jadi aku langsung menjawab tanpa banyak berpikir. Lalu aku mengambil teh barley dari lemari es dan menuangkannya ke dalam cangkir.
“Andai saja aku bisa memakannya,” kata ibuku sambil mendesah. Ia terdengar agak kecewa, dan aku memiringkan kepalaku dengan bingung.
“Hm? Apa yang menghentikanmu?”
“Oh, um, aku, uh… aku tidak bisa minum untuk sementara waktu.”
“Kenapa? Kamu sedang diet?”
“T-Tidak, aku tidak… Hanya saja, dengan situasi yang sedang terjadi, adalah hal yang wajar untuk tidak minum alkohol. Itu juga yang dikatakan dokter kepadaku…”
“D-Dokter? Ibu sakit?”
“T-Tidak, tidak juga…”
Dia sangat tidak jelas. Ibu bertingkah aneh , pikirku sambil melirik apa yang dia taruh di meja. Sepertinya yang dia beli di toko obat adalah kopi bunga matahari—alternatif kopi tanpa kafein—dan beberapa suplemen asam folat.
Hmm. Saya jelas tidak punya pengalaman pribadi dengan hal itu, tetapi saya pernah mendengar dan membaca tentang hal semacam ini di acara TV dan manga. Tiba-tiba menghindari kafein, mengonsumsi asam folat…ini adalah hal-hal yang sering dilakukan wanita saat mereka berada dalam situasi tertentu. Belum lagi dia tidak mengonsumsi alkohol dan sudah memeriksakan diri ke dokter…
Aku terkesiap keras dan menoleh ke arah ibu. Aku menatapnya tajam.
“H-Hah…? Bu-Bu, apa…? Hah? Apa?” Aku begitu terkejut hingga tidak dapat berbicara dengan baik.
Mungkin sikapku yang gelisah menunjukkan bahwa aku mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ibuku kini tampak sangat tidak nyaman juga. Kami berdua berdiri diam selama beberapa detik, lalu ia perlahan meletakkan lengannya di perutnya. Ia mengusap perutnya dengan lembut, seolah ingin membelainya.
“Aku hamil… Tee-hee.” Dia menjulurkan lidahnya dengan nada main-main.
Inilah saat yang dipilih ibuku untuk meluapkan semua kekonyolan dalam dirinya. Aku membayangkan dia mungkin tidak sanggup mengungkapkannya dengan serius.
Aku terdiam. Rasanya jiwaku telah meninggalkan tubuhku. Aku begitu gugup hingga menjatuhkan cangkirku. Untungnya, kami menggunakan cangkir yang terkenal sulit pecah, jadi tidak ada tumpahan.
Apa yang harus kukatakan…? Ada begitu banyak pikiran yang berkecamuk dalam benakku sehingga aku tidak mungkin mengatakan semuanya, tetapi ada satu yang jelas di antara semuanya—sesuatu yang paling ingin kutanyakan. Ibu… ibuku tersayang… apa sih yang kau lakukan di Tokyo?!