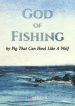Mimosa no Kokuhaku LN - Volume 2 Chapter 2

Bab Empat:
Romeo dan Rasa Benci pada Diri Sendiri
SAAT ITU TANGGAL PERTAMA SEPTEMBER—awal semester musim gugur.
Dalam perjalanan pagi ke sekolah, seperti yang kukira dirasakan kebanyakan siswa, aku merasa sangat sedih setelah liburan musim panas. Panas terik akhir musim panas dan jangkrik pagi masih terasa tak tertahankan seperti sebelumnya. Aku menyeka keringat di pelipisku dan berjalan masuk ke pintu masuk utama. Saat itulah aku melihat sosok ramping yang familiar di depan rak sepatu. Bahkan dari belakang, aku bisa tahu bahwa sosok itu milik Ushio—satu-satunya orang yang kukenal yang mampu memancarkan aura dingin dan gigih bahkan di tengah panas terik ini. Saat aku melepas sepatu dan melangkah ke papan selancar di depan lokerku, ia mendengar langkah kakiku dan berbalik.
“Oh, pagi,” katanya.
“Ya, hai,” jawabku.
Mengingat dia rutin datang ke rumahku hingga beberapa hari yang lalu, tidak ada lagi rasa reuni yang biasa setelah rehat panjang di antara kami. Kami hanya bertukar sapa seperti biasa, lalu menuju ke kelas. Namun, saat kami berjalan menyusuri lorong, aku bisa mendengar banyak siswa lain menanyakan semua pertanyaan stereotip pasca-liburan musim panas: apa kabar, ke mana saja, seberapa banyak sinar matahari yang kau dapatkan, dan sebagainya.
Penasaran, aku melirik Ushio sekilas saat kami berjalan. Kulitnya masih begitu putih bersih dan menyilaukan, sampai-sampai kau akan menganggapnya sesuatu yang sakral—tidak boleh disentuh tanpa peralatan penanganan yang tepat, agar tidak meninggalkan memar atau noda permanen. Sepotong buah persik putih terlintas di pikiranku.
“…Ada yang bisa kubantu?” tanya Ushio, cepat-cepat melipat tangannya seolah menyembunyikannya. Dia memergokiku basah, dan aku benar-benar merasa bersalah karena menatapnya.
“Eh, salahku,” kataku, tatapanku melirik ke depan dengan gugup. “Kurasa aku cuma heran kenapa kulitmu bisa begitu kebal terhadap sinar matahari, itu saja.”
“Sebenarnya tidak juga. Kulitku lumayan sensitif, jadi langsung berubah dari putih jadi merah. Kulitku tidak terlalu kecokelatan.”
“Oh, ya. Rasanya aku ingat kau pernah menceritakan ini padaku.”
Kalau tidak salah, saat saya masih sekolah dasar.
“Kamu juga kelihatannya tidak terlalu berkulit cokelat,” tambahnya.
“Ya, tapi itu karena aku di rumah saja sepanjang liburan,” kataku.
“Bukankah sebaiknya kamu mencoba berolahraga? Metabolismemu tidak akan bertahan selamanya.”
“Ya, mungkin begitu,” kataku acuh tak acuh, sambil memegangi perutku. Aku tidak punya banyak lemak atau semacamnya, meskipun perutku juga tidak terbentuk sempurna. Pernah ada saat aku memutuskan untuk mencoba angkat beban, tetapi fase itu tak berlangsung lebih dari sebulan sebelum akhirnya aku menyerah. Namun, dengan festival olahraga sekolah yang akan datang di musim gugur, mungkin ini bukan waktu yang buruk untuk kembali beraktivitas. Tapi kurasa itu baru akan terjadi setelah festival budaya, sejujurnya.
“Ya Tuhan, sungguh sulit ketika Engkau begitu baik padaku.”
Tiba-tiba kata-kata Ushio terlintas dalam pikiranku.
Sesuai permintaannya, aku berusaha berpura-pura tidak mendengarnya. Ushio sendiri kembali bersikap seperti biasa, meskipun jelas-jelas gugup dan bingung setelah keceplosan bicaranya. Di permukaan, semuanya tampak normal di antara kami. Namun di balik itu, kata-kata Ushio tersangkut di tenggorokanku seperti tulang ikan kecil yang tersangkut, sesekali mengingatkanku akan keberadaannya dengan sentakan nyeri yang tajam. Aku ragu apakah lebih aman untuk meraih dan menariknya keluar atau berdoa agar tertelan dan tercerna seiring waktu. Saat ini, aku mengandalkan yang terakhir—tanpa tahu sama sekali apakah itu pilihan yang tepat atau tidak.
Saat aku menginjakkan kaki di Ruang Kelas 2-A, aku disambut oleh hiruk pikuk yang bahkan menyaingi suara jangkrik di luar, saat teman-teman sekelasku asyik menikmati kesibukan pagi untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Di dekat tengah ruangan, aku melihat Hoshihara asyik mengobrol dengan beberapa gadis lain. Saat ia melihat ke arah kami, ia tersenyum dan melambaikan tangan dengan santai, yang dibalas dengan acuh tak acuh olehku dan Ushio. Aku tidak merasakan kecanggungan yang tersisa di antara kami; bahkan bisa dibilang kami merasa seperti teman yang lebih dekat dari sebelumnya. Namun, rasanya juga ada sesuatu yang penting dalam hubungan kami, jauh di lubuk hati.
Ada ketidakstabilan dan ketidakpastian yang nyata dalam hampir semua hal tentang hubungan kami—tapi itu sudah biasa, kukira, dan kami harus terus berjuang apa pun yang terjadi. Sekalipun aku tahu persahabatan kami dibangun di atas fondasi es yang semakin menipis, aku tak berniat untuk mundur sekarang.
Aku meletakkan tasku di meja dan menatap jam dinding di atas papan tulis. Upacara pembukaan semester akan segera dimulai.
***
“Jadi, kelas…” kata Bu Iyo, berdiri di mimbar, “tanpa basa-basi lagi, dengan senang hati saya umumkan bahwa kontribusi kelas kita untuk festival budaya ini adalah… pertunjukan panggung Romeo dan Juliet ! Woooo! Bagaimana kalau tepuk tangan meriah, ya?!”
Begitu upacara pembukaan selesai, kami kembali ke kelas untuk mengikuti jam pelajaran. Setelah guru mengucapkan salam dan kami menyerahkan PR, topik segera beralih ke festival budaya yang akan datang di bulan Oktober, dan beliau memberi tahu kami seperti apa pameran Kelas 2-A nanti. Tanggapan teman-teman sekelas saya terhadap berita ini beragam, setidaknya begitu, tetapi Bu Iyo sangat senang.
“Astaga, aku suka banget Romeo dan Juliet , ya?” katanya. “Aku nggak sabar lihat seberapa bagus akting kalian, semuanya!”
“Maksudmu kau tidak akan ikut bermain, Bu Iyo?” goda salah satu anak laki-laki—tapi Bu Iyo hanya menyilangkan tangan dan memiringkan kepalanya ke samping, seolah-olah sedang mempertimbangkannya.
“Aduh, entahlah… Haruskah aku? Menurutmu, peran apa yang seharusnya kumainkan jika aku melakukannya?”
Beberapa suara dari seluruh kelas berteriak, “Juliet!” Memang, kebanyakan dari mereka mungkin bercanda, tetapi saya melihat beberapa gadis yang tampaknya benar-benar menyukai ide itu. Secara pribadi, saya pikir cukup konyol untuk menyarankan guru tersebut sebagai pemeran utama wanita—dan untungnya, Bu Iyo juga. Beliau segera menertawakan ide itu.
“Nah, nah, teman-teman. Ini festival budaya yang dikelola mahasiswa , jadi sayangnya saya tidak bisa berpartisipasi sama sekali! Ngomong-ngomong, adakah di antara kalian yang bisa menyebutkan tokoh dari drama ini yang bukan Romeo atau Juliet?”
Dia benar, kalau dipikir-pikir; aku tidak bisa memikirkan karakter utama maupun pendukung selain duo tituler itu. Sejujurnya, aku tidak ingat banyak tentang drama itu selain beberapa dialog paling ikonik dan adegan terakhirnya. Aku melihat sekeliling kelas, dan sepertinya sebagian besar teman sekelasku bernasib sama denganku.
“Saya merasa seperti ada karakter seperti kakek-kakek tua, bukan?”
“Bung, jangan tanya aku. Aku nggak tahu apa-apa.”
“Apakah ada karakter lain selain mereka?”
“Bukankah ada orang bernama Gaston itu?”
“Tidak, dia dari Beauty and the Beast .”
“Tunggu. Aku nggak tahu Romeo dan Juliet itu film Disney.”
“Karena bukan itu, bodoh. Itu Shakespeare.”
Paduan suara yang kacau terdengar dari seluruh penjuru kelas. Baru ketika keadaan mulai benar-benar kacau, Bu Iyo menghentikannya dengan bertepuk tangan.
“Baiklah, semuanya, tenang. Ya, aku merasa kalian semua tidak akan terlalu familiar. Bahkan aku pun kesulitan mengingat detail-detail kecilnya. Tapi untungnya, aku punya sedikit penyegaran untuk membantu kita hari ini.” Ia meletakkan kotak DVD dan setumpuk kertas di mimbar. “Rupanya, ada kelas yang mementaskan Romeo dan Juliet di festival budaya tiga tahun lalu. Aku berhasil mendapatkan rekaman DVD-nya, beserta naskah singkat yang mereka gunakan. Sekarang kita sudah punya semua yang kita butuhkan untuk memastikan kita benar-benar menguasai cerita dan karakternya!”
“Tunggu. Kita mau nonton sekarang?” tanya salah satu anak laki-laki di kelas.
“Tentu saja. Siapa pun yang terlalu jauh untuk melihat layarnya, silakan naik.”
Bu Iyo mengeluarkan cakram dari kotak plastiknya, lalu memasukkannya ke pemutar DVD di meja TV di sudut ruang kelas. Layarnya tidak terlalu besar, jadi banyak teman sekelas saya yang menerima tawarannya dan menggeser kursi mereka lebih dekat. Saat layar menyala, kami disambut oleh gambaran auditorium sekolah yang digelapkan dengan muram.
“Kita letakkan panggung kita di Verona yang indah, saat pertikaian lain antara keluarga Montague dan Capulet membayangi dendam lama yang terpendam di kota itu…”
Tirai panggung dibuka saat narator memperkenalkan para aktor berkostum satu per satu ke panggung utama. Dari sana, cerita berkembang dengan tempo yang cukup cepat. Sejujurnya, rasanya lebih seperti cuplikan adegan-adegan paling ikonik dalam drama, alih-alih alur cerita yang nyata dan mudah dipahami yang bisa diikuti oleh orang awam. Saya bisa merasakan mereka menggunakan naskah yang sangat dimodifikasi dan dipadatkan tanpa perlu memeriksanya, tetapi sejujurnya, ini hanyalah festival budaya SMA. Festival ini tidak harus memenangkan penghargaan apa pun.
“Dan pagi yang muram pun tiba, matahari yang berduka bahkan enggan menampakkan kepalanya, saat kisah cinta yang malang ini mencapai akhir.”
Semuanya selesai dalam waktu dua puluh menit. Bu Iyo mematikan TV dan meminta kami semua kembali ke posisi duduk semula, lalu mulai membagikan naskah-naskah yang dijilid staples yang telah ia fotokopi dan letakkan bertumpuk di atas mimbar.
“Sekarang, perlu diketahui bahwa naskah dan arahan panggung yang kita miliki di sini hanyalah yang menurut alumni angkatan sebelumnya adalah yang terbaik,” ujarnya. “Silakan ubah dan atur ulang sesuka hati. Selama naskahnya cukup bagus untuk menghibur penonton biasa, saya tidak akan terlalu mempermasalahkan detail-detail kecilnya.” Setelah setiap siswa memegang naskah, Bu Iyo mengangguk puas. “Baiklah! Kurasa cukup sekian untuk kelas hari ini… Tapi kurasa kita masih punya sedikit waktu tersisa. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan?”
Masih ada sekitar sepuluh menit tersisa sebelum bel berikutnya berbunyi. Kelas ramai dengan obrolan menanggapi pertanyaan terbuka ini, beberapa berharap kami bisa keluar lebih awal, sementara yang lain memberikan saran mulai dari memilih denah tempat duduk baru untuk semester ini hingga menentukan pemeran untuk drama tersebut—yang terakhir tampaknya menarik perhatian Bu Iyo.
“Oh, benar juga!” katanya. “Kurasa kita harus mulai memikirkan siapa yang akan memerankan siapa. Ada yang berharap peran tertentu? Bangun pagi dapat yang terbaik, lho!”
Ruang kelas kembali riuh dengan gumaman, tetapi tak satu pun relawan yang muncul. Sepertinya semua orang bersikap menunggu dan melihat—seolah-olah bahkan mereka yang tertarik tampil pun takut untuk bersuara terlebih dahulu, sehingga menjadikan diri mereka pemimpin de facto, dan berharap orang lain yang akan memulai.
“Nggak ada sama sekali, ya?” kata Bu Iyo. “Semua peran masih terbuka untuk diambil, teman-teman! Kudengar bahkan ada kelas bertahun-tahun lalu yang melakukannya dengan Juliet perempuan dan Romeo perempuan!”
Informasi ini tidak mengubah keadaan. Tepat ketika Bu Iyo tampak hampir menyerah, menyatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu diburu-buru…
“Eh, m-maaf!”
Seorang gadis berambut keriting mengangkat tangan dan berbicara dengan terbata-bata. Namanya… Nanamori, kalau tidak salah ingat. Apakah dia tertarik memainkan peran, atau hanya sekadar ingin bertanya? Dia tidak pernah terlihat seperti tipe orang yang suka menawarkan diri, jadi saya akan agak terkejut jika jawabannya adalah yang pertama.
“Oh, uh, maaf,” katanya. “Bukannya aku ingin peran untuk diriku sendiri, tapi ada seseorang yang kupikir cocok…”
“Jadi, kau ingin mencalonkan orang lain?” tanya Bu Iyo, dan Nanamori mengangguk malu-malu—dan dalam arti yang sebenarnya. Ia benar-benar terlihat seperti tikus kecil yang penakut saat ia menarik napas dengan gugup dan mengaku:
“Aku benar-benar ingin melihat Tsukinoki-san memerankan Juliet…kalau boleh!”
Gelombang keributan yang tampak jelas melanda kelas, bahkan murid-murid yang tampak acuh tak acuh terhadap drama itu tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat ke arah Nanamori. Namun, tak seorang pun yang tampak lebih terkejut daripada sang calon sendiri.
“T-tunggu. Aku?” kata Ushio dengan mata terbelalak.
Nanamori menoleh padanya dan mengangguk beberapa kali, lalu gelisah dengan tangan di atas meja sambil menjelaskan. “Begini, um… aku anggota klub menjahit, jadi aku suka sekali membuat gaun dan sebagainya… Dan aku benar-benar berpikir kau akan terlihat luar biasa dengan gaun kuno yang dibuat dengan baik, itu saja. Kurasa itulah sebabnya aku ingin melihatmu memerankan Juliet… Eh, bukan berarti aku pernah terpikir untuk memaksamu melakukannya atau semacamnya!”
Gaya bicaranya berantakan; jelas dia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Namun, ada hasrat yang kuat dalam suaranya—begitu kuatnya keinginannya untuk melihat Ushio sebagai Juliet sehingga tampaknya mengalahkan kecemasan sosialnya. Meskipun begitu, itu hanyalah sebuah nominasi di akhir. Keputusan tetap ada di tangan Ushio, apakah dia menerimanya atau tidak. Saat aku menoleh untuk mengukur reaksinya, aku mendengar derit keras saat seseorang dengan dramatis menggeser kursinya dari bawah meja.
“Hei, kurasa itu ide bagus !” seru Hoshihara sambil berdiri dan menatap Nanamori dengan mata penuh semangat. “Aku setuju sekali dengan nominasi itu! Ushio-chan lebih dari cukup cantik untuk menjadi Juliet yang sempurna!”
“B-benarkah?!” kata Nanamori, wajahnya berseri-seri karena telah menemukan rekan yang sepemikiran. “Dia sangat ramping dan menarik, aku rasa dia akan terlihat bagus dalam pakaian apa pun dan benar-benar membuatnya bersinar di atas panggung!”
Keduanya kini resmi menjadi teman dekat—dan tampaknya kegembiraan mereka telah memicu revolusi kecil di antara anak-anak lain di kelas, karena beberapa suara lain ikut berkomentar tentang betapa mereka ingin melihat Ushio memerankan Juliet atau betapa sempurnanya dia untuk peran tersebut. Memang, sebagian besar pendukung ini adalah perempuan; para laki-laki tampaknya tidak terlalu tertarik dengan ide tersebut, meskipun tidak satu pun dari mereka yang tampak jijik.
Namun, ada satu siswa di kelas kami yang sama sekali tidak berusaha menyembunyikan rasa jijiknya terhadap konsep itu: Nishizono. Ia memasang wajah cemberut di antara rambut pirang panjangnya yang dikuncir dua dan tampak seolah ingin mengeluh. Namun ia menahan diri, mungkin karena kehadiran Bu Iyo. Selama semester musim semi, ia tidak menunjukkan pengendalian diri seperti itu dalam hal melontarkan makian kasar kepada Ushio, jadi ini tetap merupakan sedikit peningkatan menurut saya. Mungkin liburan musim panas telah sedikit melunakkannya.
“Mmm… Bagaimana pendapatmu tentang ini, Ushio?” tanya Bu Iyo. “Bukannya kita harus memutuskan sekarang atau apa pun. Kita masih punya waktu.”
Ushio memegang dagunya di antara ibu jari dan telunjuk sambil merenungkan hal ini. Semua orang di kelas tampak gelisah, menunggu jawabannya. Setelah jeda yang cukup lama, ia mengangkat kepalanya dengan penuh tekad.
“Baiklah kalau begitu,” katanya. “Aku akan mencobanya.”
Seruan “oh” menggema dari galeri kacang. Hoshihara duduk dengan raut wajah gembira, sementara Nanamori merapatkan kedua tangannya dengan gembira.
“Terima kasih, Tsukinoki-san!” katanya. “Eh, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membuatkanmu kostum tercantik yang pernah kau lihat!”
“Terima kasih. Aku akan menantikannya.”
Ushio tersenyum pada gadis itu—jenis senyum lembut yang seolah terbentuk secara alami saat pipimu mengendur dan pertahananmu melemah. Mungkin aku hanya berkhayal, tetapi rasanya hanya bayang-bayang kesedihan yang samar-samar tersembunyi di suatu tempat di bawahnya.
Tunggu. Jangan bilang…
“Baiklah, sekarang siapa yang akan menjadi Romeo kita?” tanya Bu Iyo, sambil terus melanjutkan panggilan casting sebelum aku bisa menemukan bukti kuat untuk mengonfirmasi keraguanku.
***
Beberapa menit kemudian, jam pelajaran di kelas berakhir, dan sekolah pun diliburkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ushio, Hoshihara, dan saya berjalan pulang bersama.
“Astaga, Kamiki-kun!” seru Hoshihara sambil mendorong sepedanya melewati gerbang utama kampus. “Aku masih nggak percaya kamu bakal jadi Romeo kami!”
Benar—saya sudah setuju untuk memerankan Romeo dalam drama itu. Salah satu teman sekelas saya dengan santai menyarankan saya untuk memerankannya ketika Bu Iyo bertanya, dan akhirnya saya menerima tawaran itu.
“Kamu yakin?” tanya Ushio, sambil menoleh ke arahku saat kami berjalan dengan tatapan khawatir di matanya. “Maksudku, kamu sudah punya banyak pekerjaan sebagai anggota panitia festival…”
Bukannya aku memang sudah punya hasrat mendalam untuk memerankan Romeo sejak awal, atau aku tak mungkin menolaknya kalau memang ingin. Sejujurnya, satu-satunya alasan aku menolaknya adalah karena memang begitulah seharusnya. Jauh di lubuk hatiku, aku tahu kalau Ushio yang memerankan Juliet, mungkin akulah yang akan memerankan Romeo. Karena—walaupun aku tahu ini agak kasar—aku tak bisa membayangkan ada orang lain di kelas kami yang secara sukarela menjadi pemeran utama pria bersamanya. Kalau aku menolak nominasi itu, mungkin rasanya seperti mencari Romeo lain yang sulit, yang kutahu hanya akan membuat Ushio merasa sangat canggung. Jadi, aku memutuskan untuk menerima peran itu.
Tentu saja, saya sempat cemas. Bahkan hal-hal seperti berbicara di depan umum atau memberikan presentasi kelas jelas bukan keahlian saya, jadi membayangkan harus tampil sebagai bagian dari produksi panggung di depan banyak orang saja sudah cukup membuat saya sedikit terdissosiasi. Namun, ketika saya berada di posisi Ushio dan membayangkan betapa sulitnya dia nantinya, saya tak sanggup menolak. Dia benar bahwa saya juga harus memikirkan pekerjaan saya sebagai anggota panitia festival, tapi…
“Meh,” kataku. “Aku yakin aku bisa mengatasinya.”
“Yah, setidaknya aku mengagumi optimismemu,” katanya dengan jengkel, tepat ketika seekor capung merah melesat melewati ujung hidungnya. Udara masih terasa panas, tetapi di kalender, saat itu musim gugur. Lonceng kota yang memberi tahu semua anak baik bahwa sudah waktunya pulang telah dimajukan dari pukul 18.00 menjadi 17.30, dan ketika aku memandang ke sawah, aku bisa melihat bulir-bulir padi mulai terkulai di sana-sini. Bahkan ada sedikit asap di udara, seolah-olah seseorang sedang membakar ladang di suatu tempat yang tak terlalu jauh.
“Sudah lama aku tidak bertemu Sera, kalau dipikir-pikir,” kataku—lalu sedikit menyesalinya. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku membahasnya, mengingat dia orang terakhir yang ingin kubicarakan. Mungkin dia masih dekat di benakku; kenangan buruk biasanya memang yang paling sulit dihilangkan.
“Sepertinya dia punya pacar baru yang sangat dia sukai,” kata Ushio. “Mungkin akhir-akhir ini dia terlalu sibuk dengannya.”
“Tunggu. Kamu dengar ini dari dia?” Aku agak terkejut dia tahu.
“Mm-hmm. Aku sudah bilang lewat pesan.”
“Oh, ya. Aku nggak tahu kalian sudah bertukar informasi kontak.”
“Ya, meskipun aku jarang membalas. Biasanya cuma dia yang mengirimiku pesan.”
Jadi, dia memang membalas sesekali. Aku jadi bertanya-tanya, apa sih yang masih harus mereka berdua bicarakan. Terlambat, aku menyadari bahwa ini topik yang agak sensitif dan mungkin akan memperburuk suasana hati Hoshihara. Yang mengejutkanku, ternyata tidak.
“Baguslah kalau begitu,” katanya. “Senang dia menemukan seseorang yang lebih cocok. Lagipula, sekarang tidak ada yang menghalangi kita untuk berjalan pulang bersama setiap hari lagi!”
Hoshihara menyeringai nakal, dan aku pun tak kuasa menahan senyum. Bagi pengamat luar, interaksi ini mungkin tampak seperti selembar halaman indah yang disobek dari album foto masa muda kita. Namun di tengah semua obrolan ringan yang jujur ini, masih ada momen-momen yang membuatku terdiam, momen-momen di mana aku kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Aku cukup yakin Ushio dan Hoshihara juga mengalami momen-momen seperti itu. Rasanya seperti ada penghalang kecil namun tak wajar di antara kami—hal yang sama sekali bukan gangguan besar, tetapi yang kami semua rasakan dan harap bisa kami singkirkan. Aku sangat berharap itu hanya aku yang terlalu khawatir dan terlalu banyak berpikir, tetapi dengan asumsi aku benar, aku ingin menemukan cara untuk meruntuhkan penghalang itu, atau setidaknya beradaptasi dan belajar untuk hidup dengannya.
“Ayo, Kamiki-kun! Dukung aku di sini! Kamu juga berpikir begitu, kan?!” kata Hoshihara, langsung menyadarkanku dari lamunanku saat dia memasukkan bola ke lapanganku.
“Hah? Oh, maaf,” kataku. “Bisakah kau mengulanginya? Aku tidak mendengarkan.”
“Ugh! Perhatikan baik-baik, ya?!”
Aku merasa tidak enak, meski aku tidak dapat menahan senyum dalam hati melihat betapa lucunya Hoshihara saat dia sedang marah.
“Kita lagi ngomongin gimana Ushio-chan bakal jadi Juliet yang keren banget ! Bener, kan?!”
“Ohhh, benar juga… Ya, tentu saja,” jawabku, dan Hoshihara mengangguk setuju.
“Ugh, aku tak sabar melihat penampilannya saat memakai kostum…” Ia menatap langit, matanya berbinar-binar takjub. “Aku penasaran gaun seperti apa yang akan mereka buat untuknya…”
“Kau tahu, Natsuki,” kata Ushio, poninya sedikit tergerai saat ia mencondongkan kepala ke depan untuk melihat lebih jelas wajah Hoshihara yang mendongak. “Koreksi aku kalau aku salah, tapi sepertinya kau juga ingin memerankan Juliet.”
“Siapa, aku?!” seru Hoshihara, mengerjap tak percaya beberapa kali sebelum menggeleng cepat. “Tidak, tidak, tidak! Aku sama sekali tidak cocok untuk peran itu . Belum lagi, aku terlalu pendek…”
“Menurutmu? Kurasa dari segi karakter, kamu jauh lebih cocok. Lagipula, kamu lebih manis dan feminin, jadi kamu bisa memerankannya lebih natural daripada aku.”
“Aduh, astaga. Aku nggak tahu soal itu…”
Pipi Hoshihara memerah, dan bibirnya membentuk seringai malu. Namun, bagaikan awan gelap di hari yang cerah, secercah sinar kebahagiaan yang terpancar dari senyum itu tertutupi oleh selubung kesepian yang membayangi.
“Pokoknya, menurutku kaulah yang seharusnya melakukannya,” katanya dengan tenang. “Maksudku, kalau aku Juliet, aku tidak akan pernah melihatmu memerankannya! Lagipula, bukankah kau bilang kau selalu ingin menjadi putri dalam drama sejak kecil?”
Saya juga teringat anekdot ini. Dulu, ketika saya dan Hoshihara berkunjung ke rumah Ushio, ia bercerita tentang bagaimana ia pernah menawarkan diri untuk memerankan Cinderella semasa kecil, tetapi gurunya justru menertawakannya sebagai lelucon. Meskipun Cinderella dan Juliet adalah dua karakter yang berbeda dari kisah yang sangat berbeda, keduanya adalah tokoh utama wanita dalam kisah mereka masing-masing. Ini adalah kesempatan sempurna bagi Ushio untuk melunasi hutang lama dan mewujudkan impian masa kecilnya—atau begitulah yang tampaknya dipikirkan Hoshihara.
“Wow. Kau ingat itu,” kata Ushio, terdengar benar-benar terkesan.
“Tentu saja,” kata Hoshihara. “Dan meskipun aku tahu Nanamori-san yang pertama kali mengusulkannya, aku bersumpah aku sudah berpikir akan menyenangkan kalau kau mendapat kesempatan memerankan Juliet bahkan sebelum itu. Meskipun aku khawatir kami agak memaksamu untuk melakukannya…”
Saat suara Hoshihara merendah karena gugup, Ushio memasang senyum penuh kasih sayang.
“…Kamu baik-baik saja,” katanya. “Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi Juliet yang hebat.”
Ekspresi Hoshihara yang termenung berubah menjadi seringai lebar. “Oke, ya! Aku akan mendukungmu!” katanya sambil mengangguk lebar. Nada suaranya riang, dan senyumnya berseri-seri. Aku menarik kembali ucapanku—dia jauh lebih manis saat bahagia daripada saat sedang kesal.
Dari sana, kami berjalan santai pulang, terlibat dalam obrolan ringan apa pun yang muncul di sepanjang jalan. Kami mengobrol tentang betapa beratnya PR musim panas, dan bagaimana Hoshihara pergi mengunjungi kerabatnya untuk merayakan Obon—tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan ceritanya, kami tiba di persimpangan tempat jalan kami bercabang.
“Baiklah, sampai jumpa besok!” katanya riang, lalu melompat ke atas sepedanya dan menuju rumah.
Lalu hanya ada aku dan Ushio, berjalan berdampingan di trotoar. Suasana menjadi sangat hening dengan sangat cepat begitu Hoshihara pergi, tetapi itu bukanlah keheningan yang tidak nyaman. Suara jangkrik berkicau dan anak-anak bermain di kompleks apartemen terdekat terdengar di telingaku.
Aku melirik Ushio dari sudut mataku. Ekspresinya tenang, tatapannya lurus ke depan. Postur tubuhnya sempurna seperti gambar, tulang punggungnya tegak lurus seolah-olah puncak kepalanya sedang ditahan oleh tali tak terlihat di langit. Dan mungkin kombinasi bahasa tubuh inilah yang memberiku kesan bahwa dia sedang berusaha sangat hati-hati untuk bersikap tegas tentang sesuatu.
“Hei,” kataku, “bolehkah aku bertanya satu hal?”
“Apa? Kamu tahu kamu nggak perlu minta izin. Kamu bebas bertanya sebanyak-banyaknya.”
Aku mencengkeram setang sepedaku sedikit lebih erat saat kami berjalan. “Koreksi aku kalau salah, tapi aku agak punya kesan kau sebenarnya tidak ingin berperan sebagai Juliet.”
Ushio berhenti mendadak. Beberapa langkah kemudian, aku pun ikut berhenti.
“Kenapa kamu berkata begitu?” tanyanya dengan wajah datar.
“Eh, ya, maaf kalau aku agak melenceng,” aku memulai, terbata-bata karena ekspresi Ushio yang sama sekali tak menunjukkan emosi menggerogoti kepercayaan diriku. “Dan untuk lebih jelasnya, aku juga sependapat dengan Hoshihara pada awalnya. Kupikir sebaiknya kau jalani saja, mengingat apa yang kau ceritakan sebelumnya tentang masalah Cinderella. Tapi…”
Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, “Waktu dia dan cewek lain itu mencalonkanmu untuk memerankan Juliet, aku agak menyadari kalau kamu nggak terlalu antusias dengan ide itu. Dan maksudku, setelah kupikir-pikir lagi, itu masuk akal banget, kan? Kayaknya, waktu itu kelas tiga SD waktu kamu bilang mau jadi Cinderella, jadi wajar aja kamu udah nggak terlalu suka fantasi kecil itu. Maksudku, astaga— aku selalu pengin jadi Kamen Rider waktu seusia itu, tapi kalau kamu nyuruh aku pakai kostum dan memerankannya sekarang, mungkin aku bakalan pukul mulutmu… Oh, tapi bukan berarti aku nggak boleh memerankan Juliet, atau yang kayak gitu, terus terang! Cuma penasaran gimana perasaanmu tentang semua ini, kurasa…”
Aku bisa merasakan kepercayaan diriku memudar di tengah penjelasan ini, yang berujung pada kesimpulan yang agak canggung dan tak terartikulasi—tapi Ushio mendengarkan dengan saksama sepanjang waktu. Setelah aku selesai, dia hanya menatapku dalam diam untuk beberapa saat, tatapannya membuat perutku melilit sementara aku bertanya-tanya apakah aku telah menyinggung perasaannya secara tidak sengaja. Ayolah, katakan sesuatu, sudahlah… aku memohon dalam hati, dan dia akhirnya tertawa kecil, sengau, dan tertawa geli.
“Kau benar-benar sudah memikirkan ini matang-matang.” Nadanya seperti orang dewasa yang memuji anak kecil atas hasil karyanya yang buruk.
“Y-yah, maksudku… aku tidak tahu soal itu,” kataku, tiba-tiba merasa malu.
“…Meskipun begitu, kamu punya poin yang bagus.”
Ushio menurunkan standar sepedanya dan bersandar di jok. Aku menganggap ini sebagai tanda bahwa dia ingin berhenti dan berdiskusi lebih santai tentang hal ini, jadi aku menghampirinya dan melakukan hal yang sama. Ushio menyipitkan mata untuk melawan silau matahari sambil menatap ke arah barat.
“Idemu benar sekali,” katanya. “Memang benar aku dulu sangat ingin menjadi putri seperti Cinderella waktu kecil, tapi sekarang aku sudah SMA. Jelas fantasi kekanak-kanakan itu tidak lagi menarik. Jadi ya—sejujurnya, aku bingung ketika Nanamori-san menawarkanku untuk peran itu. Tapi begitu Natsuki menyetujui nominasinya, rasanya cukup sulit bagiku untuk menolaknya saat itu, jadi aku menurutinya saja agar tidak canggung.”
Ushio tertawa kecil. Aku benar-benar mengerti; bahkan aku bisa tahu dari suasana kelas bahwa dia tidak bisa begitu saja menolak nominasi tanpa terkesan sedikit kejam kepada teman-temannya, mengkritik mereka setelah mereka bersusah payah menyuarakan dukungan mereka dan, dengan cara mereka sendiri, mencoba memvalidasi identitas barunya. Bukan berarti Ushio berutang apa pun kepada mereka, tetapi agak menakutkan membayangkan mengecewakan teman-teman sekelas seperti itu setelah mereka telah mencapai sejauh ini dalam hal penerimaan dan jelas-jelas berusaha untuk memasukkanmu. Bagi sebagian orang, itu mungkin terasa seperti bentuk pengkhianatan.
“Jadi aku benar?” tanyaku ragu. “Kau tidak mau melakukannya?”
Ushio menundukkan pandangannya, bulu matanya yang panjang menciptakan bayangan di bawah matanya.
“Yah, sejujurnya… Tidak. Aku benar-benar tidak nyaman dengan ide itu.”
Darah dingin mengalir deras di sekujur tubuhku. Tiba-tiba aku merasa jijik dengan kecerobohanku sendiri karena telah menyadari ketidaknyamanan Ushio di tengah situasi yang panas, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun untuk mencoba membantunya keluar dari situasi tersebut.
“Kalau begitu, kurasa sebaiknya kau hentikan peran itu,” kataku. “Tidak perlu memaksakan diri. Aku yakin semua orang akan mengerti kalau kau jelaskan saja kalau kau merasa sedikit tertekan. Maksudku, aku bisa langsung bilang kalau Hoshihara pasti tidak ingin kau merasa dipaksa, atau—”
“Apa—?! Tunggu sebentar!” Ushio memotong, gugup. “Sudah kubilang aku tidak nyaman! Maksudnya bentuk lampau!”
“Oh… G-gotcha, oke.” Rasa benciku pada diri sendiri langsung berubah menjadi malu ketika aku menyadari aku terlalu cepat mengambil kesimpulan. Belajarlah untuk mendengarkan, sialan , aku menegur diriku sendiri.
“Tapi sekarang,” lanjut Ushio, “aku masih ragu. Semua orang di kelas tampak jauh lebih terbuka terhadap ide itu daripada yang kukira, dan aku juga tidak merasa Natsuki sedang mencoba meningkatkan kepercayaan diriku secara artifisial. Kurasa aku merasa kurang tertekan dan lebih yakin saat ini, jadi kupikir mungkin tidak ada salahnya untuk mencobanya. Namun…” Ushio menatap pahanya. “Di saat yang sama, ada bagian lain dalam diriku yang masih merasa agak keberatan dengan ide itu. Maksudku, aku tidak tahu bagaimana reaksi orang-orang saat melihatku di atas panggung, dan akan ada banyak orang bahkan dari luar sekolah di festival budaya. Ketika aku memikirkan kemungkinan ditertawakan atau semacamnya… aku jadi cemas, kurasa. Sampai-sampai saat ini, bahkan aku sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya ingin kulakukan…”
Ushio menatapku tanpa daya.
“Menurutmu apa yang harus kulakukan, Sakuma?” tanyanya.
Jelas, apa yang Ushio inginkan untuk dirinya sendiri adalah yang terpenting. Tapi jika dia benar-benar ingin tahu pendapatku, aku punya jawaban untuknya.
“Aku… kurasa kau harus melakukannya. Jangan khawatir. Tidak akan ada yang menertawakanmu.”
“Kamu yakin?”
“Ya, aku yakin. Pokoknya, kau akan menghajar mereka sampai mati. Tunjukkan pada anak-anak desa itu kalau kau sama cantik dan berbakatnya dengan gadis-gadis lain di SMA Tsubakioka.”
Aku mengatakan ini dengan nada penuh percaya diri dan meyakinkan; Ushio menggaruk hidungnya dan mengalihkan pandangannya. Aku bisa melihat ujung telinganya memerah sedikit.
“…Baiklah kalau begitu. Kurasa aku akan berusaha sebaik mungkin.”
“Keren. Dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak membuatmu terpuruk dengan aktingku yang buruk.”
Kami berdua tertawa. Aku lega kami berhasil mengalihkan pembicaraan dari arah melankolis yang tadi—terutama karena aku benar-benar yakin Ushio sebagai Juliet akan tampil fantastis.
“Terima kasih atas dorongan kepercayaan dirimu, Sakuma.”
“Hei, jangan bahas itu. Bukannya aku benar-benar melakukan apa pun, sih…”
“Tidak, kau pasti sudah melakukannya,” katanya sambil menggelengkan kepala. “Kalau kau tidak mendesakku, mungkin aku akan memendam perasaanku dan merasa cemas sampai pertunjukan nanti. Aku senang kau bisa membaca pikiranku dengan baik.”
“Ah, ayolah. Itu bukan apa-apa, sungguh…”
Saya benar-benar merasa sedikit kesal; saya benar-benar belum melakukan sesuatu yang pantas disyukuri. Malahan, saya masih merasa bersalah karena tidak membela Ushio selama tahap casting. Namun, kekacauan emosi ini segera terhenti ketika Ushio menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, seolah berbisik pada dirinya sendiri:
“Belum lagi, aku akan… sedikit lebih nyaman denganmu berperan sebagai Romeo, kurasa… Hanya sedikit,” ulangnya, menekankan perasaannya dengan senyum malu-malu.
Sekali lagi, aku bingung harus menanggapi bagaimana. Aku tersanjung mendengarnya, tapi aku ragu apakah aku berhak mengatakan itu membuatku “bahagia”, setelah semua yang telah kita lalui akhir-akhir ini.
Ushio berdiri tegak dari posisi setengah duduknya dan meregangkan punggungnya, seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Sepertinya percakapan itu sudah berakhir—tetapi kemudian Ushio menoleh ke arahku seolah teringat sesuatu.
“Oh, ya,” katanya. “Dan sebaiknya kau juga tidak meninggalkan Natsuki sendirian. Lagipula, kau kan sesama anggota komite.”
“Y-ya, tentu saja tidak,” kataku, agak ragu dengan perubahan topik yang agak mendadak ini. “Jangan khawatir, aku tahu.”
“Keren. Aku percaya padamu,” kata Ushio lembut sambil menepuk bahuku. Lalu ia mengangkat standarnya dan mulai berjalan. Aku juga mengangkat standarku dan bergegas mendahuluinya dengan joging cepat.
***
Hari ini adalah rapat komite festival pertama kami. Hoshihara dan aku diharuskan hadir, jadi kami menuju ke ruang audio visual bersama-sama. Kami tidak tahu berapa lama rapatnya akan berlangsung, jadi kami sudah berpamitan dengan Ushio di kelas.
“Berdiri tegak, Kamiki-kun! Kamu bungkuk semua!” kata Hoshihara.
“Hm? Oh, m-maaf.”
Aku segera memperbaiki postur tubuhku. Aku pasti terlihat menyedihkan sampai-sampai dia mengkritikku, meskipun aku cukup yakin postur tubuhku tidak seburuk itu … Namun, harus kuakui aku tidak terlalu bersemangat untuk bertemu dengan anggota komite dari semua kelas lain hari ini, jadi mungkin itu ada hubungannya. Aku orang yang cukup pemalu, jadi pertemuan kelompok besar seperti ini selalu membuatku sangat gugup sebelumnya.
“Kesan pertama itu penting banget buat hal-hal kayak gini, lho,” kata Hoshihara. “Harus berani, atau mereka cuma bakal ngeliat kamu kayak orang yang gampang diganggu dan dihajar sampai babak belur!”
“Saya sangat meragukan hal itu akan terjadi,” jawab saya.
Menurut dia, sekolah menengah macam apa ini yang penuh dengan kekacauan dan kekacauan?
Berbeda sekali dengan kurangnya antusiasme saya, Hoshihara tampaknya bersemangat untuk maju. Saya sudah lama bertanya-tanya mengapa dia mengajukan diri menjadi anggota komite; sepertinya itu tidak sesuai dengan kepribadian atau prestasi akademiknya… tapi mungkin saya salah. Meskipun saya mempertimbangkan untuk langsung bertanya kepadanya, mengingat dia berjalan tepat di sebelah saya, ruang audio visual terlihat sebelum saya sempat memulai pembicaraan. Saya membujuk diri sendiri untuk tidak bertanya, yakin bahwa saya bisa bertanya kapan saja. Maka saya pun menahan diri saat kami berjalan menuju ruangan itu.
Saat masuk, kami disambut oleh layar proyektor besar di dinding sebelah kiri, dengan tiga meja panjang persegi panjang yang disusun membentuk huruf U di sekelilingnya. Sekitar separuh kursi lipat sudah terisi oleh anggota dewan lainnya yang sibuk menunggu rapat dimulai. Di sudut ruangan, saya melihat Pak Iida, guru kimia, bersandar di dinding dan berusaha keras untuk tidak menguap—tampaknya tidak terlalu senang karena ia dibebani peran pengawas.
“Kelas dan angkatan?” tanya anak laki-laki yang berdiri di ujung ruangan, di depan layar. Aku mengenali wajahnya: seingatku, dia ketua OSIS. Aku tidak ingat seberapa besar peran OSIS dalam menyelenggarakan festival budaya tahun lalu, tetapi tampaknya mereka terlibat sampai taraf tertentu.
Aku menjawab bahwa kami dari Kelas 2-A, dan anak laki-laki itu menunjukkan dua kursi kosong untuk kami duduki. Hoshihara dan aku membungkuk sopan dan duduk. Waktu sudah menunjukkan pukul empat lewat; sepertinya rapat akan segera dimulai begitu para anggota komite dari setiap kelas tiba. Saat aku melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang lain yang kukenal, aku melihat sepasang mata di sebelah kanan menatapku tajam. Itu adalah seorang anak laki-laki yang duduk di sudut ruangan, menyandarkan kepalanya di atas satu tangan dengan cemberut yang tak menyenangkan. Karena terkejut, aku memutuskan kontak mata—tetapi meskipun begitu, anak laki-laki itu tetap melotot.
A-apa sih yang orang ini mau? Dia bikin aku takut…
Aku sama sekali tidak tahu kenapa dia cemberut padaku, tapi aku tahu nama anak laki-laki itu. Matanya berbentuk almond, dan dia termasuk pria jangkung berkulit cokelat yang langsung bisa kutebak tipe atletis. Dalam hal ini, aku tahu dia anggota tim lari, karena dia Fusuke Noi—mantan rekan setim Ushio yang menyerbu kelas kami dan membuatnya jengkel di hari pertama dia masuk sekolah mengenakan seragam perempuan.
Meskipun aku tahu ada permusuhan antara dia dan Ushio, sama sekali tidak ada alasan di antara aku dan dia yang bisa membuatnya bermusuhan seperti itu; aku belum pernah bertukar sepatah kata pun dengannya. Itu masih cukup membuatku gelisah, jadi aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak bertatapan dengannya sementara anggota komite yang tersisa berhamburan masuk ke ruang audiovisual satu per satu—sampai akhirnya, orang terakhir yang kami tunggu-tunggu melenggang masuk.
“Ah, sial. Sepertinya kalian sudah mulai tanpa aku.”
Ya Tuhan. Tolong jangan.
Aku kenal wajah itu—senyum penipu berbibir terbuka itu dan wajah tampan yang menyebalkan itu dengan mata sayu yang menonjol di bawah rambut lebatnya.
Itu Sera. Itsuku Sera. Rupanya, dia anggota komite laki-laki Kelas D, datang agak terlambat (dan cukup lama setelah rekan perempuannya). Dia sedang memegang sekotak susu kopi yang terbuka di satu tangan.
“Cepat duduk,” kata ketua OSIS. “Dan dilarang makan atau minum di ruang audio visual.”
“Oh, salahku. Maaf!” Sera menghabiskan sisa minumannya sekaligus, lalu melempar karton kosong itu ke tempat sampah terdekat dengan suara “alley-oop” sebelum berjalan santai ke satu-satunya kursi kosong yang tersisa. Sepanjang jalan, dia melirik dan menatapku—dan untuk sesaat, matanya melebar, lalu menyipit lagi saat bibirnya melengkung membentuk seringai predator yang baru saja melihat mangsanya berikutnya.
Alam semesta memiliki selera humor yang buruk.
Setelah kami selesai dan membiarkan semua anggota panitia festival memperkenalkan diri satu per satu, kami menutup tirai untuk menonton tayangan slide melalui proyektor langit-langit di tengah ruangan. Itu adalah panduan orientasi yang memberikan gambaran umum tentang apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi anggota panitia.
Beberapa slide pertama merupakan ringkasan umum dari berbagai tugas yang terlibat dalam menjalankan peran kami: memeriksa secara berkala setiap kelas untuk memastikan mereka berada di jalur yang tepat dalam persiapan acara, menangani prosedur administrasi umum selama festival berlangsung, dan sebagainya. Setelah itu, kami membahas beberapa potensi jebakan dan insiden yang terjadi di festival tahun-tahun sebelumnya yang perlu kami waspadai, serta pengaturan kontingensi cuaca yang mungkin diperlukan jika hujan turun pada hari itu. Panduannya cukup komprehensif. Ketika akhirnya layar proyektor mati, ketua OSIS menyalakan kembali lampu.
“Baiklah, saya rasa itu akan memberi Anda gambaran dasar tentang apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini,” ujarnya. “Nah, tanpa basa-basi lagi, saya ingin melanjutkan dan menetapkan peran spesifik masing-masing, dimulai dengan ketua komite. Ada yang mau mencoba menjadi pemimpin?”
Tak seorang pun siswa yang mengangkat tangan. Dari sekian banyak posisi di panitia festival, ketua panitia memiliki tanggung jawab paling besar dan karenanya beban kerja paling besar. Fakta ini telah terbukti dalam presentasi tadi. Kebanyakan orang pasti akan menghindar jika menghadapi tantangan seperti itu.
Meski begitu, saya berasumsi sebagian besar siswa yang berkumpul di sini belum setuju menjadi anggota komite tanpa sedikit bujukan dari guru mereka. Kalau begitu, yang kami butuhkan hanyalah satu siswa yang memang secara sukarela menjadi pemimpin alami untuk maju dan mengambil alih. Saya cukup yakin seseorang yang memenuhi syarat akan segera mengangkat tangan—dan memang benar. Tapi ternyata dia orang terakhir yang saya duga. Dia adalah Hoshihara.
“Saya ingin mencobanya!” katanya singkat, lalu menurunkan tangannya.
Y-yah, sial… Sekarang ada kejutan . Aku benar-benar tidak mengantisipasi perubahan keadaan ini . Membayangkan dia tidak hanya mengajukan diri sebagai anggota tetapi juga menjadi ketua komite ? Aku bertanya-tanya kekuatan pendorong aneh apa yang telah mengendalikan Hoshihara yang kukenal.
“Ooh, ya! Keren banget, Natsuki-chan! Tunjukkan siapa bosnya!” Sera menyela dari pinggir lapangan.
Hoshihara meringis dan menertawakannya sebelum akhirnya menenangkan diri. “Eh, ngomong-ngomong, ya! Aku Natsuki Hoshihara, dari Kelas 2-A. Aku janji akan melakukan yang terbaik, kalau kalian semua mau menerimaku!” Ia memperkenalkan diri seolah-olah sedang wawancara kerja sebelum membungkuk dalam-dalam kepada seluruh ruangan.
Baik Pak Iida maupun ketua OSIS tidak keberatan. Mereka menyambut Hoshihara dengan hangat dan meminta tepuk tangan, yang segera direspons oleh saya dan teman-teman sekelas. Hoshihara, pada gilirannya, menundukkan kepalanya dengan anggun beberapa kali ke segala arah untuk menunjukkan rasa terima kasih, lalu menghela napas berat seolah-olah baru saja menyelesaikan tugas besar di tempat kerja dan siap untuk istirahat. Juru tulis yang ditunjuk OSIS kemudian menulis ” KETUA KOMITE: HOSHIHARA ” di papan tulis.
“Baiklah kalau begitu. Selanjutnya, kita perlu memilih tim pameran kita…”
Rapat berlanjut dengan tempo yang relatif cepat, hingga semua peran yang perlu diisi telah dibagi di antara anggota dewan yang tersisa. Saya akhirnya ditempatkan di tim administrasi—posisi yang saya pilih sebagai yang paling tidak menyita waktu, mengingat saya tahu saya akan semakin sibuk dengan latihan drama kelas kami seiring semakin dekatnya festival.
“Baiklah, semuanya. Kurasa rapat ini bisa kita akhiri. Kerja bagus hari ini, semuanya,” kata ketua OSIS, setelah mempersilakan kami pulang sekitar pukul setengah enam. Semua orang mulai mengemasi barang-barang mereka dan berdiri dari tempat duduk.
Sebelum aku sempat melakukan hal yang sama, Noi berjalan dari ujung ruangan yang berlawanan ke tempatku duduk. Dia tak berkata sepatah kata pun, hanya menatapku dengan tatapan dingin. Meskipun aku agak gelisah di dalam hati, aku berhasil mengucapkan beberapa patah kata.
“A-apa yang kamu inginkan?” tanyaku.
“Ada apa antara kamu dan Ushio, ya?” Kalimat itu saja sudah cukup untuk memberiku gambaran yang cukup jelas kenapa dia memelototiku tadi. Jadi, memang ada hubungannya dengan Ushio.
Aku bangkit dari tempat dudukku. Harus kuakui, memang ada rasa intimidasi tersendiri, berdiri berhadapan dengan pria jangkung dan berotot seperti Noi. Dia menatapku dari atas, baik saat aku duduk maupun berdiri. Malahan, berdiri justru membuat perbedaan tinggi badan kami yang drastis semakin kentara, jadi aku agak berharap tetap duduk dan bersikap tenang.
“Bukan apa-apa,” jawabku. “Kami cuma teman baik yang sudah berteman lama, itu saja.”
“Oh, ya ampun,” kata Noi dingin, tampaknya tidak puas dengan jawaban ini. “Terkejut kau masih bisa tahan berada di dekat orang aneh itu.”
Rasa permusuhan menjalar di hatiku. “Apa maksudnya ini ?”
“Maksudku, siapa sih yang mau ketahuan nongkrong sama cowok yang berdandan kayak cewek? Pasti bikin mual banget, kan?”
Aduh…
Serangkaian emosi yang saling bertentangan mulai berputar-putar di kepalaku. Aku tahu seharusnya aku marah, tapi malah aku malah merasa sangat tertekan. Dia jelas-jelas pernah menghabiskan banyak waktu bersama Ushio saat dia masih di tim lari. Dan jika dia begitu terang -terangan berprasangka dan kurang empati, bahkan kepada orang asing sepertiku, aku hanya bisa membayangkan bahwa sifat menghakiminya telah menyakiti Ushio lebih dari beberapa kali di masa lalu, entah dia sadar atau tidak. Tentu, ketidakmampuanku untuk memahami atau menghakimi perjuangan Ushio mungkin telah membuatnya cukup bersedih di masa lalu—atau bahkan sampai hari ini—tapi setidaknya aku berbeda dari si brengsek ini .
“Entahlah apa maksudmu,” kataku sambil melotot ke arah Noi, “tapi aku sudah tahu kalau Ushio sudah mengambil keputusan yang tepat dengan keluar dari tim lari.”
“Maaf?” kata Noi, alisnya berkedut karena marah.
Aku tak menyerah. Aku berdiri teguh menghadapi intimidasinya dan berpegang teguh pada apa yang kuyakini benar. Namun, tatapan kami tak bertahan lama.
“H-hei!” seseorang memanggil dari kejauhan, dan kami berdua menoleh. Ternyata Hoshihara, gemetaran saat ia berjalan tertatih-tatih ke tempat kami berdiri. “A-aku rasa kau harus minta maaf, Noi-kun. Itu sungguh tidak pantas.”
Noi mengernyit jijik dan mendecakkan lidahnya dengan nada mencela. “Terserah. Persetan dengan kalian berdua,” gerutunya, lalu meninggalkan ruangan dengan enggan.
Aku hampir jatuh berlutut di tempat. Namun, setelah menenangkan diri dan melihat sekeliling, aku melihat beberapa anggota komite lain, selain Pak Iida, masih berada di ruangan itu, semuanya melihat ke arah sini. Kupikir mereka mungkin akan turun tangan jika keadaan mulai rusuh. Untungnya, sepertinya aku aman.
“Noi-kun memang bukan orang yang paling ramah di sini, ya?” kata Hoshihara.
“Ya… Tidak yakin apa masalahnya.”
Meskipun aku sudah bilang begitu, aku cukup paham betapa rumit dan frustrasinya perasaannya terhadap Ushio. Kurasa dia mungkin anak laki-laki di tim yang paling dekat dengan Ushio di awal tahun pertama, dan yang paling banyak menghabiskan waktu bersamanya. Itu tentu menjelaskan kenapa dia begitu sulit menerima perubahan Ushio—yang bisa kupahami, sampai batas tertentu. Tapi begitu berubah menjadi prasangka dan hinaan, di situlah aku menarik garis batas. Aku tak bisa menoleransi itu sedetik pun, yang sama dengan alasan mengapa aku tahu aku tak akan pernah bisa akur dengannya.
“Kau bisa mengulanginya. Dasar brengsek, kan? Aku pasti tidak mau ketahuan nongkrong sama cowok kayak gitu,” terdengar suara dari sampingku yang jelas-jelas bukan suara Hoshihara. Seandainya bukan Sera, aku rasa kami berdua pasti akan mengangguk.
“Tidak mencari simpati darimu , ” gerutuku.
“Ah, ayolah… Jangan begitu. Kita sama-sama anggota komite, kan? Seharusnya kita berteman! Oh, ngomong-ngomong—kamu mau tahu bagaimana aku akhirnya dicalonkan?”
“Tidak, sebenarnya aku tidak yakin.”
“Jadi aku bolos kelas hari itu, ya? Dan mereka cuma milih aku buat dibantai karena aku nggak ada di sana buat nolak! Lucu banget, ya?!”
“Tenang saja, Bung. Aku tidak peduli.”
“Astaga, kamu benar-benar keras kepala… Oh ya, jadi hei! Maukah kalian berdua mampir dan makan sesuatu dalam perjalanan pulang, atau tidak? Sepertinya kita harus banyak ngobrol, tahu? Kita bisa ngobrol santai sambil makan kentang goreng atau apalah. Ayo, aku akan buru-buru ke stasiun! Yang terakhir di sana harus membeli makanan semua orang!”
Orang ini tidak punya tombol mati; aku yakin kalau kami membiarkannya, dia akan terus bicara sampai mati rasa di alam semesta. Aku perhatikan Hoshihara sudah mencuri pandang ke arah pintu masuk beberapa saat, mungkin sangat ingin pergi. Aku harus melepaskan lintah ini dari kami agar kami bisa segera pergi dari sini.
“Begini,” kataku. “Aku harus pergi, jadi kau juga harus pulang. Sendirian.” Aku memunggungi Sera dan memberi isyarat kepada Hoshihara dengan mataku bahwa sudah waktunya untuk pergi. Namun, tepat saat kami hendak pergi, suara Sera yang menyebalkan kembali mengganggu kami.
“Ooh?” katanya. “Jadi kamu dan Natsuki-chan jalan kaki pulang bareng, cuma berdua, ya? Menarik sekali…”
Bahkan tanpa menoleh, aku bisa membayangkan senyumnya yang angkuh dan bengkok dengan sempurna di benakku. Rasa tidak nyaman yang masih tersisa dari suaranya yang menjengkelkan di gendang telingaku dengan cepat meresap ke otakku, yang kemudian berubah menjadi kecemasan murni. Aku tak bisa menghilangkan perasaan seolah-olah aku baru saja terjebak dalam posisi yang sangat membahayakan oleh orang terakhir yang ingin kucari tahu. Tapi yang bisa kulakukan untuk saat ini hanyalah berpura-pura tidak mendengarnya.
Saat aku dan Hoshihara keluar dari gedung, matahari sudah mulai terbenam. Langit barat diwarnai merah menyala, dan aku bisa melihat beberapa kelelawar terbang di atas sawah di dekatnya. Dari timur, angin kering dan dingin bertiup, menandakan datangnya musim gugur.
“Sepertinya kita akan mengalami beberapa bulan yang tidak menyenangkan, ya?” kata Hoshihara lirih. Aku berasumsi dia sedang membicarakan Noi dan Sera.
“Mungkin begitu, ya,” kataku. “Tapi kalau ada yang bisa mengatasinya, itu Anda, Ibu Ketua Komite.”
“Ya ampun, jangan panggil aku begitu! Tekanannya jadi sepuluh kali lebih berat!” Meskipun jeritan ketakutannya yang berlebihan itu dimaksudkan sebagai lelucon, ada sedikit rasa gugup yang nyata di dalamnya.
“Harus kuakui, aku cukup terkejut kau mau menawarkan diri.”
“Ohhh, ya. Aku sendiri agak terkejut, sejujurnya. Biasanya aku bukan tipe orang yang melakukan hal seperti itu.” Hoshihara tersenyum malu-malu. Bahkan dia tahu itu tidak seperti biasanya.
“Apakah kamu sudah lama berpikir untuk mencoba menjadi ketua komite atau semacamnya?”
“Mmm, tidak, tidak seperti itu. Malahan, saya ingat berpikir, ‘Wah, kedengarannya terlalu banyak pekerjaan untuk orang seperti saya!’ ketika mereka membicarakannya tahun lalu.”
“Oh, serius? Terus kenapa kamu jadi sukarelawan?” tanyaku sekadar penasaran—dan raut wajah Hoshihara berubah menjadi tatapan kesepian dan penuh kerinduan.
“Kurasa aku hanya merasa seperti, entahlah… aku tidak bisa terus seperti ini selamanya, kau tahu? Maksudku, aku selalu mengandalkan orang lain dan mengandalkan mereka untuk mengatasi hal-hal sulit untukku… seperti yang kau tahu.”
Aku ingin sekali menyangkalnya, tapi sayangnya, aku teringat beberapa kejadian di mana dia benar-benar melakukannya. “Yah… ya, mungkin sedikit.”
“Aku benar-benar menekanmu di akhir semester lalu, ketika aku memintamu belajar mati-matian untuk mendapatkan peringkat pertama di ujian akhir… Dan kau malah maju dan berhasil melakukannya. Gila bagiku. Sementara itu, aku di sini duduk di peringkat 81…”
“Hei, tapi itu tetap sebuah kemajuan, kan? Bukankah kamu bilang kamu dapat peringkat ke-176 sebelumnya?”
“Tunggu, kenapa kamu ingat angka persisnya?! Ya Tuhan, itu sangat memalukan! Bagaimana caranya aku menghapus otakmu?! Ugh… Tapi ya, aku sendiri belajar cukup keras untuk ujian terakhir ini, terutama karena kita akan berkumpul untuk sesi belajar di restoran dan sebagainya… Lagipula, nilaiku bukan yang terpenting di sini!”
Dia resmi menutup buku tentang topik itu. Sepertinya saya perlu lebih hati-hati memilih kata-kata.
“Kurasa yang ingin kukatakan di sini,” lanjutnya, “adalah berkat kamu yang jadi juara pertama di kelas kami, kami berhasil membuat Sera-kun mundur. Bukan berarti itu penting, sih, karena dia bahkan tidak masuk sepuluh besar. Dan setelah itu, aku memergokimu dan Ushio-chan di puncak tangga sedang melakukan, yah… kau tahu. ‘Perbuatan itu,’ begitulah.”
Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskan padanya bahwa ungkapan berbelit-belit ini menyiratkan bahwa kami melakukan sesuatu yang jauh lebih memalukan di sana tanpa mengalihkan pembicaraan, jadi aku menahan diri.
“B-benar, ya,” kataku. “Lalu? Bagaimana dengan itu?”
“Yah, waktu pertama kali lihat itu, aku ingat aku benar-benar terguncang olehnya… Tapi kemudian aku punya, kayak, kilasan wawasan sesaat, kan? Kayak pencerahan, deh. Kayak kilatan petir yang menyambar entah dari mana, dan tiba-tiba aku bisa melihat semuanya jauh lebih terang dan lebih jelas.”
“Hah. Dan pencerahan apa ini sebenarnya?”
Kalau aku terus membiarkan orang lain melakukan semua hal sulit untukku, mereka semua akan belajar untuk berkembang dan berkembang, sementara aku tetap sama dan tertinggal. Aku benar-benar tidak bisa melupakan pikiran itu hampir sepanjang liburan musim panas. Tapi ya! Intinya, aku hanya ingin belajar untuk berkembang juga, dan membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku juga punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang hebat sendiri… kalau itu masuk akal? Ah ha ha ha, entahlah! Aku tidak yakin itu masuk akal!
Hoshihara menendang kerikil yang tergeletak di jalan dengan kakinya dan membuatnya terlempar. Ia mencoba menertawakannya di akhir, tetapi saya bisa menebak dengan tepat apa yang ingin ia katakan dan kecemasan apa yang sedang ia hadapi. Ia mengajukan diri sebagai ketua panitia festival karena ingin menerima tantangan yang akan membantunya berkembang. Saya merasa ini mungkin akan menjadi pilihan yang picik pada akhirnya, tetapi tetap saja merupakan pilihan yang valid. Dan bahkan jika ia akhirnya gagal dalam jangka panjang, ia akan tetap mendapatkan banyak keterampilan dan pengetahuan berharga dari pengalaman tersebut, jadi tetap ada nilai tambah dalam mencoba.
“Tidak, kurasa itu sudah menjawab pertanyaanku. Tenang saja, aku akan mendukungmu.”
“Ah, makasih! Aduh, kamu bikin aku malu banget!” katanya sambil ketawa kecil yang manis.
Dia benar-benar gadis yang manis dan jujur—cukup membuat saya sulit mempercayai betapa berharganya dia.
“Tapi jangan khawatirkan aku. Kau punya urusan sendiri, kan, Kamiki-kun? Harus kuakui, kurasa aku paling menantikan pementasan Romeo dan Juliet kita di festival tahun ini. Aku sudah memutuskan akan mencari cara untuk menontonnya secara langsung, sesibuk apa pun aku sebagai ketua panitia!” Suaranya penuh harap saat ia menyipitkan mata dan menatap jauh ke kejauhan. “Ya, aku sangat menantikannya…”
Di balik kegembiraannya yang tulus, ada sedikit nada melankolis dalam beberapa bisikan terakhir itu. Mengingat Hoshihara bukan salah satu aktor kami, dia hanya akan mengerjakan drama di balik layar—dan itupun, saya berasumsi dia tidak akan bisa banyak membantu membuat properti, kostum, atau persiapan lainnya karena sekarang dia memiliki banyak tugas lain sebagai ketua komite. Saya bertanya-tanya apakah mungkin dia merasa sedikit terabaikan memikirkan hal itu.
Atau mungkin…
“Hei, Hoshihara. Bagaimana perasaanmu tentang Ushio sekarang?”
“Hah? Apa maksudmu?” tanyanya dengan wajah kosong. Rupanya, aku perlu lebih spesifik.
“Apa kau bilang kau masih punya perasaan padanya? Seperti, perasaan romantis, maksudku.”
“Bweh?!”
Rahangnya ternganga, dan ia tertegun sejenak, seolah-olah pertanyaan ini tiba-tiba muncul di saat yang tak terduga. Sesaat kemudian, tulang keringnya terbentur pedal sepeda dan menjerit kesakitan, lalu berhenti di tempat dan mulai menggosok-gosoknya dengan keras.
“Ih! Kenapa tiba-tiba kamu tanya begitu ?!” katanya.
“Yah, maksudku, kau tahu…” kataku sambil menunggu dia mulai berjalan lagi. “Kurasa aku hanya berpikir kalau kau masih menyukainya, mungkin aku yang memerankan Romeo sementara dia yang memerankan Juliet bukanlah skenario yang paling menyenangkan untukmu…”
“Wah, Kamiki-kun. Kamu langsung ke sana, ya? Harus kuakui, berani sekali,” jawabnya, matanya penuh celaan. Tapi dia tidak salah; sekali lagi, mungkin aku bisa lebih berhati-hati dalam memilih kata- kataku .
“M-maaf. Kurasa aku hanya sedikit penasaran, itu saja…”
“Tidak apa-apa. Bukannya itu penting.” Dia berbalik dengan kesal, lalu melanjutkan perjalanan pulang. Aku tidak yakin apakah aku benar-benar membuatnya kesal atau tidak, jadi aku bergegas maju untuk melihat dan mengamati ekspresinya.
Tepat saat aku menyusulnya, dia membuka mulutnya dengan mata tertunduk dan berkata, “Aku masih belum tahu, ya. Astaga, aku mungkin lebih bingung sekarang daripada beberapa bulan yang lalu. Tapi yang kutahu adalah …” Dia melirikku. “Kalau Ushio-chan akan memerankan Juliet, kurasa kau memang satu-satunya pilihan yang tepat untuk memerankan Romeo-nya.”
“Kau pikir begitu, ya?”
Hoshihara dan aku sampai pada kesimpulan yang sama, meskipun kupikir mungkin itu akan sedikit lebih sulit baginya untuk menerima kenyataan daripada bagiku. Aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika aku tidak dinominasikan untuk peran itu oleh teman sekelasku yang lain. Akankah Hoshihara akhirnya menawarkanku? Rasanya tidak terlalu absurd untuk berpikir dia mungkin melakukannya, mengingat apa yang baru saja dia katakan.
Kami hampir sampai di persimpangan tempat jalan kami bercabang. Waktu sudah menunjukkan pukul enam lewat, dan matahari sudah terbenam separuh di bawah cakrawala, memberi jalan bagi bintang-bintang pertama senja yang menjulang tinggi di langit barat. Sesampainya di persimpangan, kami berdua berhenti dan berbalik menghadap satu sama lain.
“Hei…Kamiki-kun?”
“Ya?”
Wajahnya berubah serius. “Menurutmu apa arti mencintai seseorang?”
Pertanyaan itu agak mendadak dan sulit dijawab. Namun, Hoshihara sudah mengerucutkan bibirnya, seolah bertekad menunggu jawabanku dengan sabar. Aku merasa kurang tepat menjawab dengan candaan atau mengabaikannya sementara ia jelas-jelas bersungguh-sungguh.
“Wah, itu pertanyaan yang sulit…”
Aku merenungkannya. Apa artinya mencintai seseorang? Tak ada satu jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini. Jika kau bertanya kepada sepuluh orang, kemungkinan besar kau akan mendapatkan sepuluh jawaban yang sama sekali berbeda. Tapi itu semua semakin memperkuat alasan mengapa jawaban setengah hati dan klise tak akan berhasil di sini. Sambil berdiri di sana ragu-ragu, aku bisa merasakan detik-detik berlalu—lima, lalu sepuluh. Hoshihara masih menunggu dalam diam. Seekor gagak berkokok keras di atas kepala. Baru setelah gemanya mereda, aku menemukan jawaban yang kusuka.
“Yah, kurasa ketika kau benar-benar mencintai seseorang… kau ingin selalu berada di dekatnya dan berada dalam lingkup pergaulannya, kau tahu maksudku? Dan aku tidak hanya bicara kedekatan fisik, tapi juga kedekatan mental. Maksudku, kau ingin mereka memperhatikanmu, memperhatikanmu, dan tahu perasaanmu terhadap mereka…”
“Kau ingin mereka memperhatikanmu…” ulang Hoshihara, mungkin mencoba mencerna maksudku. Lalu, dengan ekspresi lembut, ia berkata, “Ya. Kurasa aku mengerti, agak.”
“Ngomong-ngomong, aku mungkin bukan orang yang tepat untuk bertanya tentang hal-hal seperti ini,” kataku. “Sejujurnya, kamu mungkin akan menemukan jawaban yang lebih baik di manga shojo atau novel roman mana pun…”
“Ah, kurasa tidak. Lagipula, kamu sendiri juga pembaca yang rajin, Kamiki-kun, dan itu salah satu alasan aku ingin tahu sudut pandangmu.”
“O-oh, benarkah? Baiklah kalau begitu… Senang aku bisa membantu, kurasa.”
Setelah itu, Hoshihara menunggangi sepedanya dengan satu kaki dan mengucapkan selamat tinggal singkat sebelum mengayuh sepedanya menyusuri jalan. Saya hanya berdiri di sana sejenak, memperhatikan dalam diam saat ia berbelok di tikungan.
“Apalah arti mencintai seseorang, ya…?” gumamku tanpa suara.
Tiba-tiba, aku merasa sangat sedih. Kemungkinan besar, dia tidak akan pernah tahu bahwa definisi yang kuberikan hanyalah deskripsi kata demi kata tentang perasaanku padanya.
***
Kini hanya tersisa sekitar sebulan lagi hingga festival budaya, dan semua kelas telah mulai mempersiapkan stan, pameran, atau pertunjukan mereka masing-masing dengan sungguh-sungguh. Mulai hari ini, Kelas 2-A akan mulai berlatih peran dan membuat kostum, properti, dan lain-lain.
Begitu jam pelajaran keenam selesai dan guru meninggalkan kelas, seorang gadis berkacamata berbingkai merah melangkah maju. Namanya Todoroki, dan dialah siswi yang ditunjuk sebagai sutradara panggung saat pembagian peran untuk para pemain dan kru. Dia adalah siswi klub seni, seorang penggemar berat film yang selalu bermimpi menyutradarai filmnya sendiri suatu hari nanti. Rasanya kata “sutradara” saja sudah cukup menarik untuk membuatnya mengajukan diri mengambil alih kendali.
“Baiklah, semuanya! Dengarkan! Kita belum pulang!” katanya. “Hei! Kau di sana! Ada apa? Kalian ada rapat klub setelah ini? Tunggu sebentar, ya? Ini cuma sebentar!”
Todoroki selalu tampak seperti sosok yang ambisius dan mampu mengatur segalanya, tetapi ia tampaknya benar-benar tertarik untuk menjadikan drama kecil kami sukses besar. Saya merasa yakin bisa mengandalkannya untuk menyelesaikan pekerjaan.
Seperti yang kalian semua tahu, kita hanya punya waktu satu bulan lagi sampai malam besar itu! Karena itu, kita harus mulai berlatih dan mempersiapkan diri dengan cepat mulai hari ini! Aku tahu beberapa dari kalian sudah sibuk dengan kegiatan ekstrakurikuler dan pekerjaan paruh waktu, tapi aku tetap sangat menghargai partisipasi kalian sebaik mungkin. Aku akan bertanggung jawab atas instruksi akting dan penyutradaraan panggung, sementara Nanamori-san akan mengawasi semua produksi set dan persiapan di belakang panggung. Tenang saja, kita berdua akan memberikan 110 persen kemampuan kita!
Bingung karena namanya dipanggil, Nanamori berdiri dan membungkuk dalam-dalam.
“Tapi butuh lebih dari satu orang untuk mementaskan sebuah drama. Jadi, mari kita semua bersatu dan menjadikan ini pementasan Romeo dan Juliet terbaik yang pernah ada di kota ini!”
Todoroki mengangkat tinjunya dan bersorak kegirangan, yang dibalas oleh beberapa teman sekelas kami, meskipun dengan antusiasme yang lebih moderat. Suasananya tidak buruk, secara keseluruhan—semangat kelas secara keseluruhan cukup tinggi. Kecuali satu hal.

“Sungguh lelucon,” kata satu-satunya yang tidak setuju.
Aku menoleh ke arah suara itu dan melihat bahwa orang itu tidak lain adalah Nishizono—siku di atas meja, pipi di atas tangannya, dan ekspresi tidak senang di wajahnya.
“Susah banget jadi yang terbaik kalau ada cowok yang main Juliet,” lanjutnya. “Kurasa itu mungkin mendiskualifikasi kita sejak awal. Yakin nggak mau pertimbangkan lagi pilihan pemeran kita sebelum kita jadi bahan tertawaan seantero kota?”
Seluruh kelas terdiam mendengar kekesalan yang terang-terangan ditujukan padanya. Ushio, yang menjadi sasaran hinaan itu, menarik bahunya dan menundukkan kepala, sia-sia mencoba menghindari tatapan canggung itu. Melihatnya terduduk di kursinya seperti ini membuat dadaku sakit, dan itu membuatku dipenuhi amarah yang meluap-luap terhadap Nishizono. Aku berharap dia punya kesempatan untuk mendinginkan kepalanya dan sedikit lebih dewasa selama liburan musim panas, tetapi sepertinya itu terlalu optimis. Aku tidak melihat ada perbaikan dalam sifat tiraninya. Seandainya Bu Iyo ada di sini, dia pasti akan meluruskan Nishizono. Tapi tidak ada guru atau anggota fakultas yang hadir dalam pertemuan kelas yang jujur ini. Yang berarti salah satu dari kami harus berdiri dan memarahinya.
“Tidak perlu dipertimbangkan lagi…” kataku, merasa aku sama cocoknya dengan siapa pun untuk pekerjaan ini. Memang, aku bukan tipe orang yang berani bicara di saat-saat seperti ini, tapi aku tidak bisa hanya berdiam diri sementara teman baikku dilecehkan, jadi aku mengumpulkan keberanian yang tersisa.
“Ugh. Kau lagi?” kata Nishizono, memutar kepalanya untuk menatapku dengan ekspresi jijik di wajahnya, tapi tanpa repot-repot membalikkan badan di kursinya. Aku bisa saja mengatakan hal yang sama padanya setelah sekian kali dia mendapat masalah karena melecehkan Ushio semester lalu—tapi rupanya konsep penyesalan bukanlah sesuatu yang familiar baginya.
“Kenapa sih kamu peduli siapa yang memerankan Juliet, hah?” lanjutku. “Dia kan nggak ganggu siapa-siapa.”
“Tentu, mungkin kalian tidak terganggu , tapi aku jamin penonton kami akan merasa jijik.”
“Enggak, nggak akan!” kata Hoshihara, sambil bangkit dari kursinya untuk membantah Nishizono menggantikanku. “Ushio-chan lebih dari cukup cantik untuk memenuhi kriteria itu! Dan dia juga bukan laki-laki…”
“Pah,” kata Nishizono. “Ya, kita lihat saja nanti apa kata penonton. Kurasa lebih baik dia berhenti sekarang sebelum mempermalukan dirinya sendiri.”
Hoshihara menundukkan pandangannya karena frustrasi; saya berasumsi ia mengalah menghadapi kekasaran Nishizono yang tak termaafkan dan menolak untuk meningkatkan ketegangan. Yang mengejutkan saya, ia segera mengangkat kepalanya dan memelototi gadis itu dengan tekad membara.
“Jika ada yang mempermalukan diri mereka sendiri di sini, itu kamu , Arisa!”
Ini benar-benar mengejutkan saya. Belum pernah saya melihat Hoshihara membantah Nishizono secara terbuka. Bahkan bahu Nishizono sedikit tersentak, betapa tak terduga tindakan pembangkangan terbuka ini.
“Maaf, ya…?” kata Nishizono. “Saya tidak yakin apa maksudnya.”
Tutur katanya kurang tajam seperti biasanya. Ia benar-benar agak bingung dengan balasan tak terduga ini. Tepat saat itu, seseorang menyela untuk memberi Nishizono sedikit pendapat, meskipun terbata-bata.
“E-eh, permisi!” kata Nanamori. “Aku cuma mau bilang, um… Aku b-benar-benar berpikir Tsukinoki-san juga cocok jadi Juliet, jadi, um…”
Ini kejutan lain lagi; bagi seorang introvert seperti Nanamori untuk melawan Nishizono rasanya hampir tak terbayangkan. Memang, ia melakukannya dengan suara lembut dan sayu, tetapi suaranya masih cukup keras untuk mencapai telingaku dari tempatku duduk di barisan paling belakang, jadi kukira semua orang di kelas juga mendengarnya. Namun, tidak seperti Hoshihara, Nishizono cepat-cepat menunjukkan amarahnya kali ini. Ia menggertakkan gigi dan menatap Nanamori dengan tatapan yang bisa menembus pelat besi. Gadis yang satunya meringkuk ketakutan.
“Aku juga tidak melihat masalah dengan Tsukinoki yang memerankan Juliet,” kata Todoroki, memancing amarah Nishizono. “Dia sama imutnya seperti gadis lainnya. Lagipula, gender memang tidak pernah dianggap penting dalam teater sejak awal. Di zaman Shakespeare, semua karakter perempuan diperankan oleh laki-laki. Dan lihat saja Takarazuka, di mana semua laki-laki diperankan oleh perempuan.”
Saya tidak bisa tidak berpikir dia sedikit salah paham tentang menerima Ushio sebagai gadis sungguhan dengan argumen ini, tetapi saya rasa itu tetap merupakan dorongan ke arah yang benar. Senang melihat orang-orang berusaha lebih keras untuk memahami dan menerima identitas Ushio (meskipun ada beberapa kesulitan). Perubahan menyeluruh ini telah dimulai sebelum liburan musim panas, tetapi sekarang rasanya Nishizono adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh kelas kami, dan kami mengepungnya dari semua sisi. Dia melihat sekeliling ruangan, putus asa untuk menemukan setidaknya satu orang lain yang mungkin memihaknya—tetapi setiap siswa yang berkontak mata dengannya segera memalingkan muka. Bahkan mereka yang biasanya berteman baik dengan Nishizono menolak untuk menerimanya kembali dalam hal ini. Maka, karena tidak punya pilihan lain, dia hanya gemetar karena marah sejenak, lalu bangkit dari tempat duduknya.
“Kalian semua idiot ! Aku pergi dari sini!” katanya sambil menyampirkan tasnya di bahu sambil bergegas ke pintu dan membukanya lebar-lebar, lalu menghentakkan kaki keluar ke lorong.
Kelas hening sejenak setelah itu. Akhirnya, Todoroki melanjutkan pidatonya, seolah tersadar dari linglung.
“Eh, baiklah, semuanya!” katanya. “Kalau begitu, ayo kita mulai bekerja, ya?!”
Kelas dibagi menjadi dua kelompok: kelompok akting dan kru belakang panggung. Kelompok pertama tetap di Ruang Kelas 2-A untuk berlatih bagian kami, sementara kru belakang panggung pindah ke ruang serbaguna untuk memulai persiapan. Hoshihara ada urusan panitia festival, jadi ia bergegas pergi begitu Todoroki selesai menjelaskan.
Ada sekitar sepuluh orang yang tersisa di kelas—meskipun ini bukan semua aktor, lho. Beberapa tidak hadir karena ada rapat klub atau urusan lain yang lebih penting. Meski begitu, jumlah peserta hari pertama cukup banyak.
Setelah mendorong semua meja ke belakang kelas, saya dan para aktor lain berkumpul untuk melakukan latihan vokal, lalu membaca naskah dan berlatih dialog kami (kebanyakan hanya untuk bersenang-senang). Pada satu titik, saya dan Ushio duduk di kursi, saling berhadapan di tengah lingkaran dengan naskah kami. Todoroki berdiri menjulang di atas kami dengan megafon di satu tangan. Saya berasumsi dia berencana untuk benar-benar menguji kami sampai kami berhasil, mengingat peran kami sejauh ini adalah yang paling penting dalam drama ini. Anehnya, tidak ada yang mengomentari megafon yang anehnya tidak perlu itu.
“Oke, mari kita mulai dari halaman tiga. Bagian di mana Romeo memasuki panggung.”
Saya membuka naskah saya ke halaman yang tepat; isinya adegan Romeo menyelinap ke pesta dansa keluarga Capulet. Untuk pementasan drama kelas kami, ini sebenarnya prolognya (drama sebenarnya dimulai dengan adegan pertikaian antara keluarga Montague dan Capulet, tetapi versi kami hanya memuat informasi itu di narasi pembuka).
Aku menelan ludah dan berdeham untuk membaca baris pertamaku:
“Keindahan apakah itu, yang menerangi ruangan—yang tergantung seperti permata di malam hari, atau seekor merpati salju di antara kawanan—”
“Potong,” kata Todoroki, sebelum menghela napas lelah.
Cut? Benarkah? Aku yakin itu bukan kata yang biasa digunakan saat latihan panggung. Gadis ini benar-benar pecandu film. Terserahlah, setidaknya aku tahu maksudnya…
“Ya, tidak. Tidak akan berhasil,” kata Todoroki, sambil membungkukkan bahunya.
“Apa yang tidak berhasil?” tanyaku.
“Suaramu itu.”
Permisi…? Dan apa yang harus kulakukan?
“Sulit sekali mendengar apa yang kau katakan,” lanjutnya. “Bukannya kau bicara terlalu pelan, tapi rasanya seperti kau hanya menggumamkan kata-katamu. Lagipula, tidak ada emosi dalam suaramu. Kau terdengar seperti tikus mati.”
Kenapa, kamu…!
Dia terlalu blak-blakan untuk seorang gadis yang hampir tidak pernah kuajak bicara sebelumnya. Jujur saja, aku pun tak bisa memungkiri kalau penyampaianku terasa kaku. Aku hanya merasa akan terlalu malu untuk mencoba berakting sepenuhnya terlibat secara emosional dalam peran itu—terutama karena semua dialog Romeo begitu muluk-muluk dan dilebih-lebihkan sampai-sampai benar-benar membuatku ingin bergidik. Mungkin kami perlu mengadaptasi naskahnya lebih jauh lagi untuk sedikit mengurangi hal-hal itu.
“Memang, aku sendiri bukan ahli , ” kata Todoroki, “tapi kurasa kau sebaiknya fokus melakukan latihan vokal yang intens, Kamiki. Oke, selanjutnya—aku ingin kau membaca beberapa baris, Tsukinoki.”
“O-oke,” kata Ushio.
Ia jelas merasa gugup; ia menjilati bibir dan membetulkan posisi duduknya selama beberapa saat. Jelas Todoroki juga menyadari hal ini, saat ia tersenyum lembut dan mencoba menenangkannya.
“Jangan terlalu dipikirkan,” katanya. “Ini baru latihan sekarang, jadi kamu bisa santai sedikit. Apalagi sekarang si Nona Kuncir yang nakal sudah pergi.”
Saya tidak dapat menahan tawa kecil mendengar julukan ini.
Ushio menarik napas dalam-dalam, lalu menatap lurus ke depan. Sepertinya ia sudah siap sekarang.
“Baiklah,” katanya lembut. “Dari mana aku harus mulai?”
“Kita mungkin harus mulai dengan adegan pesta dansa, sama seperti Kamiki. Buka halaman lima, dan baca dari mana dia mengetahui bahwa Romeo adalah seorang Montague, dan karena itu musuhnya.”
Ushio membalik halaman dan membacakan baris pertamanya:
“Memikirkan cinta pertamaku akan lahir dari satu-satunya kebencianku! Oh, celakalah aku, bahwa aku harus jatuh cinta begitu dalam pada musuh bebuyutan…”
Setelah menyelesaikan dialognya, Ushio memberanikan diri melirik sekilas naskahnya—mungkin penasaran ingin tahu seberapa baik dialognya tetapi mengantisipasi hal terburuk.
“Nah, itu yang kumaksud!” kata Todoroki, matanya berbinar-binar saat ia meninggikan suaranya menjadi sorak sorai. “Apa yang kau takutkan, hah?! Itu spektakuler! Percayalah, kau tidak perlu khawatir. Kau tidak terdengar terlalu monoton atau berlebihan. Kurasa kau menemukan keseimbangan yang sempurna, sungguh. Ada rasa pilu di dalamnya, percayalah!”
“K-kau benar-benar berpikir begitu…?” tanya Ushio merendah. Aku tahu dia senang mendengar pujian itu. Dan aku setuju dengan Todoroki—dia memang berbakat dalam hal ini. Saking berbakatnya, aku sampai agak terkejut. Pembacaannya begitu penuh emosi, dan suaranya yang serak semakin menegaskan ketulusan penuh kerinduan dalam kalimat itu.
“Oke, aku mau tanya: apa kamu pernah ikut audisi akting yang sebenarnya?” tanya Todoroki. “Sejujurnya, suaramu sama bagusnya dengan para calon aktor yang kutahu sudah mengikuti les akting untuk belajar cara mengekspresikan emosi dengan meyakinkan seperti itu.”
“Tidak, aku belum pernah melakukan hal seperti itu,” kata Ushio. “Meskipun ada masa di mana aku melakukan latihan vokal di waktu luangku. Mungkin itu sedikit membantuku, siapa tahu.”
Benar. Suatu kali, waktu kami jalan pulang sekolah, Ushio bilang dia pernah latihan vokal sebelumnya karena agak khawatir dengan suaranya yang rendah.
“Wow, kau tidak bilang…” kata Todoroki, menatap naskahnya sendiri dengan ekspresi termenung. Setelah ragu-ragu sejenak, ia membolak-balik naskah dan menunjukkan satu halaman tertentu kepada Ushio. “Hei, bagaimana kalau kita coba adegan ini selanjutnya? Bagian ‘di mana kau Romeo?’. Maaf, aku tahu ini bagian yang cukup panjang.”
“Mmm, ya, aku tidak yakin aku bisa melakukannya dengan adil…”
“Oh, kamu nggak harus sempurna atau apa pun! Aku cuma mau dengar kamu bawakan itu. Itu salah satu adegan paling ikonik di seluruh drama, jadi kita akan latihan intensif nanti, jangan khawatir.”
Ushio masih tampak ragu, dilihat dari caranya bergerak gelisah dan melirikku dengan sembunyi-sembunyi. Sepertinya dia ingin tahu pendapatku, jadi kukatakan saja.
“Kurasa itu belum perlu,” kataku. “Kita masih punya banyak waktu—dan aku tidak ingin Ushio langsung begitu hebat sampai aku terlihat lebih buruk jika dibandingkan. Kurasa aku lebih suka kita tidak terburu-buru.”
“Itu masalahmu , Kamiki,” balas Todoroki. “Kau hanya perlu meningkatkan kemampuanmu juga, dan kau akan baik-baik saja.”
Aku tak punya ruang untuk bantahan. Ushio memikirkannya sejenak, lalu mengangguk. “Baiklah,” katanya, sudah bulat tekadnya. “Aku akan mencobanya.”
“Bagus!” kata Todoroki. “Aku suka dengar itu! Silakan saja kapan pun kau siap.”
Ia berpose sangat angkuh, bak sutradara, melipat tangannya penuh harap dan mencondongkan tubuh ke satu sisi. Aku terdiam dan menyaksikan dengan penuh harap ketika Ushio menarik napas dalam-dalam dan tenang, lalu langsung mengenakan pakaian yang tepat untuk perannya.
“O Romeo, Romeo, mengapakah engkau Romeo?”
Cara ia merangkai kata-kata satu per satu membuatnya hampir terdengar seperti doa yang rendah hati. Ada nuansa menyayat hati dalam suaranya yang membuat saya tak kuasa menahan diri untuk tidak terpikat. Penampilannya sungguh memukau, terasa terlalu nyata untuk sekadar akting. Saya belum pernah melihat Romeo dan Juliet versi lain selain versi ekonomis kelas sebelumnya, namun suara Ushio tetap membangkitkan gambaran jelas seorang perempuan muda yang merengek minta cinta dari balkon rumahnya di benak saya. Dan, sebagai pemeran Romeo, tak butuh waktu lama bagi saya untuk membayangkan diri saya menjadi sosok yang ia rengekkan, yang membuat saya sedikit gerah.
Tak lama kemudian, Ushio selesai membacakan dialognya, dan saya menyadari seluruh kelas diselimuti keheningan. Semua siswa—yang rajin berlatih bersama kami, yang berpartisipasi tetapi jelas-jelas tidak serius, dan yang tidak serius membaca—hanya menatap Ushio dengan takjub. Saya ada di antara mereka, mulut ternganga dan bahkan tidak bisa berkata sepatah kata pun. Ketika Ushio menyadari perubahan suasana kelas ini, ia tampak kebingungan, dan setelah itu wajahnya langsung memerah.
“Eh, maaf,” katanya. “Aku hanya—”
“Itu luar biasa !” teriak Todoroki.
Penilaian yang satu ini dari direktur kami menghancurkan bendungan, dan seketika kelas menjadi riuh, meletus dengan persetujuan bagaikan lebah yang keluar dari sarangnya.
“Sialan, Tsukinoki…”
“Dia terdengar seperti pengisi suara yang sah!”
“Saya pikir saya sedang menonton sinetron sungguhan selama semenit.”
“Wah, gila sekali !”
Semua orang di kelas bergegas menghampiri dan mengerumuni Ushio, beberapa di antaranya memujinya begitu berlebihan sampai-sampai mereka meminta encore. Sementara itu, Ushio masih tampak bingung dengan pujian-pujian meriah ini.
“Um… B-apa itu cukup bagus, ya?” tanyanya.
“Maksudku, ya—itulah yang semua orang bilang, kan?” potongku, berharap bisa menghancurkan rasa tak percayanya. “Penampilanmu tadi sungguh hebat. Rasanya kau benar-benar berada di level yang jauh berbeda dibandingkan kami semua.”
“Oh. B-baiklah, oke…”
Ushio menundukkan kepala dan mencengkeram kain roknya sementara bahunya mulai bergetar pelan. Tiba-tiba, aku merasa mungkin ini bukan situasi yang menyenangkan baginya; sepertinya murid-murid lain yang berkumpul di sekitarnya juga menyadari perubahan sikapnya ini, dan mereka perlahan mulai tenang dan mundur.
Dengan wajah masih tertunduk ke lantai, Ushio bangkit dari tempat duduknya. “Maaf, aku perlu ke toilet,” ujarnya tanpa pikir panjang, lalu bergegas meninggalkan ruangan.
Saya agak panik. Apakah kita baru saja menginjak ranjau emosi?
“Sebentar, aku mau lihat,” kataku sambil segera mengejar Ushio tanpa menunggu persetujuan siapa pun.
Syukurlah, tak butuh waktu lama untuk menemukannya. Seperti dugaanku, dia sebenarnya tidak perlu ke toilet. Malahan, dia hanya berdiri di ujung lorong, menatap ke luar jendela dengan mata tertunduk. Dia membelakangiku, jadi aku tak bisa menebak ekspresinya.
“Ushio, kamu baik-baik saja?” Aku memanggilnya.
“Aku baik-baik saja,” jawabnya dengan suara sengau tanpa menoleh—tapi dia jelas-jelas tidak tampak baik-baik saja. Respons lemah ini justru semakin memperkuat kekhawatiranku.
“K-kamu pikir memerankan Juliet agak berlebihan? Aku yakin belum terlambat bagimu untuk mundur dan membiarkan orang lain memainkan peran itu, kalau perlu.”
“Bukan, bukan itu…” katanya sambil terisak. “Aku cuma…senang, itu saja. Semua pujiannya, semua orang yang begitu baik padaku… Cuma…sudah lama, kurasa.”
Oh… Jadi begitulah. Ketika saya mengingat kembali semua yang telah dilalui Ushio sejak masa transisinya, saya benar-benar mengerti mengapa perubahan ini terasa sangat berat. Meskipun saya lega mendengarnya, saya pikir saya harus memberinya waktu sendiri untuk menenangkan diri.
“Baiklah,” jawabku. “Kalau begitu, kembali saja setelah kamu agak tenang. Tidak perlu terburu-buru. Pelan-pelan saja.”
Ushio mengangguk, tetapi tidak berkata sepatah kata pun. Aku berbalik dan berjalan kembali menyusuri lorong, lega karena kecemasanku terbukti tidak berdasar. Begitu aku kembali ke kelas, teman-teman sekelasku mengerumuniku dengan ketakutan yang sama tergambar di wajah mereka.
“Bagaimana kabar Tsukinoki?” tanya Todoroki dengan nada khawatir.
“Dia baik-baik saja, ya,” kataku. “Kedengarannya sih, cuma terlalu bahagia aja.”
“Oh, syukurlah…”
Todoroki menghela napas panjang seolah beban di pundaknya terangkat. Murid-murid lain pun menghela napas lega, beberapa di antaranya mengungkapkan betapa khawatirnya mereka karena tak sengaja mengatakan sesuatu yang menyinggung.
“Kau tahu, aku harus mengakui…” kata Todoroki, menyentuh bingkai kacamatanya dengan satu jari sambil tersenyum hampir meminta maaf. “Sejak hari pertama dia datang ke sekolah dengan seragam perempuan, aku agak ragu bagaimana cara berinteraksi dengannya. Rasanya seperti aku berjalan di atas kulit telur karena takut salah bicara, sejujurnya… Tapi aku senang mendengar dia bahagia.”
“Ooh, ya! Aku benar-benar tahu maksudmu!” kata gadis lain. “Ini agak menegangkan, karena aku belum pernah kenal orang seperti dia sebelumnya. Aku selalu khawatir akan mengatakan sesuatu yang ceroboh dan menyakiti perasaannya secara tidak sengaja, jadi biasanya aku memilih untuk tidak mengatakan apa-apa…”
“Kalian terlalu berlebihan,” kata salah satu pria di ruangan itu. “Perlakukan saja dia seperti orang lain, duh. Bersikap seolah dia makhluk rapuh yang harus kalian pakai sarung tangan khusus untuk berinteraksi hanya akan membuatnya semakin merasa tidak nyaman, kau tahu.”
“Kamu bilang begitu sekarang, tapi aku ingat kamu benar-benar menghindari Tsukinoki-kun untuk sementara waktu juga,” kata gadis lainnya.
“Aku tidak menghindarinya, aku hanya… entahlah. Kurasa aku tidak tahu harus berkata apa.”
“Ya, tepat sekali. Kamu tidak lebih baik dari kami.”
Satu per satu, teman-teman sekelas saya ikut berbagi perasaan mereka tentang Ushio dan transisinya, tetapi satu hal yang tampaknya mereka semua sepakati adalah mereka tidak sepenuhnya yakin bagaimana cara berinteraksi yang benar dengannya lagi. Meskipun sebagian diri saya lega mendengar bahwa saya bukan satu-satunya yang berjuang dengan hal itu pada awalnya, sebagian diri saya yang lain merasa sedikit sedih memikirkan Ushio dan semua interaksi ramah yang telah dikorbankan oleh keputusannya, setidaknya untuk sementara waktu.
Aku merasa agak canggung hanya berdiri di ambang pintu, jadi aku kembali ke kelas—ketika tiba-tiba, aku mendengar suara memanggil, “Hei!” saat aku lewat. Aku menoleh dan melihat seorang gadis atletis berkulit agak kecokelatan menatap balik ke arahku. Itu Mashima, dan tepat di sampingnya berdiri Shiina, yang memasang ekspresi acuh tak acuh.
“Butuh sesuatu?” tanyaku, berpikir mungkin ada hubungannya dengan drama itu. Lagipula, mereka berdua aktor sepertiku—Mashima berperan sebagai inang Juliet, dan Shiina berperan sebagai Friar Laurence.
“Enggak juga,” kata Mashima. “Cuma mau cerita sedikit tentang kemampuan akting Ushio.”
Meskipun tidak setegas Hoshihara, baik Mashima maupun Shiina telah mendukung transisi Ushio sejak hari pertama. Mungkin ini ada hubungannya dengan mengapa saya melihat mereka lebih sering bergaul dengan Hoshihara daripada Nishizono akhir-akhir ini; mungkin mereka berdua memutuskan tidak bisa lagi menoleransi perilaku Hoshihara terhadap Ushio.
“Ya, dia memang berbakat alami,” kataku. “Aku cukup terkesan.”
“Ya, aku yakin… Aku yakin itu juga membuatmu sedikit bingung, ya, Kamiki?” Mashima menggoda.
“Apa…? Maksudku, tidak? Aku tidak yakin apa yang kau maksud.”
“Benarkah? Entahlah… Kamu kelihatan merah banget dari tempatku duduk ,” katanya sambil menyeringai nakal. Sayangnya, sepertinya aku sedang diolok-olok.
“Kenapa sih kamu lihatin aku? Perhatikan yang lagi tampil, astaga.”

“Oh, jangan khawatir. Kami juga mengawasinya. Benar, kan, Shiina?”
“Memang,” kata Shiina sambil mengangguk. “Aku juga merasa penampilannya cukup mengesankan. Saking mengesankannya, aku hampir bertanya-tanya apakah dia punya bakat menjadi aktris sejati… Tapi cukup sampai di situ saja, Kamiki-kun. Apa ada yang lupa kau sampaikan pada Marine dan aku?”
“Maaf?”
Aku benar-benar bingung. Pikiranku kosong melompong. Kecuali…
“Oh, begitu,” kataku. “Terima kasih sudah menjadi sukarelawan di tengah kesibukan kalian, teman-teman. Apalagi dengan kegiatan ekstrakurikuler kalian.”
Mashima berada di tim softball putri, dan Shiina berada di kelompok tiup.
“Ya, aku benar-benar kewalahan,” kata Mashima. “Salah satu senior pensiun saat liburan musim panas, jadi sekarang mereka mengangkatku jadi kapten tim. Seolah-olah aku belum punya banyak pekerjaan… Tapi tidak apa-apa. Aku juga ingin berpartisipasi dan menikmati festival budaya, jadi aku tidak keberatan menjadi sukarelawan sebagai aktor.”
“Wah,” kataku. “Kapten tim, ya? Keren banget.”
“Aku tahu, kan? Belikan aku soda perayaan kapan saja, Sobat.”
“Kurasa aku tidak akan melakukannya, tapi terima kasih atas tawarannya. Jadi, eh… bagaimana denganmu, Shiina?”
“Sebenarnya, aku tidak terlalu stres. Kami bukan klub paling disiplin di dunia, jadi kami hanya bersikap santai saja… Tidak, tunggu dulu. Bukan itu maksudku .” Shiina sedikit melebarkan matanya seolah menegurku. “Dengar, kau. Kalau aku tidak salah, kau akhirnya mendapat peringkat pertama di ujian akhir semester berkat bantuan kami, kan? Bukan berarti aku merasa kami pantas mendapatkan semua pujian itu, tapi setidaknya aku rasa beberapa kata terima kasih pantas untuk diucapkan.”
Cara bicaranya yang kasar membuatku sedikit mundur—tetapi kemarahannya itu beralasan, mengingat sudah berbulan-bulan sejak hasil ujian diumumkan dan aku sama sekali tidak berusaha berbicara sepatah kata pun kepada mereka.
“Ya, Shiina agak teliti soal hal-hal semacam itu,” kata Mashima. “Kalau aku pribadi sih, nggak terlalu peduli.”
“Kau terlalu longgar, Marinir,” kata Shiina. “Rekan satu timmu tidak akan pernah menghormatimu dengan sikap seperti itu.”
“Ugh… Aku benci kau benar,” kata Mashima sambil memutar tubuhnya ke kiri dan ke kanan.
“Yah, eh…” potongku, dan mereka berdua mengalihkan perhatian mereka kepadaku. “Maaf atas keterlambatannya, tapi terima kasih, kalian berdua. Kalian benar-benar datang dengan sangat baik. Rasanya aku tak akan pernah bisa meraih juara pertama tanpa bantuan kalian.”
Dengan sedikit dengusan puas, Shiina menjawab, “Baiklah, kurasa.” Setidaknya dia tampak puas, yang memang penting untuk tujuanku.
“Jadi, ceritakan pada kami, Kamiki—bagaimana hubunganmu dengan Nakki?” tanya Mashima dengan acuh tak acuh.
“Benda apa?” tanyaku.
“Apa, bukannya sudah jelas? Maksudku…” Dia mendekat dan berbisik di telingaku, “Kamu naksir dia, ya?”
“Bwuh?!” gerutuku. “A-apa yang kaukatakan, dasar bodoh?! Sungguh! Berhentilah berasumsi aneh-aneh tentangku.”
“Oh, kau tidak? Huh, aneh. Kurasa aku salah paham saja, ya?” Mashima menyeringai penuh arti saat mengatakannya, yang membuat Shiina mengernyitkan dahinya bingung.
“Kenapa kamu nyengir? Aku jadi merinding nih… Apa terjadi sesuatu antara Natsuki dan Kamiki-kun?”
“Enggak, nggak apa-apa! Jangan bikin kepala kecilmu pusing, Shiina.”
Mashima mengedipkan mata kecil seolah mengatakan rahasiaku aman bersamanya. Tentu saja aku menghargainya, tapi ini membuatku penasaran: kapan tepatnya dia menyadari perasaanku pada Hoshihara? Apakah saat aku mengajukan diri menjadi panitia festival? Atau saat sesi belajar kelompok? Atau setelah kami mulai berjalan pulang bersama setiap hari? Atau mungkin…
Sial. Aku tidak terlalu halus, kan?
Ada beberapa poin referensi yang bisa dengan mudah dijadikan dasar hipotesis bahwa aku naksir Hoshihara, kalau dipikir-pikir. Jika Ushio dan (kemungkinan besar) Sera sudah tahu aku, tidak terlalu absurd untuk berpikir Mashima mungkin punya firasat juga. Malahan, Shiina sebenarnya tampak agak naif karena tidak tahu apa-apa saat itu, terutama untuk seseorang yang sangat pintar membaca buku.
“Saranku sih: jangan terlalu lama menatap gadis itu,” lanjut Mashima. “Nakki benar-benar ceroboh. Aku ingat suatu kali kita pergi ke bioskop, dan dia menumpahkan seember penuh popcorn ke tanah.”
“Dan ada saat dia menganggur karena dia pikir kami akan keluar jam sembilan malam, bukan jam sembilan pagi,” kata Shiina.
“Oh iya, aku ingat itu!” Mashima tertawa. Tapi kemudian raut wajahnya berubah lebih tulus. “Tetap saja, kurasa dia sedang berusaha memperbaiki diri akhir-akhir ini, dan senang sekali melihatnya.”
“Benar,” kata Shiina sambil mengangguk. “Dia benar-benar memaksakan diri akhir-akhir ini.”
Mashima dan Shiina sudah mengenal Hoshihara jauh lebih lama daripada saya. Hati saya menghangat mendengar dua teman lamanya mengakui usaha yang telah ia lakukan.
“Oh, hai,” kata Mashima sambil melirik ke arah pintu. “Sepertinya Ushio sudah kembali.”
Aku menoleh mengikuti tatapannya, dan benar saja, dia ada di sana. Todoroki adalah orang pertama yang menyapanya dan menanyakan kabarnya, tetapi tak lama kemudian teman-teman sekelas kami yang lain juga berkumpul untuk memeriksanya.
“Ayo kita sapa, ya?” kata Mashima pada Shiina, sebelum menghampiri Ushio. Aku bisa merasakan senyum mengembang di wajahku saat aku mengikuti mereka.
***
Dalam beberapa minggu terakhir, terjadi peningkatan tajam jumlah siswa yang berlarian panik ke sana kemari di gedung sekolah. Sering kali, mereka adalah anggota panitia festival yang hanya berusaha menyeimbangkan berbagai tugas mereka. Hari ini, saya ada di antara mereka. Tidak ada satu tugas pun yang terlalu sulit atau memakan waktu, tetapi ada begitu banyak yang harus diselesaikan. Rupanya, kami yang berada di tim administrasi akan dibebani dengan semakin banyak tugas tambahan seiring berjalannya waktu, dan karena itu, saya diperlakukan seperti asisten bagi anggota panitia lain yang membutuhkan bantuan. Meskipun saya memilih peran ini karena saya pikir itu akan menjadi pekerjaan yang cukup santai, ternyata tidak demikian.
Bagaimanapun, saya sedang berkeliling gedung, memasang poster-poster karena sekolah sudah libur. Ini salah satu tugas termudah yang pernah diberikan kepada saya—tidak ada bandingannya dengan mendirikan tenda administrasi besar-besaran kemarin di tengah hujan, dengan personel yang jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan. Setelah merapikan poster terakhir di papan pengumuman sekolah, saya menusukkan paku payung di setiap sudut.
“Baiklah, kurasa itu saja.”
Aku bertepuk tangan dua kali sambil mengagumi hasil karyaku sejenak sebelum kembali ke ruang OSIS—kantor pusat de facto kami sebelum festival. Segala macam tugas, mulai dari penyelesaian konflik hingga pekerjaan administrasi, ditangani di sana.
“Hei, aku sudah selesai!” teriakku sambil masuk ke ruangan untuk menyampaikan laporanku. Setelah semua pekerjaan serabutan yang kulakukan untuk tim publisitas selesai, aku sudah selesai di sini—tetapi suara Hoshihara dari seberang ruangan menghentikan langkahku. Ia sepertinya sedang meminta maaf untuk sesuatu, dilihat dari caranya menundukkan kepala kepada seorang senior yang raut wajahnya tidak terlalu ramah.
“Aku benar-benar minta maaf! Itu tidak akan terjadi lagi!” katanya dengan gugup.
“Saya akan memeriksanya lagi, jadi ini bukan masalah besar, tapi lain kali kamu harus lebih berhati-hati,” kata kakak kelas itu sambil melambaikan tumpukan kertas di tangannya. “Kita tidak boleh mengajukan aplikasi yang salah ke pusat layanan kesehatan. Itu bisa menimbulkan masalah serius, kamu tahu.”
“Ya, aku mau. Maaf sekali lagi…”
Hoshihara menundukkan kepalanya karena malu ketika anak laki-laki senior itu pergi, lalu berjalan tertatih-tatih kembali ke tempat duduknya. Sepertinya aku datang di saat yang kurang tepat; aku merasa kasihan pada Hoshihara dan ingin menghiburnya, tetapi aku takut jaminan kosong itu hanya akan membuatnya semakin sedih. Saat aku berdiri di sana merenungkan apa yang harus kulakukan, seorang kakak kelas lain menghampiri Hoshihara.
“Hei, eh, Hoshihara-chan? Ada waktu sebentar?” tanyanya sambil tersenyum sopan.
Kepala Hoshihara terangkat secepat cahaya. “Ya, ada yang bisa kubantu?!”
“Aku cuma perlu persetujuanmu untuk ini. Jadi, um… Kalau kamu bisa langsung memberi stempelnya untukku, itu akan sangat bagus.”
“Oh, mengerti! S-tentu saja!” Hoshihara merogoh tumpukan kertas kerja yang telah menjadi mejanya untuk menemukan stempel ketua komite, lalu menempelkannya pada cetakan yang dibawa kakak kelasnya untuk disetujui.
“Terima kasih! Dan, eh… Ngomong-ngomong, bagaimana dengan evaluasi anggarannya?”
“Oh! Baiklah, eh… K-kurasa aku sudah setengah jalan, mungkin?”
Untuk sepersekian detik, ekspresi kakak kelas itu menegang. “Oke, oke. Yah, skenario terburuknya, kurasa tidak apa-apa asalkan selesai besok. Usahakan jangan sampai melewatkan hal penting, oke?”
“Ya, aku tahu. Maaf sudah menunggu…”
“Baiklah kalau begitu, aku serahkan padamu!”
Setelah itu, kakak kelas itu bergegas pergi, dan Hoshihara mendesah lemah. Sepertinya tugasnya benar-benar menumpuk. Aku sudah punya firasat buruk ini akan terjadi sejak awal, tetapi seiring festival semakin dekat, aku tahu ia semakin kewalahan. Bahkan, aku tidak ingat satu kali pun dalam ingatanku baru-baru ini ia pulang sekolah sebelum aku. Aku jadi penasaran sampai jam berapa ia pulang untuk mengerjakan tugasnya.
“Sebaiknya kau tidak meninggalkan Natsuki dalam kesulitan.”
Kata-kata Ushio terlintas dalam pikiranku.
Aku menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangan. “Ada yang bisa kubantu?” teriakku dari kejauhan.
Mata Hoshihara terbelalak, tapi kemudian ia menepisnya sambil tersenyum malu. “Tidak apa-apa. Lagipula, bukankah kamu harus kembali ke kelas sekarang?”
Dia benar. Akhir-akhir ini, begitu selesai dengan tugas komite hari itu, aku langsung menuju ke kelas untuk latihan drama.
“Ya, secara teknis,” kataku. “Tapi aku juga tidak diwajibkan untuk datang.”
“Nah, lanjutkan! Tidak apa-apa! Kamu harus memprioritaskan latihan sebanyak mungkin. Aku sudah mengurusnya—sungguh.”
Ia bergeming, tampak yakin bahwa ia benar-benar bisa menangani semuanya sendiri. Entah itu atau ia hanya tidak ingin bergantung pada orang lain untuk meminta bantuan kali ini, apa pun yang terjadi. Mungkin ia berpikir itu akan menjadi kegagalan pribadinya dan hanya akan semakin menunda kemandirian yang ia dambakan.
Saya tidak bisa sepenuhnya menolak cara berpikir ini. Meskipun cara itu jauh lebih sepi dan seringkali tidak efisien, tetap ada manfaatnya menyelesaikan tugas sendirian. Namun dalam kasus ini, saya sungguh-sungguh ingin membantu Hoshihara, dan saya tidak tega melihatnya berjuang keras.
“Hei, Hoshihara,” kataku dengan suara yang cukup pelan agar anggota komite lain yang bekerja di ruangan itu tak bisa mendengarnya. “Ingatkah kau waktu kita pergi ke restoran bersama bulan Juli lalu?”
“Y-ya…” katanya, jelas sedikit bingung dengan apa yang kumaksud.
“Ya, waktu itu kamu bilang kalau aku berhasil dapat peringkat pertama di kelas kita di ujian akhir, kamu akan melakukan apa pun yang aku minta, kan?”
“Y-ya… Kenapa kamu baru membahasnya sekarang?”
Hoshihara mundur sedikit, kembali ke mode bertahan. Bahkan ada sedikit ketakutan di raut wajahnya. Aku berharap bisa memulai pembicaraan dengan perlahan dan lancar agar dia lebih mudah yakin, tetapi aku langsung menyesal tidak langsung menyampaikan usulanku sejak awal dan malah mundur.
“Aku ingin kau mengizinkanku membantu,” kataku. “Itu permintaanku.”
“Hah?!” Hoshihara menatapku dengan mulut ternganga, benar-benar tercengang.
“Sudah lama aku memikirkan kapan sebaiknya memainkan kartu itu, tapi kupikir untuk situasi seperti ini, sebaiknya langsung pakai saja di kesempatan pertama yang ada. Maksudku, biasanya aku tipe orang yang menyimpan semua item penyembuhan terbaiknya sampai bos terakhir di RPG mana pun, lalu tidak pernah menggunakannya, jadi aku tidak mau itu terjadi di sini.”
“Maksudku, sama saja, tapi…apa kau yakin itu semua yang kau inginkan?”
“Baiklah, jika kamu memang menentangnya, aku tidak keberatan untuk memikirkan hal lain.”
“Enggak! Enggak, nggak apa-apa! Aku nggak masalah. Aku akan cari kerjaan buat kamu.” Hoshihara mundur dengan gugup, mengacak-acak tumpukan kertas di mejanya. Sesaat kemudian, dia menyerahkan beberapa lembar kertas berukuran A4 kepadaku. “Baiklah, bolehkah aku minta kamu memeriksa selebaran dan pamflet ini? Ternyata ada banyak kesalahan ketik…”
“Tentu, serahkan saja padaku. Aku jago mengoreksi.”
Saya mengambil dokumen itu dan duduk di kursi kosong terdekat. Saya langsung menelusuri setiap kalimat di halaman pertama dengan jari saya, mengamati setiap katanya dengan saksama.
“Kamu benar-benar telah berubah, Kamiki-kun,” kata Hoshihara.
“Tidak begitu yakin soal itu,” kataku tanpa komitmen sambil terus mengoreksi.
Seberkas penyesalan perlahan merayapi dadaku. Aku tak bisa menahan rasa ingin menyesali keputusan ini nanti. Tapi aku tak pernah berencana meminta Hoshihara melakukan sesuatu yang benar-benar akan membuatnya tak nyaman, jadi aku tahu jauh di lubuk hatiku bahwa inilah cara yang tepat untuk memanfaatkannya.
Beberapa saat kemudian, saya selesai mengoreksi dan meletakkan pena merah saya. Memang ada banyak kesalahan ketik dan tata bahasa, jadi saya senang kami bisa menemukannya selagi masih ada waktu untuk merevisi. Bukan berarti orang waras akan repot-repot mencari kesalahan ketik di pamflet acak yang diberikan kepada mereka di festival budaya SMA.
“Hei, sudah selesai.” Aku menyerahkan bukti yang sudah ditandai itu kembali ke Hoshihara.
Dia meliriknya sekilas, lalu mengangguk puas. “Terima kasih banyak, Kamiki-kun. Tanggal jatuh temponya sudah hampir tiba, jadi kamu benar-benar membantuku.”
“Jangan bahas itu. Dan jangan ragu untuk memberi tahu saya jika Anda butuh bantuan dengan hal lain.” Saya mencoba bersikap tenang, tetapi akhirnya merasa ngeri dengan kurangnya karisma saya. Astaga, saya tidak punya bakat apa pun…
Namun, upaya itu tetap tepat sasaran bagi Hoshihara, yang dengan malu-malu mengalihkan pandangannya. “Senang sekali aku bisa bergantung padamu,” katanya. “Aku sangat senang kau bergabung dengan komite bersamaku, Kamiki-kun.”
“Eh… B-tentu saja. Ngomong-ngomong, aku mungkin harus kembali ke kelas sekarang.”
“Oke, ya. Semoga sukses di luar sana.”
Aku berbalik arah dan keluar dari ruang OSIS, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang meski jiwaku mengancam untuk keluar dari tubuhku kapan saja.
“Aku sangat senang kau bergabung dengan komite bersamaku, Kamiki-kun.”
Astaga… Apa hari ini bisa lebih baik lagi?! Aku sangat setuju dengan Hoshihara—aku sangat senang bisa bergabung dengan komite juga. Wah, aku hampir bisa merasakan air mata kebahagiaan mengalir. Kalau saja tidak ada orang lain di gedung ini sekarang, aku mungkin sudah melompat-lompat di lorong dengan gembira. Aku perlu berterima kasih kepada Ushio karena telah mendorongku untuk menjadi sukarelawan di kesempatan berikutnya.
“Hai, Sakuma.”
Tepat saat aku pikir tak ada yang dapat menghentikan langkahku, aku mendengar sebuah suara memanggilku dari belakang, dan aku terdorong ke depan sambil meringis.
“Ugh…” aku mengerang. Itu Sera—tangannya dimasukkan ke saku, seringai licik terpampang di wajahnya seperti biasa.
“Ugh? Yah, itu bukan cara yang baik untuk menyapa teman lama, ya? Kalau bukan aku, kurasa kau pasti sudah menyakiti perasaan mereka!”
“…Percayalah, aku tidak akan bereaksi seperti itu jika itu bukan kamu.”
Yah. Mungkin saja.
Aku sebenarnya bukan penggemar berat Sera—atau, yah, sejujurnya aku benci sekali sifatnya. Tapi suasana hatiku sedang bagus sekali hari ini, jadi kupikir aku bisa menoleransinya sedikit lebih lama.
“Apa yang kamu inginkan?” tanyaku.
“Tidak ada yang istimewa. Aku cuma lihat kamu kelihatan ceria banget di sini dan mau sapa. Ada kabar baik nggak hari ini, atau gimana?”
Sial, orang ini jeli sekali… Atau aku saja yang mudah dibaca?
“Ya, kurasa begitulah,” jawabku samar-samar, tak ingin membocorkan rahasia tapi terlalu senang untuk menyangkalnya.
“Oh, kau tidak bilang…” jawab Sera dengan nada menyeramkan, lalu mengamatiku dari ujung kepala sampai ujung kaki. “Biar kutebak—ini ada hubungannya dengan Natsuki-chan, kan?”
Bagaimana dia bisa tahu hal itu?
“Tidak,” kataku. “Bukan urusanmu.”
“Ehem,” kata Sera sambil berdeham. “Astaga, aku senang sekali kau bergabung dengan komite bersamaku, Kamiki-kun!”
“Apa…?”
“Nah? Kesan yang bagus, atau apa?”
“Tidak sedikit pun. Senang juga tahu kamu menguping, terima kasih.”
Sera tertawa terbahak-bahak. Dia kandidat yang cukup bagus untuk orang yang paling tidak kusuka. Aku hampir muak dan ingin pergi, tapi setidaknya aku ingin disuntik dulu sebelum melakukannya.
“Bukankah seharusnya kamu juga jadi anggota komite?” tanyaku. “Mungkin kamu harus mencoba sedikit bekerja sekali seumur hidupmu.”
“Apaaa? Aku sih. Aku lagi patroli gedung sebagai bagian dari tim supervisi. Harus mengawasi orang-orang dan memperingatkan mereka kalau mereka lengah atau berbuat salah!”
“Hah. Ya, aku yakin. Kau mungkin hanya bermalas-malasan seperti biasa. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan selama kau tidak menggangguku, tapi jangan membuat masalah bagi Hoshihara, kau dengar?”
“Oh, nggak akan, Sobat. Padahal aku mau tanya—kenapa kamu tiba-tiba jadi protektif banget sama Natsuki-chan, ya?”
Ada nada yang agak genit dalam suaranya saat dia menanyakan pertanyaan ini melalui seringai palsunya, tetapi hal itu menutupi kilatan sadis di matanya.
“…Karena dia teman satu komiteku,” kataku. “Tentu saja aku akan mengkhawatirkannya.”
“Harus kuakui, aku nggak yakin aku lihat apa yang menurutmu menarik dari gadis itu,” kata Sera. “Bukannya dia nggak imut, terlalu dangkal, atau semacamnya. Cuma, entahlah… Kayaknya agak membosankan, lho? Aku sih, lebih milih Ushio daripada dia, kapan pun.”
Aku merasakan kedutan saat otot-otot di sudut mataku menegang. Kupikir ini caranya menantangku; dia mungkin berpikir kalau dia terus-terusan menjelek-jelekkan Hoshihara, aku akan marah besar. Kalimat ini memang akurat, dalam kebanyakan kasus. Tapi karena aku tahu dia hanya ingin memancing emosiku, aku bertekad untuk tidak memberinya reaksi yang diinginkannya.
“Yah, kalau begitu, itu masuk akal,” kataku. “Karena aku yakin dia juga tidak akan mau mati bersama pria sepertimu.”
“Meskipun begitu, dia punya payudara yang cukup bagus.”
“Aku akan meninju mulutmu.”
“Ha ha ha!”
Aku sudah muak dengan badut ini. Tak ada gunanya mencoba mengobrol dengan orang bodoh seperti dia. Aku kembali ke jalur semula dan mulai berjalan kembali ke Kelas 2-A.
“Apaaa, udah mau berangkat?” kata Sera.
“Aku ada latihan,” kataku. “Jangan ikuti aku.”
“Oh ya, kelasmu sedang mempelajari Romeo dan Juliet , kan?”
Aku bahkan tidak menanggapinya kali ini; aku hanya berjalan melewatinya.
“Hai. Sakuma,” panggil Sera. Untuk sekali ini, ada sesuatu dalam nadanya yang terdengar tulus. Ini membuatku agak penasaran, jadi aku berbalik.
“Ada apa sekarang?”
“Menurutmu mengapa Romeo dan Juliet sama-sama mati di akhir drama?”
“…Itu hanya serangkaian kebetulan yang tragis.”
“Tidak, yang ingin kukatakan adalah: mengapa tidak bisa hanya salah satu saja?”
“Aku tidak tahu. Kenapa?”
Sera tersenyum lembut dan ramah. “Karena dengan begitu, ceritanya jadi jauh lebih menarik.”
***
Rasanya saya berlari hampir mencapai kapasitas maksimal akhir-akhir ini—terutama karena, dengan semua pekerjaan komite dan latihan akting saya, jumlah jam yang saya habiskan untuk berinteraksi dengan orang lain meningkat pesat. Akibatnya, saya jadi jauh lebih sedikit membaca beberapa minggu terakhir dibandingkan saat saya langsung pulang sekolah dengan banyak energi mental berlebih setiap hari. Di sisi lain, nafsu makan saya meningkat drastis—mungkin akibat langsung dari aktivitas fisik saya yang lebih aktif daripada biasanya.
Hari ini lagi-lagi bekal makan siang saja tidak cukup, jadi saya pergi ke toko mahasiswa. Saya menuruni tangga dan menyusuri lorong lantai satu, melewati pintu masuk utama, hingga ke ujung antrean panjang menuju konter.
“Oof. Cukup sibuk hari ini…”
Toko sekolah penuh sesak dengan orang-orang—semuanya pastilah orang-orang yang sudah selesai makan siang sepertiku dan berharap mendapatkan camilan tambahan atau es krim. Hal ini cukup membuatku patah semangat, meskipun orang-orang memang bilang musim gugur adalah musim pesta, sejujurnya. Namun, aku tidak tertarik untuk menerobos kerumunan orang, dan masih banyak waktu tersisa sebelum jam makan siang berakhir, jadi aku memilih untuk menunggu sampai kerumunan menipis. Karena banyak pejalan kaki yang melewati toko sekolah, aku tetap berpegangan pada dinding agar tidak menghalangi siapa pun. Kebanyakan siswa yang lewat pada jam ini sedang dalam perjalanan pulang setelah makan siang di kafetaria—dan di antara mereka, aku melihat seorang gadis berambut pirang mencolok yang menonjol dari kerumunan.
Itu Nishizono, sedang dalam perjalanan pulang dari kantin bersama sekelompok gadis dari kelas lain. Aku menghubungkannya: dia sudah meninggalkan kelas tepat di awal jam makan siang untuk beberapa waktu. Jadi, inilah yang dia lakukan. Aku berasumsi dia mungkin merasa terlalu terasing di Kelas 2-A untuk menghabiskan waktu bersama kami lagi.
“Hei, mau mampir ke toko pelajar?”
“Ooh, ya! Aku mau beli Pinos!”
“Kau tahu es krim hanya bisa mencapai pahamu, kan?”
“Baiklah. Kalau begitu, aku pesan Garigari-kun.”
“Jangan berpikir es loli soda lebih enak…”
“Ada yang mau membagi Choco Monaka?”
Suara mereka yang melengking dan feminin terdengar jelas bahkan di tengah hiruk pikuk jam makan siang, tetapi saya perhatikan Nishizono tidak ada di antara mereka. Setelah diamati lebih dekat, ia tampak tidak terlalu terlibat dalam percakapan, hanya memberikan tanggapan singkat dengan senyum paksa setiap kali disapa. Sejujurnya, ia tampak seperti ikan yang keluar dari air—bukan berarti saya terkejut.
Meskipun ia telah lama menjadi ratu Kelas 2-A, bukan hal yang mudah untuk masuk ke dalam struktur kelompok pertemanan dan geng yang sudah mapan di kelas lain, terutama bagi seseorang yang sombong seperti Nishizono. Semakin lama aku menatapnya, semakin aku menyadari betapa tidak nyamannya ia mencoba berbaur. Senyum palsunya terkulai dan sesekali memperlihatkan ekspresi muram di baliknya.
Saat aku mengamatinya sekilas dari kejauhan, ia kebetulan melirik ke arahku, dan tatapan kami bertemu. Matanya terbelalak lebar, dan wajahnya memerah karena amarah, seolah-olah aku baru saja menghina seluruh keluarganya. Ini bukan hal yang ideal. Aku segera berbalik—tapi tetap saja tidak ada bedanya. Nishizono langsung menuju ke arahku; aku mencoba menjauh seolah-olah tidak menyadarinya, tapi sudah terlambat. Ia berteriak dari belakang, dan saat aku berbalik, aku menerima tendangan keras di paha.
“Hei, aduh! Sakit!” rengekku.
“Kemarilah.” Ia mencengkeram dasiku dengan kasar dan menyeretku ke pintu masuk tangga terdekat, tempat beberapa siswa lain berkeliaran. Baru setelah itu ia akhirnya melepaskanku. “Kau pikir kau bisa menunjuk-nunjuk dan menertawakanku dari jauh sekarang, hah? Kau punya masalah, atau apa?”
“Siapa yang bilang aku menertawakanmu?”
“Oh, benar juga. Karena kalau tidak, kenapa kau menatapku seperti orang aneh?”
Aku meluangkan waktu sejenak untuk membetulkan dasiku dan menahan desahan. “Itu bahkan tidak disengaja,” kataku. “Kau hanya kebetulan masuk ke dalam pandanganku, itu saja. Mungkin sebaiknya kau coba untuk tidak terlalu paranoid.”
“Eh, permisi? Kamu mau bilang aku gila atau apa?”
“Tidak, tentu saja tidak… Lihat, itulah yang sedang kubicarakan.”
Nishizono mendecakkan lidahnya keras-keras karena frustrasi dan menggosok pelipisnya dengan kedua tangan. “Ya Tuhan, kalian semua benar-benar menyebalkan, sumpah…”
Suasana hatinya sedang sangat mudah tersinggung hari ini. Meskipun biasanya dia pemarah, kesan saya terhadapnya adalah dia masih bisa berbicara dengan lancar dan logis bahkan ketika sedang argumentatif. Saat ini, sepertinya emosinya benar-benar menguasai dirinya, seolah-olah semua saluran berpikir rasionalnya telah ditutup sementara. Saya tahu tidak ada percakapan produktif yang bisa dilakukan selama dia seperti ini.
“…Bisakah aku pergi sekarang?” tanyaku.
“Mana mungkin.”
“Mengapa tidak?”
Dia melotot ke arahku sejenak, lalu melipat tangannya seolah-olah ingin membuat dirinya tampak lebih besar dari yang sebenarnya. “…Kau sudah mengindoktrinasi Natsuki dengan omong kosong anehmu itu, ya?”
“Apa yang memberimu ide itu?”
“Karena aku tahu dia tidak akan pernah berbicara seperti itu kepadaku sebelumnya.”
“Bicara padamu seperti apa?”
“…Dia balas membantahku. Bilangnya akulah yang mempermalukan diriku sendiri dan sebagainya.”
Hal itu sungguh menggelikan dan mengerikan bagiku sehingga aku merasa harus mengungkapkan isi hatiku padanya, kata-kata itu mengalir deras dari perutku lebih cepat daripada yang bisa mulutku ucapkan.
“Kau memang suka sekali berpura-pura jadi korban, ya?” kataku. “Jadi tunggu dulu, biar kujelaskan—kau pikir kau bisa melontarkan makian sesuka hatimu pada Ushio, tapi ketika Hoshihara membelanya dan menegurmu, kau langsung berasumsi pasti ada konspirasi besar di mana aku mencoba membuat teman-temanmu melawanmu? Kau sadar kan kalau Ushio juga bagian dari kelompok teman itu? Tentu saja mereka akan melawan kalau kau terus menghinanya minggu demi minggu. Kalau kau tidak bisa membaca maksud tersirat di sini dan sedikit merenung ketika gadis manis seperti Hoshihara saja bilang kau sudah keterlaluan, kurasa kau mungkin tak tertolong lagi. Cari tahu.”
Nishizono menundukkan pandangannya, dan bahunya mulai gemetar. Ia tetap seperti itu cukup lama, tanpa mengangkat kepalanya. Akhirnya, aku mulai khawatir mungkin aku sudah keterlaluan, jadi aku membungkuk untuk mengukur ekspresinya dengan lebih baik—ketika tiba-tiba, tinjunya melayang melewati wajahku, nyaris menyentuh hidungku.
“Hei, hati-hati!” kataku.
Beruntung aku berhasil menghindarinya; seandainya aku mencondongkan tubuh sedikit saja ke depan, hidungku bisa saja patah. Tapi aku tak sempat bersyukur—Nishizono sudah haus darah dan langsung menyerangku. Ia mendorongku ke dinding dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kukira bisa dihasilkan tubuhnya yang mungil.
“Kau terus saja bicara, seolah kau sudah tahu segalanya tentangku !” teriaknya. “Sementara itu, kau tak pernah punya ide orisinal atau membentuk opini sendiri tentang apa pun dalam hidupmu!”
Dia meludahi wajahku, namun jelas tidak peduli saat dia mencengkeram kerah bajuku dengan satu tangan dan mengayunkannya ke arahku dengan tangan yang lain.
“Woa, hei! Hen-hen!” teriakku.
Dia terus-menerus memukuliku dengan tinjunya, jadi tak ada kesempatan bagiku untuk lengah dan melepaskan diri. Yang bisa kulakukan hanyalah melindungi wajahku. Baru ketika lengan bawahku mulai mati rasa, aku mendengar suara berwibawa berteriak marah dari tangga. Aku mengintip dari sela-sela pergelangan tanganku untuk melihat bahwa Nona Iyo-lah yang datang menyelamatkanku.
“Hei! Apa yang kau lakukan?!” teriaknya. “Hentikan itu sekarang juga, Arisa!”
Ibu Iyo segera bergerak untuk menahan Arisa, yang melawan sedikit sebelum akhirnya menyerah lemas di bawah kekuasaannya, tampaknya karena sudah kehabisan tenaga.
“Kamiki, apakah kamu terluka?” tanya guru itu.
“Ku-kurasa aku baik-baik saja,” kataku.
Lenganku memang sakit karena dipukul, tentu saja, tapi itu bukan masalah besar. Paling parah, aku mungkin akan mendapat beberapa memar yang parah. Bu Iyo mencengkeram bahu Nishizono dan memutarnya untuk menatap matanya.
“Kenapa kau lakukan ini?” tanyanya, tetapi tak ada jawaban. Bibir Arisa terkatup rapat. Rupanya, bahkan Bu Iyo pun menyadari tak ada gunanya mencoba mendapatkan jawaban seperti ini, jadi ia membiarkan gadis itu pergi. Wajahnya berubah termenung saat ia memikirkan semuanya, lalu berkata, “Kalian berdua sudah makan?”
“Oh, uh… Ya,” kataku.
“Arisa?”
Nishizono tampak bertekad untuk tetap diam, tetapi saya melihat kepalanya mengangguk-angguk dengan gerakan sekecil apa pun—yang saya duga dimaksudkan sebagai anggukan.
“Bagus,” kata Bu Iyo. “Kalian berdua, ikut aku.”
Dan dengan itu, guru kami pun pergi. Saya melirik sekilas ke arah penyerang saya sebelum mengikutinya, dan Nishizono pun membuntuti kami tak lama kemudian. Kami menaiki tangga, menyusuri lorong, dan masuk ke ruang guru, lalu mengikutinya ke bilik konseling yang disekat. Ruangan itu nyaman, hanya berisi meja dan empat kursi di bawahnya, yang sebagian besar digunakan (sesuai namanya) oleh para konselor sekolah ketika membahas kinerja dan rencana pendidikan tinggi siswa mereka.
Bu Iyo duduk di salah satu sisi meja dan memberi isyarat agar kami melakukan hal yang sama, jadi saya pun melakukannya. Arisa ragu sejenak, lalu mengambil tempat duduk di sebelah saya—menggesernya sejauh mungkin sebelum benar-benar duduk.
“Sekarang, saya akan bertanya lagi kepada kalian berdua,” kata Bu Iyo. “Apa yang terjadi di sini?”
Mengingat Nishizono masih bersikeras untuk tutup mulut, saya pikir kalau ada yang akan menjawab pertanyaan ini, pastilah saya orangnya.
“…Dia dan saya saling bertatapan saat dia berjalan di lorong, lalu kami terlibat pertengkaran kecil.”
“Dan apa sebenarnya perdebatan itu?” tanya Ibu Iyo.
“Aku tidak salah,” kata Nishizono, tiba-tiba memotong. “Aku tahu aku tidak salah. Aku janji, Ushio akan lebih baik jika tetap menjadi anak laki-laki. Kenapa kalian tidak bisa melihat itu…?”
Ia menggumamkan kata-kata itu sambil menundukkan kepala seperti penyihir yang sedang membaca mantra. Hal ini saja sudah cukup untuk memberi Bu Iyo gambaran yang cukup jelas tentang akar pertengkaran kecil kami.
“Begitu…” Kursi lipat Bu Iyo berderit pelan saat ia bersandar di sandaran kursi. “Dan apa yang membuatmu merasa begitu, Arisa?”
Nishizono mengangkat kepalanya sedikit, alisnya berkerut hati-hati. “…Karena tidak ada kerugiannya.”
“Apa maksudmu?”
“Kalau dia tetap jadi laki-laki, nggak akan ada yang ngeremehin dia atau ngelakuin hal yang beda. Tapi sekarang dia udah pura-pura jadi perempuan, semua aspek hidupnya bakal jauh lebih susah. Siapa pun yang otaknya masih waras pasti bisa ngelihat itu.”
Hal ini membangkitkan kenangan buruk di benak saya—saat Nishizono mengajukan argumen serupa ketika ia muncul sebentar di sesi belajar singkat kami semester lalu. Saat itu, hal itu langsung membuat saya terdiam; saya bahkan tidak bisa memikirkan argumen balasan yang bagus. Namun, saya telah banyak berpikir dan berkembang sendiri sejak saat itu.
Nishizono tak ragu sama sekali bahwa ia benar. Ia sungguh-sungguh yakin, dari lubuk hatinya, bahwa hanya ia yang memikirkan kepentingan terbaik Ushio. Dan saya pikir dedikasinya yang teguh pada keyakinan ini adalah salah satu alasan utama ia mampu membuat posisinya tampak begitu kuat, meskipun kami jelas-jelas tidak sependapat. Namun, bukan itu masalahnya—ia hanya salah arah. Ia tidak menyadari bahwa bagi Ushio, ini bukan soal untung rugi.
“Nishizono, kurasa—”
“Tidak apa-apa, Kamiki,” sela Bu Iyo. “Aku bisa mengatasinya.” Ia kembali mencondongkan tubuh ke depan di kursinya dan menatap tajam Nishizono, yang menghindari tatapannya seperti balita yang kesal. “Kau benar. Aku yakin banyak hal yang jauh lebih sulit baginya sekarang. Dan mungkin akan semakin sulit ke depannya.”
“Tepat sekali, jadi—”
“Tapi itu justru alasan yang lebih kuat untuk mendukung keputusannya, kataku. Karena aku ingin dia bahagia lebih dari apa pun.”
Dia menekankan setiap kata seakan-akan benar-benar ingin membuat Nishizono terkesan, tetapi gadis itu hanya menggertakkan giginya karena kesal.
“Kau ingin dia bahagia?” tanya Nishizono. “Kalau begitu, itu alasan yang lebih tepat untuk tidak mendukungnya. Bagaimana kau bisa membenarkan keputusan seperti itu jika kau tahu betapa picik dan impulsifnya orang-orang, dan kau tahu itu hanya akan menimbulkan masalah baginya? Orang-orang selalu berubah pikiran. Bukankah tugasmu sebagai guru adalah memikirkan kesejahteraan masa depan murid-muridmu?”
Bu Iyo menarik napas pendek. “Arisa. Apa kamu pernah berpikir dalam hati bahwa kamu berharap terlahir sebagai laki-laki?”
“Eh, maaf? Dari mana asal usul itu ? Tidak, tentu saja tidak.”
“Yah, cukup adil. Tapi seperti katamu: orang selalu berubah pikiran. Bayangkan semua hal yang masih menunggu untuk terjadi dalam hidupmu yang belum kau alami. Apa terlalu aneh untuk berpikir bahwa pengalaman-pengalaman ini bisa membuatmu menyadari siapa dirimu sebenarnya di suatu titik? Atau bahwa kau belum sepenuhnya jujur pada dirimu sendiri dalam satu atau lain hal?”
“Maksud saya…”
“Dengar, Arisa. Kau tidak salah berpikir bahwa ya, orang memang terkadang berubah pikiran tentang keputusan besar, tapi itu poin pembeda yang sia-sia. Ushio sudah membuat perubahan besar dalam kasus ini, dan aku bisa menjamin bahwa keputusan itu telah melalui banyak pertimbangan. Dia tidak membuatnya dengan mudah. Jadi, tidak benar bagimu untuk tidak menghormati identitasnya saat ini hanya karena kau takut dia akan berubah pikiran.”
Nishizono menggigit bibirnya. Masih tak ada sedikit pun rasa sesal di raut wajahnya, tapi aku tahu ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai menyerah.
“Saya mengerti Anda hanya mencoba mengungkapkan kekhawatiran Anda terhadap Ushio dengan cara Anda sendiri,” lanjut Bu Iyo. “Dan secara teori, saya bisa menghargai perasaan itu. Tapi itu bukan alasan untuk menyakiti orang lain secara verbal atau fisik. Tindakan seperti itu hanya akan kembali merugikan Anda dalam jangka panjang, ketika Anda sendiri yang sedang berjuang dan membutuhkan teman atau uluran tangan. Dan jika Anda merasa hanya butuh pelampiasan untuk melampiaskan rasa frustrasi Anda sebelum meluap dan meluap, Anda tahu saya selalu senang membantu—”
“Sudah cukup,” kata Nishizono, memotong ucapan guru itu saat ia bangkit dari tempat duduknya. “Jangan khotbah omong kosong. Aku, yang sedang berjuang dan membutuhkan? Mana mungkin itu terjadi. Aku sudah berada di puncak sepanjang hidupku, dan di situlah aku akan bertahan. Simpan nasihatmu untuk para pecundang yang benar-benar membutuhkannya.”
Dan dengan itu, Arisa keluar dari bilik konseling, menolak membiarkan Bu Iyo berbicara lagi.
“Saya sudah berada di puncak sepanjang hidup saya, dan di situlah saya akan bertahan.”
Itulah yang diklaim Nishizono. Tapi saat aku melihatnya berjalan tertatih-tatih seperti anak kecil yang kehilangan orang tuanya setelah mengamuk dan kabur dari toko kelontong, aku harus bilang: dia benar-benar terlihat sangat menyedihkan sekarang.
Bu Iyo bangkit dari tempat duduknya dan meninggalkan bilik konseling—lalu kembali beberapa saat kemudian, entah karena tidak bisa menyusul Nishizono atau karena menyadari bahwa membujuknya lebih jauh saat ini akan sia-sia. Ia kembali duduk di kursinya dan menundukkan kepalanya tanda pasrah.
“Wah, ini susah banget…” katanya, suaranya berat karena kelelahan. Rupanya, dia benar-benar memaksakan diri untuk tetap tegar. Aku agak terkejut melihatnya begitu jujur di depanku, tapi itu tidak mengurangi rasa hormatku padanya.
“Tidak, Anda luar biasa, Bu Iyo. Anda menutup semua argumennya seolah-olah itu bukan apa-apa. Anda sama sekali tidak membiarkannya membuat Anda gentar… tidak seperti saya.”
Melihat bagaimana orang dewasa seperti Bu Iyo menangani diri mereka sendiri dalam situasi seperti ini menyadarkan saya betapa jauhnya saya harus melangkah, baik dari segi kedewasaan intelektual maupun emosional. Saya hanya berharap bisa sefasih beliau saat berdebat dengan Nishizono di restoran semester lalu.
“Tidak perlu memaksakan diri untuk berdebat dengannya,” kata Bu Iyo, sambil sedikit membungkuk ke depan agar bisa duduk tegak kembali. “Tindakan lebih berpengaruh daripada kata-kata. Selama kau terus bersikap dengan cara yang menunjukkan betapa kau menghormati identitas Ushio, kurasa itu akan mengirimkan pesan yang lebih kuat daripada argumen yang meyakinkan.”
“Kau benar-benar berpikir begitu?”
“Ya! Percayalah sedikit pada instrukturmu, kenapa tidak?!”
“…Baiklah, kalau begitu,” kataku setelah ragu sejenak.
Bu Iyo menyeringai padaku, lalu meregangkan punggungnya. “Ah, sial. Jam pelajaran kelima akan segera dimulai, dan aku bahkan belum sempat makan siang…”
“Tidak bisakah kamu membawa makananmu ke kelas dan makan sambil mengajar?” tanyaku.
“Ooh, hei. Nah, ada ide nih… Gila! Mana mungkin aku bisa lolos begitu saja!”
Balasan Bu Iyo yang jenaka cukup untuk menghapus kesuraman yang mungkin tersisa setelah percakapan dengan Nishizono. Melihat senyumnya yang ceria dan berseri-seri, saya merasa bisa mengandalkan wanita ini lebih dari siapa pun di dunia ini.
***
Hari-hari yang memusingkan itu terus berlanjut, dengan jadwal yang semakin padat. Setiap hari sepulang sekolah, saya dibebani segudang tugas sebagai anggota komite—kebanyakan pekerjaan serabutan yang tak ada orang lain yang sempat melakukannya. Seperti mengumpulkan berbagai berkas wajib dari setiap kelas atau membawa bahan bangunan tambahan seperti kayu dan selotip pengepakan ke kelompok yang membutuhkan. Hari ini, saya berada di gimnasium membantu merakit gapura raksasa yang akan menghiasi gerbang depan sekolah pada hari festival. Hiasan khusus ini tidak berafiliasi dengan kelas mana pun, sehingga menjadi tanggung jawab OSIS untuk membuatnya setiap tahun. Kali ini, mereka memilih motif kastil Eropa yang desainnya mencolok dan rumit sekaligus sulit untuk disatukan.
“Baiklah, di sana.”
Saya telah menyelesaikan struktur dasar untuk menara utama kastil. Struktur itu akan diwarnai dan didirikan bersama dengan yang lainnya nanti, jadi ini sudah cukup untuk hari ini. Saya memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan bagian lain yang menjadi tanggung jawab saya, jadi saya meletakkan pemotong styrofoam saya dan berdiri dari lantai. Ketika saya membungkuk untuk meregangkan otot-otot saya yang pegal, tulang belakang saya berderak di pinggang.
Saya mengamati kelompok-kelompok lain yang berkumpul di sana-sini, sibuk mengerjakan pameran mereka masing-masing. Seluruh auditorium telah diubah menjadi bengkel darurat untuk segala macam dekorasi dan pajangan seni berukuran besar yang terlalu rumit untuk dikerjakan di ruang kelas yang sempit. Ruang olahraga hanya dibuka untuk kami pada hari-hari tertentu, jadi meskipun sesekali ada obrolan ringan, semua orang sibuk bekerja, berusaha memanfaatkan waktu yang sedikit itu sebaik-baiknya.
“Hei, kita kehabisan styrofoam!” kata salah satu anggota komite senior tanpa nama. Tatapannya tertuju padaku, karena hanya aku yang sudah berdiri. “Kita butuh lebih banyak styrofoam di sini.”
Ya, Sobat. Kami mendengarmu tadi, aku ingin menyindir, tapi aku tahu ini caranya menyuruhku mengambil lebih banyak. Baiklah, terserah. Aku baru saja menyelesaikan tugas besar dan sedang berada di tempat yang tepat untuk berhenti, jadi kupikir sebaiknya aku berhenti saja.
“Baiklah,” kataku. “Aku akan ambil lagi.”
“Terima kasih, kamu penyelamat,” kata siswa kelas atas itu, lalu kembali bekerja.
Sepertinya dia tidak membutuhkannya saat ini, jadi saya pikir saya bisa berjalan pelan-pelan dan memanfaatkan jalan-jalan itu untuk meregangkan kaki saya sedikit.
“Oh, kamu mau beli styrofoam lagi, Kamiki-kun?” tanya Hoshihara sambil mengangkat kepalanya. Ia mengenakan baju olahraga dan memegang kikir kayu di satu tangan. Dahinya berkilap keringat karena terlalu lama berada di gym yang panas dan lembap.
“Ya. Ada yang lain lagi selagi aku di sini?”
“Kau yakin? Oke, kalau begitu ya, kurasa kalau kau bisa membawa pulang styrofoam sebanyak mungkin, itu bagus. Kita juga agak kehabisan stok di sini…”
“Oke. Aku bawain juga buat kamu.”
“Keren! Makasih banyak, Kamiki-kun!”
Tiba-tiba aku merasakan ledakan energi. Karena Hoshihara sudah mengucapkan terima kasih sebelumnya, aku tak bisa lagi bersantai. Astaga, aku memang mudah ditebak dalam hal-hal seperti ini—tapi aku cukup suka dengan diriku sendiri.
“Hei. Lem kita habis,” kata sebuah suara tepat saat aku hendak pergi mengambil styrofoam secepatnya. Ternyata Noi.
Kasihan sekali dirimu, Bung, aku ingin sekali membalas, tapi aku segera menyadari dia mungkin memintaku membelikannya sementara aku pergi. Dan meskipun permintaannya yang kasar dan tidak langsung ini jelas membuatku kesal, aku tahu cepat atau lambat seseorang harus mengisi ulang persediaannya, jadi kupikir aku akan memberinya sedikit. Tapi dia pasti akan berterima kasih.
“Ugh… Baiklah, terserah…” kataku sambil mengangguk dengan enggan.
“Dan akan kembali dalam waktu tiga menit juga,” imbuh Noi sambil mendengus merendahkan.
Ter-terkutuklah dia!
Aku berjalan keluar dari pusat kebugaran itu dengan langkah panjang dan geram.
Setelah pekerjaan komite saya selesai, saya harus menghadiri gladi bersih.
“Enggak, kamu malu-maluin banget! Katakan dengan lantang dan bangga!” bentak Todoroki saat aku dan Ushio berlatih adegan balkon untuk kesekian kalinya. “Hal terburuk yang bisa dilakukan aktor adalah setengah-setengah! Kamu nggak mau mempermalukan diri sendiri di atas panggung, kan?!”
Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia harapkan dariku; aku berusaha berbicara lebih keras dan lebih percaya diri, tetapi Romeo terlalu banyak menggunakan kalimat romantis yang berbunga-bunga dalam versi ini, yang terlalu berlebihan dalam hal rasa ngeri—terutama untuk penyendiri pesimis sepertiku. Aku tidak bisa menghitung berapa kali aku ingin mencari alumni mana pun yang menulis naskah ini dan memberi mereka sepotong pikiranku. Tunggu… Itu saja!
“Hei, bolehkah kita ubah sedikit dialognya?” tanyaku. “Kalau kita bisa membuatnya terdengar sedikit lebih maskulin, kurasa aku bisa memerankannya jauh lebih natural, yang akan membuat aktingnya lebih meyakinkan.”
“Apa? Nggak mungkin,” kata Todoroki. “Itu bakal bikin drama ini jadi membosankan. Cinta yang polos dan naif seperti itulah yang bikin Romeo dan Juliet jadi klasik! Itulah pièce de résistance!”
“Maksudku, kamu mungkin berpikir begitu, tapi entahlah… Hei, Ushio. Bagaimana menurutmu? Bukankah lebih baik kalau kita ubah beberapa hal ini?”
Aku menoleh ke Ushio, berdoa agar ia mau menolongku. Ia tak pernah sekalipun mendapat kritik tajam dari Todoroki atas kemampuan aktingnya—hanya pujian yang meluap-luap setiap kali ia melafalkan sebuah dialog. Tentu saja ia bisa meyakinkan sutradara panggung untuk membuat beberapa perubahan demi aku, meskipun aku tak bisa. Atau begitulah yang kupikirkan.
“Kenapa harus begitu?” tanya Ushio. “Tidak bisakah kita melakukannya sesuai yang tertulis?”
Sial. Penolakan mentah-mentah. Aku tidak punya pilihan lain.
“Lihat, bahkan Tsukinoki pun setuju denganku,” kata Todoroki. “Kau hanya perlu sedikit lebih mengakuinya, Kamiki, dan aku janji itu tidak akan terasa memalukan. Mau aku bawakan sendiri untukmu sebagai contoh?”
“Eh… Kamu yakin mau melakukan itu?” tanyaku.
“Ha. Dia pikir aku tidak bisa, ya? Lihat dan pelajari saja.”
Todoroki berdeham pelan untuk membersihkan tenggorokannya, lalu melafalkan salah satu solilokui Romeo dari ingatannya tanpa melihat naskahnya. Segala hal tentang penampilannya—dari ekspresi wajah hingga intonasi vokalnya—jauh lebih mencekam dan dramatis daripada penampilanku, sehingga rasanya lucu membandingkan keduanya. Aku harus memberinya pujian; aku sungguh tidak menyangka dia punya bakat itu.
“Wah… Luar biasa,” kataku, senang mengakui keunggulannya.
“Aku tahu, kan?” Todoroki membusungkan dadanya dengan bangga. “Bukannya aku menyombongkan diri, tapi aku agak penggemar film, lho. Hal-hal seperti ini datang begitu saja kepadaku.”
Saya cukup yakin bahwa sekadar menonton banyak film biasanya tidak berkorelasi dengan peningkatan kemampuan akting seseorang. Namun, dia memang punya bakat yang luar biasa, jadi mungkin saya salah.
“Ya, itu benar-benar hebat, Meiko,” kata Ushio, menggunakan nama depan Todoroki. “Seandainya kamu juga bisa tampil di panggung bersama kami.”
“Tidak, tidak, tidak,” kata Todoroki. “Aku ingin menyutradarainya, jangan khawatir. Dan semua orang tahu seorang sutradara tidak bisa berakting dalam produksinya sendiri. Itu akan sangat aneh.”
“T-tidak, itu tidak akan…” terdengar suara kesal yang terdengar dari kejauhan. Aku menoleh dan ternyata itu Nanamori, yang menatap tajam ke arah kami. Ia baru saja membahas logistik kostum dengan beberapa aktor lain, tapi rupanya percakapan itu sudah berakhir sekarang.
“Tidak akan?” tanya Ushio.
Nanamori menggelengkan kepala dan dengan malu-malu berjalan menghampiri kami. “Yah, eh, begini… Sebenarnya ada beberapa film di mana sutradaranya memainkan peran utama. Atau peran kecil. Atau bahkan hanya sekadar muncul sebentar.”
“Oh, ya. Kau tidak bilang,” kata Ushio. “Itu sedikit trivia yang menarik.”
“Ya, aku juga sangat menyukai film…”
Saya tidak tahu—bukan hanya soal sutradaranya, tapi juga fakta bahwa Nanamori penggemar berat film. Setidaknya, saya berasumsi begitu jika dia merasa perlu menyela dan mengoreksi seperti itu dari jauh, meskipun biasanya dia penurut. Di sisi lain…
“Maksudku, ya, aku tahu itu. Jelas sekali,” kata Todoroki, berbohong sambil menggigit bibirnya.
“…Poser,” kataku.
“Maaf, ya?! Kau pikir aku akan membiarkannya begitu saja?! Baiklah, kau yang minta! Aku akan dua kali lebih kritis terhadap aktingmu sekarang, Kamiki!”
“Tunggu, ya?!”
Sial… Seharusnya aku simpan saja pikiran itu untuk diriku sendiri. Yah, sudahlah.
Ushio dan Nanamori mulai terkekeh sendiri, menyaksikan Todoroki mengolok-olokku. Aku merasa agak picik karena melontarkan sindiran itu, dan sedikit malu—tapi aku pasti akan melakukannya lagi, sungguh. Jadi, terserahlah; kalau dikritik habis-habisan saat latihan berarti aku akan jadi aktor yang lebih baik di hari pertunjukan, biarlah. Aku hanya harus tegar dan belajar menghadapi dialog-dialog yang bikin malu… kurasa begitu.
Meski begitu—meskipun masih banyak hal yang bisa diperbaiki dalam hidupku saat ini, akhir-akhir ini aku merasa benar-benar memanfaatkan waktuku di sekolah sebaik-baiknya. Aku selalu mengernyitkan dahi setiap kali mendengar ungkapan bahwa bagian paling menyenangkan dari festival budaya siswa adalah tahap persiapannya, tapi mungkin ada benarnya juga. Seandainya saja hari-hari sederhana dan sibuk ini bisa berlangsung selamanya.
***
Begitu saja, kami langsung terjun ke bulan Oktober. Angin semakin dingin seiring teriknya sinar musim panas yang keras dan tak kenal ampun akhirnya menyerah dan berganti dengan temperamen musim gugur yang lembut dan cepat berlalu. Iklim yang sejuk dan segar begitu nyaman dan sejuk sehingga saya hampir tak ingin mengucapkan selamat tinggal saat melangkah masuk ke dalam gimnasium.
Hari ini adalah gladi resik pertama kami untuk Romeo dan Juliet sebagai persiapan untuk acara utama di festival budaya Sabtu depan. Memang, kami belum menghadirkan semua aktor dan kru, tetapi hari ini kami akan mengenakan kostum untuk pertama kalinya, menggunakan ruang ganti tim basket sebagai ruang ganti sementara. Sayangnya, kostum Romeo saya masih dalam tahap pengerjaan, jadi saya hanya bisa mengenakan seragam sekolah seperti sebelumnya.
Karena tak ingin hanya berdiam diri di tengah auditorium menunggu yang lain bersiap-siap, aku menuju ke pojok gym dan bersandar ke dinding. Aku merasa sedikit cemas. Terlepas dari semua tugas panitia festival yang harus kulakukan, aku berhasil meluangkan cukup banyak latihan akting sehingga sejujurnya kupikir aku bisa memainkan peran itu dengan cukup baik sekarang—tapi aku masih merinding membayangkan harus tampil di depan penonton, apalagi di panggung sebesar ini.
“Kau tampak agak tegang, Sobat,” kata teman lamaku Hasumi sambil berjalan di sampingku. Seperti biasa, rasanya ia bisa melihat menembus diriku. Ia anggota kru belakang panggung, tetapi ia datang ke sini untuk gladi resik hari ini, untuk menyempurnakan pencahayaan setiap adegan. Bagi seorang pria yang tampaknya senang mengamati orang dan drama mereka dari jauh tanpa pernah terlibat langsung, rasanya peran yang tepat baginya adalah bertugas menjaga lampu sorot dari atas panggung peragaan busana. Meskipun ini jelas arti kata “drama” yang sangat berbeda.
“Ya, entahlah, Bung. Cuma agak gelisah, kurasa. Maksudku, kau tahu aku nggak suka jadi pusat perhatian…”
“Percayalah, aku tahu. Aku tak percaya saat kau mengajukan diri untuk memainkan peran utama.”
“Enggak, aku juga sama kayak kamu… Aku sendiri agak nggak percaya, tapi kurasa Ushio mungkin punya andil besar. Kalau dia nggak jadi Juliet, aku pasti nggak akan mau jadi Romeo.”
Sejujurnya, setelah kupikir-pikir lagi, aku telah melakukan banyak hal selama beberapa bulan terakhir yang membuatku menonjol di antara orang banyak dengan cara yang tak pernah kulakukan sebelumnya—dan semua itu ada hubungannya dengan Ushio. Dialah yang meyakinkanku untuk menjadi sukarelawan panitia festival juga. Dan aku tak akan pernah memaksakan diri untuk meraih juara pertama di ujian terakhir kami jika bukan karena mencegahnya berkencan dengan Sera. Rasanya seperti riak-riak dari gejolak awal Ushio yang memilih untuk membuat perubahan besar dalam hidupnya masih menyebar dan memengaruhiku hingga hari ini, membuatku menjalani hidupku sendiri dengan lebih tegas juga. Cukup melegakan memikirkannya seperti itu.
“Kurasa kau harus berterima kasih pada Tsukinoki karena telah membawa pemain kecil sepertimu menjadi pusat perhatian, ya?” kata Hasumi.
Mataku terbelalak. “Astaga… Kadang-kadang kamu ngomongin hal yang cukup dalam, Bung.”
“Setuju saja,” kata Hasumi, tampaknya tak memikirkan apa pun. “Pokoknya, coba lihat. Sepertinya pemeran utama wanitamu baru saja tiba.”
“Tunggu, beneran?”
Hasumi menyentakkan dagunya ke arah pintu masuk utama gedung olahraga. Aku menoleh dan melihat semua aktor lainnya—yang telah selesai berganti pakaian—kini memasuki auditorium dalam satu kelompok besar. Benar saja, Ushio berada tepat di tengah kerumunan itu, mengenakan gaun panjang dan elegan, roknya yang berenda berkibar-kibar saat ia berjalan.
Ia menoleh ke arahku, dan tatapan kami bertemu. Ia mengucapkan beberapa patah kata kepada para aktor lain, lalu pamit dari kerumunan dan bergegas menghampiriku.
“Yah, kurasa sebaiknya aku ke atas saja,” kata Hasumi. Aku tidak tahu apakah dia sengaja menjauhkan diri dari situasi ini, tapi dia dan Ushio tidak punya banyak kesamaan, jadi aku tidak akan memaksanya untuk tetap di sana dan bersosialisasi.
“Baiklah,” kataku. “Sampai jumpa.”
Aku memperhatikan Hasumi berjalan pergi, melewati Ushio yang sedang menuju catwalk. Ushio menoleh ke arahnya, lalu berlari menghampiriku.
“Maaf, apakah saya mengganggu?” tanyanya.
“Nggak, kamu baik-baik saja. Lagipula kita nggak pernah ngobrol lama-lama.”
“Oh, ya? Kukira kalian berdua cukup dekat.”
“Eh. Aku tidak akan sejauh itu .”
Tentu, kami makan siang bersama, dan kami akan berpasangan untuk kegiatan berpasangan di kelas olahraga dan sebagainya. Tapi aku sama sekali tidak menganggap kami “dekat”. Kalau boleh kusebut begitu, aku akan menyebut kami “akrab.”
“Kalian biasanya membicarakan apa?” tanya Ushio.
“Cuma hal-hal acak. Kadang-kadang dia tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sangat mendalam dan introspektif, lalu tiba-tiba menghilang dari percakapan seolah-olah tidak ada apa-apanya.”
“Hah. Kedengarannya dia orang yang cukup baik, ya.”
“Ya, maksudku… Dia jelas bukan orang jahat , itu sudah pasti.”
Aku memilih kata-kataku dengan hati-hati karena agak memalukan untuk mengatakannya dengan lantang, tetapi aku harus mengakui bahwa Hasumi adalah pria yang cukup baik—setidaknya karena dia cukup baik untuk menghubungi dan mengobrol dengan seorang penyendiri sepertiku sepanjang waktu.

“Ngomong-ngomong, kostum itu terlihat sangat bagus untukmu,” kataku, mengganti topik pembicaraan.
“K-kau pikir begitu?” jawab Ushio, terdengar agak ragu, tapi tak mampu sepenuhnya menyembunyikan kegembiraan dalam suaranya. “Semua orang memujiku, tapi entahlah… Kurasa mungkin ini agak berlebihan?”
Ushio menunduk menatap gaunnya dan gelisah. Aku ingat dia bersikap sama ragunya saat kami bertemu di luar stasiun kereta, kalau dipikir-pikir; mungkin dia memang belum terbiasa memakai pakaian feminin.
“Nah, menurutku itu bagus. Maksudku, kau pemeran utama wanita, kan? Kau seharusnya tampil menonjol di atas panggung. Aku yakin Nanamori-san akan senang.”
Ushio menanggapi dengan dengungan ragu, memalingkan muka seolah terlalu malu untuk melihat dirinya sendiri. Ia tampak agak khawatir; saya berasumsi ada bagian dari dirinya yang ingin menghargai visi dan usaha Nanamori, tetapi itu tidak cukup untuk mengatasi rasa malunya yang lebih umum karena terlihat mengenakan gaun pesta, terlepas dari siapa pun yang membuatnya.
“Hei! Kita mulai latihannya sekarang, semuanya!” teriak Todoroki dari ujung auditorium. Semua aktor yang tadinya berkeliaran di sekitar gym langsung menghentikan obrolan mereka dan berjalan ke atas panggung.
“Kalau begitu, kurasa sebaiknya kita segera berangkat, ya?”
Ushio dan saya mengikutinya dan menuju ke sana.
Selama pertunjukan sebenarnya, kami akan menutup tirai jendela dan meredupkan semua lampu di gimnasium kecuali yang di atas panggung—tetapi karena ini hanya gladi resik dan kami tidak tampil di depan penonton, kami hanya memutar seluruh pertunjukan dengan lampu menyala. Setelah narator memperkenalkan alur dan latar, kami langsung masuk ke adegan pertama, di mana Romeo dan Juliet bertemu setelah Romeo menyelinap ke pesta dansa yang diadakan di kediaman Capulet. Mereka langsung jatuh cinta satu sama lain, cinta mereka yang membara tak kunjung padam bahkan setelah akhirnya terungkap bahwa mereka berasal dari dua keluarga yang berseteru.
Tak ada kekuatan duniawi yang mampu menolak cinta ini. Biarkan mereka mengejarku jika mereka mau—jubah malam akan menyembunyikanku dari pandangan mereka.
Sebagai Romeo, saya menyatakan cinta kepada Juliet saat dia berdiri di balkonnya—atau catwalk, dalam hal ini. Semoga saja, pencahayaan yang cerdas dan properti papier-mâché kami bisa menciptakan ilusi balkon yang cukup bagus pada malam pertunjukan.
…Astaga. Seberapa sering pun kami berlatih adegan ini, wajahku tetap saja memerah. Entah kenapa aku tidak menyadarinya lebih awal, tapi aku sungguh tak percaya Romeo dan Juliet , dari semua hal, telah menjadi salah satu drama standar yang dipentaskan siswa di sekolah. Aku tak bisa membayangkan adegan ini tidak canggung sekali bagi siapa pun seusia kami, kecuali mereka sudah berpacaran. Namun, ketika Ushio benar-benar di atas panggung memerankan Juliet, aku sama sekali tidak merasakan ketegangan atau rasa malu darinya.
“Hatiku terbuka di hadapanmu, wahai Romeo yang lembut, di sini, di bawah sinar bulan yang pucat…”
Setiap kata yang ia ucapkan dibawakan dengan begitu tulus sehingga masing-masing membangkitkan emosi yang kuat dan saling bertentangan jauh di dalam dadaku—campuran gairah yang membara dengan duka yang pahit dan dingin, yang menyampaikan badai cinta Juliet, yang disampaikan Ushio kepadaku hanya dengan suaranya. Rasanya begitu realistis sehingga terkadang aku harus bertanya pada diri sendiri: apakah ia benar-benar hanya berakting di sini? Apakah kredibilitas penampilannya semata-mata hasil dari latihan dialog dan vokal yang dipadukan dengan bakat alami? Ataukah perasaan Ushio yang sebenarnya yang kudengar, hanya tersaring melalui kata-kata Juliet?
“Sudah hampir pagi. Oh, perpisahan adalah duka yang begitu manis! Andai saja aku bisa mengikatmu dengan benang sutra dan menjagamu sampai esok hari.”
Tetapi sekarang bukan saatnya untuk bertanya-tanya tentang hal-hal seperti itu.
Aku mengucapkan selamat tinggal terakhirku pada Juliet, lalu pergi meninggalkan malam.
Dari sana, Romeo membunuh Tybalt untuk membalaskan dendam Mercutio dan diusir dari kota kelahirannya, Verona. Juliet, yang masih sangat mencintainya, menyusun rencana untuk memalsukan kematiannya sendiri dan melarikan diri dari kota untuk mengejarnya. Pada akhirnya, ia berhasil—tetapi sebuah nasib buruk membuat Romeo diberitahu tentang kematiannya yang terlalu dini sedemikian rupa sehingga ia tidak menyadari bahwa itu semua tipuan, dan ia akhirnya bunuh diri dengan racun daripada hidup tanpa Juliet. Ketika Juliet mengetahui hal ini, ia bunuh diri dengan belati Romeo. Dengan kematian mereka sebagai pemicu, keluarga Montague dan Capulet akhirnya sepakat untuk menyelesaikan perbedaan mereka dan mengubur perseteruan lama mereka.
“Oke, kurasa sudah selesai!” kata Todoroki, lalu mulai bertepuk tangan dengan keras.
Aku menganggap ini sebagai izin untuk berhenti berpura-pura mati dan bangkit dari panggung. Semua aktor lain bergegas keluar dari sisi panggung, berceloteh tentang betapa tegangnya mereka selama pertunjukan, betapa senangnya mereka akhirnya selesai, dan berbagai perasaan lainnya. Suasana di atas panggung menjadi lebih rileks, dan seluruh rombongan menghela napas lega.
“Kerja bagus,” kata Ushio, menghampiriku untuk memberi selamat. Sepertinya pertunjukan yang panjang itu membuatnya sedikit lelah, dilihat dari wajahnya yang memerah dan lapisan tipis keringat yang membasahi kulitnya.
“Iya, kamu juga,” kataku. “Kita bahkan nggak pernah salah.”
“Tentu saja tidak. Dengan kecepatan seperti ini, seharusnya performanya berjalan lancar. Meskipun…”
“Meskipun?”
“Aku agak terbakar dalam hal ini.”
Ushio mencengkeram kain di sekitar dadanya dan mengepakkannya untuk mengangin-anginkan gaunnya. Aha. Jadi dia tidak terlalu lelah; kostumnya seperti sedang membakarnya hidup-hidup. Saya berasumsi gaun itu tidak memiliki sirkulasi udara yang baik, meskipun cukup sulit untuk mendesain dengan mempertimbangkan hal itu dan mampu menyediakan semua kain dan bahan yang paling ideal untuk kostum yang sebenarnya hanya dirancang untuk dipakai satu hari.
“Kenapa kamu tidak coba bicara dengan Nanamori-san saja?” tanyaku. “Masih ada waktu sebelum festival. Mungkin dia bisa menyesuaikan diri.”
“Ya, kurasa begitu.” Ushio berjalan ke jendela yang terbuka dan menyibakkan poninya, memperlihatkan dahinya yang indah bak porselen yang tertiup angin sepoi-sepoi. Jarang sekali ia mengibaskan rambutnya ke belakang dan mengacak-acaknya seperti ini, tapi mungkin ia merasa terbebas sekarang setelah latihan selesai. Bagaimanapun, senang melihatnya berterus terang. Aku memperhatikannya menurunkan tangannya dan tertawa kecil sebelum berbalik menatapku.
“Kau tahu, Sakuma,” katanya, “aku perhatikan akhir-akhir ini kau sering sekali menatapku. Apa kau tidak bisa menahan diri?”
“Siapa, aku?! Tidak, aku belum pernah!”
“Oh, ya, kau sudah melakukannya. Kau benar-benar melakukannya barusan. Setidaknya katakan sesuatu kalau kau mau menatapnya—kalau tidak, agak mengerikan.”
Setelah dia menyebutkannya, saya jadi ingat beberapa kali saya berhenti untuk mengamatinya baik-baik dalam beberapa minggu terakhir. Ini jelas kebiasaan buruk yang perlu diperbaiki.
“M-maaf,” kataku. “Aku tidak bermaksud jadi orang aneh…”
“Tidak perlu minta maaf,” kata Ushio. “Aku tahu kau tidak sedang mengamatiku atau semacamnya, jadi tidak menyeramkan—hanya sedikit aneh, mungkin.”
“Saya akan berusaha untuk tidak membiarkan hal itu terjadi lagi.”
Aku benar-benar merasa bersalah dan bertekad untuk berubah… Tapi sekarang setelah dia menunjukkannya, aku jadi bingung harus menatap ke mana lagi. Aku jadi merasa sangat tidak nyaman sampai-sampai aku memalingkan tubuhku secara diagonal dari Ushio, hanya untuk memastikan tidak ada kemungkinan aku tak sengaja menatapnya. Dia mengerutkan kening, seolah cemberut karena keputusannya ini.
“Ugh, oke, sekarang kamu cuma bertingkah konyol,” katanya. “Kamu boleh menatap mataku saat kita ngobrol, bodoh!”
Dia mencengkeram bahuku dan menarikku hingga menghadapnya sekali lagi, dan tatapan kami langsung terkunci. Untuk sesaat, aku kehilangan kemampuan merangkai kata. Aku tak bisa mengalihkan pandangan darinya—seolah ada kekuatan magis yang mencengkeram dan tertanam di pupil matanya, mengancam untuk menghisap dan menelanku bulat-bulat. Ushio juga menegang, sama bingungnya denganku karena kontak mata yang tak terduga dalam ini. Astaga, ini terasa aneh sekali… Apa-apaan ini?
“Hei! Bravo, kalian berdua!”
Ushio dan aku hampir melompat kaget, lalu berbalik dan melihat Todoroki berjalan menghampiri dan memuji kami, langkahnya bersemangat.
“Ya ampun, acaranya seru banget! Kalau begini terus, kita pasti sudah siap untuk acara utamanya!”
Ssst, Nak… Kau membuatku ketakutan setengah mati. Tapi sejujurnya, aku berterima kasih padanya; kalau saja dia tidak menyela, siapa yang tahu berapa lama aku dan Ushio akan terjebak dalam kebuntuan yang canggung itu.
“Kau benar-benar istimewa, Tsukinoki!” seru sang sutradara. “Dan gaun itu! Gaun itu benar-benar meningkatkan penampilanmu ke level selanjutnya! Kalau aku bisa menominasikanmu untuk Aktris Utama Terbaik, aku pasti akan melakukannya!”
“Ah ha ha… Makasih,” kata Ushio, meskipun masih ada nada gelisah dalam suaranya. Aku menganggap ini sebagai konfirmasi bahwa dia juga mengalami perasaan aneh yang sama seperti yang kurasakan beberapa saat yang lalu, dan dia juga masih terguncang. Sungguh… apa itu ?
“Dan untukmu, Kamiki…” lanjut Todoroki. “Kau sudah cukup berkembang. Kurasa kau sudah hampir lumayan sekarang.”
“Wah, pujiannya kurang banget… Kalau begitu, aku nggak masuk nominasi Aktor Utama Terbaik, ya?”
“Enggak! Tapi kalau kamu kerja keras lima tahun lagi, mungkin kita bisa bahas itu nanti!”
“Sial. Aku nggak yakin punya kesabaran untuk bertahan selama itu.”
“Pokoknya, selama kalian berdua terus tampil seperti itu, kita bisa menang! Tapi untuk hari ini, kurasa kalian pantas istirahat yang cukup! Tenang saja, kalian berdua—dan hati-hati di jalan pulang!”
Dengan itu, Todoroki melompat turun dari panggung dan berlari kecil.
“…Gadis itu benar-benar bersenang-senang akhir-akhir ini,” kataku. “Dia benar-benar suka duduk di kursi sutradara.”
“Mungkin suatu hari nanti kita akan melihat salah satu filmnya dinominasikan untuk penghargaan,” kata Ushio.
“Aku bisa mempercayainya, ya.”
Ushio dan saya menyaksikan Todoroki melompat-lompat keluar dari gimnasium dan berputar di sudut, lalu kami sendiri turun dari panggung.
Ketika teman-teman sekelas kami berhamburan keluar gedung dalam kelompok dua atau tiga orang, saya pun mengikutinya—meskipun saya masih harus menunggu Ushio, yang masih berganti pakaian di ruang klub tenis meja di dalam gedung olahraga. Di luar, matahari sudah mulai terbenam, dan saya bisa merasakan angin dingin bertiup dari utara. Saat kesunyian malam mulai menyelimuti, saya bisa mendengar kicauan jangkrik lonceng dari suatu tempat di kejauhan.
Saya duduk di anak tangga beton kecil menuju gimnasium dan menunggu. Waktu menunjukkan pukul setengah enam. Ketika saya melihat ke arah gerbang utama kampus, saya melihat sekelompok anggota tim tenis dengan tas raket tersampir di bahu mereka, banyak yang mengeluh tentang betapa lelah atau laparnya mereka saat pulang latihan.
“Maaf ya, lama banget nunggunya,” kudengar Ushio berkata dari belakangku, jadi aku berbalik. “Butuh waktu lebih lama dari yang kukira karena akhirnya aku ngobrol sebentar dengan Nanamori-san soal kostum. Siap pulang?”
“Ya, ayo pergi,” kataku sambil berdiri dan menyeka debu di celanaku.
Tepat saat kami hendak pergi ke tempat parkir sepeda, sebuah suara yang tak asing terdengar dari seberang jalan.
“Tunggu, sudah selesai?!” teriak Hoshihara dari lorong yang menghubungkan gedung sekolah utama dengan gedung olahraga, lalu berlari menghampiri kami. “Tapi kukira gladi resiknya hari ini…”
“Memang. Kamu melewatkannya, maaf,” kata Ushio sambil tersenyum meminta maaf.
“Aduh, man ! Aku juga ingin sekali melihatmu memakai gaun itu…” Hoshihara menjatuhkan bahunya, pasrah.
“Kamu akan mendapat kesempatan lagi, jangan khawatir. Lagipula, gladi resik tidak akan pernah sekeren pertunjukannya.”
“Mrrmm… Ya, kurasa itu benar…” Hoshihara langsung menegakkan kepala dan bahunya kembali. Yah, setidaknya dia cepat sembuh.
“Sudah selesai dengan pekerjaan komite hari ini?” tanyaku.
“Ya.” Dia mengangguk. “Aku ingin menonton latihannya, jadi aku berusaha menyelesaikan semuanya secepat mungkin, tapi kurasa aku masih belum cukup cepat… Oh, tapi aku punya satu kabar baik untuk dibagikan!”
“Ya? Apa itu?”
“Kalian nggak akan percaya! Kita selesai membangun gapura masuk festival hari ini! Hore!” Ia mengepalkan tinjunya ke udara. Antusiasmenya sungguh menular.
“Wah, serius, ya? Gila, kalian menyelesaikannya dengan sangat cepat.”
“Yah, secara teknis belum selesai . Kami masih harus memasangnya di atas gerbang utama antara sekarang dan sehari sebelum festival. Tapi menyelesaikan semua bagiannya saja sudah sangat merepotkan… Senang rasanya sudah selesai.”
“Ya, aku yakin. Kamu bekerja keras untuk itu.”
Aku masih bisa membayangkannya mengenakan celemek kerjanya, penuh noda, tapi ia asyik melukis dengan kuas kecilnya. Aku sudah berusaha meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk membantu lengkungan di sela-sela latihan dan tugas komiteku, tapi aku masih belum sesering Hoshihara mengerjakannya.
“Ya, maksudku, itu akan jadi hal pertama yang dilihat orang-orang ketika mereka datang ke festival!” katanya. “Ingin membuatnya menjadi bentuk yang bisa kita semua banggakan. Meskipun akhirnya aku jadi malas mengerjakan beberapa tugas ketua komite lainnya dan akibatnya banyak orang jadi kerepotan…”
“Nah, kamu hebat sekali,” kataku. “Luar biasa kamu berhasil menyelesaikan tugas sebesar ini sementara kamu sudah sibuk mengawasi orang lain. Kamu pantas mendapat pujian untuk itu, kataku.”
“Aduh… Kamu pikir begitu? Aduh, kamu bikin aku malu!”
Hoshihara tersenyum malu dan menggaruk pipinya dengan satu jari. Aku tahu dia bilang alasan utamanya ingin mencoba menjadi ketua komite adalah untuk membantunya berkembang, tapi dari sudut pandangku, dia sudah mencapai tujuan itu dan bahkan lebih. Aku cukup senang melihat ini; itu menginspirasiku untuk mendorong diriku menjadi orang yang lebih baik juga. Aku tersenyum padanya, lalu menoleh ke arah Ushio… Tapi kemudian aku harus menatapnya dua kali.
Ushio tidak berekspresi, wajahnya begitu kosong dan dingin serta tanpa emosi sehingga hampir seperti menatap topeng kayu yang dicat.
“Ushio?” tanyaku.
“Hm? Ada apa?” jawabnya, wajahnya langsung merona.
“Oh, eh… Tidak ada apa-apa, maaf. Siap pulang?”
“Ya, kurasa sekaranglah saatnya.”
Suaranya terdengar sama seperti biasanya. Aku bertanya-tanya, mungkin aku hanya berkhayal, atau mungkin itu hanya tipuan cahaya yang aneh karena melihat wajahnya dari sudut tertentu di bawah sinar matahari terbenam.
“Ooh, aku tahu!” Hoshihara menimpali. “Sudah mulai malam—gimana kalau kita mampir dan makan di suatu tempat dalam perjalanan pulang?”
Kini ada ide yang bisa saya dukung. Saya langsung menyetujuinya, dan Ushio pun langsung setuju. Kami masing-masing menghubungi orang tua kami untuk memberi tahu, lalu naik sepeda dan menuju restoran lokal dekat stasiun.
Angin terasa nyaman di pipiku saat kami mengayuh sepeda menyusuri jalanan yang familiar. Di malam musim gugur yang menyenangkan seperti ini, aku akan puas bersepeda sampai ke ujung dunia—meskipun mungkin itu bukan karena suhu di luar, melainkan karena kebersamaan di sisiku. Sudah lama sekali sejak kami bertiga pulang sekolah bersama.
Kami tiba di restoran. Suasananya hampir seramai yang kami perkirakan, mengingat saat itu jam makan malam Jumat malam. Meskipun para pelayan sibuk mondar-mandir, mereka berhasil mendudukkan kami dengan cepat tanpa perlu menunggu lama. Ushio dan saya duduk bersama di satu sisi meja, sementara Hoshihara menyelinap ke sisi lain dan membuka menunya.
“Astaga, aku bahkan nggak tahu mau pesan apa…” katanya. “Ooh, kita bisa pesan salad besar dan dibagi tiga, mungkin! Lalu pesan pizza atau apa pun untuk dimakan bersama. Ngomong-ngomong, astaga… entahlah kalau kalian, tapi kayaknya aku bisa pesan sepiring steak panggang ini.”
“Wah, selera makanmu ternyata tinggi sekali,” kataku datar, tanpa bermaksud positif atau negatif. Tapi Hoshihara memakainya seperti lambang kebanggaan.
“Yah, tentu saja! Aku sedang tumbuh!” katanya sambil membusungkan dada. “Dan aku sudah bekerja keras hari ini, jadi aku pantas mendapatkannya. Harus tahu cara memberi penghargaan pada diri sendiri atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Jangan sampai mengabaikan kesehatan diri sendiri!”
“Oh, begitukah cara kerjanya?”
“Ya, memang!” Dia melirikku dan Ushio bergantian. “Kalian juga harus memastikan kalian makan cukup. Seperti kata nenekku: kalau satu apel sehari bisa menjauhkanmu dari dokter, makin banyak apel yang kau makan, makin sehat dan bahagia dirimu!”
“Kedengarannya nenekmu sungguh baik hati,” kata Ushio sambil tersenyum.
“Ya, dia manis sekali. Meskipun aku memang pernah mengalami fase gendut parah waktu SD gara-gara dia. Wah, susah banget sih berusaha langsing lagi… Dimarahin segala macem sama cowok-cowok di kelas, dan sebagainya.”
Aku bisa membayangkan macam-macam julukan yang diberikan kepadanya, mengingat betapa kejamnya anak laki-laki kecil. Meskipun harus kuakui, aku agak sulit percaya bahwa seseorang sekecil Hoshihara pernah kurus kering.
“Ah, sial! Maaf, lupakan saja!” katanya sambil menepuk-nepuk pipinya dengan tangan. “Bukannya mau merusak suasana atau apa. Jadi, kalian berdua sudah memutuskan?”
“Ya, kurasa aku siap memesan,” kataku.
“Aku juga,” kata Ushio. “Kalau kau tahu apa yang kau inginkan, Natsuki, kurasa aku akan menekan tombol panggil.”
“Oke, ya! Ayo!”
Ushio menekan tombol panggil, dan seorang pelayan segera datang untuk mencatat pesanan kami. Kami pun memesan minuman soda, jadi kami bertiga berjalan mengisi gelas masing-masing dengan minuman manis apa pun yang kami inginkan sebelum kembali ke bilik, dan Hoshihara mengangkat gelasnya ke udara.
“Baiklah! Bagaimana kalau bersulang?”
“Apa acaranya?” tanyaku, dan segera menjadi jelas bahwa dia belum memikirkan sejauh itu.
“Uhhh… Malam Festival Budaya?”
“Festivalnya baru minggu depan.”
“Baiklah kalau begitu… Malam Festival Budaya Malam Malam Malam Malam Malam… Malam?”
“Ya, nama yang bagus. Benar-benar mudah diucapkan…”
Dan secara teknis, itu delapan hari dari sekarang, bukan tujuh.
“Jangan terlalu ambil pusing soal hal-hal kecil!” katanya. “Ayo, kalian berdua! Ambil gelas kalian! Bersulang!”
Kami bertiga mengangkat gelas dan berdenting-denting, lalu mulai menenggak soda manis kami bersama-sama. Minumanku cuma Pepsi biasa, tapi harus kuakui—aku tak pernah tahu rasanya bisa semanis malam ini.
“Oh ya, jadi salah satu kelas senior akan membuat rumah hantu, kan? Tapi kita tidak boleh membuatnya terlalu gelap, karena itu membahayakan keselamatan, jadi kami bilang mereka perlu sedikit mencerahkan suasana—dan astaga , itu tidak berjalan dengan baik. Yang kumaklumi, soalnya, siapa yang mau masuk rumah hantu dengan lampu menyala, tahu? Sudah coba bicarakan dengan fakultas untuk menemukan titik tengah yang tepat, tapi semua pilihan yang bisa kita pikirkan masih belum cukup terang untuk mendapatkan persetujuan mereka… Astaga, jadi ketua komite terkadang menyebalkan!”
Hoshihara mengambil kentang goreng dari piringnya satu per satu sambil memikirkan beberapa keluhannya akhir-akhir ini. Tiba-tiba ia menjadi sangat cerewet setelah menghabiskan sebagian besar makanannya; kupikir mungkin melahap dan melampiaskan rasa frustrasinya adalah indikator tingkat stres yang sangat tinggi yang dialaminya. Ia sudah menghabiskan steak dan setengah pizzanya, lalu dengan senang hati melahap sepiring penuh salad. Bahkan sekarang, ia masih mengunyah kentang goreng, jadi sepertinya masih ada ruang di perutnya. Sebagian diriku agak khawatir ia akan makan begitu banyak sekaligus, tetapi sebagian diriku yang lain merasa hangat dan nyaman melihat betapa bahagianya ia saat ia mengisi pipinya seperti tupai.
“Wah, kau benar-benar punya banyak hal yang harus kau kerjakan, Natsuki,” kata Ushio, yang memaksudkannya dalam arti kiasan.
“Ah, ayo! Katakan betapa hebatnya aku! Eh heh heh!” kata Hoshihara, memegangi wajahnya dengan kedua tangannya sementara bibirnya melebar membentuk seringai lebar.
“Kamu jelas sudah bekerja sangat keras. Sungguh mengesankan melihatnya.”
“Wah ha ha! Eh, nggak masalah kok, kok!”
Dari sikapnya, saya jadi bertanya-tanya apakah Hoshihara merasa sedikit mabuk—bukan karena dia minum alkohol, tentu saja. Namun, setelah menenangkan diri sejenak, dia mendesah pelan dan tampak muram sejenak.
“Dan bagaimanapun juga, itu belum cukup… Aku masih punya jalan panjang untuk berkembang…” katanya, lalu mengangkat gelasnya dan mengerucutkan bibirnya di balik sedotannya.
Saya tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan ini; sebagai sesama anggota komite, saya telah melihat sendiri betapa kerasnya ia bekerja. Namun, Hoshihara masih belum puas dengan kinerjanya sendiri. Saya belum pernah melihat sisi dirinya yang lebih rendah hati dan tegas seperti ini sebelumnya. Meskipun hal itu membantu saya menghargainya dalam sudut pandang yang baru dan lebih holistik, hal itu juga membuat saya merasa sedikit aneh di lubuk hati.
“Tidak, kurasa yang kau lakukan sudah lebih dari cukup,” kataku.
Hoshihara tidak membalasnya secara langsung; ia hanya menuangkan gelembung besar ke dalam sodanya sebagai ucapan terima kasih.
“Pokoknya!” katanya, sambil melepaskan sedotan dari mulutnya, lalu kembali ke nada mengeluhnya yang tadi dan mengganti topik. “Aku nggak percaya aku masih belum sempat melihat kalian mementaskan Romeo dan Juliet sekali pun!”
“Oh, benarkah?” kataku. “Hah.”
Setelah dia menyebutkannya, aku jadi lupa kapan dia pernah datang ke latihan sepulang sekolah. Dia pasti terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai ketua komite sampai tidak sempat duduk.
“Agak bertanya-tanya apakah saya harus berhenti mencoba dan menunggu sampai kinerja sebenarnya pada tingkat ini…”
“Mungkin ide yang bagus, ya. Malahan, kamu mungkin sedikit beruntung, dalam hal itu.”
“Hmm? Bagaimana caranya?”
Maksudku, kamu pasti tidak mau menonton dokumenter pembuatan film sebelum menonton film aslinya, kan? Idenya hampir sama. Kamu hanya bisa merasakan sesuatu untuk pertama kalinya sekali, jadi lebih baik kamu tunggu dan lihat versi finalnya saja. Dan percayalah—kamu pasti ingin melihat Juliet-nya Ushio di panggung sungguhan, dengan pencahayaan yang sebenarnya dan semuanya. Penampilannya memang cukup hebat untuk pantas mendapatkannya.
“Oh, benarkah?! Maksudku, aku sudah mendengar banyak hal hebat, tapi ya, aku tidak sabar!”
“Pasti sepadan. Dia benar-benar seperti aktris profesional, sumpah.”
“Kau bisa berhenti sekarang,” tegur Ushio. “Kau hanya membesar-besarkan ekspektasinya.”
“Oke, oke… Salahku,” kataku sambil tersenyum malu. “Tapi dia memang cocok memerankan Juliet. Harus kuakui, aku agak khawatir, karena awalnya dia bilang dia sebenarnya tidak mau, tapi sekarang dia sudah benar-benar menguasai peran itu. Nggak heran kalau dia dilirik agensi bakat atau semacamnya.”
Setelah selesai memujinya, aku menghabiskan sisa sepertiga gelas cola-ku. Esnya sudah mencair saat itu, jadi agak encer.
“Tunggu,” kata Hoshihara. “Dia… tidak mau melakukannya?”
Suaranya gemetar.
Seketika, saya menyadari apa yang baru saja saya katakan.
“Dia bilang padaku kalau dia sebenarnya tidak ingin melakukannya pada awalnya.”
Rasa dingin menjalar di tulang punggung saya saat saya menyadari betul bagaimana ungkapan ini dapat ditafsirkan, mengingat Hoshihara adalah salah satu dari dua orang yang awalnya mencalonkannya.
“Ya Tuhan, apa aku…? Ushio-chan, ma-maaf,” kata Hoshihara, wajahnya seputih kertas. “Aku tidak memaksamu, kan…?”
Kepanikan menjalar ke seluruh tubuhku. Satu keceplosan lidahku telah merampas senyum Hoshihara. Ini gawat—aku harus segera bertindak cepat untuk mengendalikan kerusakan.
“Ti-tidak, sama sekali tidak seperti itu!” kataku. “Dia hanya tidak yakin bagaimana hasilnya nanti, itu saja! Dan itu pun hanya awalnya! Sekarang dia benar-benar senang menerima peran itu!”
“Benarkah… benarkah itu, Ushio-chan?” Hoshihara tampak bersedia mendengarkanku, tetapi ia jelas tidak sepenuhnya yakin. Namun, ini tidak masalah, karena begitu Ushio menyetujui jaminanku, semuanya akan baik-baik saja lagi.
“Ayolah, Ushio. Bukankah itu yang kaukatakan sebelumnya?” desakku. “Awalnya kau tidak suka ide itu… tapi sekarang kau benar-benar menikmatinya, kan?”
Ushio tidak menjawab. Ia hanya duduk mematung, bibirnya terkatup rapat, menatap meja. Keheningan ini semakin memperparah kepanikanku menjadi tekanan batin yang mendalam. Apa yang terjadi? Kenapa ia diam saja?
“Ushio…?” ulangku.
Lalu, akhirnya, ia mendesah panjang—seolah melepaskan semua tekanan yang terpendam di dadanya. Desahan ini terdengar bukan seperti desahan lega, melainkan desahan seseorang yang berusaha menunda hal yang tak terelakkan.
“Tidak, aku masih berharap tidak melakukannya. Aku menyesal pernah mengambil peran Juliet,” katanya dengan nada acuh tak acuh. Lalu ia menatap Hoshihara dengan tatapan penuh belasungkawa. “Aku benar-benar minta maaf, Natsuki. Tapi sejujurnya, begitulah perasaanku.”
“Itu tidak benar!” teriakku, begitu keras sampai aku terkejut. Beberapa orang yang duduk di meja lain menoleh, tetapi tak seorang pun berdiri untuk ikut campur. “Kau bohong besar. Aku tahu kau tidak benar-benar bermaksud begitu. Kenapa kau seperti ini? Itu… itu bukan yang kau katakan kemarin! Kau bilang kau sangat senang semua orang menerima dan memujimu lagi setelah sekian lama—”
“Kita harus pergi,” kata Ushio, mengabaikanku sepenuhnya sambil bangkit dari tempat duduknya. Ia menyampirkan tasnya di bahu, mengambil struk belanja, dan berjalan menuju kasir sendirian. Hoshihara hanya duduk terpaku sejenak, tampak seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, sebelum dengan gelisah berdiri dan mengikuti langkah Ushio.
Sementara itu, aku merasa terpaku di tempat. Lumpuh. Tak mampu menggerakkan satu otot pun. Otakku tak mampu membayangkan satu pun penjelasan yang mungkin mengapa Ushio berkata seperti itu. Kakiku terasa goyah dan tak menentu, seolah-olah kakiku sendiri. Seolah-olah ini mimpi buruk yang tak bisa kukendalikan. Suara-suara pelanggan yang berceloteh di sekelilingku semakin teredam dan menjauh—lalu suara dentingan keras terdengar di telingaku.
Aku menoleh dan melihat Ushio berdiri di kasir, menunggu seorang staf datang untuk membayar tagihannya. Namun, aku belum siap untuk berdamai. Aku tahu begitu kami melakukannya, kami mungkin akan langsung keluar dari restoran dan berpisah tanpa menyelesaikan masalah ini. Namun, aku juga tahu bahwa hampir mustahil kami bisa menyelamatkan situasi malam ini, bahkan jika kami tetap di sini dan mencoba membicarakannya—dan ada sesuatu yang memberitahuku bahwa jika aku tidak bangun dan bergabung dengan mereka di kasir, Ushio akan membayar tagihanku sendiri, yang mana aku tidak merasa nyaman dengan pikiran itu.
Maka dengan berat hati aku berdiri dan menuju kasir, tempat kami bertiga bergantian duduk sebelum berjalan santai keluar dari restoran. Hari sudah gelap, dan angin dingin terasa semakin menusuk kulitku karena keringat dingin ketakutan yang kini membasahi kulitku. Membayangkan akhir yang mengerikan seperti ini membuatku dihantui rasa takut yang amat besar.
“Tunggu!” teriakku saat mereka hendak mengambil sepeda. “Ini tidak benar! Kita semua hanya tertawa dan bersenang-senang sampai beberapa menit yang lalu, kan? Apa kita benar-benar akan membiarkan satu hal kecil saja membuat kita saling bermusuhan di sini?!”
Tak satu pun dari mereka bersuara. Hoshihara hanya menatap tanah dengan canggung, sementara Ushio balas menatapku dengan mata dingin. Aku mengepalkan tangan.
“Ayo. Katakan sesuatu, kenapa tidak?” aku memohon padanya.
“…Maaf, Kamiki-kun,” kata Hoshihara, perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan senyum paling dibuat-buat yang pernah kulihat. “Dan kamu juga, Ushio-chan. Aku merasa sangat bersalah. Kurasa aku terlalu bersemangat, sampai-sampai tidak memikirkan orang lain selain diriku sendiri. Kalau dipikir-pikir lagi, jelas tidak tepat bagiku untuk mencalonkan orang lain tanpa setidaknya memastikan mereka setuju terlebih dahulu… Aku benar-benar minta maaf.”
Dia menundukkan kepalanya, lalu mendongakkannya kembali.
“Yang bisa kukatakan sebagai pembelaanku adalah aku sungguh, sungguh ingin melihatmu memerankan Juliet, Ushio-chan. Membayangkanmu berdandan, berdiri di bawah sorotan lampu di atas panggung… Ya, entahlah. Ada sesuatu yang agak ajaib dalam diriku, kurasa. Jadi aku…” Suaranya melemah, kepalanya kembali menunduk termenung ke tanah. Lalu, seolah tiba-tiba menyadari ia tak sanggup lagi, ia berkata, “Baiklah, ya. Kurasa aku akan pulang.”
Hoshihara lalu berjalan melewati Ushio untuk mengambil sepedanya dari rak. Aku memanggilnya, tetapi tidak ada jawaban. Rasanya suaraku bahkan tidak sampai ke telinganya—atau mungkin dia mendengarnya tetapi tidak punya tenaga lagi untuk berbalik. Apa pun itu, yang bisa kulakukan hanyalah menyaksikan tanpa daya saat dia melompat ke sepedanya dan pergi menyusuri jalan. Begitu dia berbelok di tikungan dan menghilang dari pandangan kami, Ushio juga mulai berjalan pergi lagi.
“…Tunggu sebentar,” kataku.
Ia berhenti, tapi tak menoleh. Cahaya yang bocor dari jendela restoran membentuk bayangan hitam panjang di tanah, tak jauh dari tempatnya berdiri.
“Mengapa kamu berbohong padanya seperti itu?” tanyaku.
“Aku tidak berbohong.”
“…Jadi, kau benar-benar menyesal mengambil peran Juliet?”
“Aku benar-benar melakukannya.”
Ushio berbalik, dan wajahnya tampak sama seperti saat di luar gimnasium tadi: ekspresinya kaku, dingin, dan kosong seolah dipahat dari batu. Dalam sepersekian detik itu, aku hampir tersentak melihatnya.
“Tapi jangan khawatir,” katanya. “Aku akan tetap tampil di drama itu. Aku tidak akan mempersulitmu atau siapa pun.”
“Bukan itu yang aku khawatirkan!”
Kenapa kau lakukan itu pada Hoshihara?
Aku hampir mengatakannya keras-keras, tapi kutahan kata-kataku. Dia mungkin takkan memberiku jawaban langsung, berapa kali pun aku bertanya. Aku perlu memikirkannya matang-matang—membaca makna tersirat dari ucapannya. Bukankah itu persis seperti yang kujanjikan sebelumnya? Kukatakan padanya aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memahami hal-hal yang terlalu sulit untuk dia katakan, bukan? Nah, sekaranglah saatnya—jadi apa yang kutunggu?
Saya berpikir, dan saya berpikir—sampai akhirnya, saya mendengar bunyi klik kecil di dalam otak saya.
“Apa karena…kamu mencoba menjodohkanku dengan Hoshihara?” tanyaku.
Ushio tidak menanggapi.
“Kau pikir kau hanya menghalangi, atau semacamnya?” tanyaku lebih lanjut. “Itukah sebabnya kau mengatakan semua itu? Itukah sebabnya kau mencoba menjauhkannya? Untuk memaksa kita lebih dekat dengan menjauhkan diri?”
Ushio tetap diam saja, tetapi aku menganggap diamnya sebagai konfirmasi diam-diam. Dan dengan kesadaran ini muncullah perasaan sengsara yang mendalam bercampur amarah yang membara.
“Aku tidak butuh bantuan seperti itu darimu… Aku sama sekali tidak membutuhkannya,” kataku, suaraku bergetar. Aku merasa dikhianati, sejujurnya. Apa dia benar-benar berpikir aku tidak akan menyadarinya? “Dan ini bukan hanya tentang Hoshihara. Aku tahu pasti kau juga sangat terluka memperlakukannya seperti ini. Jadi kenapa? Kenapa kau mencoba menjadikan dirimu martir? Tidak ada yang menginginkan itu… Itu tidak akan membuat siapa pun di sini bahagia.”
Rasanya seperti ada pisau yang menusuk hatiku. Kalaupun dia memang ingin menjodohkanku dengan Hoshihara, pasti ada cara yang lebih baik daripada ini. Aku tahu orang secerdas Ushio pasti bisa menemukan cara dalam waktu singkat. Jadi, kenapa dia memilih jalan ini?
Mungkinkah karena… dia benar-benar telah menumbuhkan kebencian yang aneh terhadap Hoshihara, dan dia rela melakukan apa pun untuk menjauhkan diri, betapapun kejamnya? Atau mungkinkah dia benar-benar menyesal menerima peran Juliet, dan dia hanya bersikap sangat jujur? Tapi jika memang begitu, mengapa dia mengatakan betapa senangnya dia karena semua orang tampaknya menyukai penampilannya ketika aku menemukannya berlinang air mata di lorong kemarin? Apakah itu hanya kebohongan spontan untuk menutupi alasan sebenarnya dia menangis?
Ada begitu banyak hal yang ingin kukatakan saat ini—begitu banyak hal yang ingin kukatakan—namun entah bagaimana, tak satu pun terasa tepat. Pada akhirnya, yang bisa kulakukan hanyalah berdiri di sana dan menatap matanya. Akhirnya, Ushio mendesah, lalu memasang wajah yang bagiku tampak seolah ia baru saja menyerah pada dunia.
“Kau tidak akan mengerti, Sakuma.”
Lalu dia pergi ke tempat parkir sepeda, meninggalkanku berdiri mematung di jalan. Aku merasa tak ada kata-kata yang bisa kuucapkan saat ini yang tidak akan membuatnya semakin terluka.
“Ya… Dan bagaimana mungkin aku bisa?” gerutuku dalam hati.
Bahkan kata-kata ini pun tak berarti lagi saat larut, tak terdengar dan tak diindahkan, ke dalam kegelapan malam yang merayap masuk.
***
Aku terbangun karena suara jendela kamarku yang berderak karena angin.
Setelah mengusap mataku, aku berbalik untuk melihat jam di meja samping tempat tidurku dan melihat bahwa baru pukul tujuh pagi. Mengingat hari Minggu dan tidak ada sekolah, kupikir aku bisa tidur sebentar lagi. Aku memejamkan mata—hanya untuk terbangun tiba-tiba oleh kilas balik ke malam sebelumnya. Rasa dingin menjalar di punggungku, dan suasana pagi yang menyenangkan yang kunikmati membeku sebelum akhirnya dihancurkan oleh kapak es metaforis.
Aku memikirkan rasa sakit di senyum Hoshihara. Dinginnya raut wajah Ushio. Dan aku memikirkan beberapa kata terakhir yang diucapkannya: “Kau takkan mengerti, Sakuma.” Semua gambaran dan momen dari hari itu terus berputar-putar di kepalaku tanpa arah dan alasan, dan aku bisa merasakan diriku semakin terjerumus ke dalam spiral pesimistis. Aku membuka mata dan menghela napas panjang, berusaha memeras setiap oksigen yang tersisa dari paru-paruku.
“…Kurasa aku akan bangun saja.”
Aku duduk di tempat tidur dan memutar tubuhku untuk menurunkan kakiku ke lantai. Aku merasa kurang istirahat pagi ini; aku juga kesulitan tidur tadi malam. Aku terus-menerus memikirkan penyesalan demi penyesalan di kepalaku, berharap aku mengatakan atau melakukan sesuatu yang berbeda, tetapi akhirnya aku tak mampu lagi berpikir jernih sebelum akhirnya pingsan.
Aku keluar kamar dan menuruni tangga, lalu berhenti di kamar mandi untuk mencuci muka sebelum masuk ke dapur dan membuat sarapan. Aku mengolesi roti panggang dengan mentega, menuangkan segelas susu untuk diriku sendiri, lalu berjalan ke ruang tamu—di mana aku mendapati Ayaka sedang berbaring di sofa dengan piyamanya, iseng menonton ramalan cuaca sambil menyendok yogurt tawar yang diberi madu dalam jumlah yang tak terkira ke dalam mulutnya. Aku duduk di sampingnya dan mulai makan.
Agak sulit mendengar suara penyiar berita karena angin di luar. Hari itu mendung dan mendung dengan sedikit gerimis. Wanita di TV sempat mengatakan sesuatu tentang tekanan atmosfer rendah, tetapi ia meyakinkan kami bahwa cuaca akan membaik besok.
“Ushio-san nggak bakal ke rumah lagi?” tanya Ayaka, matanya masih tertuju ke TV. Nah, ini agak aneh—jarang dia buka mulut untuk bicara kecuali untuk merendahkanku. Tapi kali ini, bukan karena pertanyaannya yang tiba-tiba itu yang membuatku ragu, melainkan karena aku tidak punya jawaban yang tepat.
“Uhhh… Kenapa kamu bertanya?”
“Enggak ada alasan pasti, kurasa. Cuma sadar dia udah lama nggak ke sini.”
Lebih tepatnya, Ushio belum pernah ke rumah sejak liburan musim panas berakhir. Kurasa kekhawatiran utamanya tentang rasa tidak nyaman di rumah sudah berkurang sekarang karena dia bisa keluar rumah untuk sekolah di siang hari hampir sepanjang minggu, jadi tak ada alasan lagi baginya untuk menjadikan rumahku sebagai pelarian.
“Jadi dia tidak akan datang lagi?” desak Ayaka, berbalik menghadapku dengan mata menyipit dan termenung. Ini membuatku merasa sangat buruk. Ada satu waktu, selama liburan, ketika Ayaka nongkrong bersamaku dan Ushio, dan kami bertiga bermain game bersama. Jarang sekali melihat adikku segugup itu, tetapi dia perlahan-lahan mulai rileks dan tampak benar-benar terhubung dengan Ushio. Itu pertama kalinya setelah sekian lama aku melihat Ayaka tersenyum, dan Ushio juga tampak sangat senang. Aku tahu Ayaka ingin nongkrong bersamanya lagi, begitu pula aku. Tapi…
“Sulit untuk dikatakan… Dia mungkin akan datang jika kamu mengundangnya.”
“Kalian berdua bertengkar atau apa?”
“Mmm… Aku tidak tahu apakah aku akan menyebutnya seperti itu …”
Menurutku, itu bukan “pertengkaran” yang sebenarnya—lebih seperti perbedaan pendapat. Kami masing-masing punya ide sendiri tentang apa yang terbaik untuk semua orang, dan kami memang tidak bisa sependapat. Kalau dipikir-pikir, kami pernah mengalami beberapa momen kecil perselisihan dan ketegangan di masa lalu—seperti saat kami pergi ke akuarium, atau saat Hoshihara pertama kali mencalonkan Ushio untuk memerankan Juliet… Mungkin perselisihan kecil ini hanya menumpuk hingga akhirnya tak bisa dipertahankan, dan insiden dua malam lalu justru menjadi momen ketika kami akhirnya menyadari bahwa kami sudah mencapai titik puncak. Tentu saja sudah ada tanda-tanda peringatan bahwa ini pasti akan terjadi cepat atau lambat.
“Kalau kalian berdua sampai tawuran, mendingan kalian minta maaf,” kata Ayaka, sambil kembali menatap layar TV. “Karena aku sudah bisa menjamin kalian yang salah.”
“…Ya, mungkin saja.”
Saya ingin lebih cerdas dalam menangani perselisihan seperti ini. Bukan berarti orang yang lebih cerdas bisa menyelesaikan segalanya, terutama jika menyangkut perasaan orang lain—tetapi saya merasa bisa mencegah situasi menjadi begitu tak terkendali jika saja saya memproses situasi sedikit lebih cepat. Merasa kehilangan dan tak berdaya, saya menggigit ujung roti panggang saya yang gosong, dan rasa pahit yang seperti abu menyebar di lidah saya.
“Hei, jangan begitu. Aku cuma bercanda,” kata Ayaka, terdengar agak terkejut. “Jadi kalian berdua memang bertengkar, ya?”
“Seperti yang kukatakan, itu bukan pertengkaran sungguhan. Lebih seperti sedikit perselisihan.”
“…Oke,” jawabnya lega. Ia menyendok yogurt lagi ke mulutnya tanpa bertanya lebih jauh. “Yah, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kurasa kau harus mencoba membicarakannya.”
“Ya, mungkin…”
Aku tahu ini, tentu saja. Tapi itulah bagian tersulitnya—dan tidak ada jaminan kami bisa mencapai kesepahaman meskipun kami berdua mengungkapkan isi hati. Sangat mungkin mencoba mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata hanya akan berujung pada ketegangan dan perselisihan lebih lanjut . Terutama dalam kasus kami, ketika masih banyak hal yang sengaja kami hindari, seperti perasaanku terhadap Hoshihara. Atau perasaan Hoshihara yang rumit terhadap Ushio. Atau dalam kasus Ushio…
“Wah, ini berat sekali,” kataku sambil menyesap susuku.
Aku ingat bagaimana, sehari sebelum liburan musim panas, aku mengatakan pada Ushio bahwa dia adalah sahabatku, dan aku akan tetap tertanam kuat dalam hidupnya apa pun yang terjadi—tapi sekarang, aku bahkan tidak yakin apakah aku bisa mengatakannya dengan percaya diri lagi.
Ayaka meletakkan sendoknya ke dalam mangkuk kosongnya dengan suara dentingan keras , lalu berdiri.
“Sebaiknya kau bawa Ushio-san ke rumah lagi lain kali.” Sambil memalingkan muka, ia menambahkan, dengan nada kurang percaya diri, “Maksudku, kalau kau mau, tentu saja.”
Aku membeku sesaat, tak bisa berkata-kata. Lalu aku tersadar dan mengangguk. “Ya, jangan khawatir. Setidaknya aku akan mengundangmu.”
“Bagus.”
Ayaka membereskan piring-piringnya dan menuju ke dapur. Aku menunggunya pergi, lalu menjatuhkan diri dengan keras ke sofa. Aku tahu dia tidak mungkin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan teman-temanku, tapi aku tetap merasa kata-katanya tanpa sengaja memberiku sedikit keyakinan lebih untuk memperbaiki kekacauan ini. Mungkin aku hanya memilih untuk menafsirkannya sebagai apa yang perlu kudengar saat ini, tapi bagaimanapun juga, aku tahu aku belum siap untuk menyerah pada Ushio.
***
Dan kemudian hari Senin tiba lagi. Aku melintasi sawah dengan sepedaku, menikmati angin dingin yang menerpa wajahku dan warna keemasan tanaman sambil menempuh rute biasa ke sekolah. Musim gugur akhirnya tiba, seolah-olah cuaca badai kemarin telah menyapu bersih sisa-sisa musim panas yang tersisa.
Saat melewati gerbang utama, saya melihat siluet-siluet tersembunyi dari pameran kelas-kelas lain berserakan di sekitar kampus—beberapa di antaranya hanya seukuran mobil kecil, sementara yang lain tingginya lebih dari satu lantai. Semuanya tertutup terpal biru pelindung.
Aku memarkir sepedaku di tempat parkir sepeda, lalu menuju pintu masuk utama. Aku berhenti di tengah jalan ketika melihat sekelompok kecil siswa berkumpul di sekitar salah satu dinding gedung sekolah. Terlebih lagi, mereka semua tampak seperti anggota panitia festival—dan setiap orang dari mereka memasang ekspresi muram. Aku punya firasat buruk, jadi aku mengubah arah untuk mampir dan melihat apa yang terjadi.
Dan kemudian saya melihatnya.
Awalnya, saya pikir itu hanya bongkahan sampah besar—gumpalan Styrofoam raksasa yang bentuknya tidak beraturan, yang seluruhnya telah dicat, dengan bagian-bagian runcingnya patah menjadi dua, sehingga memperlihatkan struktur rangka di bawahnya.
Ini bukan sampah; aku mengenalinya. Itu adalah gapura yang seharusnya berada di atas gerbang utama pada hari festival.
“Sialan…” gerutuku dalam hati.
Patung itu telah bengkok dan rusak parah hingga tak berbentuk. Apakah angin membawanya pergi berfoya-foya kemarin? Daun-daun basah menempel di seluruh permukaannya, dan semuanya tertutup lumpur. Akan butuh waktu lama untuk mengembalikannya ke bentuk aslinya. Saya berharap bagian-bagian lainnya baik-baik saja; saya tidak bisa melihat fondasinya di mana pun, tetapi saya berasumsi patung itu disimpan dengan aman di tempat lain, atau telah tertiup angin ke arah yang sama sekali berbeda.
Tiba-tiba, saya teringat ekspresi gembira dan puas di wajah Hoshihara ketika dia memberi tahu kami bahwa pekerjaan itu akhirnya selesai beberapa hari sebelumnya, dan gelombang kesengsaraan melanda saya, diikuti oleh rasa kesal yang perlahan muncul di dada saya.
Ugh… Kenapa ini harus terjadi sekarang , sialan…?
“Oh, Bung… Apa-apaan itu?” terdengar suara bodoh dari belakangku. Itu Noi dari tim lari—mungkin sedang dalam perjalanan pulang dari latihan pagi, dilihat dari rambutnya yang kusut karena keringat. Dia melirik tumpukan styrofoam dan meringis. “Ini lengkungannya? Apa tidak ada yang sempat mengamankan benda sialan itu?”
” Sudah diamankan,” kata salah satu anak laki-laki di dekatnya. “Kami pasang terpal di atasnya, beri pemberat, dan sebagainya… Tapi anginnya memang sekencang itu.”
Alasan ini rupanya membuat Noi kesal, yang langsung marah besar. “Oke, kalau begitu kenapa kita meninggalkannya di luar sejak awal?!” teriaknya, melotot ke arah anak laki-laki yang lain. “Demi Tuhan, ini terbuat dari styrofoam. Orang bodoh mana pun pasti tahu kalau tersapu angin.”
“Yah, maksudku… kami hanya mengikuti perintah ketua komite,” kata anak laki-laki yang satunya. “Dia menyuruh kami menyeretnya ke sini…”
Aku mendengar suara “fwump” keras dari belakangku—jadi aku menoleh untuk melihat bersama semua siswa di sekitar. Dan di sana, Hoshihara berdiri terpaku dengan linglung, tasnya tergeletak di tanah di dekat kakinya, mungkin terlepas dari bahunya.
“Hei, Nona Ketua Kecil,” kata Noi. “Benarkah? Kenapa kau menyuruh mereka menaruhnya di luar, hah?”
Hoshihara membungkuk dan dengan canggung mengambil tasnya dari lantai, matanya bergetar seolah-olah ia benar-benar kehilangan arah. “Ruang di dalam… tidak cukup,” katanya, “jadi saya membiarkan salah satu kelas mahasiswa baru menggunakan ruang kami untuk pameran mereka…”
“Oh, yah, bukankah itu sempurna,” kata Noi sambil mendecakkan lidah. “Kau memprioritaskan orang lain dan malah merugikan timmu sendiri.”
Hoshihara mundur seperti anak kecil yang ditegur. Aku hampir yakin ada banyak anggota komite di sekitar yang mengerti situasi ini dan dengan senang hati akan membelanya—tapi tak seorang pun melakukannya. Malahan, sepertinya mereka semua mulai memihak Noi, memandangnya seolah-olah dia semacam pengkhianat. Aku tak tahan berdiam diri dan melihatnya diperlakukan seperti ini, jadi aku memberanikan diri dan melangkah maju untuk membelanya.
“Hei, ayolah,” kataku. “Bersikaplah masuk akal. Tidak ada yang bisa memprediksi cuaca akan seburuk ini, kan? Dan maksudku, benda itu sudah rusak sekarang, jadi menyalahkan orang lain tidak akan membantu kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah melanjutkan dan memperbaikinya sekarang.”
“Oh ya?” kata Noi, melotot ke arahku sambil berjalan mendekat untuk menatapku. “Gampang banget buat orang penyendiri kayak kamu ngomong gitu. Kayaknya solusi yang cepet banget buat orang yang nggak pernah ada kegiatan sepulang sekolah. Beberapa dari kita sampai bolos kerja atau latihan buat bikin benda bodoh ini. Jadi, jangan ikut campur dan bilang ke kami kalau nggak masalah kalau harus balik lagi dan memperbaiki sesuatu yang sudah kita kerjakan.”
Aku tidak punya alasan kuat untuk ini. Semua yang dia katakan tidak salah—dan sepertinya anggota komite lainnya cenderung setuju.
“Ya, tepat sekali!”
“Wah, urusanku sudah cukup banyak…”
“Saya tidak mampu lagi melewatkan pertemuan klub!”
Sementara murid-murid lain berkicau mengeluh, aku menyadari bahwa usahaku membela Hoshihara mungkin malah jadi bumerang. Aku menggertakkan gigi dan mencoba memikirkan cara lain yang bisa kugunakan untuk menyelamatkan kami berdua dari kekacauan ini.
“…Kalian tidak perlu memperbaikinya,” kata Hoshihara, yang sekarang menundukkan kepalanya karena malu—atau begitulah yang kupikirkan, tapi kemudian ia langsung bersemangat dan tersenyum. “Jangan khawatir! Fokus saja pada pekerjaan lain yang sudah kalian lakukan. Soal lengkungan yang rusak itu, yah…aku akan mencari solusinya sendiri.”
“Seperti apa?” tanyaku, pura-pura tidak tahu. Tapi Hoshihara tidak menjawabku.
“Untuk saat ini, kita coba pindahkan saja ke tempat lain,” katanya sambil berjalan ke tumpukan yang bentuknya aneh itu. “Aku tidak mau ambil risiko tertiup angin lagi.”
Dia kemudian mencoba mengangkat semuanya sendiri. Seandainya hanya masalah berat, mungkin ini bisa dilakukan, tetapi mengingat ukurannya yang besar dan bentuknya yang aneh, pasti terlalu berat untuk diangkat sendirian. Saya bergegas membantunya. Kami mengangkat sisa-sisa lengkungan yang hancur dan mengangkutnya ke area yang jarang dilalui di belakang pusat kebugaran. Karena kami sekarang tahu bahwa terpal dan sedikit beban saja tidak akan mencegahnya tertiup angin, kami mengambil tali tambang dan mengikatnya langsung ke dinding.
“Terima kasih,” kata Hoshihara datar. “Maaf merepotkan.”
Sekilas, dia tampak tidak menunjukkan ekspresi apa pun—tapi aku tahu mungkin ada pusaran emosi yang bergejolak di kepalanya saat ini. Bagiku, sepertinya dia sedang berusaha menangkal rasa sakit akibat kegagalan dan ketidakmampuan dengan mematikan rasa terhadap perasaan apa pun.
“…Jangan terlalu dibesar-besarkan,” kataku. “Masih ada waktu tersisa sebelum festival, dan aku dengan senang hati akan membantumu membereskannya.”
“Oke.”
“Juga…” Aku terdiam, agak ragu apakah aku harus mengatakan ini di bagian selanjutnya. Tapi aku tahu ini mungkin kesempatan terbaik dan satu-satunya yang kudapat, jadi aku melanjutkan, “Soal ucapan Ushio di restoran kemarin… Kurasa kau juga tidak perlu terlalu memikirkannya. Bukannya dia tidak menyukaimu lagi atau semacamnya. Hanya saja… Yah, kurasa mungkin dia merasa sedikit—”
Bel tanda pulang sekolah berbunyi sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku. Biasanya, aku tak akan membiarkan hal ini mengganggu pikiranku, tetapi kami berdiri begitu dekat dengan salah satu pengeras suara luar gedung sehingga suaranya memekakkan telinga, dan aku bahkan tak bisa mendengar suaraku sendiri lagi. Sepertinya aku salah memilih waktu dan tempat untuk memulai pembicaraan ini. Ketika lonceng kecil itu akhirnya berakhir, Hoshihara memaksakan sudut bibirnya membentuk senyum tipis.
“Lebih baik kita berangkat,” katanya. “Kita akan terlambat.”
Saat dia berjalan menuju gedung utama, aku tahu aku telah membuang satu-satunya kesempatanku untuk membicarakan hal ini secara wajar—tetapi yang bisa kulakukan hanyalah mengikutinya dengan enggan.
“Kau pasti sedang memikirkan sesuatu, ya?” tanya Hasumi di sela-sela gigitan.
Saat itu jam makan siang dan kami makan bersama seperti biasa.
“Ma-maksudmu?” tanyaku pura-pura bodoh—tapi aku tahu persis apa maksudnya. Seharian aku melirik Hoshihara dan Ushio, bahkan saat kuliah, dan dia baru saja memergokiku melakukannya lagi. Aku agak terkejut melihat mereka berdua masih makan siang bersama di meja Ushio seperti biasa hari ini, tapi mereka berdua hanya makan dalam diam tanpa memulai percakapan apa pun. Sungguh menyesakkan untuk terus mengawasi, bahkan dari jauh.
“Ada sesuatu?” tanya Hasumi.
“Ya… Agak. Ceritanya panjang,” kataku.
“Apa ini tentang lengkungan itu? Bagaimana lengkungan itu bisa rusak atau apalah?”
“Tunggu. Bagaimana kamu tahu tentang itu?”
“Mendengarnya dari seorang teman.”
Kabar itu memang cepat sekali menyebar. Aku berasumsi temannya ini juga anggota komite, atau kabar tentang runtuhnya lengkungan itu sudah beredar di kalangan mahasiswa. Aku agak berharap bukan yang terakhir.
“Pondasinya dan semuanya baik-baik saja,” jelasku, “tapi seluruh bagian atasnya rusak parah. Kurasa kita mungkin bisa memperbaikinya tepat waktu, kalau kita cepat, tapi…”
Masalah utamanya—setidaknya menurutku—adalah Hoshihara. Dia pasti merasa sangat bersalah saat ini, sebagai orang yang memerintahkan yang lain untuk memindahkan gapura itu ke luar. Dan mengingat dia pasti masih terguncang oleh apa yang terjadi dengan Ushio, dia sudah tidak dalam kondisi pikiran terbaik untuk menghadapi kecelakaan besar seperti ini.
Selama kelas hari ini, aku sudah memikirkan apa yang bisa kulakukan untuk membantu; kupikir hal pertama yang harus kulakukan adalah mencurahkan waktu dan tenaga sebanyak mungkin untuk memperbaiki lengkungan itu, lalu mencoba menyelesaikan masalah antara dia dan Ushio. Aku tahu itu permintaan yang besar, tapi aku tidak bisa hanya berpangku tangan sementara seorang teman sedang membutuhkan bantuan. Aku ingin menyelesaikan kekacauan ini sebelum festival budaya berakhir, apa pun yang terjadi.
“Kedengarannya benar-benar menyebalkan,” kata Hasumi, sama sekali tidak peduli.
“Memang bakal menyebalkan, ya,” jawabku. “Tapi terlalu penting untuk tidak melakukannya.”
Sekolah telah usai untuk hari itu, dan teman-teman sekelasku perlahan-lahan berkemas untuk pulang atau memindahkan meja-meja untuk memberi ruang di tengah ruangan. Menjelang festival, semakin banyak siswa yang begadang untuk mengikuti gladi resik dan persiapan di belakang panggung. Meski begitu, Hoshihara adalah yang pertama mengemasi barang-barangnya dan bergegas keluar. Aku berasumsi dia sedang terburu-buru menyelesaikan pekerjaannya sebagai ketua komite hari itu agar bisa menghabiskan sebagian besar sore untuk merestorasi gapura. Aku menyampirkan tasku di bahu, menghela napas pelan, dan berjalan menuju meja Ushio.
“Jadi begitu,” kataku.
“Ada apa?” tanyanya sambil berbalik di kursinya. Dia tidak tampak terkejut atau terganggu dengan pendekatanku, hanya acuh tak acuh terhadap kehadiranku. Aku kesulitan sekali membaca ekspresinya sejak kejadian di restoran itu.
“Cuma mau bilang, mungkin aku nggak bisa ikut latihan hari ini, maaf. Kayaknya aku bakal kebanjiran pekerjaan lagi nih, soalnya tinggal kurang dari seminggu lagi.”
“Jangan khawatir. Kalau begitu, prioritaskan itu. Kamu sudah cukup menguasai bagian itu sekarang, jadi kurasa melewatkan sedikit latihan tambahan tidak akan merugikan.”
Ini tanggapan yang sangat sopan; aku sudah siap ditegurnya dengan ketus sampai-sampai aku agak kecewa. Mungkin aku memang terlalu banyak berpikir.
“…Terima kasih, ya. Aku menghargainya,” kataku, lalu keluar dari kelas.
Meskipun ketegangan canggung itu hanya ada di kepalaku, aku tak bisa berpura-pura malam di restoran itu tak pernah terjadi. Aku masih ingin mengatasi perasaan-perasaan buruk ini dan membicarakannya nanti. Tapi untuk saat ini, aku harus fokus membangun kembali gapura itu. Kalau kami tidak bisa memperbaikinya tepat waktu untuk festival, itu akan sangat buruk bagi Hoshihara. Jadi, aku mengalihkan pikiranku dan menuju ke tempat terbuka di belakang gedung olahraga.
“Tunggu… Apa-apaan ini…?”
Lengkungan itu tidak lagi berada di tempat kami meninggalkannya pagi ini. Tiba-tiba, aku merasakan darah mengalir dari wajahku saat aku memikirkan kemungkinan bahwa lengkungan itu telah dikira sebagai bongkahan sampah raksasa dan dibuang ke insinerator atau semacamnya.
Ya Tuhan, aku harap tidak… Lalu apa yang akan kita lakukan ?
Saat saya berlari panik mengelilingi gedung mencari jejaknya, saya mendengar suara styrofoam bergesekan dengan linoleum melalui salah satu jendela kecil gedung. Saya mengintip ke dalam dan melihat tumpukan sisa-sisa yang kami ikat di luar sedang diseret melintasi lantai gimnasium oleh sekelompok kecil anggota komite yang telah berinisiatif untuk mulai merestorasi lengkungan tersebut.
Pemandangan ini sungguh memanjakan mata. Lega rasanya, bukan hanya karena tahu benda itu belum dibuang, tetapi juga karena melihat orang lain sudah membantu. Apakah Hoshihara yang menyuruh mereka melakukannya? Saya bertanya-tanya. Saya sempat berpikir restorasinya mungkin hanya akan menjadi tanggung jawab saya dan dia saja, jadi ini sungguh melegakan.
Aku berjalan memutar untuk masuk ke ruang olahraga dan membantu. Saat kami segera bekerja, aku mendengar dari anggota komite lainnya bahwa bukan Hoshihara yang meminta mereka memulai restorasi, melainkan ketua OSIS.
“Ya, kurasa dia merasa cukup bertanggung jawab atas semua ini,” kata salah satu dari mereka. “Membuatnya mengurus semua hal yang belum pernah dia tangani sendiri sebelumnya.”
“Aduh… Benar-benar cowok yang baik hati,” kata kakak kelas yang duduk di sebelahku sambil mereka mengukir beberapa potongan styrofoam baru. “Iya, kamu jelas tahu kalau Hoshihara-chan akhir-akhir ini benar-benar kelelahan.”
Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang kukira, tapi semua orang sepertinya sudah sependapat sekarang. Aku senang mengetahui bahwa aku salah mengira masalah besar ini akan menjadi masalah yang lebih besar daripada yang sebenarnya. Tentu saja, mungkin masih ada beberapa anggota komite yang merasa agak kesal dengan seluruh masalah ini, tapi aku cukup yakin mereka tidak akan marah sekarang karena ketua OSIS sudah terlibat. Yang tersisa sekarang hanyalah membangkitkan semangat Hoshihara kembali, dan kita akan—
“Hei, adakah di antara kalian yang melihat Hoshihara-san?” tanya seorang siswi sambil berlari kecil ke arah kami dari seberang gedung olahraga.
Dia bendahara OSIS, kalau tidak salah ingat. Tapi semua panitia festival di sekitar hanya saling pandang dan menggelengkan kepala. Kurasa gadis itu butuh persetujuan Hoshihara untuk sesuatu.
“Yah, sudahlah…” kata gadis itu. “Dia belum ke ruang OSIS seharian, dan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan…”
“Mungkin sedang bermalas-malasan di suatu tempat,” salah satu anak laki-laki senior mengejek.
“Ini,” kataku, menahan diri untuk tidak terpancing oleh gurauan spontan ini sambil mengeluarkan ponsel dari saku. “Aku punya nomornya. Aku bisa coba menghubunginya.”
Aku mencari namanya di buku teleponku dan menekan tombol panggil, tetapi tidak ada hasil.
“Maaf, tapi nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif.”
Aku menggelengkan kepala, dan bendahara mengerutkan kening.
“Mmm… aku penasaran apa dia benar-benar pulang , ya. Dia tidak pernah terlihat seperti tipe orang yang suka bolos tugas, tapi ya sudahlah… Kurasa aku harus memikirkan cara lain saja. Maaf mengganggu kalian.”
Dan dengan itu, bendahara pun pergi. Dari sikapnya, sepertinya situasinya tidak terlalu mendesak, tetapi saya tetap merasa khawatir. Karena seperti katanya, Hoshihara bukan tipe orang yang suka bermalas-malasan. Saya jadi bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi.
“Maaf, saya perlu keluar sebentar,” kataku, lalu meninggalkan gimnasium.
Pertama-tama, saya menuju pintu masuk utama sekolah dan memastikan bahwa sepatu Hoshihara masih ada di rak sepatunya. Setidaknya ini memberi tahu saya bahwa dia pasti ada di suatu tempat di kampus. Dari sana, saya mengambil pendekatan eliminasi, menelusuri setiap lorong di gedung utama dan gedung serbaguna. Namun, Hoshihara tidak ditemukan di mana pun. Saya mencoba memikirkan tempat lain yang mungkin dia kunjungi yang belum saya periksa, selain ruang klub dan kamar mandi… dan hanya satu tempat yang terlintas di pikiran.
Aku dihantam gelombang déjà vu saat menaiki tangga menuju pintu yang mengarah ke atap—dan benar saja, aku menemukannya duduk di tangga, hanya beberapa langkah di bawah bordes. Bingo. Itu tempat yang sama ketika aku menemukan Ushio setelah dia kabur di akhir semester lalu. Mungkin itu pilihan yang tepat bagi orang-orang yang butuh tempat pelarian, mengingat tempat itu merupakan salah satu area paling sunyi dan terpencil di gedung ini… Begitulah pikiranku saat aku mendekat, dan Hoshihara mengangkat kepalanya, menyadari kehadiranku.
“K-Kamiki-kun?” tanyanya. “Apa yang kamu lakukan di sini…?”
Dia tampak terkejut. Tapi lebih dari itu, dia tampak sengsara.
“Mencarimu,” kataku. “Ada cewek dari OSIS yang datang dan butuh bantuanmu. Katanya dia tidak melihatmu seharian.”
“Aduh, astaga,” katanya. “Memangnya ini benar-benar mendesak?”
“Tidak yakin… Sepertinya tidak bagiku.”
“Oh… Baiklah, lupakan saja.”
Dia agak pesimis. Ini bukan Hoshihara yang kukenal.
“Kamu…tidak akan pergi check in, setidaknya?” tanyaku.
“Tidak perlu. Aku yakin mereka akan baik-baik saja tanpaku.”
“Oh, ayolah. Kau tahu itu tidak benar…”
” Memang ,” katanya, sambil mencondongkan tubuh ke depan dan memeluk kakinya erat-erat. “Maksudku, aku masuk untuk memberikan laporan tentang lengkungan itu kepada ketua OSIS saat jam makan siang, dan kau tahu apa katanya? Menyerahkan sisanya padanya saja. Lalu dia hanya bertepuk tangan, dan boom—langsung menemukan cukup banyak orang yang senggang sore ini untuk membantu memperbaikinya, lalu duduk dan mulai mengerjakan tumpukan dokumen yang kutumpuk seakan-akan itu adalah hal paling sederhana di dunia. Saat melihatnya, aku langsung berpikir, ‘Astaga. Sepertinya mereka memang tidak membutuhkanku di sini…'”
Dia meluangkan waktu sejenak untuk membiarkan sindiran kecil ini meresap pada dirinya sendiri sebelum melanjutkan.
“Malah, rasanya aku hanya menghalangi orang lain dengan mencoba membantu. Seperti ketika aku menyuruh mereka memindahkan gapura ke luar, misalnya. Atau bagaimana aku terus mengacaukan semua perhitungan anggaran kami. Belum lagi…” Ia menundukkan kepala, dan poninya tergerai seperti tirai untuk menyembunyikan wajahnya. “Aku dan mulutku yang besar dan bodoh itulah yang membuat Ushio-chan menyetujui sesuatu yang akhirnya sangat ia sesali…”
“Tapi itu sama sekali tidak benar,” bantahku. “Aku janji, Ushio sebenarnya tidak kesulitan memerankan Juliet. Ya, awalnya dia agak ragu bagaimana reaksi orang-orang saat dia memerankan karakter itu—tapi begitu dia benar-benar punya kesempatan untuk mendalami karakternya, semua orang menyukainya . Mereka tak henti-hentinya memuji kehebatannya, mengatakan bahwa dia bisa menjadi aktris sejati jika dia mau… Dan aku tahu pasti Ushio sangat tersentuh oleh semua itu. Aku yakin 99,9 persen dia senang menerima peran itu sekarang, dan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman aneh yang aku tahu kita bertiga bisa selesaikan jika kita duduk dan membicarakannya.”
Memang, ini lebih merupakan omelan emosional daripada argumen logis dari saya, tetapi hanya itu yang bisa saya berikan untuknya saat ini. Harapan saya adalah dengan menunjukkan kepada Hoshihara betapa sungguh-sungguhnya saya meyakini hal ini, dia mungkin bersedia mempertimbangkan kembali spiral kebencian diri yang telah ia mulai. Namun, tampaknya dia menolak untuk dibujuk, sambil menggelengkan kepalanya.
“Kamu salah,” katanya.
“Tentang apa?”
“Bukan cuma masalah Juliet… Aku juga melakukan kesalahan yang sama di akuarium.”
Butuh sedikit waktu bagiku untuk memahami “kesalahan” apa yang dia maksud—tapi kukira maksudnya adalah kesalahpahamannya yang memaksa Ushio menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada hari dia menciumku di puncak tangga ini. Aku masih ingat betapa pucat dan tercekiknya dia saat berusaha keras untuk mengeluarkan kata-kata di pujasera akuarium—dan betapa menyesalnya Hoshihara di perjalanan pulang dengan kereta karena telah menyinggung ciuman itu lagi.
“Kupikir aku sudah sangat proaktif mendukung kalian… Tapi pada akhirnya, aku malah terus-terusan mengambil kesimpulan yang merugikan Ushio-chan. Rasanya setiap kali aku mencoba melakukan sesuatu , hasilnya malah bumerang dan memperburuk keadaan. Terkadang aku merasa harus berhenti mencoba dan menyelamatkan semua orang dari masalah…”
Ia meringkuk, meremas kakinya lebih erat lagi, seolah mencoba menghancurkan sesuatu di dalam dirinya yang tak bisa kulihat. Melihatnya seperti ini sungguh menyayat hati.
“…Aku tahu maksudmu, Hoshihara.”
Dan itu benar—saya tahu persis apa yang dimaksudnya.
Terkadang aku merasakan hal yang sama, dan bukan hanya dengan Ushio. Perasaan mengerikan itu, ketika dihadapkan dengan kebodohan dan kecerobohan diri sendiri setiap kali kau mencoba melakukan sesuatu, dan gagal total. Malam demi malam, kau akan terjaga di tempat tidur, merenungkan segala hal yang seharusnya bisa kau lakukan secara berbeda dan betapa parahnya kau telah mengacaukan segalanya. Akhirnya, kau hanya ingin meringkuk di balik cangkangmu dan tidak pernah melakukan atau mengatakan apa pun kepada orang lain lagi. Kau tidak mungkin menyakiti orang lain jika kau tidak pernah berinteraksi dengan mereka sejak awal. Dan jika kau bisa meyakinkan diri untuk melihatnya seperti itu, tidak bertindak pun terasa tidak terlalu buruk.
Di saat yang sama… tak ada gunanya berdiam diri. Tak perlu dikatakan lagi, tak seorang pun pernah berkembang atau mencapai tujuan sebagai pribadi tanpa melakukan apa pun. Dan bahkan jika kau baik-baik saja dengan hanya berdiam diri saat itu, ada kemungkinan besar kau akan menyesal karena tidak bertindak sama besarnya dengan hal lainnya. Tentu, mungkin ada orang di luar sana yang benar-benar melihat nilai dalam menjauhi urusan orang lain—tetapi bagi gadis manis dan baik hati seperti Hoshihara, yang senang berteman dengan semua orang, mengasingkan diri hanya akan semakin menyakitinya dalam jangka panjang.
…Atau mungkinkah demikian?
Bisakah aku benar-benar mengatakan dengan pasti bahwa berhenti mencoba dalam kasus ini adalah hal yang buruk baginya? Mungkin menjauhi Ushio dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman lamanya seperti Mashima dan Shiina akan membuatnya lebih bahagia. Jika aku benar-benar peduli padanya dan apa yang terbaik untuknya, bukankah seharusnya aku lebih menerima pilihannya untuk berhenti menggali lubang yang lebih dalam? Maksudku, siapa aku yang berani menasihatinya? Dia jauh lebih berpengalaman dalam hubungan interpersonal daripada aku, seorang pria yang bisa menghitung semua temannya dengan satu tangan. Apa salahku?
Aduh, apa yang kulakukan? Ini sungguh sia-sia.
Semakin saya memikirkannya, semakin saya tidak benar-benar mengerti. Tidak ada jawaban yang “benar” di sini—sejauh itu, saya tahu pasti. Namun, saya masih belum siap menyerah, entah karena alasan apa. Saya tidak ingin sekadar melontarkan omong kosong optimisme yang klise dan mencoba mengatakan kepadanya bahwa itulah yang seharusnya dia lakukan hanya karena kedengarannya bagus di poster motivasi. Saya ingin benar-benar memikirkan ini dan mencapai kesimpulan saya sendiri. Tetapi perasaan itu pun terasa salah; bukankah bertahun-tahun pendidikan publik saya hingga saat ini telah menanamkan dalam diri saya nilai untuk memercayai insting dan memilih respons yang paling masuk akal ketika kita tidak tahu jawabannya? Terkadang, tidak apa-apa mengikuti kata hati. Sial, itulah yang saya lakukan selama ini. Jadi kenapa saya kesulitan menghadapi hal ini sekarang? Mengapa saya sepertinya tidak bisa—
“…Kamiki-kun?”
Hoshihara menatapku dengan bingung, pasti bingung kenapa aku tiba-tiba terdiam. Sementara itu, aku bahkan tidak menyadari dia mengangkat kepalanya.
“Oh, ya, eh… Maaf,” kataku, hanya melontarkan kata-kata acak untuk mengisi kekosongan. Dan membayangkan aku datang ke sini dengan harapan bisa membangkitkan semangatnya, padahal sekarang yang bisa kulakukan hanyalah bertahan di tengah banjir keraguan diri yang kelam mengancam menelanku bulat-bulat, megap-megap dengan setiap suku kata tak bermakna yang berhasil kukeluarkan dari paru-paruku. “Kurasa aku hanya merasa seperti… aku tak tahu apa-apa lagi.”
“Hah? Tapi…kamu baru saja bilang kamu tahu maksudku…”
“Tidak… Aku hanya berusaha bersikap seolah aku mengerti. Tapi kenyataannya, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Semua kata-kata ini, pikiran-pikiran yang keluar dari mulutku… Semuanya hanya ide yang kupinjam dari orang lain. Aku tidak punya satu hal pun yang bisa kuberikan padamu yang benar-benar bisa disebut milikku…”
Semakin banyak aku bicara, semakin aku merasakan kesedihan yang mendalam dan menyakitkan tumbuh di dadaku—seolah-olah hatiku terlilit benang, dan seseorang menarik kedua ujungnya. Mengapa ini harus begitu menyakitkan? Apa yang sebenarnya kuderita? Apakah hanya aku? Apakah aku satu-satunya yang cukup malang untuk harus berjuang begitu keras dengan ini? Hanya untuk mencari tahu bagaimana perasaanku tentang hal-hal semacam ini?
Tidak, itu tidak mungkin. Tidak ketika aku masih remaja biasa, dan ada orang-orang seperti Ushio di luar sana dengan masalah pribadi yang jauh lebih kompleks dan gejolak batin yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun… pergumulan yang hanya sedikit orang di dunia ini yang benar-benar bisa mengerti atau memahaminya. Artinya, satu-satunya orang yang bisa ia andalkan adalah dirinya sendiri. Ia mungkin telah menghabiskan ratusan, ribuan jam untuk memeriksa diri dan meragukan dirinya sendiri seperti ini. Masalah identitasku yang bodoh mungkin tampak menyedihkan dan biasa saja jika dibandingkan dengan masalahnya. Entah bagaimana, itu justru membuatku merasa semakin sedih. Seolah-olah aku bahkan tidak bisa menjadi bola stres yang tak berdaya dengan cara yang menarik —dan aku tahu itu adalah hal yang sangat kasar dan tidak masuk akal untuk dikatakan, terlebih lagi.
Sialan. Aku harus segera menyingkirkan pikiran negatif ini. Aku hanya berputar-putar saja saat ini, membiarkan rasa rendah diri menumpuk sementara pikiranku tenggelam semakin dalam ke jurang gelap yang tak terduga. Semua yang kupikirkan selama ini semakin tak nyata dan tak pasti setiap detiknya. Semburan panas membuncah di balik bola mataku, dan yang bisa kulakukan hanyalah menundukkan kepala dan menggertakkan gigi gerahamku dengan penuh penderitaan untuk menahan luapan emosi yang datang.
Saat itu juga, saya bisa melihat kaki Hoshihara menuruni tangga—berhenti tepat satu anak tangga lebih tinggi dari tempat saya berdiri, beberapa inci di bawah.
Aku mencoba menatapnya—hanya untuk merasakan rambutku tergerai saat ia meletakkan tangannya di atas kepalaku. Aku membeku sesaat, terkejut dengan sentuhan tak terduga ini.
“Jadi, kau juga belum sepenuhnya paham, ya?” katanya, suaranya terngiang lembut di telingaku sambil mengelus rambutku. “Dan kupikir aku tidak paham karena aku terlalu bodoh atau semacamnya. Tapi kalau orang pintar sepertimu saja kadang tersesat, kurasa mungkin tak heran aku tak tahu harus berbuat apa.”
“…Kau salah paham,” gerutuku, masih menunduk ke tanah. Aku tak sanggup menepis tangannya. “Kau tidak bodoh, dan aku jelas bukan jenius atau semacamnya. Ini bukan soal kebijaksanaan atau kecerdasan buku—ini lebih mendasar dan vital dari itu. Ini seperti… sesuatu yang mendasar, hampir seperti kesadaran.”
“…Ya, maaf. Kurasa aku tidak mengerti. Tapi kurasa kau juga tidak perlu terlalu stres memikirkan hal-hal ini.”
“Tetapi-”
“Tidak apa-apa,” katanya, suaranya selembut sinar matahari, perlahan mencairkan ketegangan di tubuhku bagai salju. “Kau akan baik-baik saja, Kamiki-kun.”
Saat dia mengulangi ucapannya, aku merasakan garukan jarinya yang menggali sedikit, memijat kulit kepalaku saat dia menyisirkannya ke rambutku.
Semuanya takkan baik-baik saja. Aku tahu itu. Hoshihara hanya mengatakannya untuk membangkitkan semangatku. Tak ada alasan atau logika di baliknya, tak ada secuil pun bukti konkret yang bisa kuandalkan. Ia benar-benar hanya berusaha menghiburku.

Aku bertanya-tanya apakah itu sebabnya—mengapa kebaikannya yang murni dan murni mengalir begitu bebas ke paru-paruku. Rasanya begitu nikmat dan nyaman menghirup beberapa kata ini hingga aku menyerahkan hatiku pada perasaan itu dan, untuk sesaat, bahkan membiarkan diriku memercayainya.
Mungkin saat ini, itu saja yang saya butuhkan.
Mungkin saat ini, itu sudah cukup.
Hoshihara perlahan menarik tangannya, dan tiba-tiba aku merasa, sesaat, sendirian tanpa beban telapak tangannya yang menenangkan. Namun, rasa sakit itu tetap hilang.
“Kamiki-kun…” panggilnya. “Terima kasih sudah bicara soal itu.”
“…Tidak, akulah yang seharusnya mengatakan itu. Rasanya aku baru saja mengatasi beberapa rintangan mental yang berat, berkatmu.”
Hoshihara menyeringai riang, lalu berjalan melewatiku menuruni tangga. “Sebaiknya kita cepat kembali. Aku harus minta maaf kepada semua orang, lalu segera bekerja! Pasti ada yang bisa kubantu!”
Ketika dia turun ke tempat pendaratan, dia berbalik untuk melihat ke arahku.
“Ada apa?” tanyanya. “Kamu tidak ikut?”
“Oh, ya—tidak juga,” kataku, lalu bergegas menuruni tangga.
Aku merasa sangat bersalah karena datang ke sini untuk menyelamatkannya, lalu entah bagaimana membuatnya hanya memikirkan diriku sendiri dan memaksanya untuk menghiburnya. Jika ada lubang raksasa di dekat sini yang bisa kumasuki, mungkin aku akan melakukannya. Tapi saat ini, tubuhku terasa ringan—seolah beban telah terangkat dari pundakku. Mungkin perasaan terbebas ini hanya akan bertahan sebentar, tetapi aku bersyukur kabut di hatiku telah sirna untuk sementara waktu.
Tentu, masih banyak yang belum kupahami. Tapi meskipun aku tak tahu ke mana aku akan pergi, aku bisa melihat jalan di depanku sekarang—jalan yang sangat mirip dengan jalan di depanku.
Setelah menuruni tangga, Hoshihara dan aku pergi ke ruang OSIS. Ia tampak agak gelisah; kukira ia khawatir mereka akan marah atau kecewa padanya karena telah mengabaikan tugasnya sebagai ketua komite, meski hanya sesaat. Aku berharap bisa memberinya kata-kata penyemangat yang menyemangati, tetapi tak ada hal baik yang terlintas di benakku sebelum kami sampai di pintu tujuan.
Hoshihara meletakkan tangannya di dadanya dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali.
“Kamu akan baik-baik saja?” tanyaku, sedikit khawatir.
Dia terkekeh, berpura-pura tersenyum sementara alisnya terangkat. “Tanganku tak henti-hentinya gemetar. Bagaimana kalau mereka sudah menunjuk orang lain sebagai ketua komite yang baru?”
“Nah, aku sangat meragukan itu…” Aku belum pernah mendengar anekdot tentang seorang mahasiswa yang diberhentikan dari posisi kepemimpinan sukarela. Lagipula, memang tidak ada yang ingin menjadi ketua panitia festival sejak awal. “Kurasa mereka tidak akan memintamu mundur hanya karena hal sekecil itu. Lagipula, hanya kau yang mereka punya.”
“Wah, terima kasih. Jangan dipaksa… Tapi kau benar.” Hoshihara mengepalkan tangannya ke dada, seolah ingin menyemangati dirinya sendiri. “Aku yang setuju, jadi aku harus menyelesaikan ini sampai akhir.”
“Ya, itulah semangatnya.”
“Oke… Ayo mulai.”
Aku bisa melihat api tekad Hoshihara menyala di pupil matanya. Ia menarik napas dalam-dalam untuk terakhir kalinya, lalu membuka pintu ruang OSIS.
“Maafkan aku karena bermalas-malasan, semuanya!” teriaknya begitu melangkah masuk, membungkukkan tubuh bagian atasnya hingga hampir sejajar dengan lantai. Semua panitia festival dan anggota OSIS di ruangan itu langsung menghentikan kegiatan mereka dan menoleh ke arah Hoshihara. Mereka semua tampak tercengang. Aku hanya bisa menyaksikan dengan gelisah dari belakang sementara keheningan canggung itu terus berlanjut.
Begitulah adanya, hingga salah satu siswa kelas atas tersenyum dan berkata, “Hei, jangan khawatir.”
Ini diikuti oleh beberapa persetujuan dari mahasiswa lain di ruangan itu, masing-masing menyela untuk meyakinkannya bahwa itu “tidak masalah” atau “tidak masalah” sebelum kembali mengerjakan apa pun yang sedang mereka lakukan. Reaksinya cukup acuh tak acuh secara keseluruhan—dan ketika Hoshihara mengangkat kepalanya, dia tampak agak ragu bagaimana harus bereaksi. Saya bisa mengerti alasannya. Dia mungkin kesulitan membedakan apakah kurangnya teguran ini disebabkan oleh kebaikan anggota komite lain atau karena mereka memang tidak berharap banyak padanya sejak awal. Saya ingin percaya bahwa itu yang pertama—tetapi saya jelas tidak punya cara untuk membuktikannya.
Tepat ketika aku berpikir mungkin aku harus mengatakan sesuatu untuk menenangkannya, salah satu anak laki-laki di belakang kelas bangkit dari mejanya. Ternyata dia ketua OSIS. Saat ia berjalan ke arah kami dengan raut wajah tegas, Hoshihara menegang.
“Hoshihara,” katanya. “Aku punya pesan untukmu dari salah satu siswa baru. Mau dengar sekarang?”
“Pesan?” jawabnya. “U-untukku?”
“Ya, dari Kelas 1-B. Mereka ingin berterima kasih karena kamu sudah menyediakan sebagian ruang di dalam ruangan untuk pameran mereka… Kamu tahu, ruang yang awalnya disediakan untuk gapura itu?”
Mata Hoshihara melebar, dan ekspresi presiden berubah lembut.
“Kalau kamu tidak memberi mereka ruang itu,” katanya, “mungkin kerja keras mereka yang akhirnya hancur. Jadi, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri.”
Setelah itu, ketua OSIS kembali ke mejanya. Hoshihara hanya berdiri di sana sejenak sebelum menghela napas panjang dan berat.
“Oh, syukurlah…” katanya.
Melihatnya perlahan mulai ceria kembali, beban pikiranku terangkat. Senang sekali mendengarnya ; itu berarti pemindahan gapura itu memang bermanfaat. Dan meskipun keadaannya jelas bisa lebih baik, pertimbangan Hoshihara itu tidak luput dari perhatian orang-orang yang diuntungkan.
“Hei, jangan cuma berdiri di sana!” kata salah satu anggota komite lainnya. “Kita punya banyak pekerjaan hari ini! Ayo, kita pergi!”
Saat Hoshihara bergegas ke mejanya, kupikir sebaiknya aku segera pergi dan kembali ke pusat kebugaran. Lagipula, masih ada lengkungan yang perlu diperbaiki.
***
Kemarin saja, kami sudah cukup jauh menyelesaikan pekerjaan restorasi. Dengan kecepatan seperti ini, kami mungkin bisa menyelesaikan semuanya sebelum hari festival, dan dengan banyak waktu luang. Rasanya agak antiklimaks, sejujurnya, tetapi setidaknya semuanya berjalan sesuai jadwal. Hoshihara tampaknya juga telah pulih sepenuhnya dan kembali ceria seperti biasanya, yang berarti semuanya baik-baik saja.
Baiklah. Tidak juga.
Masih ada satu masalah besar yang perlu ditangani.
Sambil aku dan Hasumi menyantap hidangan, aku melirik Hoshihara, yang secara teknis masih duduk dan makan siang bersama Ushio meskipun situasi saat ini. Satu-satunya perbedaan nyata dari hari sebelumnya adalah hari ini, Hoshihara sebenarnya berusaha memulai percakapan yang menyenangkan dengan Ushio—tetapi ia hanya ditanggapi dengan dingin dan beberapa tanggapan singkat. Bahkan dari kejauhan, aku bisa merasakan ketegangan yang canggung di udara. Jelas ada keretakan di antara mereka berdua, dan aku tahu Hoshihara berusaha menjembatani celah tersebut, tetapi tampaknya itu tidak berhasil dengan baik; hati Ushio seolah tertutup rapat. Upaya Hoshihara untuk berinteraksi dengannya perlahan-lahan semakin berkurang, hingga akhirnya ia terdiam total.
Mungkin aku harus mencoba pergi ke sana.
Pasti ada yang bisa kulakukan untuk membantu. Dan kalau aku mau bergerak, sekarang mungkin satu-satunya kesempatanku, karena aku akan terlalu sibuk mengerjakan gapura sepulang sekolah. Yang lebih penting, aku hanya merasa gelisah duduk diam dan menyaksikan semua ini. Aku memutuskan untuk pergi ke sana dan melihat apakah aku bisa membantu Hoshihara.
“Hei, Hasumi,” kataku. “Keberatan kalau aku mundur sebentar?”
“Lakukan saja, Bung.”
Saya sangat bersyukur dia bukan tipe orang yang suka mengorek informasi atau bertanya—meskipun ada kemungkinan juga dia tidak peduli.
Dengan bekal makan siang yang masih setengah dimakan, aku berjalan menuju meja Ushio. Hoshihara menyadari kedatanganku bahkan sebelum aku sempat menyapa. Ia tersenyum lebar, sementara Ushio tampak sangat terganggu dengan kehadiranku. Sambutan yang beragam ini jelas membuatku bimbang, apakah ini benar-benar ide yang bagus.
“Hei, keberatan kalau aku makan siang dengan kalian?” tanyaku.
“…Maksudku, kurasa tidak,” jawab Ushio dengan enggan.
Maka kami bertiga pun duduk di sana, berkerumun di sekitar meja Ushio dengan bekal makan siang masing-masing. Meskipun begitu, tempat duduknya memang tidak terlalu luas. Namun, tidak ada meja kosong lain yang bisa kami minggir untuk memberi ruang lebih, jadi kami mulai makan meskipun ruang geraknya terbatas. Setelah beberapa suap, saya melanjutkan apa yang Hoshihara tinggalkan dan mencoba sendiri untuk mencairkan suasana.
“Aduh, Hoshihara… Makan siangmu sedikit sekali,” kataku. “Apa itu benar-benar cukup untukmu?”
Seketika, ketegangan di wajah Hoshihara mulai mereda. “Oh, tentu saja!” katanya bangga. “Kenapa, kau pikir aku akan selalu lapar setelah makan sebanyak itu semalam?”
“Maksudku…agak, ya.”
“Yah, maaf mengecewakan, tapi perlu kamu tahu kalau komunitas perutku jauh lebih besar di malam hari! Tapi karena baru siang, ini sudah lebih dari cukup untuk membuatku kenyang.”
Uh… Datang lagi?
“Apa sih ‘ komunitas lambung’ itu?” tanyaku memberanikan diri. “Ada komunitas yang hidup di dalam ususmu, atau semacamnya?”
“Atau, maaf—bukan ‘komunitas’, tapi kau tahu maksudku. Maksudnya, seberapa banyak yang bisa kau muat di dalamnya, atau apalah. Ya Tuhan, apa ya istilahnya…?”
“Uhhh…” Aku melirik ke arah Ushio, berharap ada tali penyelamat.
Dia memutar matanya, tak terhibur. “Kapasitas.”
“Itu dia!” seruku.
“Ooh, ya! Bagus sekali, Ushio-chan!” kata Hoshihara. “Benar, kapasitas ! Itu yang kumaksud! Dasar, benar-benar linglung… Tapi ya, aku mau bilang—sepertinya kotak bento -mu sendiri ‘berkapasitas kecil’, Ushio-chan.”
“Benarkah?” kata Ushio.
“Uh-huh… Oh, hei! Kamu bahkan belum menyentuh omelet gulungmu. Apa kamu tipe yang selalu menyimpan yang terbaik untuk terakhir?”
“Oke, begini,” kata Ushio, tampak kesal sambil meletakkan sumpitnya dan menatapku, lalu Hoshihara. “Aku benar-benar tidak butuh kalian berdua bersikap seperti ini di dekatku.”
“Kita tidak bertindak seperti apa pun,” kataku secara refleks.
“Oh ya? Terus, kamu ngapain di sini, Sakuma?” Matanya menyipit. “Bukankah biasanya kamu makan siang sama Hasumi-kun?”
“Yah, maksudku…ya, tapi…”
Ushio mendesah kecewa, tampaknya merasa tak perlu membuktikan apa pun lagi, lalu mengalihkan pandangannya ke Hoshihara. “Dan kau, Natsuki? Kenapa kau begitu susah payah mendekatiku hari ini?”
“Aku…h-hanya berbicara padamu seperti yang selalu kulakukan.”
“Tidak, kau tidak,” kata Ushio, jelas-jelas mulai kesal. “Kau bahkan hampir tidak bicara sepatah kata pun padaku kemarin. Jelas sekali kau hanya berpura-pura.”
Rasa sesal membuncah di dadaku. Aku telah mengambil langkah yang salah. Aku sadar mungkin seharusnya aku tidak datang ke sini setelah—tunggu, tidak. Masih terlalu dini untuk mundur dulu. Ushio benar; kita tidak bisa hanya berpura- pura peduli dan berharap semua ini akan berlalu. Kita harus benar-benar duduk dan membicarakan semuanya.
“Kalau ada yang berpura-pura di sini, itu kamu, Ushio,” kataku.
Seketika, saya merasakan ketidaknyamanan di mulut—seperti baru saja menggigit kerang yang lezat dan berair, lalu disambut oleh tekstur berpasir yang berdesakan di sela-sela gigi saya. Mungkin ini bukan pilihan kata yang tepat bagi saya.
“Dan apa yang membuatmu berkata begitu?” tanya Ushio, kemarahan perlahan muncul dalam suaranya.
“Kau tahu betul betapa anehnya kau bersikap seperti itu di restoran malam itu,” jawabku, rasa tajam yang tak menyenangkan masih terasa di lidahku. “Orang tidak mungkin tiba-tiba bersikap kejam pada teman-temannya begitu saja, apalagi saat kita sedang bersenang-senang semalaman sampai saat itu… Kalau itu bukan pura-puramu, aku tidak tahu apa- apaan itu.”
Tidak, sialan! Apa yang kulakukan?! tanyaku pada diri sendiri. Pasti ada cara yang lebih halus untuk mengungkapkannya; aku sangat kesal pada diriku sendiri karena hanya bisa membahas topik ini dengan cara yang paling tidak bijaksana.
“Bukan apa-apa,” kata Ushio. “Aku cuma bilang apa yang sebenarnya kurasakan.”
“Kau bohong. Ushio yang asli tidak akan pernah mengatakan hal-hal itu.”
Ekspresi Ushio tiba-tiba berubah tajam. “Dan siapa sebenarnya ‘Ushio yang asli’?” Nada suaranya begitu tajam hingga rasanya seperti ada pisau yang menancap di leherku. “Kau pikir aku ini orang seperti apa, Sakuma? Orang suci rasionalitas yang lembut dan santun yang tak pernah berkata negatif tentang apa pun? Jangan paksa aku memenuhi standarmu yang mustahil hanya karena kau telah menciptakan gambaran sempurna tentang diriku di kepalamu.”
“I-itu sama sekali bukan yang ingin kukatakan…”
“Kurasa aku sudah cukup mendengar.”
Ushio mulai mengemasi bekal makan siang dan peralatan makannya yang tinggal setengah. Hoshihara membuka mulut ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya tak kunjung keluar. Aku pun merasakan hal yang sama; aku terus berpikir perlu melakukan sesuatu, tetapi pikiran-pikiran itu tak kunjung terwujud. Tanpa sadar, Ushio sudah berdiri dengan kotak bento di tangan dan tubuhnya menoleh ke arah pintu. Setelah jeda yang lama, ia melemparkan tatapan enggan ke arah kami dari balik bahunya.
“Maaf,” katanya, “tapi kurasa aku mau menghabiskan makan siangku di kafetaria. Rasanya aku ingin sendiri saja sekarang.”
Dan dengan itu, ia keluar dari kelas. Hoshihara berdiri beberapa sentimeter dari kursinya, tetapi tidak beranjak dari kursinya, malah terkulai lemas. Aku memegang kepalaku; aku benar-benar mengacaukannya. Seharusnya aku memikirkannya matang-matang sebelum bicara, jangan sampai emosiku mengambil alih dengan mengorbankan emosi Ushio.
Aku tak bisa menyangkal pernyataannya bahwa aku telah menciptakan gambaran yang sangat spesifik tentang dirinya di kepalaku—gambaran yang begitu kutakutkan akan menyimpang darinya, sampai-sampai aku menuduhnya bukan “Ushio yang sebenarnya” begitu dia bertindak sebaliknya. Kupikir mungkin jika aku bisa terus memasukkannya ke dalam kotak kecil yang sudah ditentukan itu, aku akan lebih mudah memahami apa yang membuatnya bersemangat dan apa yang sedang dialaminya. Tapi itu cara yang sepenuhnya salah. Sial, itu sama sekali tidak lebih baik daripada cara Nishizono memperlakukannya.
Hoshihara menghela napas panjang. “…Kurasa sebaiknya kita tutup mulut saja.”
Tak ada yang bisa kukatakan untuk itu. Dan di sini, aku baru saja mengira telah menemukan jalanku, tetapi ternyata jalan itu langsung tertutup kabut tebal. Kini aku kembali ke titik awal. Apa sebenarnya yang seharusnya kulakukan—
“Astaga, di sini suram sekali,” kata sebuah suara enteng, memecah keheningan. “Ada yang mati, atau apa?”
Aku menoleh dan dengan cemas melihat Sera entah bagaimana berhasil menyelinap masuk ke kelas lagi. Ia berjalan santai dengan senyum acuh tak acuhnya dan menjatuhkan pantatnya di kursi kosong Ushio. Hal ini membuat Hoshihara tampak tidak nyaman, tetapi Sera sepertinya tidak akan peduli.
“Tadi ketemu Ushio di lorong waktu aku jalan ke sini,” katanya. “Kalian nggak mungkin ribut, kan?”
“Itu bukan perkelahian,” kataku. “Kami hanya…salah menangani situasi, itu saja.”
“Oho…?”
Sera tiba-tiba tampak tidak tertarik dengan percakapan kami saat ini saat dia mencondongkan tubuh dan mengambil telur dadar gulung dari makan siangku lalu melahapnya.
“Hei, apa-apaan ini?!” kataku.
“Mrm,” kata Sera, sambil mengecap bibirnya sambil mengunyah. “Jadi, keluargamu membuatnya dengan kaldu dashi yang dicampur ke dalam telur, ya? Lumayan, lumayan. Aku juga suka begitu.”
Sialan dia… Aku menantikannya sepanjang hari…
Dia melahap sisa omelet gulungku, lalu menjilati jarinya sambil mendengus. “Yah, lumayan juga, kurasa. Lagipula kalian kan tidak punya harapan untuk bisa menghubungi Ushio sejak awal.” Dia pikir dia sudah tahu semua rencana kami. Aku hampir meledak karena dorongan untuk membantahnya semakin kuat, tetapi Hoshihara sudah terpancing sebelum aku sempat membuka mulut.
“Oh ya?! Dan apa yang membuatmu begitu yakin?!” katanya.
“Hei, nggak usah ketus! Aku nggak bermaksud menjatuhkan kalian atau apalah. Aku cuma bilang, meskipun kalian bisa hidup berdampingan dengannya, kalian nggak akan pernah bisa benar-benar dekat dengannya, tahu? Soalnya kalian punya privilese yang nggak dia punya. Kamu ngerti maksudku?”
“Dan kenapa begitu, ya?” tanyaku, mengambil alih. Aku bahkan sudah tidak marah lagi; aku hanya ingin dia cepat dan langsung ke intinya.
“Mmm… Baiklah, kalau kau berinisiatif …” kata Sera, berusaha sejengkel mungkin. “Oke, begini. Kau laki-laki, kan, Sakuma?”
“Ya.”
“Dan kamu suka perempuan, kan?”
“…Ada apa dengan itu?”
“Baiklah, begitulah. Itu hak istimewa untukmu.”
“Maaf? Saya tidak mengerti maksud Anda. Itu bukan hak istimewa, itu hanya norma—”
Saat kata-kata itu terucap dari bibirku, aku merasakan firasat buruk di perutku, seperti aku baru saja tak sengaja terjerat jerat.
“Benar sekali. Itu normal.” Sera mencondongkan tubuh untuk melihat wajahku lebih jelas, seperti pemburu yang girang mengintip mangsa bodoh apa yang telah jatuh ke dalam perangkapnya. Senyumnya tersungging. “Jadi maksudmu, Ushio tidak normal. Dan itulah kenapa aku tahu hubunganmu dengannya akan selamanya terputus.”
“Aku tidak bermaksud baik atau buruk,” kataku. “Jangan terlalu dipikirkan.”
“Ah, tapi justru keceplosan kecil dan tak berpikir panjang inilah yang sering kali mengungkapkan isi hati seseorang yang sebenarnya … Atau begitulah yang pernah kudengar dari seorang pria berjas rapi di sebuah acara bincang-bincang, heh.”
Sera bersandar di kursinya, terhuyung-huyung ke depan dan ke belakang dengan kedua kaki belakangnya. Hoshihara melirikku dengan gugup.
“Lagipula,” lanjut Sera, “ini bukan masalah baik atau buruk. Yang penting apa yang kau anggap normal itu berbeda dengan yang dianggap normal oleh Ushio. Dan kalau kau saja tidak melihat dunia dengan cara yang sama seperti orang lain, akan sangat sulit bagimu untuk memahami mereka lebih dalam. Itulah kenapa kurasa kalian tidak akan pernah bisa cocok sebagai teman atau terhubung dengannya. Sejujurnya, hal terbaik yang bisa Ushio lakukan untuk dirinya sendiri adalah segera pergi dari kota kecil kumuh ini dan pindah ke tempat di mana ia bisa bertemu lebih banyak orang seperti dirinya. Sama seperti beruang kutub yang hidup di Kutub Utara dan unta yang hidup di gurun, setiap orang punya lingkungan yang paling cocok untuk mereka berkembang. Dia seperti ikan yang hidup di luar air di pedalaman ini. Maksudku, ayolah—apa aku salah?”
Setiap kata terasa seperti jarum kecil yang menusuk dadaku. Aku tak menemukan bahan substansial untuk dijadikan argumen balasan. Sejujurnya, untuk pertama kalinya, perkataan Sera terdengar ada benarnya. Aku hanya tak sanggup mengakuinya. Aku sama sekali tak ingin membenarkannya di sini—karena itu juga berarti mengakui bahwa tak banyak yang bisa kulakukan untuk Ushio dalam jangka panjang.
“…Dan bagaimana denganmu, ya?” tanyaku.
“Hm? Apa itu?” tanya Sera.
“Apakah menurutmu kamu bisa lebih baik dalam berhubungan dengan Ushio?”
“Mmm… Ya, mungkin! Maksudku, aku cukup yakin setidaknya aku bisa lebih memahami apa yang dia alami daripada kamu . Belum lagi…”
Sera membiarkan kaki kursinya jatuh ke tanah dengan suara berdenting yang keras .
“Saya tidak menyebut orang lain menjijikkan hanya karena saya tidak memahaminya.”
Dengan itu, dia berdiri dari kursinya.
“Terima kasih untuk omelet gulungnya. Enak banget.”
Sera menyenandungkan lagu riang sambil menyelinap keluar kelas. Menurut standarnya, ini adalah retret yang cukup patuh. Aku penasaran apakah dia berencana untuk memeriksa Ushio, tetapi aku tak punya nyali untuk mengejarnya. Pria itu terasa seperti cermin dalam beberapa hal; setiap kali kami mengobrol, rasanya aku dipaksa untuk menghadapi bagian diriku yang paling tidak kusuka. Bahkan rasa permusuhanku sebelumnya terhadapnya kini digunakan untuk melawanku.
“…Eh, apakah ‘normal’ punya arti baru yang tidak kuketahui, atau apa?” tanya Hoshihara.
Dari ekspresinya, sepertinya dia benar-benar penasaran dan bingung. Tapi aku tidak punya kapasitas mental untuk mencoba memberinya jawaban saat itu.
***
Sejak insiden saat makan siang hari itu, saya dan Ushio praktis tidak berbicara sama sekali. Ya, kami masih saling membacakan dialog saat latihan, tetapi itu bukan percakapan yang sebenarnya. Kami hanya menjalankan tugas sebagai aktor. Ushio juga mulai makan siang sendirian di kafetaria setiap hari, yang berarti semakin sedikit kesempatan bagi Hoshihara untuk menghubunginya juga.
Aku tahu keadaan ini tidak berkelanjutan—tapi mungkin aku salah. Mungkin bagi Ushio, ini sangat melegakan karena tidak harus berurusan dengan kami sepanjang waktu. Sangat mungkin ini memang skenario idealnya, dan Hoshihara dan aku menentang keinginannya dalam mencoba “menyelesaikannya”.
Namun, ada satu hal yang membuat saya berpikir sejenak: Saya merasa seperti belum melihat Ushio tersenyum akhir-akhir ini. Tentu saja, kami jarang bertemu sekarang, jadi mungkin itu persepsi yang salah berdasarkan interaksi yang terbatas. Tapi jika firasat saya benar… maka saya tahu saya perlu mengubah situasi ini.
Saya ingin mencari cara untuk lebih dekat dengan Ushio.
Tetapi aku tahu jika aku tidak berhati-hati, aku hanya akan menyakiti kita berdua.
Itu dilema landak klasik yang pernah saya baca di sebuah buku, dulu sekali. Sayangnya, saya benar-benar lupa judul buku itu, apalagi apa yang disarankan penulisnya sebagai pendekatan ideal untuk dilema semacam itu—dengan asumsi memang ada. Saya berasumsi jika saya membuka setiap jilid buku di rak buku saya, mungkin suatu saat nanti saya akan menemukannya—jadi saya mulai menghabiskan waktu luang yang ada untuk membaca.
Waktu berlalu begitu cepat. Besok adalah hari festival.
***
Saya berangkat dari rumah sekitar satu jam lebih awal dari biasanya. Udara pagi yang segar dari luar terasa bersih dan segar. Saya mengayuh sepeda melewati seorang nenek yang sedang mengajak anjingnya berjalan-jalan dan sekelompok anak SMP yang sedang menuju latihan pagi. Saya berjalan ke jalan raya, melewati sawah, dan langsung menuju cahaya fajar yang menyilaukan, sinar matahari musim gugur yang lembut menerpa wajah saya.
Setibanya di SMA Tsubakioka, saya turun dari sepeda sebelum berjalan kaki ke kampus dan sejenak mengagumi lengkungan yang telah direkonstruksi, berdiri megah di atas gerbang utama. Seluruh panitia festival telah berkumpul untuk mendirikannya di lokasi akhirnya kemarin. Melihatnya akhirnya rampung dengan segala kemegahannya sudah cukup untuk memenuhi saya dengan rasa pencapaian yang mendalam lagi.
Aku melewati bawah gapura dan melangkahkan kaki ke kampus. Parkir sepeda masih sepi saat ini, tapi aku melihat sepeda Hoshihara. Dan di sana, kupikir aku mungkin akan menjadi orang pertama yang sampai di kampus untuk pertama kalinya, tapi sepertinya ketua komite kami yang andal sudah memulai harinya. Aku memarkir sepedaku, lalu masuk ke dalam gedung. Semua ruang kelas dihias dengan gaya layak festival, dengan papan nama dan poster mencolok berjajar di dinding, ditambah balon hias dan perada di mana-mana. Aku sudah bisa membayangkan dengan jelas kerumunan orang yang akan memadati lorong-lorong ini hanya dalam beberapa jam saja.
Aku berjalan menuju ruang OSIS dan membuka pintunya.
“Wah, sial,” kata Hoshihara, berbalik menghadapku yang berdiri di depan rak buku logam, tampaknya sedang memilah-milah beberapa kertas. “Kau datang pagi sekali.”
“Ya, kurasa aku agak gelisah menunggu,” kataku.
“Oh, hai, aku juga! Aku sangat bersemangat dan gugup tadi malam, sampai-sampai aku hampir tidak bisa tidur! Aku terus membaca pidato sambutanku berulang-ulang…”
“Oof, ya. Baguslah sudah hafal itu supaya kamu tidak lupa.”
“Nah, aku boleh membacanya dari kartu isyaratku kalau aku mau, jadi tidak ada risiko aku benar-benar melamun atau semacamnya.”
“Hah? Lalu kenapa kamu menghabiskan begitu banyak waktu untuk terobsesi?”
Aku tak kuasa menahan tawa mendengarnya, meskipun aku tahu mungkin agak kasar. Aku menarik kursi dari meja terdekat dan duduk. Hoshihara berhenti sejenak dan ikut duduk.
“Mmm, entahlah,” katanya. “Kurasa aku hanya ingin membuatnya terasa meyakinkan, tahu? Seperti, ‘Hei, semuanya! Lihat betapa hebat dan cakapnya aku sebagai ketua komite!'”
“Oh, itu adil… Ya, masuk akal.” Aku bisa memahami perasaannya.
“Yah, bukan berarti aku tidak berlatih beberapa kali agar tidak terbata-bata atau semacamnya. Pasti ingin mengakhiri semuanya dengan baik, setidaknya, mengingat betapa banyak masalah yang kutimbulkan untuk semua orang selama ini…”
“Ya, aku tak sabar mendengar pidatomu. Aku tak mau melewatkannya.”
“Oh, tidak, tidak, tidak! Jangan terlalu bersemangat!” kata Hoshihara sambil terkekeh malu. “Ini tidak akan jadi sesuatu yang istimewa, percayalah!”
Hingga sekitar sebulan yang lalu, hanya berada di dekat Hoshihara saja sudah cukup membuat jantungku berdebar tak terkendali. Tapi sekarang, rasanya menenangkan dan nyaman berada di dekatnya—seperti perasaan yang kau rasakan setelah menyesap secangkir teh hangat. Bukan berarti aku tidak lagi memiliki perasaan padanya, lho—malah, perasaanku padanya sekarang lebih kuat daripada sebelumnya—hanya saja sifat perasaan itu mulai sedikit bergeser menjadi sesuatu yang lebih rumit daripada sekadar suka.
Maka aku bertanya pada diriku sendiri: apa yang sebenarnya kuinginkan terjadi antara aku dan dia? Apa aku ingin kami jadi pacar? Aku tahu aku bohong kalau bilang perasaan itu tidak ada. Tapi, katakanlah kami memang mulai berpacaran, lalu bagaimana?
Bagaimana perasaan Ushio tentang hal itu?
“Yah, sejujurnya…” kata Hoshihara, membawaku kembali ke dunia nyata. “Aku nggak akan melewatkan pertunjukan Romeo dan Juliet -mu sama sekali… Jadi, balas saja, ya.”
“Kedengarannya bagus,” kataku. “Kurasa aku akan bertemu denganmu di sana kalau begitu.”
“Ya. Aku sangat menantikannya.”
Hoshihara tersenyum paling riang dan puas yang pernah kulihat. Aku mengangguk tegas sebagai jawaban, berharap kami bisa mewujudkan perasaan yang tersirat di dalamnya.
Setelah upacara pembukaan selesai, saya langsung ditugaskan sebagai resepsionis di luar gerbang utama sebagai bagian dari tim administrasi. Saya akan bekerja sama dengan para dosen dan anggota panitia lainnya untuk mencatat nama-nama dan keperluan lainnya untuk semua tamu festival. Hari itu hari Sabtu, jadi banyak alumni dan bahkan anak-anak dari sekolah lain yang datang, selain keluarga dan kerabat mahasiswa setempat. Saking banyaknya orang yang datang, terutama setelah pukul sembilan, suasana menjadi sangat ramai sampai-sampai saya pusing.
“Baiklah, Kamiki. Aku akan mengantarmu,” kata salah satu anggota tim administrasi lainnya ketika jam sebelas tiba dan lalu lintas sudah agak mereda.
“Salin itu.”
Aku bangkit dari kursiku dan berjalan keluar dari tenda resepsi. Tidak ada pekerjaan komite yang harus kulakukan untuk sementara waktu, jadi aku bebas keluar dan menikmati festival sampai pertunjukan Romeo dan Juliet pukul dua. Tapi setelah pertunjukan selesai, aku harus langsung kembali bekerja di gerbang utama, jadi tiga jam itu adalah waktuku untuk melihat-lihat pameran dan stan minuman di kelas lain.
Meski begitu, saya tidak merasa ada keharusan yang kuat untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Malahan, saya hanya ingin segera menyelesaikan waktu luang ini. Tidak ada pameran yang sangat saya nanti-nantikan, dan saya juga tidak punya teman untuk bergabung. Alih-alih, saya berencana menghabiskan waktu ini dengan membantu di kantor pusat panitia festival, karena OSIS memberi tahu kami bahwa mereka membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapatkan jika kami punya waktu luang. Ini adalah waktu istirahat yang menyenangkan bagi penyendiri seperti saya.
Setelah berganti sepatu di pintu masuk, saya menuju ruang OSIS. Semua siswa lain yang saya lewati di sepanjang jalan tampak menikmati kemeriahan pesta sepuasnya. Di antara sekian banyak atraksi, ada rumah hantu dan kafe bertema, jadi ada juga siswa yang berjalan-jalan masih mengenakan kostum untuk pameran kelas mereka—beberapa di antaranya bahkan mengecat rambut mereka hanya untuk hari ini, karena hari itu adalah satu-satunya saat fakultas menutup mata terhadap apa yang seharusnya menjadi pelanggaran berat terhadap peraturan sekolah. Bukan berarti tidak ada siswa seperti Nishizono yang mengabaikan peraturan tersebut sepanjang tahun, tapi sayangnya…
Tiba-tiba saya merasa ingin tahu.
Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Ushio saat ini.
Hoshihara dan aku sama-sama anggota panitia festival, jadi kami bahkan belum sempat membuat rencana untuk berkeliling dan melihat-lihat festival bersama. Artinya, Ushio harus nongkrong dengan orang lain atau berjalan-jalan sendirian.
Ya ampun… Bagaimana kalau yang terakhir?
Aku tahu sebenarnya bukan tugasku untuk mengkhawatirkan apakah dia bersenang-senang, tapi aku tetap merasa sedikit cemas. Aku berjalan melewati ruang OSIS dan terus menyusuri lorong, sambil terus memperhatikan Ushio saat aku berjalan di dalam gedung. Aku tidak tahu kenapa, tapi membayangkan dia duduk sendirian di sudut kampus yang terpencil itu sungguh menyentuh hatiku.
Ketika saya sampai di lantai dua, saya bisa mendengar ketukan rendah dan berat menggema di seluruh gedung dari lapangan atletik di bawah sana. Saya melihat ke luar jendela aula dan melihat tim tari jalanan sekolah telah memulai penampilan mereka di panggung luar, dengan anak laki-laki dan perempuan berkaus longgar menggoyangkan tubuh mereka mengikuti irama. Saya melihat ke area tempat duduk penonton, bertanya-tanya apakah mungkin Ushio ada di sana. Tentu saja saya bisa mengenali rambutnya yang seputih salju bahkan dari atas sini, di lantai dua.
“Oh, hai! Ada apa, Kamiki?”
Mendengar namaku dipanggil, aku menoleh dan melihat Mashima dan Shiina berdiri di seberang aula. Shiina tidak membawa apa-apa, sementara Mashima membawa churro dan beberapa kue kering segar yang dibungkus plastik. Ia tampak menikmati festival itu persis seperti yang ia inginkan.
“Kalian sendirian?” tanya Mashima.
“Untuk saat ini, ya…” jawabku, tiba-tiba merasa sedikit canggung.
“Aduh, kasihan banget sih… Kasihan banget. Nih, mau churro?” tanyanya sambil menyodorkan sisa camilan kayu manis gorengnya yang sudah digigit.
“Apa…? Ti-tidak, singkirkan benda itu dari wajahku.”
“Ah ha ha! Lihat betapa gugupnya dia! Wah, kamu asyik sekali digoda, Kamiki.”
“Ayo, Marinir,” kata Shiina. “Tunjukkan sopan santunmu.”
Ya, tidak bercanda, saya menyetujuinya dalam hati.
“Baiklah—kalau begitu, kurasa aku akan menggigitmu !” kata Mashima, sambil langsung memasukkan churro yang sudah dimakan sebagian ke mulut Shiina. Gadis yang satunya langsung menggerutu dan mengerang protes. Namun, ia tak ingin membuat kekacauan lebih parah dengan meludahkannya, jadi ia dengan enggan menggigit ujungnya dan mengunyah. Mereka berdua hampir saja bisa main-main seperti ini tanpa memikirkan apa-apa. Aku agak iri.
“Oh ya—apakah kalian pernah melihat Ushio di suatu tempat?” tanyaku.
“Ushio?” tanya Mashima. “Ya, cukup yakin dia bersama Loki-chan. Kayaknya aku juga lihat Nanamori-san bersama mereka? Lupa.”
Sebagai referensi, yang ia maksud dengan “Loki-chan” adalah Todoroki. Itu hanya plesetan dari dua suku kata terakhir namanya—tidak ada hubungannya dengan mitologi Nordik.
“Oh, begitu,” kataku. “Jadi dia sedang berkencan dengan seseorang, kalau begitu…”
Mungkin Ushio dan Todoroki menjadi lebih dekat daripada yang kusadari berkat kerja sama mereka dalam drama kelas. Kalau dipikir-pikir, aku sering melihat mereka berdua mengobrol selama latihan.
“Jadi, apa rencanamu selanjutnya, Kamiki?” tanya Mashima. “Mau coba bergabung dengan mereka?”
“Enggak. Aku sebenarnya mau bantu di kantor pusat.”
“Kena kau. Keren, keren… Oh, sial! Lihat jamnya! Kontes trivia akan segera dimulai! Ayo, Shiina! Ayo!”
“Mmmf?! Hrey, waidduh… Marinir, tunggu!” teriak Shiina, menutup mulutnya dengan satu tangan sambil mengejar Mashima. Mereka memang sahabat karib; mereka sudah saling kenal sejak kecil, kalau tidak salah ingat. Lucu juga melihat mereka rukun meskipun memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang—tapi mungkin, seperti magnet, itulah yang membuat mereka begitu mudah tertarik satu sama lain. Sulit untuk tidak merasa sedikit iri dengan hubungan seperti itu.
Bagaimanapun, aku merasa konyol karena khawatir Ushio mungkin sendirian, tapi sekarang setelah tahu dia tidak sendirian, aku bisa berhenti mencarinya dan kembali ke markas komite untuk membantu. Seharusnya beban pikiranku berkurang—tapi, ada yang terasa janggal. Seperti angin dingin yang berhembus menembus lubang di hatiku. Seharusnya aku senang Ushio sudah menemukan teman untuk menikmati festival bersama, kan? Jadi kenapa aku merasa seperti ini?
Tunggu! Apakah itu—
Tepat saat itu, aku melihat wajah yang familiar di ujung lorong. Aku bisa mengenali rambut pirang keperakan terang itu dari jarak satu mil. Itu Ushio. Dan seperti kata Mashima, dia bersama Todoroki dan Nanamori. Mereka bertiga berjalan menyusuri lorong ke arahku, tetapi mereka sepertinya belum menyadari kehadiranku, jadi aku segera bersembunyi di sudut terdekat.
…Tunggu. Kenapa aku melakukan ini?
Tentu saja itu hanya tindakan refleks. Aku tidak punya alasan khusus untuk tidak ingin mereka melihatku. Meskipun aku pernah mengalami sensasi serupa sebelumnya; setiap kali aku sedang menjalankan tugas atau semacamnya dan kebetulan melihat salah satu teman sekelasku dari sekolah sedang keluar, aku merasakan dorongan yang sama untuk berbelok ke arah lain agar kami tidak perlu menghadapi kecanggungan karena berpapasan di tempat umum. Bedanya, ini bukan tempat tak terduga untuk berpapasan dengan Ushio, dan aku benar-benar sudah mencarinya sampai beberapa saat yang lalu. Tidak masuk akal aku mengelak seperti itu. Dan akhirnya aku terjebak dalam kondisi tengah yang aneh ini, tidak menunjukkan diri kepada Ushio atau melarikan diri, hanya mengamatinya dari balik bayangan.
Ketiga gadis itu tampak asyik mengobrol, dan mereka tampak asyik mengobrol, terlalu jauh hingga saya tak tahu apa yang mereka bicarakan. Ushio mengatakan sesuatu kepada Nanamori, lalu terkekeh ketika Todoroki menyela dengan sesuatu yang saya duga semacam gurauan.
Baiklah, coba kau lihat itu… Kurasa Ushio masih tahu caranya tersenyum.
Aku merasakan angin dingin menusuk dadaku sekali lagi.
Rasanya aneh—sedikit rindu, sedikit hampa. Apa mungkin aku iri pada Todoroki dan Nanamori? Iri karena mereka berhasil berteman dekat dengan Ushio beberapa minggu terakhir ini, sementara aku berjuang keras hanya untuk menyelamatkan status quo? Bukan, bukan itu. Aku tidak merasakan emosi tertentu terhadap mereka berdua. Perasaan ini memang berkaitan denganku dan Ushio, tapi aku tak tahu pasti. Entah kenapa, rasanya hampir seperti patah hati. Kalau begitu, mungkin maksudnya… Ah.
Akhirnya, aku menyadari betapa dinginnya dadaku saat itu.
Itu mengecewakan.
Aku sudah bilang ke diriku sendiri kalau aku khawatir Ushio sendirian, tapi kenyataannya, aku malah berharap aku akan menemukannya sendirian dan butuh teman.
Jauh di lubuk hati, yang kuinginkan dari semua ini hanyalah kesempatan bagiku untuk mengulurkan tangan persahabatan dan membuatnya berkata, “Aduh, Sakuma. Apa jadinya aku tanpamu?” Aku hanya mencari kesempatan untuk membuatnya merasa berhutang budi padaku—karena ternyata, aku merasa itulah cara kami menjalin ikatan yang lebih erat. Dan ketika kusimpulkan seperti itu, memikirkannya saja sudah cukup membuatku ingin muntah.
Sekeji apa aku ini? Aku benar-benar secara tidak sadar berharap Ushio sedang sengsara saat ini, hanya untuk memuaskan hasratku yang terdistorsi untuk merasa dibutuhkan dan diandalkan olehnya. Tapi, bahkan jika semuanya berjalan persis seperti yang kuinginkan, itu tidak akan membuat Ushio dan aku setara sebagai teman, tidak—karena seluruh metodologi rencana kecilku didasarkan pada bagaimana aku menemukannya dalam posisi lemah yang darinya aku bisa menyelamatkannya dengan turun tangan dan berperan sebagai ksatria berbaju zirah putih berkilau.
Membayangkan aku mampu menyimpan pikiran-pikiran jahat dan menjijikkan seperti itu tanpa menyadarinya membuatku merinding. Seluruh tubuhku gemetar, dan tiba-tiba aku merasa mual. Pada akhirnya, aku sama sekali tidak peduli dengan perasaan Ushio—aku hanya ingin dia memvalidasi perasaanku … Dia benar-benar berhak ingin menjauhiku.
Ya Tuhan. Tunggu sebentar.
Apakah saya selalu seperti ini?
Apakah semua hal yang kupikir kulakukan karena kebaikan atau pertimbangan—bukan hanya untuk Ushio, tapi untuk semua orang—benar-benar hanya hasil dari keinginan egoisku sendiri? Mengapa aku ingin berteman dekat dengan Ushio sejak awal? Apakah itu benar-benar karena aku menyayanginya sebagai pribadi, atau karena kami sudah saling kenal begitu lama—atau hanya agar aku bisa merasa lebih baik tentang diriku sendiri dan betapa baiknya diriku ?
Tidak… Tidak, tidak mungkin begitu—bukankah begitu?
“Tunggu. Kamiki?”
Mendengar namaku dipanggil, aku tersadar kembali. Aku terlalu asyik dengan duniaku sendiri sampai-sampai tak menyadari Ushio dan dua gadis lainnya sudah berjalan menyusuri lorong menuju tempatku berdiri. Ternyata Todoroki yang memanggilku, dan sekarang ia memiringkan kepalanya dengan heran.
“Kamu nggak lagi malas kerja, kan?” tanyanya dengan nada mengejek. “Kalau kamu mau jadi panitia festival, setidaknya kamu harus bersikap seperti itu…”
Di belakangnya, aku bisa melihat Nanamori terkekeh.
“Yah, sebenarnya aku bahkan tidak—”
Aku mulai protes, lalu menatap Ushio, yang hanya berdiri di sana dengan wajah tak nyaman. Seketika, rasa malu dan bersalah membuncah di dadaku, dan aku tak bisa lagi menahan diri.
“L-Lihat, aku tidak bermalas-malasan, oke?” kataku, lalu langsung menghentakkan kaki pergi.
Aku tahu aku mungkin membuat mereka berpikir ada sesuatu yang sangat aneh telah merasukiku; aku hampir bisa merasakan tatapan menghakimi mereka di punggungku saat aku berjalan pergi. Tapi aku tak sanggup lagi berhadap-hadapan dengan Ushio. Dialah orang terakhir yang ingin kulihat emosi-emosi buruk yang sedang kucoba atasi saat ini.
Kepalaku rasanya mau pecah. Tengkorakku masih bergaung dengan gema kesadaran yang memilukan bahwa aku ternyata jauh dari sebaik yang kukira.
Aku bahkan tidak tahu lagi aku ini apa .
“Kamu merasa sedikit gelisah, Kamiki-kun?”
Aku berbalik di kursiku dan melihat Hoshihara berdiri di sampingku, menatapku dengan ekspresi gelisah. Di tangannya terdapat setumpuk kuesioner yang hasilnya baru saja kuhitung beberapa menit sebelumnya.
Setelah menghilang dari pandangan Ushio, aku pergi ke ruang OSIS. Di sana, aku menawarkan diri untuk membantu Hoshihara, yang sedang disibukkan dengan tugas-tugas manajerial seperti menangani keluhan dan perselisihan tamu sambil mengurus barang hilang, jadi dia dengan senang hati mencarikan beberapa pekerjaan sambilan untuk kuambil alih. Saat itu, hanya aku dan dia yang ada di ruangan itu, tetapi selalu ada orang yang keluar masuk, jadi rasanya kami tidak sendirian.
“T-tenang? Kenapa kamu bilang begitu?”
“Ekspresimu tegang sekali,” katanya sambil menatap tajam. “Aku jadi bertanya-tanya, apa mungkin kamu gugup soal drama itu atau apalah.”
“Oh, mengerti… Eh, bukan seperti itu. Jangan khawatir.”
Bukan berarti aku tidak cemas dengan penampilannya. Tapi bukan itu yang sedang kupikirkan saat ini.
“Yah, kalau kau bilang begitu… Ngomong-ngomong, aku sebenarnya butuh sesuatu lagi darimu,” katanya, terdengar agak ragu untuk membahasnya. “Sepertinya totalmu salah.”
“Tunggu, aku melakukannya?!”
Ia mengangguk dan menyerahkan setumpuk kertas itu kepadaku. Kuesioner yang kami kumpulkan sepanjang hari itulah yang memberi kesempatan kepada siswa dan tamu untuk menilai kontribusi setiap kelas terhadap festival, yang hasilnya akan kami umumkan saat upacara penutupan. Kelas dengan peringkat tertinggi secara keseluruhan akan memenangkan penghargaan. Hal ini telah menjadi sumber motivasi utama bagi banyak siswa selama berminggu-minggu persiapan menjelang acara, sehingga mendapatkan hasil yang tepat merupakan tanggung jawab yang cukup besar.
“M-salahku,” kataku. “Akan kuhitung lagi.”
“Maaf soal itu, ya. Aturannya, kita harus terus menghitung ulang sampai angka kita cocok.”
“Ya, aku tahu. Maaf merepotkan…”
Merasa benar-benar bersalah, saya segera menghitung ulang suara. Saya senang dia berhasil menemukan kesalahan dalam ulasannya; hasilnya tidak akan memuaskan jika ketahuan bahwa kami telah memberikan penghargaan kepada kelas yang salah hanya karena kesalahan matematika sederhana.
“Wah, itu agak aneh sih,” kata Hoshihara sambil tersenyum lembut. “Aku selalu menganggapmu tipe orang yang bisa mengerjakan hampir semua pekerjaan dengan mudah. Kedengarannya mungkin agak buruk, tapi aku sebenarnya agak lega mengetahui orang sehebat dirimu juga terkadang bisa salah.”
Aku tahu maksud tersirat di sini adalah dia tidak mempermasalahkannya, dan aku menghargai keramahannya. Tapi sejujurnya, sentimen ini agak tidak masuk akal bagiku saat itu, jadi kata-katanya hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan.
“…Kau terlalu memujiku,” kataku, sedikit merendahkan diri. “Kelihatannya begitu karena aku biasanya menghindari apa pun yang sebenarnya tidak ingin kulakukan. Aku tidak berbakat dalam hal apa pun, dan aku janji, aku selalu membuat kesalahan yang tak pernah kau sadari. Kalau kau pikir orang sepertiku mampu , maka anggota komite lainnya pasti seperti pahlawan super yang tak pernah salah di matamu.”
Hoshihara mengerjap beberapa kali. “K-Kamiki-kun, apa yang merasukimu?”
Dia tampak benar-benar khawatir. Sial. Kurasa aku agak terlalu merendahkan diri di sana.
“Maaf,” kataku. “Lupakan saja.”
Apa yang sebenarnya kulakukan di sini? Apa yang kuharapkan dengan menghina diriku sendiri seperti ini, selain menempatkan Hoshihara dalam posisi canggung karena harus menghiburku? Yang, tentu saja, sepertinya ia siap melakukannya, dilihat dari raut khawatir di matanya saat ia mendekatkan wajahnya.
“Kau yakin tidak merasa sedikit gelisah?” tanyanya. “Mungkin ide bagus untuk mencoba menarik napas dalam-dalam. Oksigen itu sangat penting, kau tahu.”
Pernyataan terakhirnya cukup aneh hingga membuatku tersenyum, tapi aku tetap menuruti sarannya dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Latihannya sendiri sepertinya tidak terlalu berpengaruh, tapi aku merasa sedikit lebih rileks sekarang.
“Apakah itu berhasil?”
“Ya. Merasa sedikit lebih baik sekarang, terima kasih.”
“Oke, fiuh,” katanya, ketegangan di wajahnya mereda. Melihat senyumnya lagi jelas merupakan penyemangat yang lebih baik daripada latihan pernapasan apa pun.
Aku benar-benar harus berhenti bersikap bimbang; pertunjukan besarnya tinggal beberapa jam lagi. Kalau aku tidak bisa segera kembali ke kondisi pikiranku yang biasa, itu akan menghambat penampilanku. Aku menyingkirkan pikiran-pikiran eksistensialku untuk sementara waktu dan mulai membaca ulang tumpukan kuesioner, kali ini kuteliti satu per satu.
“Oh ya—jadi, apakah kamu melihat Ushio-chan hari ini?” tanya Hoshihara.
Tepat ketika kupikir aku sudah mencapai kondisi yang relatif tenang, mendengar nama Ushio saja sudah cukup untuk mengirimkan gelombang emosi yang tak menyenangkan beriak lagi di hatiku yang baru tenang. Tapi aku tak ingin membuat Hoshihara khawatir lagi, jadi aku berusaha sebaik mungkin untuk menjawab dengan tenang.
“Ya, sudah,” kataku. “Dia sedang nongkrong bareng Todoroki dan Nanamori-san.”
“Benar, itulah yang kudengar… Penasaran apa yang mereka bertiga bicarakan.”
“Hah?” Aku tertegun sejenak. “Tunggu, kamu sudah tahu tentang itu?”
“Hm? Tahu tentang apa?”
“Bahwa dia sedang bergaul dengan mereka.”
Aku bisa merasakan nada bicaraku menjadi lebih tegas, meski itu tidak disengaja.
“Eh, y-ya,” kata Hoshihara sambil mengangguk bingung. “Dia bilang dia mau menghabiskan hari bersama mereka beberapa waktu lalu…”
Oh, begitu. Jadi ada yang sudah menerima memonya.
Aku sudah bisa merasakan diriku kembali terjerumus ke dalam suasana hati yang aneh dan depresif; aku sedikit tersinggung karena dia memberi tahu Hoshihara tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku, sementara pada saat yang sama kesal pada diriku sendiri karena membiarkan hal sekecil itu menggangguku. Jelas, Ushio bebas bergaul dengan siapa pun yang diinginkannya. Dia tidak berkewajiban memberi tahuku jika dia berencana untuk bergaul dengan seseorang selama festival budaya, terutama mengingat dia tahu aku akan terlalu sibuk dengan pekerjaan komiteku untuk menghabiskan banyak waktu dengannya sendiri. Memikirkannya secara rasional, cukup absurd bagiku untuk kesal karena dia tidak memberi tahuku tentang hal ini—dan terlepas dari apakah perasaan itu valid atau tidak, aku bisa saja bertanya padanya sendiri sebelumnya apakah hal itu benar-benar akan menggangguku sebanyak itu. Intinya, aku merasa seperti orang bodoh karena memiliki emosi tentang hal itu.
“Kamiki-kun?”
Meski begitu, fakta bahwa dia memberi tahu Hoshihara, tetapi tidak kepadaku, adalah pil pahit yang harus ditelan. Aku bahkan tergoda untuk menganggap ini sebagai tanda bahwa Ushio tidak ingin berhubungan lagi denganku—tapi tidak, masih terlalu dini untuk menyimpulkan itu. Menduga-duga sejauh itu bahwa dia hanya tidak memberi tahuku tentang rencananya akan sangat paranoid. Aku harus berhenti berpikir bahwa setiap hal kecil yang dia lakukan ada hubungannya denganku. Namun… Ushio juga mengenalku dengan sangat baik sehingga terkadang rasanya dia bisa membacaku seperti buku. Sangat mungkin dia sudah tahu betapa buruk dan egoisnya perasaanku padanya sejak lama, dan bahwa pertengkaran kami saat makan siang kemarin hanyalah pemicunya… Kalau begitu, mungkin dia memang tahu—
“Kamiki-kun, aku bicara padamu!”
“Hah? Oh…”
Ketika aku tersadar, kulihat Hoshihara kini tengah menunduk seperti orang tua yang khawatir, mencoba melihat wajahku lebih jelas.
“Ada apa?” tanyanya. “Kamu baik-baik saja?”
“M-maaf, salahku. Agak melamun sebentar.”
“Kamu merasa tidak enak badan? Kalau kamu perlu berbaring di ruang perawat atau semacamnya, kamu bisa melakukannya. Tidak perlu memaksakan diri untuk membantu…”
“Tidak, sungguh. Aku baik-baik saja, sumpah.”
“Kamu bilang begitu, tapi…”
Tepat saat itu, pintu ruang OSIS berderak terbuka. Aku menoleh dan melihat seorang siswa laki-laki mengacungkan semacam kunci dengan dua jarinya sambil berjalan masuk.
“Hei, aku menemukan ini di lantai luar,” katanya. “Apakah ini barang hilang?”
Hoshihara menatapnya, lalu kembali menatapku, bergantian. Setelah ragu sejenak, ia melirikku sekali lagi sebelum bergegas membantu anak laki-laki itu.
“Ya, kamu bisa tinggalkan saja di sini,” katanya. “Aku hanya punya sedikit dokumen yang perlu kamu isi, jadi tunggu sebentar…”
Saat Hoshihara menjelaskan prosedurnya kepada anak laki-laki itu, aku berbalik dan memijat pelipisku. Aku bilang padanya aku baik-baik saja, tapi nyatanya, otakku terasa seperti bubur. Sejak kapan aku jadi tipe orang yang begitu memikirkan hal-hal seperti ini? Aku benar-benar tidak tahu. Tapi satu hal yang bisa kukatakan dengan pasti adalah: hampir semua hal yang membuatku stres selama beberapa bulan terakhir ini ada hubungannya dengan Ushio, entah bagaimana caranya. Dan jika aku masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menyakitinya meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk bersikap perhatian, mungkin lebih baik aku tidak ikut campur dalam hidupnya sama sekali.
Saat itu pukul 13.57, dan acara berjalan sekitar sepuluh menit lebih lambat dari jadwal sebelumnya di gedung olahraga. Bahkan dari balik tirai, orang-orang bisa mendengar kerumunan yang semakin banyak. Lebih dari separuh kursi di auditorium sudah terisi. Semua aktor telah mengenakan kostum untuk acara utama, sementara yang lain berdiri gelisah berkerumun di belakang panggung—dan saya termasuk di antara mereka. Kostum Romeo saya yang agak terlalu ketat semakin memperparah ketegangan.
“Oke, teman-teman! Setelah mereka menurunkan instrumen mereka dari panggung, kalian boleh keluar! Seharusnya tidak lebih dari lima menit lagi!”
Pengumuman dari salah satu anggota panitia yang membantu menjalankan acara ini justru semakin menambah kegugupan kami. Aku menyeka keringat di telapak tanganku dan kembali membaca naskahku. Sebagai salah satu dari dua karakter utama, aku punya banyak sekali dialog, jadi aku ingin menghabiskan setiap detik terakhirku untuk memastikan dialog-dialog itu tertanam di kepalaku sebelum kami naik panggung.
Namun, hal itu tidak terjadi.
Aku sama sekali tak bisa fokus. Rasanya seperti ada badai emosi yang dahsyat menyambar otakku, menyapu bersih semua yang telah kuhafal dengan susah payah selama beberapa minggu terakhir dan mengancam akan membawanya pergi seperti puing-puing. Aku terus seperti ini sepanjang sore, merepotkan Hoshihara karena aku terus-menerus melakukan kesalahan saat membantunya di ruang OSIS. Aku benar-benar kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi pada apa pun.
“Sakuma,” kata sebuah suara—dan aku hampir melompat kaget.
Ushio berdiri di sana, berpakaian seperti Juliet, dengan ekspresi khawatir di wajahnya.
“Kamu kelihatan pucat sekali… Apa kamu akan baik-baik saja?” tanyanya.
“Y-ya, aku akan baik-baik saja,” kataku sambil terus menundukkan pandanganku ke arah lain karena aku tak sanggup menatap matanya.
“Kalau kamu mau ke kamar mandi, sebaiknya kamu pergi sekarang. Aku yakin tidak akan ada yang keberatan meskipun acaranya harus ditunda beberapa menit.”
“Ya, aku tahu. Terima kasih, aku baik-baik saja.”
“…Ada yang mengganggumu?” tanyanya, nadanya tiba-tiba berubah serius. Mungkin dia bisa melihat kebencian dan rasa tidak nyaman di raut wajahku. Aku merasa tidak enak; Ushio punya lebih banyak alasan untuk merasa gugup naik panggung sekarang, tapi di sini dia justru mengatasi rasa tidak amanku .
“Tidak,” kataku. “Sama sekali tidak.”
“Kamu tidak masih memikirkan kejadian kemarin, kan?”
Dengan itu, kukira maksudnya adalah ketika aku meledak-ledak padanya saat makan siang. Itu pasti salah satu alasannya, tentu saja, tapi hal utama yang menggerogotiku saat ini adalah apakah aku, Sakuma Kamiki, sebenarnya orang baik, bahkan sedikit pun. Dan aku tak ingin membicarakan itu dengan Ushio. Aku tak bisa.
“Tidak, Ushio. Itu tidak ada hubungannya denganmu.”
Ekspresinya menguap begitu cepat, sampai aku bersumpah mendengarnya menghilang. “Oh, begitu? Baiklah kalau begitu.”
Dia berbalik dan berjalan kembali ke tempat asalnya. Maaf, Ushio, kataku dalam hati. Aku tidak bermaksud bersikap dingin padanya, tapi aku tidak punya kapasitas ekstra untuk mengkhawatirkan orang lain saat ini. Sial, aku bahkan sedang tidak dalam kondisi pikiran yang tepat untuk terlibat dalam drama ini, tapi tirai akan segera dibuka.
“Oke, tempat-tempatnya, semuanya!” kata Todoroki, mencoba menyemangati semua orang. “Kita sedang bersiap-siap untuk meluncur ke sini, jadi lihatlah dengan semangat!”
Waktunya hampir tiba. Narator duduk di depan pengeras suara dan membuka naskah. Seburuk apa pun perasaanku, aku tahu pertunjukan harus tetap berlanjut. Tentu, akan ada festival budaya lagi tahun depan, tapi ini kesempatan pertama dan terakhir kami untuk mementaskan Romeo dan Juliet sebagai Kelas 2-A. Kami sudah berlatih mati-matian untuk momen ini. Sekalipun aku sedikit salah dialog, aku bisa berimprovisasi dan menemukan cara untuk kembali ke jalur semula. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju tempatku di sisi panggung.
Seluruh auditorium riuh dengan suara orang-orang yang berceloteh, berdeham, dan menggesekkan kaki kursi lipat mereka di lantai. Suara-suara ini sendiri tak terlalu riuh, tetapi bersama-sama membentuk hiruk-pikuk menegangkan yang memenuhi gedung olahraga dari langit-langit hingga lantai.
“Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut siswa Kelas Dua 2-A SMA Tsubakioka untuk membawakan pementasan drama klasik Shakespeare, Romeo dan Juliet !” ujar penyiar OSIS yang bertugas memfasilitasi acara panggung di gedung olahraga.
Lampu padam, dan keheningan menyelimuti penonton sementara auditorium diselimuti kegelapan. Akhirnya, tirai mulai dibuka.
“Kami memulai kisah kami di Verona yang indah, tempat dendam lama antara keluarga Montague dan Capulet membuat pertikaian di jalanan kota hampir terjadi setiap hari. Namun, pada suatu hari yang menentukan, seorang anak laki-laki Montague bernama Romeo menyelinap ke sebuah pesta dansa yang diadakan di kediaman keluarga Capulet…”
Ushio dan aku melangkah keluar menuju sorotan lampu dari sisi panggung yang berseberangan, dan seketika semua mata penonton tertuju pada kami. Sesaat, aku bahkan tak bisa bernapas, seolah tatapan mereka masing-masing memiliki massa yang nyata dan secara kolektif membebaniku. Mereka kini mengamati setiap gerakan kami dengan penuh harap, menunggu untuk dihibur. Saat aku menyadari fakta sederhana ini, aku mulai merasakan tekanan; detak jantungku melonjak, dan keringatku pun mengalir deras. Aku bahkan melewatkan isyarat untuk baris pertamaku.
“Astaga, kurasa itu Tsukinoki , bro!”
Tiba-tiba, saya mendengar suara-suara memanggil dari tengah kerumunan.
“Sial, mereka benar-benar membiarkannya berdandan dan berperan sebagai Juliet?”
“Tunggu, tunggu, tunggu. Itu Tsukinoki-senpai?”
“Saya lupa—apakah kita diizinkan mengambil foto?”
“Tunggu dulu. Kamu yakin itu cowok?”
Sungguh menjengkelkan betapa selektifnya pendengaran saya memilih untuk bersikap—seolah-olah otak saya hanya menangkap hal-hal yang diketahuinya tidak ingin saya dengar.
Tunggu. Hal-hal yang tidak ingin kudengar? Bukankah seharusnya Ushio yang kukhawatirkan?
Lagipula, dialah yang awalnya begitu cemas tentang bagaimana orang lain akan menerimanya jika dia memerankan Juliet. Dia benar-benar memberi tahu saya bahwa salah satu alasan utama dia ragu adalah karena orang-orang mungkin akan menertawakannya. Memang, tidak ada tawa yang benar-benar terdengar dari penonton saat itu—tetapi saya tahu dia pasti menganggap komentar-komentar yang tidak bijaksana dan sindiran-sindiran kasar itu jauh lebih personal daripada saya.
Namun, meskipun ia berada di atas panggung, di hadapan kerumunan penonton yang penasaran dan menghakimi, sayalah yang terobsesi, sementara ia seratus persen fokus pada penampilannya sebagai Juliet. Cara ia melipat tangan di belakang pinggang, menunduk menatap kakinya seperti gadis kecil yang bosan—itu persis gambaran Juliet yang merasa sangat gelisah di pesta dansa keluarga.
Hal ini membangkitkan dua emosi dalam diri saya, yang pertama adalah kekaguman. Saya sungguh terkesan dengan bagaimana ia berhasil tetap tenang di tengah sorotan dan tidak membiarkan beberapa suara mengganggu mengganggu atau menghalanginya. Itu adalah bukti betapa luar biasanya bakatnya—sesuatu yang sejujurnya hampir saya lupakan mengingat semua yang terjadi beberapa bulan terakhir.
Di sisi lain, penampilannya yang sempurna justru memperparah dua emosi lain yang saya rasakan: tekanan. Lagipula, drama itu berjudul Romeo dan Juliet —kita tidak mungkin punya Juliet yang sangat berbakat, tapi Romeo-nya biasa saja. Jadi, inilah yang harus saya capai. Dan dengan otak saya yang sudah terbebani hari ini, tekanan berada di atas panggung hampir cukup untuk membuat saya gila.
Entah bagaimana aku berhasil menahannya, dan membasahi mulutku yang kering dengan air liur untuk mengucapkan kalimatku: “Oh, wanita siapakah itu, yang kini menghiasi mataku? Pernahkah aku mengenal cinta sejati atau keindahan sebelum malam ini? Kurasa tidak!”
Saat aku mengucapkan kata-kata manis pertama tokohku kepada Juliet, aku berjalan melintasi panggung menuju Ushio, lalu berlutut dan menyampaikan lamaranku.
“Oh, gadis cantik, apakah kau mau—”
Omong kosong.
Rasa dingin menjalar di tulang punggungku saat aku terbata-bata, salah mengucapkan kalimat itu sejak awal. Kudengar beberapa tawa kecil dari penonton. Aku bisa merasakan wajahku memanas.
“Eh… B-bolehkah aku berdansa?” kataku, cepat-cepat mengulang kalimatku di tempat.
“Dan apa yang boleh aku panggil kamu, Tuan yang baik?” tanya Ushio.
“Hanya seorang gelandangan dan pejalan kaki, Nona—tidak layak disebut.”
“Baiklah, wahai pejalan kaki yang baik hati—saya dengan senang hati akan memberimu tarian ini.”
Entah bagaimana, aku berhasil tidak merusak suasana sepenuhnya , tapi jelas aku kesulitan untuk tetap tenang dibandingkan dengan Ushio. Aku berdiri dan membungkuk, meletakkan tangan kiriku di dada sambil mengulurkan tangan kananku ke arah Ushio. Dia menerimanya, dan kami langsung masuk ke adegan dansa. Bukan berarti ada tarian sungguhan yang ditampilkan, lho; kami hanya berputar-putar mengelilingi panggung sambil berputar-putar seolah sedang menari.
Meskipun itu baru prolognya, sebenarnya inilah adegan dalam drama di mana Romeo dan Juliet berada dalam jarak fisik yang paling dekat—jadi Ushio dan aku cukup dekat untuk mendengar napas satu sama lain saat kami melakukan tarian dasar kami. Namun, aku mendapati diriku tak mampu mempertahankan kontak mata dengannya, tatapanku secara alami teralihkan karena takut ia akan melihatku sebagai sosok yang sebenarnya—atau, sebaliknya, karena aku merasa penampilannya sebagai Juliet terlalu cemerlang untuk dipandang langsung terlalu lama.
“Pasti ada sesuatu yang mengganggumu, ya?” kata Ushio, cukup pelan hingga hanya aku yang bisa mendengarnya. Aku agak terkejut dia akan mencoba menanyaiku tentang hal ini selama pertunjukan, tetapi aku dengan hati-hati mengangkat pandanganku untuk bertemu pandang dengannya. Ada kilatan amarah di pupil matanya, dan itu cukup untuk mengintimidasiku.
“Ti-tidak,” kataku. “Sudah kubilang, aku baik-baik saja…”
“Kalau begitu, fokuslah pada permainannya.”
“Aku tahu… aku mencoba, hanya saja…”
“Hanya apa?”
“Hanya saja… aku tidak tahu…”
“Katakan saja.”
“Kurasa aku merasa seperti—”
Tepat saat itu, aku tersandung dan tak sengaja menginjak jari kaki Ushio.
“Aduh!” Ushio menjerit kesakitan.
“Aduh, m-salahku!” kataku.
“Tidak apa-apa. Lanjutkan—kamu bilang begitu?”
“…Sudahlah. Itu tidak sepadan.”
“Kok bisa?”
“Bahkan jika aku memberitahumu, itu tidak akan memperbaiki apa pun… Lagipula, adegan dansanya sudah berakhir.”
Kami baru saja menyelesaikan putaran kecil kami di sekitar panggung, dan narator menimpali dengan beberapa firasat yang tidak terlalu halus tentang bagaimana karakter kami “tidak akan menikmati kebersamaan satu sama lain untuk waktu yang lama, karena takdir yang kejam akan segera memisahkan mereka.” Karena tidak punya pilihan selain menunda percakapan ini untuk nanti, Ushio mengalah saat adegan memudar dan kami keluar di sisi panggung yang berlawanan.
“Wah…”
Aku mendesah lelah begitu keluar dari sorotan. Belum genap tiga menit sejak drama dimulai, dan aku sudah merasa sangat lelah. Aku menahan diri untuk tidak langsung menjatuhkan diri ke lantai dan malah menyandarkan punggungku ke dinding di dekatnya. Selanjutnya adalah adegan balkon besar—adegan terpanjang di seluruh drama. Aku bertanya-tanya apakah aku sanggup melewatinya tanpa kesalahan, terutama ketika suasana antara aku dan Ushio sedang terasa canggung dan tegang.
“Hei, Kamiki,” kata Todoroki, yang sudah menungguku di belakang panggung. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan curiga. “Kamu tadi agak kaku di luar… Kamu lagi nggak enak badan atau gimana?”
Kalau dipikir-pikir, Hoshihara juga bilang begitu. Bahkan Ushio sudah bilang kalau aku terlihat pucat. Aku jadi bertanya-tanya, apa mungkin wajahku terlihat jauh lebih pucat daripada yang kusadari? Mungkin ada baiknya aku bercermin dulu.
“…Maaf soal itu,” kataku. “Tapi tidak, aku baik-baik saja. Jangan khawatir.”
Aku memaksakan diri untuk membuktikan kesehatanku yang prima, tetapi itu tidak banyak meredakan kekhawatiran Todoroki.
“Kalau kamu bilang begitu… Baiklah, asal kamu melakukannya seperti yang sudah kami latih, semuanya akan baik-baik saja. Dan kalau situasinya lebih buruk, kami bisa menukarmu dengan pemain pengganti.”
“Pengganti…? Seperti siapa?”
“Seperti aku.”
Dia mengatakannya tanpa nada ironi. Aku hanya bisa menggelengkan kepala tak percaya.
“Tidak, tidak, tidak,” kataku. “Ayolah. Kurasa itu tidak akan berhasil…”
“Kenapa tidak? Aku tahu semua dialognya, dan aku yakin kostumnya pas untukku.”
“…Cukup yakin akan sedikit aneh jika Romeo tiba-tiba berganti jenis kelamin di tengah-tengah cerita.”
“Oh, astaga. Mana mungkin ada yang sadar… Oke, mungkin mereka sadar,” katanya sambil tersenyum malu, lalu menyelipkan sejumput rambut yang terurai ke belakang telinga. “Kau benar. Aku memerankan Romeo itu mustahil. Atau mungkin lebih tepatnya: menggunakan siapa pun sebagai pemeran pengganti itu mustahil. Kau satu-satunya yang bisa kita andalkan, Kamiki. Jadi, yang bisa kuminta hanyalah kau keluar dan berusaha sebaik mungkin. Mari kita buat drama ini sukses, oke?”
“…Baiklah, ya.”
“Bagus, aku suka mendengarnya.” Dia mengangguk, lalu menoleh ke atas panggung. “Oh, astaga. Adegan selanjutnya sudah hampir dimulai. Semoga sukses di luar sana, Kamiki! Hajar mereka sampai mati!”
Dan dengan itu, Todoroki menghilang, mungkin untuk berbicara dengan Ushio atau kru pencahayaan. Tidak ada waktu untuk bersantai di sini; seperti kata Todoroki, tak seorang pun bisa memerankan Romeo selain aku, dan aku ingin pertunjukan ini sukses seperti yang ia lakukan. Maka, demi Ushio dan semua aktor lain yang telah berlatih keras untuk sampai sejauh ini, aku menguatkan diri dan memompa semangat untuk adegan berikutnya.
“Tertarik oleh cahaya yang bocor dari jendela di dekatnya saat keluar, Romeo melompati tembok taman perkebunan Capulet dan menyelinap masuk untuk melihat lebih dekat,” kata narator. Aku mengepalkan telapak tanganku yang berkeringat dan kembali ke panggung.
Ushio kini berdiri tinggi di atas panggung peraga, yang telah dibentuk menyerupai balkon oleh tim properti. Di atas sana, di bawah sorotan lampu, ia menatap langit seolah sedang berdoa, wajahnya begitu khidmat sehingga saya tak bisa lagi mendengar satu pun penentang di antara penonton. Mereka semua bersorak untuk penampilan Ushio saat itu.
“Tapi pelan—cahaya apa yang menembus jendela itu?” kataku, melafalkan kalimat yang mungkin paling sering kulatih saat latihan. “Wah, ini Juliet! Haruskah aku pergi dan menyatakan cintaku padanya?”
Ushio menatapku dari atas. Kini setelah kami berdiri di dua tingkat yang benar-benar berbeda, aku tak malu menatap matanya langsung. Sepanjang bagian pertama percakapan ini, kami bertukar dialog, tak satu pun dari kami tergagap atau lupa sepatah kata pun.
“Jika mereka menemukanmu di sini, nyawamu mungkin akan melayang,” katanya.
“Jangan khawatir, Juliet sayang. Jubah Malam akan menyembunyikanku dari pandangan mereka.”
Akhirnya, aku merasa kembali ke ritmeku yang biasa. Kuharap aku sudah menebus penampilanku yang menyedihkan di babak pembuka saat itu—bukan karena aktingku masih agak kaku, tapi untuk ukuran festival budaya SMA, kurasa aku pantas mendapat nilai kelulusan.
Setelah adegan di balkon selesai, tibalah saatnya bagi keduanya untuk menikah secara diam-diam. Saat Friar Laurence (diperankan oleh Shiina) mencuri perhatian, saya dengan patuh membacakan upacara pernikahan saya.
“Apa pun yang terjadi, kesedihan tidak akan mampu menghilangkan kebahagiaanku.”
Tidak buruk.
Dari sana, Romeo membunuh musuh bebuyutannya, Tybalt, dalam sebuah duel, lalu terpaksa melarikan diri dari kota, yang akhirnya memisahkannya dari Juliet. Aku menengadah ke langit dan mengutuk takdir karena telah membuatku menjadi orang bodoh karena keberuntungan.
Sejauh ini, kami baik-baik saja.
Dan akhirnya tibalah babak terakhir, dan adegan terakhir Romeo—di mana ia menemukan tubuh Juliet yang tak bernyawa dan mengiranya sudah mati, lalu memilih bunuh diri dengan racun yang ia miliki daripada hidup tanpanya. Selama saya bisa melewati adegan terakhir ini, ceritanya sudah berakhir. Ada sebuah podium besar di tengah panggung—sebenarnya hanya set piece sederhana yang dibuat dengan menutupi meja guru dengan kain—tempat Ushio berbaring, telentang dan tak bergerak.
“Oh, betapa kejamnya ini!” teriakku, berpura-pura tercengang saat aku perlahan mendekat, langkah demi langkah yang menakutkan, mencoba menyampaikan campuran tragis antara penyangkalan dan ketidakpercayaan yang dialami karakterku saat ini dalam penampilanku.
Akhirnya, kami hampir selesai.
Memang, mungkin belum genap dua puluh menit sejak pertunjukan dimulai—tapi bagiku, dua puluh menit itu terasa seperti pertempuran berabad-abad melawan kecemasan pertunjukan yang telah menguras habis cadangan mentalku. Aku ingin memanjakan diri dengan sesuatu yang manis dan lezat setelah ini selesai. Aku yakin ada kedai es krim di suatu tempat di festival itu, kan?
…Tunggu, tidak. Aku harus berhenti terlalu terburu-buru. Lagipula, aku masih punya beberapa dialog lagi yang harus kubawakan.
Saya berjalan ke arah tumpuan tempat Ushio berbaring dan berhenti tepat di depannya, lalu berbalik ke arah penonton untuk menyampaikan monolog yang membangkitkan semangat, penuh kesedihan dan kemarahan serta semua emosi lain yang mungkin dirasakan Romeo saat dipaksa menghadapi kematian Juliet.
Setidaknya, itulah rencananya.
Namun kemudian aku merasakan keringat mengalir di pelipisku.
Aku tak dapat mengingat dialogku.
Pikiranku kosong melompong. Lututku mulai gemetar karena aku diliputi rasa tak berdaya yang melayang, seolah terlempar ke ruang hampa. Aku hanya bisa berdiri di sana, tak mampu berkata sepatah kata pun, sementara detik demi detik yang menyiksa terus berlalu.
Ushio membuka sebelah matanya saat ia berbaring telentang di atas alas, pupil abu-abunya menatapku dengan cemas. Namun, satu-satunya kata yang terlintas di benaknya hanyalah “Aduh!” atau “Apa yang harus kulakukan?!” Dan seiring ketidaksabaran dan frustrasi yang semakin kuat, aku bisa merasakan tubuhku semakin panas.
Keributan terjadi di antara penonton saat orang-orang bertanya-tanya mengapa pertunjukan dihentikan. Saya bisa melihat Todoroki berdiri di sisi panggung dalam penglihatan tepi saya, melambaikan tangan dan tubuhnya dengan liar untuk menyampaikan pesan kepada saya. Namun, saya tidak bisa menangkap makna apa pun dari gerakannya. Jalan pikiran saya masih terhambat oleh kendala teknis di beberapa stasiun di ujung jalur.
Ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan.
Aku harus melakukan sesuatu, dan cepat. Kalau tidak, aku akan merusak seluruh pertunjukan kalau terus begini.
Saat itu juga, aku merasakan jemariku yang basah oleh keringat menyentuh sesuatu yang halus dan berkilau. Baru kemudian aku ingat apa yang kupegang di tangan kananku—sebuah botol kaca kecil. Sebotol racun yang dibeli karakterku dari apoteker dalam perjalanannya ke sini.
Tentu saja. Itu saja.
Mungkin aku tak perlu mengingat dialogku. Aku bisa saja menenggak racun ini lalu meninggalkan panggung, kejang-kejang kesakitan. Tentu, itu akan menjadi cara yang cukup tiba-tiba dan tidak wajar untuk mengakhiri drama, tetapi dari sudut pandang visual, itu tetap akan menjadi cara yang cukup baik untuk menyampaikan betapa sedihnya Romeo saat memikirkan Juliet telah meninggal tanpa perlu kata-kata. Itu sudah cukup bagiku, dan mungkin yang terbaik yang bisa kulakukan saat ini. Beginilah Romeo-ku menemui ajalnya. Aku mengangkat botol itu ke bibirku, dan—
“Tunggu!”
Aku membeku di tempat.
Juliet duduk tegak dari tempatnya berbaring di atas alas.
“Jangan sampai kau binasa tanpa sepatah kata pun, sayangku,” katanya.
Bisik-bisik meletus di antara penonton, beberapa bahkan meninggikan suara karena terkejut. Dan saya pun ikut terperangah bersama mereka. Adegan inilah yang seharusnya membuat Romeo mengira Juliet sudah mati, lalu bunuh diri. Keberhasilan Juliet untuk kembali sadar dan menghentikannya sebelum racun menyentuh bibirnya mengubah seluruh alur cerita.
Mengapa dia hidup kembali begitu cepat? Sekarang kami tidak punya pilihan selain—
Tidak, ini bukan salah Ushio. Ini salahku. Dia hanya berimprovisasi untuk menutupi kesalahanku setelah aku tiba-tiba terdiam. Kesadaran ini membuatku merasa sangat bersalah, sampai-sampai jantungku rasanya mau copot. Pertunjukan Romeo dan Juliet kami di kelas resmi hancur—dan itu semua salahku.
“Romeo yang manis, kau tak perlu mati di sini hari ini,” kata Ushio, melangkah pelan dari podium untuk berdiri tepat di hadapanku. “Mari kita pergi ke negeri yang jauh di mana tak seorang pun yang mengenal kita mungkin merasa pantas untuk mengejarnya. Setelah debu perseteruan yang menyedihkan ini mereda, kita bisa kembali lagi ke Verona. Sekarang, ayo!”
Suaranya penuh kasih sayang saat ia mengulurkan tangannya. Aku berdiri di sana ragu sejenak, ragu apakah aku bisa mengulurkan tanganku juga.
Apakah aku berhak menggenggam tangan Ushio? Aku, pria yang memaksakan begitu banyak perasaan egoisnya padanya dengan dalih hanya berusaha menjadi teman baik? Perbuatanku pasti telah menyakitinya berkali-kali lipat, tanpa aku sadari apa yang telah kulakukan. Tapi aku juga tahu—setidaknya saat ini—bahwa dengan tidak menggenggam tangannya, aku hanya akan menciptakan lebih banyak masalah bagi semua orang. Lebih dari segalanya, aku tak ingin perhatiannya terbuang sia-sia. Maka kubiarkan Ushio menggenggam tanganku, dan ia dengan mudahnya mengaitkan jari-jariku yang berkeringat dengan jari-jarinya sendiri, menekan telapak tangannya erat-erat ke telapak tanganku saat ia membawaku turun panggung dan kami menyelinap ke sisi panggung.
“Dan begitulah akhirnya Romeo dan Juliet, melawan segala rintangan, berhasil menghindari tangan takdir yang kejam, dan hidup bahagia selamanya,” ujar Todoroki melalui pengeras suara, mengambil alih peran sebagai narator untuk akhir cerita dadakan yang baru ini. Saat lampu meredup dan tirai panggung ditutup, hening sejenak—diikuti tepuk tangan yang remeh dan tersebar.
***
” Goblog sia !”
Saat kami sampai di belakang panggung, Todoroki mulai memaki saya.
“Kok bisa kamu tersedak gitu di adegan terakhir? Ugh… Padahal aku tadinya mau memuji kamu karena udah bisa ngapa-ngapain di babak kedua… Bukan berarti kamu masih terlalu kaku, lho!”
“Ya, aku tahu,” kataku. “Percayalah, aku benar-benar minta maaf…”
Aku merasa sangat bersalah, tapi yang bisa kulakukan hanyalah meminta maaf saat itu. Apalagi aku tahu Todoroki telah mencurahkan lebih banyak kerja keras dan semangat untuk menyukseskan drama ini daripada siapa pun, yang justru membuat celaannya semakin menyakitkan. Namun, setelah menyebutku idiot dan tolol dengan segala cara yang bisa dibayangkan, ia seolah kehabisan akal untuk marah, dan ia hanya menghela napas dan menggelengkan kepala.
“…Yah, setidaknya kamu sudah berusaha sebaik mungkin, kurasa,” katanya. “Keren banget hari ini, Kamiki. Kita harus melakukannya lagi kapan-kapan!”
Ia menyeringai nakal padaku, lalu berlari untuk memberi selamat kepada para aktor lainnya. Aku memperhatikannya perlahan-lahan keluar dari area belakang panggung, bertukar tos dan pujian dengan seluruh pemain dan kru.
“Kau tampak sangat gelisah di sana, Kamiki,” terdengar suara Mashima dari belakangku. Aku berbalik dan melihatnya berdiri di sana bersama Shiina seperti biasa, dengan ekspresi meremehkan yang jenaka di wajahnya. “Apa yang terjadi dengan semua kepercayaan dirimu saat kau melawan Arisa, hah?”
“…Lihat, ini cerita yang panjang, oke?”
“Ya, aku yakin… Yah, terserahlah. Kurasa tetap seru untuk ditonton.”
Shiina melangkah maju dengan ekspresi yang agak rendah hati. “Secara pribadi, saya… saya pikir itu cukup bagus, sebenarnya. Tentu saja, saya agak penasaran bagaimana semuanya bisa melenceng begitu jauh… Tapi saya cukup menyukai adegan terakhir itu.”
Tatapannya sungguh-sungguh, jadi aku tahu dia tidak mengatakan ini hanya untuk membuatku merasa lebih baik. Namun, aku kurang suka sanjungan, jadi itu membuatku agak malu.
“Te-terima kasih, itu sangat berarti,” kataku. “Meskipun aku tidak yakin apakah aku pantas menerima pujian atas sesuatu yang sebenarnya hanya sebuah kesalahan.”
“Ya, serius,” sela Mashima. “Pokoknya, sampai jumpa nanti!”
Saat kedua gadis itu melambaikan tangan dan menuju pintu, saya melihat area belakang panggung perlahan-lahan semakin sepi. Ada jeda waktu yang cukup lama antara acara ini dan jadwal acara berikutnya, jadi bahkan anggota panitia yang bertanggung jawab mengelola tempat acara pun pergi beristirahat di ujung gedung olahraga.
“Sakuma,” kata sebuah suara—satu-satunya orang tersisa yang akan memanggil namaku. Aku agak takut untuk berbalik, tetapi aku tahu aku juga tidak bisa mengabaikannya.
Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Ushio. “Kerja bagus, Ushio.”
“Itu mengerikan ,” katanya, menepisku. “Bagaimana mungkin kau pergi dan mempermalukan adegan paling klimaks itu? Bayangkan dirimu di posisiku , hanya berbaring di sana dan berpura-pura mati. Aku belum pernah merasakan rasa malu yang lebih mendalam seumur hidupku.”
Dia melontarkan kritik yang cukup pedas, tapi kata-katanya yang tajam menutupi raut kesedihan yang terpancar di wajahnya. Aku bahkan tak mampu bersikap defensif atau terluka perasaanku saat ini. Aku hanya merasa bersalah.
“…Maaf.”
“Kenapa kau membeku seperti itu?” tanyanya, ekspresinya dengan cepat berubah dari muram menjadi tegas.
“Eh…” Aku tidak yakin bagaimana menjawabnya—atau apakah aku harus mengatakan yang sebenarnya padanya.
“Apakah ini salahku?” tanyanya.
Tidak, aku hampir berkata begitu, tapi aku menahan diri. Aku tahu, berusaha setengah-setengah menyembunyikannya hanya akan membuatku kehilangan kepercayaannya. Dan aku merasa terlalu lelah untuk memikirkan apa pun sekarang, setelah kami baru saja menyelesaikan penampilan besar kami. Aku memutuskan untuk menyelesaikannya saja agar pikiranku tenang, dan aku mulai mencurahkan perasaan yang perlahan menumpuk di dalam diriku seperti lapisan-lapisan endapan emosi.
“…Kurasa akhir-akhir ini, aku merasa apa pun yang kulakukan, aku hanya akan menyakitimu, atau setidaknya mempersulitmu pada akhirnya,” akuku. “Dan aku juga mulai menyadari bahwa mungkin jauh di lubuk hatiku, aku bukanlah orang yang baik… Sial, entahlah, otakku mungkin hanya mencari simpati murahan dengan menceritakan semua ini kepadamu, berharap kau akan meyakinkanku bahwa itu tidak benar… Jadi, kurasa aku hanya berpikir, mungkin aku harus berhenti menghabiskan waktu bersamamu sama sekali.”
Begitu aku selesai, wajah Ushio langsung murung. “Itu hal yang sangat buruk untuk dikatakan di depanku, kau tahu.”
“Y-ya, maksudku…kamu tidak salah. Maaf.”
Dia benar—itu sungguh mengerikan. Sungguh menjijikkan membayangkan aku sedang memanipulasinya secara tidak sadar agar merespons seperti yang kuharapkan. Sekali lagi, aku terpaksa merendahkan diri untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya. Sekali lagi, sifat asliku yang memalukan mulai menunjukkan sisi buruknya. Aku benar-benar muak pada diriku sendiri karena masih belum belajar apa pun.
Kini akhirnya aku mengerti apa maksud Hoshihara. Mungkin lebih baik aku tutup mulut saja dan berhenti berusaha membantu orang lain. Setidaknya dengan begitu, tak akan ada yang tahu betapa bodoh dan tak berperasaannya aku ini. Sial, mungkin aku malah beruntung dan semua orang akan langsung menganggapku orang baik dan berniat baik. Tapi bicara langsung—nah, itu menakutkan. Apalagi setiap pernyataan yang bisa kau buat mengandung risiko yang sepadan.
Diam itu emas.
Bibir yang lepas menenggelamkan kapal.
Paling sedikit dikatakan, paling cepat diperbaiki.
Ada begitu banyak idiom dan peribahasa yang berasal dari berabad-abad lalu yang menunjukkan bahwa orang-orang telah mengenal keutamaan berdiam diri sejak zaman kuno. Dalam banyak kasus, itu adalah pilihan terbaik dan teraman untuk melindungi diri sendiri dan keluarga. Namun, mengucapkan kata-kata, dan benar-benar mewujudkannya, itu menakutkan—karena itu berarti menurunkan kewaspadaan dan membuat diri sendiri rentan. Dan saya muak menyakiti orang lain dan diri saya sendiri disakiti.
“Maaf,” kataku. “Kau benar—seharusnya aku tidak mengatakan apa-apa. Seharusnya aku menyimpan semua itu untuk diriku sendiri. Rasanya setiap kali aku membuka mulut, aku hanya akan mengatakan sesuatu yang bodoh dan menyakiti orang lain… Seharusnya aku diam saja selamanya sebelum aku benar-benar gila dan tak bisa diselamatkan lagi…”
“Tidak harus selalu begitu,” kata Ushio seolah-olah sedang menyampaikan permohonan yang emosional. “Memang, terkadang kau mungkin mengatakan hal-hal yang cukup tidak bijaksana yang secara alami akan membuat orang lain terluka perasaannya… Tapi itu bukan berarti kau harus tutup mulut selamanya. Kurasa tidak, dan kau juga jelas tidak boleh.”
Keyakinan dalam suaranya menyentuh hatiku.
“Karena maksudku… kau juga yang mengulurkan tangan dan menawarkan diri untuk berjalan pulang bersamaku di hari pertama aku datang ke sekolah dengan berpakaian seperti perempuan, ingat?” lanjutnya. “Kau tahu betapa bahagianya aku saat itu? Atau hari itu setelah aku pertama kali mendapat peran Juliet—kau benar-benar menebak dengan tepat tentang keenggananku untuk melakukannya, dan kau membicarakannya denganku. Itu saja membuatku merasa jauh lebih baik…”
Saya hanya berdiri di sana, mendengarkan Ushio dalam diam.
“Tentu, mungkin kau bisa menjalani hidupmu tanpa pernah menyakiti siapa pun jika kau tak pernah berkata sepatah kata pun… Tapi itu akan jadi bentuk kehidupan yang sangat menyedihkan, bukan? Lagipula, bukankah setiap hubungan pasti ada suka dukanya? Untuk setiap masa sulit yang kulewati bersamamu, Sakuma, selalu ada banyak masa indah yang bisa menebusnya… Ya, hubungan kita memang cukup sulit beberapa minggu terakhir ini. Aku akui aku memang tak ingin menghabiskan banyak waktu bersamamu akhir-akhir ini.”
Keterusterangannya dalam hal ini menusuk dadaku bagai pisau yang menusuk.
“Tapi saat ini, aku…”
Iris abu-abunya bergetar saat air mata menggenang di sudut matanya. Ia mengulurkan tangan dan menghapusnya dengan punggung tangannya.
“Saat ini, aku hanya…”
Tetapi bibirnya yang gemetar tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, dan dia pun menundukkan kepalanya.
“… Ugh, lupakan saja. Aku bahkan tidak tahu apa yang ingin kukatakan, atau apa yang kurasakan, atau apa yang kuinginkan… Tapi tolong jangan bilang kau harus diam selamanya. Aku tidak mau itu, dan kau juga tidak.”
Tiba-tiba, dadaku terasa sesak. Aku bisa merasakan diafragmaku naik dan ada benjolan di tenggorokanku. Sekarang aku mengerti kenapa aku mengkhawatirkan diriku sendiri sampai mual memikirkan semua ini. Akhirnya semuanya masuk akal—bukan di kepalaku, tapi di hatiku.
Itu karena aku ingin selalu berada di sisi Ushio. Aku belum siap jika dia tidak membutuhkanku.
Aku berusaha sekuat tenaga menahan gejolak emosi yang membuncah dalam diriku, lalu menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, aku menemukan suaraku.
“…Baiklah,” kataku, dan Ushio mengangkat kepalanya. Matanya yang pucat menatap tajam ke arahku, tapi aku tak mau mengalihkan pandanganku lagi. “Kalau begitu aku ingin kita terus bicara, Ushio. Tentang apa saja. Dan tanpa terlalu memikirkannya—apa pun yang terlintas di pikiran, bahkan jika itu percakapan dangkal dan tak penting yang pasti akan kita lupakan besok… Aku tahu mungkin akan ada lebih banyak waktu di kemudian hari di mana aku akan mengatakan atau melakukan hal-hal yang hanya akan menyakiti atau mempersulitmu—tapi aku harap kita bisa membicarakan momen-momen itu kapan pun itu datang.”
Aku menyingkirkan semua kepura-puraan dan mengungkapkan perasaanku kepada Ushio. Awalnya dia tampak agak terkejut, lalu tersenyum sambil mendesah pasrah dan mengangguk.
“Kalau kamu nggak apa-apa, Sakuma, aku juga nggak apa-apa,” katanya. “Kalau aku mulai ngalamin hal buruk lagi mulai sekarang… aku pasti bakal kasih tahu kamu. Jadi ya—kita coba terusin obrolannya, oke?”
Dengan itu, Ushio dengan malu-malu menggaruk pipinya dengan satu jari.
Aku tahu kami belum benar-benar menyelesaikan masalah mendasar apa pun di sini, pada akhirnya—kami hanya menyerahkan tanggung jawab kepada diri kami di masa depan. Aku yakin akan ada lebih banyak kecemasan dan penderitaan yang menanti kami berdua di kemudian hari. Tapi untuk saat ini, aku dan dia baik-baik saja. Dan saat ini, di saat ini, hanya itu yang kubutuhkan untuk merasa baik-baik saja.
Pintu ke area belakang panggung terbuka dengan suara keras .
“Aha! Ternyata kalian!” kata Hoshihara, berlari menghampiri begitu melihat kami. Katanya dia berencana datang dan menonton drama itu, jadi kukira dia sudah menonton di auditorium bersama penonton lainnya sampai sekarang. “Fiuh, syukurlah! Aku khawatir kalian sudah kembali ke ruang tunggu atau semacamnya.”
“Hai,” kataku. “Apa yang membawamu ke sini?”
“Bagaimana menurutmu, bodoh?!” Dia membungkuk ke depan dengan penuh semangat. “Aku di sini untuk memberi kalian kesan-kesanku, tentu saja! Dan percayalah, ada banyak hal yang ingin kubicarakan, tapi yang terpenting…”
Dia berhenti sejenak dan mengepalkan tinjunya untuk memberikan efek dramatis, lalu berteriak:
“Ya Tuhan, aku sangat senang ini adalah akhir yang bahagia!”
Seketika, para anggota panitia yang sedang sibuk mempersiapkan babak selanjutnya datang untuk menanyakan keributan apa yang terjadi. Saya meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja dan menyuruh mereka pergi sebelum mendengarkan ulasan Hoshihara yang menggebu-gebu.
Kalian nggak ngerti—aku benar-benar kekanak-kanakan kalau soal akhir yang menyedihkan atau resolusi yang pahit-manis! Jadi, aku tadinya berpikir, ‘Wah, ini bakal jadi cerita yang bikin nangis lagi, ya?’ Tapi ternyata enggak! Romeo dan Juliet ternyata hidup di masa itu! Aku nggak nyangka banget —ceritanya malah bikin aku emosional banget!
“Ya, soal itu…” kataku sambil tersenyum malu. “Percaya nggak kalau aku bilang Ushio cuma improvisasi karena aku salah dan lupa dialogku?”
“Kau bercanda! Apaaa?!” Hoshihara menghela napas takjub mendengar hal ini. “Wah, sialan. Sekarang aku punya sejuta pertanyaan lagi yang ingin kutanyakan padamu… Tapi, ngomong-ngomong, kesampingkan itu!”
Wajah Hoshihara berubah serius saat dia berbalik menghadap Ushio, yang tampak sedikit bingung dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba ini.
“A-ada apa?” tanya Ushio.
“Aku sangat senang mendapat kesempatan melihatmu memerankan Juliet, Ushio-chan. Kau begitu cantik, menawan, dan memukau di atas panggung, sampai-sampai aku berharap bisa seperti itu suatu hari nanti…” Ekspresinya yang penuh hormat berubah menjadi ekspresi pasrah yang menyakitkan. “Sejauh yang kutahu, kaulah Juliet terbaik yang pernah ada. Hanya ingin memberitahumu itu. Itu saja.”
Setelah menyampaikan pendapatnya, Hoshihara menundukkan kepalanya seolah-olah malu atau kalah.
Pada akhirnya, kami tidak pernah sampai pada kesimpulan apakah Ushio benar-benar menikmati dirinya di atas panggung atau apakah ia menyesal telah setuju untuk memerankan Juliet. Jika yang terakhir benar, maka ada kemungkinan pujian Hoshihara yang begitu tinggi akan menyinggung perasaan Ushio. Namun, meskipun Hoshihara tahu itu, ia jelas merasa terdorong untuk memberikan kesan yang sebenarnya kepada Ushio.
Ushio tampak agak tidak nyaman sejenak, mungkin merasa ditempatkan dalam posisi yang canggung, lalu akhirnya mampu menjawab.
“Setelah festival selesai…”
Hoshihara mengangkat kepalanya, dan Ushio tersenyum lembut.
“…kita bertiga harus keluar dan merayakannya.”
Hoshihara tampak tercengang sesaat—namun kemudian matanya berkaca-kaca karena mulai dipenuhi air mata, dan dia praktis menerkam Ushio.
“Ushio-chaaaan!” dia menangis.
“Wh-whoa!” Ushio berseru ketika Hoshihara membenamkan dahinya di dada Ushio dan merintih seperti bayi.
“Oh, syukurlah… kukira kau membenciku-hee-heeee…!” isak Hoshihara lega. Ushio hanya berdiri tertegun sejenak, sebelum perlahan-lahan mengendur dan meletakkan tangannya di atas kepala Hoshihara.
“…Aku benar-benar minta maaf, Natsuki.”
Saya pikir saya bisa menganggap ini sebagai rekonsiliasi.
Tentu saja, belum semuanya dibahas, diselesaikan, dan dirangkum dengan rapi. Tapi setidaknya, aku tidak merasa Ushio akan terus-menerus mendorong Hoshihara. Aku berdiri memperhatikan mereka berpelukan dari jarak yang cukup dekat, menyandarkan punggungku ke dinding. Aku tahu sebentar lagi akan ada siswa lain yang datang untuk mempersiapkan diri di belakang panggung, tapi aku belum siap untuk pergi. Aku ingin tetap di sini, menikmati sisa-sisanya sedikit lebih lama, dan menghargai momen ini selagi bisa, karena aku tahu perasaan ini mungkin tidak akan bertahan selamanya.
Karena jangan salah—ini belum berakhir, dan masih terlalu dini untuk berpuas diri. Sekalipun aku dan Hoshihara mungkin puas dengan keadaan sekarang, aku tahu perasaan terasing dan terisolasi mungkin masih mengintai di dada Ushio, menusuk duri-durinya semakin dalam ke dalam hatinya. Dan aku tak mau puas dengan akhir yang kurang dari dongeng di mana tak seorang pun harus menderita dan kami bertiga bisa tertawa lepas, bermain-main bersama di lereng bukit hijau yang berkelok-kelok menuju negeri nun jauh di mana kami semua bisa hidup bahagia selamanya.
Sampai kita bisa mewujudkan mimpi itu, saya akan terus melanjutkan dialog ini.